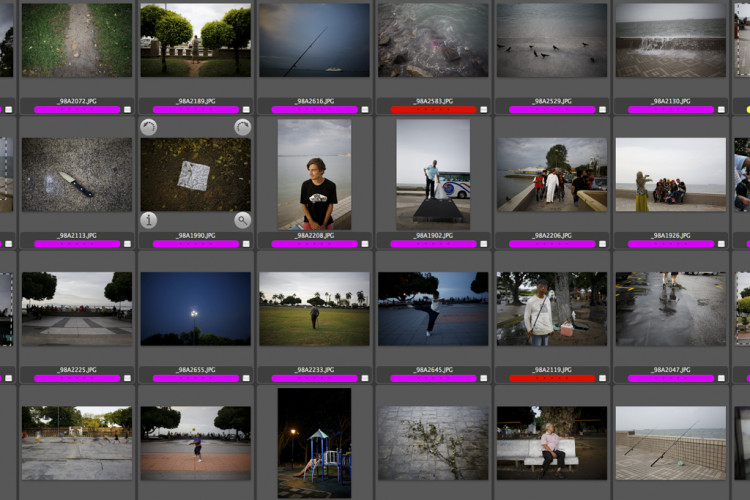Jangan Salahkan Tuhan yang Hilang Saat Kita Semakin Lalim
Dalam submisi Open Column ini, Kirana Anjani Ariella Lugijana menyandingkan novel Ketika Senja Jatuh di Nara (2025) dengan pembacaannya terhadap Alkitab, dan dengan segala yang terjadi dalam iklim alam dan politik hari ini di Indonesia.
Words by Whiteboard Journal
Belalah mereka yang tak dapat membela dirinya sendiri. Lindungilah hak semua orang yang tak berdaya. Berjuanglah untuk mereka, dan jadilah hakim yang adil. Lindungilah hak orang miskin dan orang tertindas.
Amsal 31:8-9 (BIMK)
Ketika Senja Jatuh di Nara karya Zaky Yamani (2025) bercerita tentang perjalanan Debora, seorang perempuan muda yang tidak terima dengan kenyataan bahwa dirinya adalah seorang anak angkat. Debora yang dunianya tiba-tiba runtuh mendesak ibunya untuk mengizinkannya untuk pergi ke kampung halamannya, Nara, untuk mencari ibu kandungnya yang tega membuangnya saat ia masih bayi. Atau setidaknya, bisikan-bisikan cerita ibunya yang masih tertinggal di Nara.
Lembar-lembar awal buku ini cukup mengejutkan saya ketika saya berpapasan dengan nama-nama tokoh yang saya jarang jumpai jika tidak sedang membaca Alkitab. Serius, kaget dikit. Nara adalah sebuah perkampungan swadaya yang hidup dari hasil tanah yang diolah dan digarap masyarakatnya secara kolektif. Lahir dari orang-orang terpinggirkan karena ketidakadilan, warga di Desa Nara hidup secara egaliter lewat hasil alam yang mereka hidupi dan balik menghidupi mereka. Hingga suatu waktu, datanglah seorang pendeta yang menyebarkan ajaran Kekristenan di Nara.
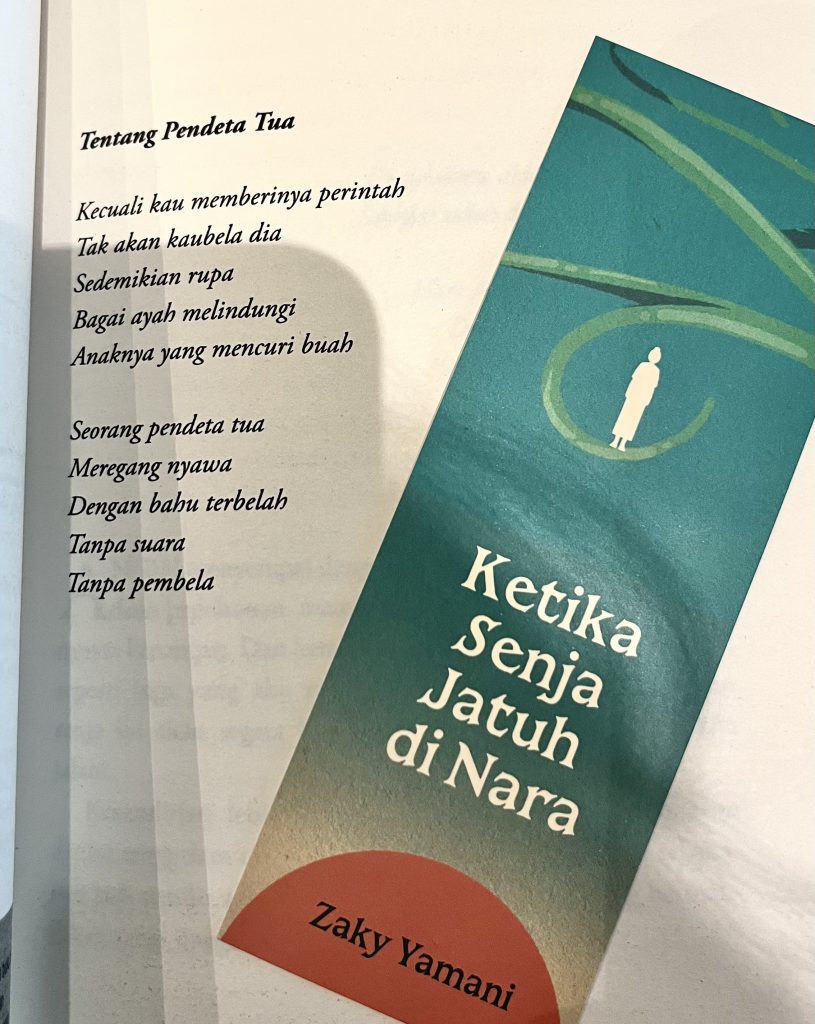
Puisi di buku Ketika Senja Jatuh di Nara. (Image via Kirana Anjani Ariella Lugijana)
Tidak lama setelah kedatangan Bapa Ernest, seorang pendeta—yang nantinya memiliki murid bernama Yohanes, pendeta berpengaruh di Nara, chef’s kiss for the Biblically accurate representation—tokoh-tokoh dengan nama bercorak Kristen mulai bermunculan. Minggir sedikit dari cerita di buku ini, sebagai seorang Kristen, saya masih tidak bisa berdiri di belakang semangat misionaris dan pengabaran injil sebagai berita baik yang menghapuskan budaya praktik lokal masyarakat adat atas nama ‘keselamatan’. Ya, tentu saja saya senang ketika ada berbondong-bondong orang yang menerima Yesus sebagai juruselamatnya. Namun, dibalik itu semua, apa saja yang hilang dan dihapuskan dari ingatan kolektif masyarakat adat tersebut? White knight syndrome.
Ketika Senja Jatuh di Nara pun sedikitnya menggambarkan bagaimana Kekristenan bergesekan dengan budaya dan kearifan lokal di Nara. Kristen atau bukan, sepertinya dengan mudah kita dapat mengkategorisasikan praktik penyebaran agama yang mengabaikan kearifan lokal sebagai salah satu cengkraman kolonial yang masih dilanggengkan oleh institusi agama di Indonesia.
Tidak hanya Kekristenan yang menjadi momok kolonialisme baru di Nara, tapi juga—tentu saja tidak lain dan tidak bukan—kapitalisme. Meskipun cerita perjalanan Debora yang menyingkap sejarah dan kejadian Nara merupakan cerita fiksi, sejarah dan kejadian serupa masih terus dibarukan setiap harinya dan dirasakan oleh orang-orang yang tinggal dekat dengan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Persis dengan Nara yang berada di pinggiran hutan yang disulap jadi kebun kelapa sawit.
Lucunya, ‘kapitalisme’ dan sistem nilai tukar berbasis mata uang yang dibawa ke Nara diperkenalkan oleh seseorang bernama Paulus. Saya sempat nyengir—nyengé, Bahasa Sundanya—sendirian di kafe ketika menyadari oksimoron yang jenius ini. Paulus di Alkitab dan di buku ini sama-sama memiliki influens yang besar; yang satu menyebarkan agama, yang lainnya kapitalisme. Memang betul, Yohanes yang nantinya akan menjadi gembala gereja di Nara akan ikut berjuang untuk masyarakat desa, tapi ternyata nasibnya pun malang. Sebagai anggota gereja yang juga pernah mengirim salah satu kakak rohaninya ke Kalkuta di India, hal ini agak memuakkan. Karena memang inilah yang terjadi: Misionaris, meski dikirim oleh gereja, seringkali harus berjuang sendirian di perantauan.
Praktik-praktik pengiriman misionaris ini sudah lama mengganjal dalam pikiran saya, meski saya selalu bingungbagaimana cara mengartikulasikannya. Kisah Bapa Ernest dan Yohanes di Nara secara lengkap menggambarkan apa yang selalu saya pikirkan: Gereja-gereja di kota besar yang jemaatnya bergelimang harta sering kali hanya akan ‘mendoakan’ dan berharap Kristus secara ajaib akan menolong misionarisnya dan komunitas di mana misionaris tersebut tinggal. Konyol! Mirip sekali dengan apa yang dilakukan Paus Francis belakangan ini. Meski dia sangat keren dan revolusioner bagi kaumnya, Paus Francis yang terus-menerus mengabarkan dan mempertontonkan solidaritasnya kepada Palestina di hadapan dunia dibalas dengan gereja-gereja di seluruh dunia yang seakan-akan buta dan tuli. Jika saya boleh menerka pikiran Yesus, agaknya Dia tidak mati untuk Kekristenan menjadi tangan panjang kapitalisme yang apatis.
Hancurnya komunitas masyarakat adat yang dekat dengan kekristenan di Nara beserta dengan ekosistem alam yang juga dieksploitasi habis-habisan menggambarkan dengan sempurna betapa apatisnya Kekristenan Indonesia di tengah bangsa yang lalim ini.
Kejahatan HAM dan ekologis besar-besaran di negeri ini tidak sedikitpun menggerakan gereja sebagai tubuh Kristus untuk secara berani menentang praktik-praktik kapitalisme yang terang-terangan berseberangan dengan Kekristenan dan praktik pengajaran Kristus. Ketika ketidakadilan dan penindasan menjadi sampar di negeri ini, gereja memilih untuk diam dan tidak berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas. Tidak jarang pula anggota gereja dengan harta berlimpah yang malah turut andil dalam penindasan di negeri ini.
Saya pun bertanya-tanya, di mana kasih Yesus di tengah-tengah bangsa yang lalim ini?
Di akhir perjalanan Debora, ia mengungkap kisah generasi ketiga gereja yang kalah oleh kapitalisme yang sudah terlanjur meluluhlantakkan Nara. Pada akhirnya, gereja menjadi perpanjangan tangan penindas yang turut mencengkram Nara dalam ketakutan. Mengutip perkataan Om Zaky—yang sangat baik sekali untuk mau berbincang bersama saya dan teman saya, Giant—tentang akhir dari kisah bayangan-bayangan yang masih menghantui Nara, “Ketika alam sudah dirusak secara habis-habisan, tidak ada kekuatan manusia yang bisa mengembalikannya seperti semula.”
Di tengah-tengah keserakahan penguasa yang semakin terang-terangan dan tidak tahu malu, saya menolak menjadi bagian Kekristenan yang acuh. Semoga masih ada kasih Yesus di tengah bangsa yang lalim ini.
…belajarlah berbuat baik. Tegakkanlah keadilan dan berantaslah penindasan…
Yesaya 1:17a (BIMK)
Ketika Senja Jatuh di Nara merupakan novel yang kemudian memotivasi saya untuk kembali mengunjungi draf tulisan ini. Seharusnya, tulisan ini dirilis Jumat Agung lalu. Karena kebisuan gereja Kristen Indonesia sudah memuakkan belakangan ini dan perlu rasanya bagi saya sebagai anggota gereja untuk mengejawantahkan urgensi bagi gereja untuk mulai bergerak. Ternyata tuntutan-tuntutan pekerjaan—Jakarta dan kesibukannya yang sombong!—lebih besar dari 24 jam yang kumiliki kala itu. Senang rasanya saya diperkenalkan dengan buku Ketika Senja Jatuh di Nara—terima kasih Giant atas rekomendasinya—dan berkesempatan untuk berbincang bersama Om Zaky Yamani dalam dua kesempatan yang berbeda.