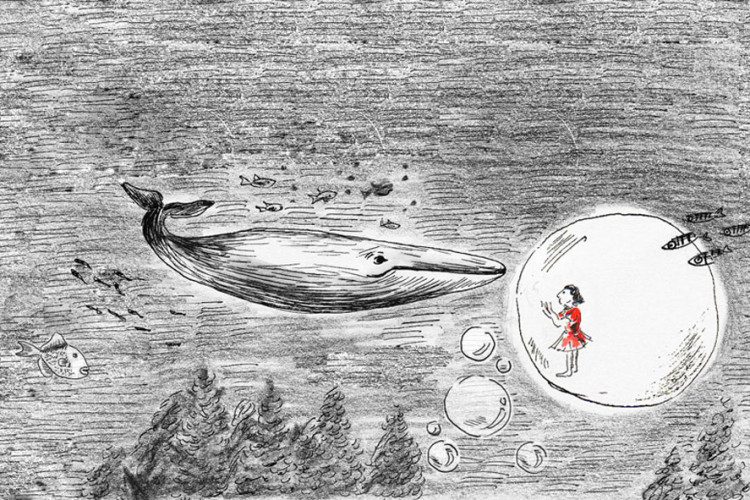Tangkal Racun Sosial Media
Pada column hari ini, Siti H. Hanifiah membahas kebutuhan kita akan validasi di media sosial dan bagaimana itu dapat meracuni kesehatan mental kita.
Words by Whiteboard Journal
“Eh menurut lo feed Instagram gue gimana? Bagus gak? Gak norak kan? Likes dong postingan gue yang baru.”
Jangan terkejut apabila mendengar percakapan tersebut di depan umum. Agak aneh tapi itu nyata, saat ini banyak orang yang lebih peduli dengan citra mereka di Instagram daripada dunia nyata. Tidak perlu berbohong pada diri sendiri, mungkin salah satu dari kita adalah mereka yang lebih peduli dengan banyaknya likes dan follower.
Baru-baru ini saya memilih untuk uninstall semua akun media sosial saya. Dari Twitter, Instagram dan Facebook. Awalnya saya berpikir bahwa saya hanya lelah dengan kehidupan di media sosial. Namun, baru-baru ini saya menyadari bahwa saya lelah dengan kehidupan sosial zaman sekarang.
Mengikuti segala macam perkembangan kehidupan dengan mengunggah kebahagian di instastory, mengecek tiap menit siapa yang melihat instastory kita, menghitung banyaknya likes dari setiap unggahan kita, membalas setiap dm atau komentar di setiap unggahan, dan masih banyak lagi. Belum lagi muncul perasaan tidak enak apabila ada teman yang mention kita di instastory, kadang muncul perasaan wajib repost unggahan mereka. Walau sebenarnya belum tentu mereka ingin kita repost juga, tapi terkadang perasaan tidak nyaman tersebut muncul begitu saja. Terasa melelahkan bagi introvert seperti saya, yang biasanya nyaman dengan privasi.
Sejak saya aktif di media sosial, banyak perubahan yang terjadi dalam pribadi saya. Rajin mengomentari dan likes unggahan teman-teman saya, dengan harapan mereka juga melakukan hal yang sama. Hal yang mungkin tidak bisa kita dapat di dunia nyata dengan mudah. Sedangkan Instagram dan Twitter memberi kemudahan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Jujur, awal mulanya saya merasa nyaman dengan keadaan ini. Lama-kelamaan saya merasa hampa dan justru muncul perasaan negatif di dalam diri sendiri.
Belakangan saya membaca sebuah artikel menarik di situs i-D yang membahas tentang tingkat depresi yang tinggi akibat berlama-lama bermain Instagram. Menurut survei terbaru, remaja dari usia 14-24 tahun rentan mengidap depresi dan cemas berlebih akibat penggunaan Instagram, Snapchat, dan Facebook. Melihat dan membandingkan kehidupan orang lain yang lebih baik memunculkan perasaan negatif ke dalam diri sendiri.
Saya juga merasakan hal yang sama, di saat melihat teman-teman seperjuangan telah lebih sukses dalam hal karir atau sudah menikah dan memiliki keluarga yang bahagia. Tidak perlu munafik dan membohongi diri sendiri, saya merasa tidak nyaman dengan unggahan pamer kehidupan di media sosial. Bukan bermaksud nyinyir, namun hal tersebut terkadang memicu perasaan buruk di dalam diri.
Belakangan muncul pembicaraan mengenai aplikasi FaceApp, beberapa teman saya ikut mengunggah foto #OldChallenge mereka. Awalnya saya merasa lucu juga, bisa melihat wajah kita di masa tua. Saya pun mencoba install aplikasi tersebut dan mengecek wajah saya dengan filter “Old”. Tiba-tiba saya takut untuk tua karena wajah saya sangat buruk di aplikasi tersebut. Kemudian saya bertanya kepada diri saya, “Kenapa kamu takut?”. Usia saya masih 31 tahun dan untuk apa takut pada hal yang belum terjadi. Saya saja belum tentu hidup sampai usia 80 tahun.
Terkadang hal-hal yang viral di media sosial memang menyenangkan untuk sebagian orang, namun untuk beberapa orang bisa memberi dampak negatif ke dalam dirinya secara tidak sadar. Membandingkan penampilan dan kehidupan dengan orang lain di media sosial merupakan hal yang biasa terdengar. Perubahan citra dan kebutuhan diakui oleh orang lain menjadi santapan wajib bagi para pengguna media sosial saat ini. Tidak hanya remaja, orang dewasa pun ikut meramaikan epidemik ini.
Membandingkan kekayaan, kecantikan, kesuksesan karir, jalan-jalan ke luar negeri atau hal remeh lainnya yang bisa diunggah di media sosial demi pengakuan dari dunia luar. Sejak kehadiran media sosial, kata “Pamer” bisa dengan mudah dilakukan hanya dengan sekali klik. Dulu, sebelum ada media sosial “Pamer” menjadi kata yang tabu dan negatif. Sekarang hal tersebut menjadi lumrah dan sangat diterima oleh masyarakat.
“Social comparison plagues me the most on social media. It’s not the influencers or models or celebrities that get to me – it’s the acquaintances and friends of friends. When all you know about a person is their perfect pout on a night out, their most recent work success, it’s all too easy to assume that that is their reality.” – Sarah Raphael
Bagi Sarah Raphael, editor Refinery29, media sosial membuatnya muak dengan kehidupan nyatanya. Menurutnya, kita jadi membandingkan kehidupan dengan orang lain dan berpikir buruk terhadap diri sendiri. Ada benarnya pernyataan tersebut, mungkin itu alasan saya menghapus semua aplikasi media sosial saya di ponsel.
Awalnya saya merasa terlalu banyak bersosialisasi di Instagram dan Twitter, namun setelah hampir dua bulan saya menghapus aplikasi tersebut saya menyadari satu hal. Bukan salah media sosial yang membuat saya merasa tidak nyaman dengan unggahan dan aktivitas di dunia maya tersebut. Namun perubahan sosial di generasi sekarang yang saya tidak bisa “Keep up”, sehingga saya memilih untuk melakukan “Social Media Detox”.
Pengakuan dan citra keren karena kehidupan sosial saat ini dinilai hanya dari sebuah akun media sosial. Tingginya penghargaan media sosial tersebut pada mayoritas orang yang tidak bisa dipahami sehingga saya memilih untuk sign out dari platform tersebut. Jadi untuk apa menyalahkan media sosial kalau kita tidak introspeksi diri terlebih dahulu?