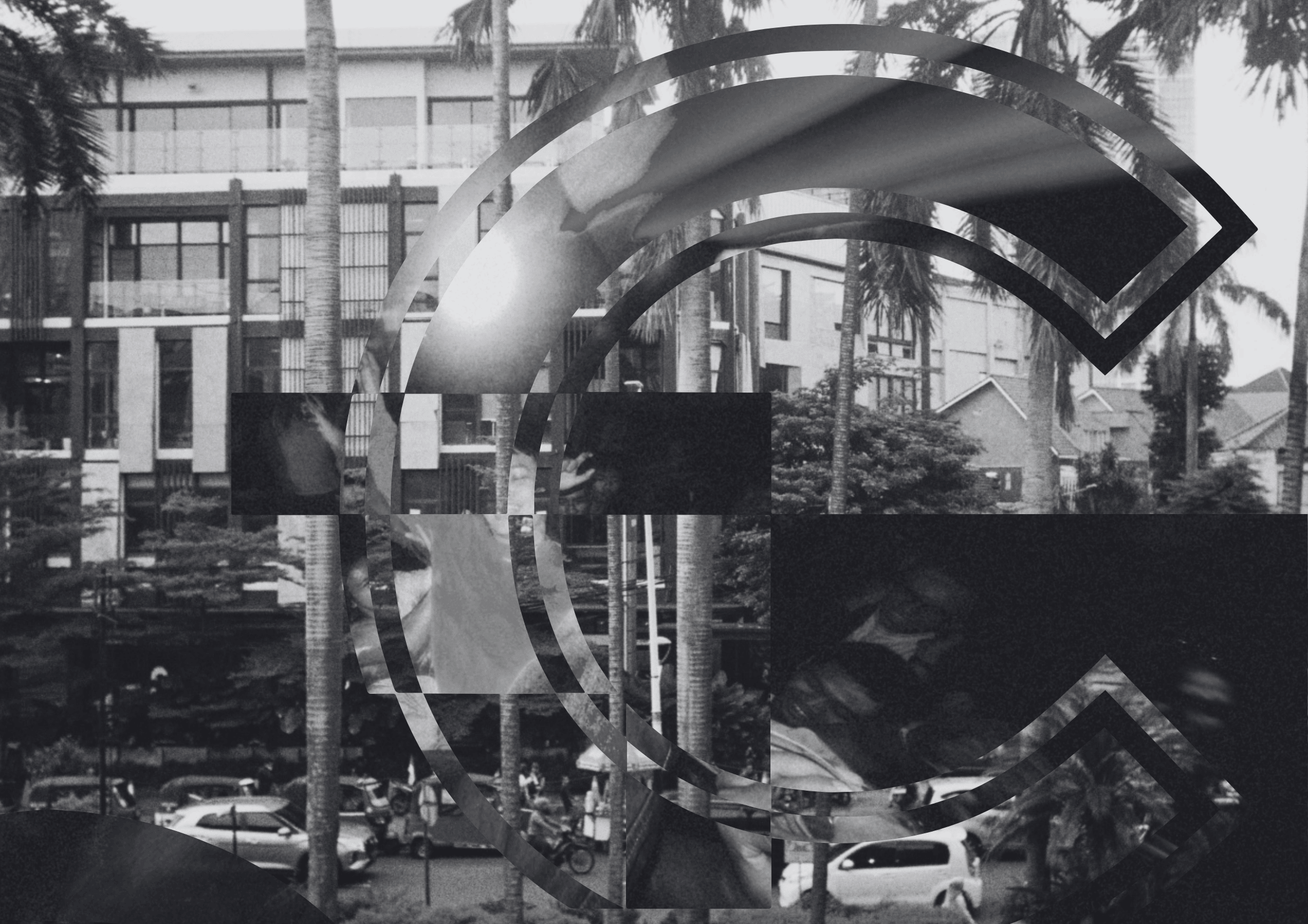
Mengejar Bisik-Bisik Jakarta: Gaung Harapan di Tengah Hiruk Pikuk Urban
Dalam submisi Open Column ini, Gisela Swaragita menangkap bisik-bisik yang terus berbising di Jakarta, sekaligus menghidupkan “suara-suara” itu yang lahir dari dinamika musik, kelindan antar warga, dan opini lantang kita yang menolak untuk dibungkam.
Words by Whiteboard Journal
Di ujung selatan Taman Margasatwa Ragunan, di seberang kandang buaya, ada danau besar yang dikelilingi jalan setapak dari konblok merah bata.
Setiap sore kalau sempat, aku akan berjalan dari gedung kost-ku di seberang pintu masuk Taman Margasatwa, menuju ke danau itu untuk lari.
Aku akan masuk sebelum gerbang ditutup pada pukul empat, lalu aku akan duduk di bangku di bawah pohon trembesi di depan kandang pelikan, menunggu cuaca teduh. Kemudian aku akan berjalan ke arah kandang terbuka favoritku, rumah kuda nil kerdil. Di situ aku akan pemanasan sambil menonton si kuda nil kerdil berenang di kubangan, atau makan kalanjana ditemani serombongan ayam yang entah kenapa hidup satu kandang dengannya.
Lalu aku akan lari. Pelan-pelan saja. Kecepatan rata-rataku 10 menit/km—amat lambat walau aku selalu merasa sudah ngebut. Aku akan berlari menyusuri selokan yang menyetor air ke kubangan kuda nil kerdil, kolam perahu bebek, kandang buaya, sampai akhirnya tiba di danau. Dengan headphone Sony-ku yang sudah boncel, aku akan mendengarkan lagu-lagu yang malu aku dengarkan keras-keras lewat speaker—koleksi bubblegum-pop, pop-punk, nu-metal—yang terburuk dari dekade 2000. Apa pun yang familiar dan nostalgis.
Sore yang sempurna di Ragunan adalah ketika cuaca sejuk, tidak terik dan tidak hujan. Matahari keemasan, memantul di permukaan air yang berkelip-kelip. Bau ganggang menguar dari mulut selokan yang menyetor air ke danau. Biawak-biawak liar berenang pelan-pelan memotong permukaan air dari satu ujung ke ujung lainnya.
Berlari dalam lanskap ini, aku akan menyambut berbagai ide yang tidak muncul di kepala ketika aku duduk tegang di depan layar laptop di meja kerja. Maka, ritual lari sore ini menjadi waktu yang krusial untuk merenungkan apa yang harus aku lakukan dengan Norient City Sounds: Jakarta Whispers, projek yang memakan sebagian besar waktuku di tahun 2025.
Norient adalah sebuah entitas di kota Bern, Swiss yang berfokus pada musik, suara, dan pergerakan manusia yang berhubungan dengannya. Pertama kali aku terhubung dengan Norient adalah di tahun-tahun pandemi ketika mereka mencari jurnalis musik dwibahasa dari Indonesia. Di paruh pertama dekade 2020 aku menyumbang beberapa tulisan untuk berbagai projek termasuk lokakarya dan buku.
Sekitar awal 2025, aku dihubungi oleh Suvani Suri, seniman asal India yang menjadi kurator Norient City Sounds: Delhi Sensate pada 2023. Rupanya Suvani diminta untuk membimbing kurator Norient City Sounds berikutnya. Ia menunjukku, kontributor reguler yang tinggal di Jakarta, untuk menggarap edisi 2025.
Norient City Sounds adalah seri multimedia berisi pameran virtual dan publikasi digital yang mengeksplorasi musik dan suara dari berbagai kota di dunia. Selain Jakarta dan Delhi, seri NCS pernah menjelajahi Nairobi, Beirut, dan Bogotá. Kota-kota ini disikapi sebagai “kawah candradimuka” di mana kelindan kegiatan warga membentuk suara-suara yang menjadi ciri khas kota tersebut, dan komunitas-komunitas musiknya punya warna-warna unik milik mereka sendiri.
Tugasku sebagai kurator adalah merenungkan tema besar yang menubuhi Jakarta dalam suara. Kemudian, aku harus memilih dan memanggil para kontributor, menginstruksikan karya yang harus mereka kerjakan, serta menyatukan mereka semua dalam narasi yang mengenkapsulasi seri ini sebagai kesatuan.
Judul yang aku pilih untuk narasi ini akhirnya adalah “Jakarta Whispers”, atau “Bisik-bisik Jakarta”. Sebagai penduduk Jakarta yang selamanya merasa menjadi pendatang, aku tidak pernah terbiasa dengan polusi suara yang datang dari puluhan juta manusia yang berkegiatan di kota ini setiap harinya. Ruang sonik Jakarta penuh sesak dengan pekaknya dangdut dorong, tahu bulat, jingle iklan, sirine kendaraan pejabat—semua berlomba menjadi paling keras, seakan-akan keselamatanmu terjamin ketika kamu menjadi yang paling nyaring. Kesunyian menjadi kemewahan, dan kesendirian menjadi kelegaan.
Aku membayangkan sebuah metafora: fasad utama kota megapolitan yang komersil dan korporat ini adalah teriakan-teriakan yang bising. Sementara subkultur bawah tanah adalah bisikan-bisikan yang bertahan dan bahkan tumbuh subur, semata karena disirami renjana para pelakunya. Bisikan-bisikan inilah—termasuk kerja-kerja komunitas musik, ruang-ruang alternatif, panggung-panggung kecil di kawasan ruko tua—yang kurasa berharga untuk direkam dan dirayakan.
—
Ketika aku telah mencapai KM ke-4, langit akan berubah lembayung. Serombongan burung hitam akan melesat dari pucuk-pucuk pohon dan terbang rendah ke permukaan air, mencari ikan. Para biawak akan malu-malu muncul dari lubang-lubang yang mereka gali di sekeliling danau untuk berkeliaran di atas tanah, tapi akan terbirit-birit masuk ke air lagi ketika mereka melihat aku berlari ke arah mereka.
Ketika aku mengakhiri lariku di KM ke-5, matahari biasanya sudah menyusup ke balik barisan hutan bambu di sebelah barat danau. Dalam gelap, aku akan berjalan pulang diiringi sayup-sayup azan Magrib dari masjid-masjid di perkampungan yang mengelilingi kompleks Taman Margasatwa. Deru mesin dan klakson dari kendaraan-kendaraan yang baru lolos dari kemacetan di TB Simatupang bertalu-talu, melalui jalan-jalan tembus Kebagusan di balik tembok-tembok kebun binatang. Pelan-pelan aku akan berjalan menyusuri selokan melewati kandang buaya, kolam perahu bebek, kembali ke rumah kuda nil kerdil. Terkadang aku dikagetkan seekor–dua ekor biawak gendut yang melata di jalan gelap di depanku. Tapi setelah beberapa tahun melakukan ini, aku tidak lagi takut. Aku hanya akan diam sambil menunggu si biawak tergesa menyeberang dan menghilang di badan air atau gerumbul semak terdekat.
Saat berjalan pelan-pelan ini lah aku menghubungi rekan-rekanku dan melontarkan ide-ide yang mungkin terdengar impulsif, walau telah dipikirkan masak-masak selama satu jam durasi lari.
Misalnya, saat aku meminta Nyon, sahabat yang aku rekrut sebagai desainer grafis, untuk mengambil inspirasi visual kunci dari nama-nama daerah di Jakarta yang menggunakan nama flora: pete, cabe, kelapa, duren, jeruk, labu, cempaka, melati, dan lain-lain. Saat itu pula aku berkonsultasi perihal offline event/release party dengan Robonggo, kawan yang aku rekrut sebagai desainer video, tapi juga tetua kolektif Paguyuban Crowd Surf yang punya portfolio panjang membuat acara musik yang menyenangkan.
Aku sedang beristirahat di pinggir kandang binturong ketika memberanikan diri merekrut senior-senior yang aku hormati: pentolan band pop Jirapah, Mar Galo, untuk menjadi penata suara, serta PR manager, Maya, yang telah sering bekerja sama denganku untuk liputan-liputan konser di masa lalu.
Aku segera menyadari bahwa salah satu hal pertama yang dilakukan kurator adalah menggali kontak dari jejaring pertemanan yang tak sadar aku bangun setelah bertahun-tahun bersenang-senang di skena. Kumpulan kontributor yang aku ajak adalah gabungan antara teman-teman main yang aku kenal dari Jogja, serta mereka yang menerimaku kini di Jakarta.
Secara umum, aku membagi kontribusi mereka menjadi dua: perihal kota dan perihal panggung.
Di kategori kota, ada Kathleen Malay, filmmaker yang berkenalan denganku di Jogja sepuluh tahun lalu ketika dia masih aktif dengan unit eksperimental Ora Iso. Kathleen merekam sebuah soundwalk berisi suara-suara kehidupan Jakarta yang membuatmu merasa seakan sedang berjalan di antara labirin perkampungan. Rugun Sirait, juga berkenalan denganku di Jogja circa 2016 ketika ia masih mahasiswa dan aktif di kolektif Terror Weekend, mengajak kita merenungi frasa “Jakarta Keras” yang tidak hanya mencerminkan beratnya hidup tapi juga bisingnya deru mesin kota ini. Maezara, rekan kerjaku di New Naratif, menyetor setumpuk foto analog yang ia ambil di Jakarta dan sekitarnya—memantikku untuk menulis satu cerita pendek mengenai satu akhir pekan yang dijalani seseorang seperti dirinya: muda, tinggal di Jakarta, dan punya kehidupan sosial yang berpusar pada musik.
Di kategori panggung, Dymussaga mengajak kita berjalan kaki dari stasiun MRT Fatmawati ke Rossi Musik, sembari merenungkan geliat resistensi yang ditunjukkan oleh kolektif-kolektif kecil yang membuat acara musik sendiri. Musisi metal/punk Saifulhaq membagikan tuntunan lengkap untuk kolektif-kolektif bawah tanah yang menjadi tuan rumah bagi band-band dari seluruh dunia yang sedang tour dan ingin manggung di Jakarta. Sementara, Aghnia, seorang pekerja kantoran, mengabadikan tempat-tempat di Jakarta yang menjadi pusat kegiatan penggemar musik seperti dirinya: venue yang kita semua cintai, Toba Dream dan Rossi, tempat nongkrong inklusif Kongsi 8, juga pasar-pasar tempat kita berburu kaset dan plat. Peter G. Y. Rumondor, fotografer panggung favoritku sebelum dia fokus jadi atlet, membagikan foto-foto konser yang hangat dan intim. Anida Bajumi, salah seorang paling omnipresent di skena musik Jakarta, mempersilakan kita mengintip isi folder video di telepon genggamnya, membeberkan momen-momen paling hangat dari konser-konser yang ia hadiri. Kumpulan footage itu dijahit oleh Robonggo menjadi sebuah montase, sebuah tribut yang intim untuk komunitas yang kita hidupi.

Photo via Peter G. Y. Rumondor

Photo via Peter G. Y. Rumondor

Photo via Peter G. Y. Rumondor

Photo via Peter G. Y. Rumondor

Photo via Peter G. Y. Rumondor

Photo via Peter G. Y. Rumondor
Selain itu, proses ini juga membuatku mengobrol panjang dengan teman lamaku, Dania Joedo, yang aku kenal sejak band-band kami sering berbagi panggung di Jogja di dekade 2010-an. Obrolan ini mengisi banyak lubang penasaranku mengenai dirinya yang akhirnya melela sebagai transpuan dan kini aktif menjadi aktivis HAM. Aku juga berkesempatan mengobrol dengan musisi yang albumnya sering aku dengarkan berulang-ulang, Haikal Azizi, figur di balik moniker Bin Idris, soal kehidupannya sebagai anak Betawi asli.
Semua nama yang kusebutkan di atas adalah orang-orang yang kerja-kerjanya aku kagumi dan kepribadiannya aku sayangi. Sepanjang trimester kedua 2025, ketika karya-karya mereka mulai dikumpulkan untuk dijahit menjadi satu seri NCS, aku kerap tersungkur dalam syukur bahwa orang-orang hebat ini bersedia melakukan ini denganku—orang yang belum pernah jadi kurator dan mengerjakan semuanya sembari berdoa semoga aku tidak mengecewakan.
—
Seri publikasi digital NCS: Jakarta Whispers akhirnya rilis pada 27 Agustus 2025. Sehari setelahnya, demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta. Affan Kurniawan, pengemudi ojol berusia 21 tahun, dilindas kendaraan lapis baja oleh anggota Brimob di depan gedung DPR pada. Tragedi ini disusul kemarahan kolektif membara, dan memantik tindakan makin represif dari aparat gabungan Polisi dan TNI. Sejumlah nama lain meninggal, hilang, ditangkap, digebuki aparat.
Sebagian besar kontributor dan rekan kerja di NCS: Jakarta Whispers akhirnya melakukan aksi protes lewat kantong-kantong aktivis masing-masing. Dengan wajah cemong-cemong kena pasta gigi yang dipercaya bisa meredam perih gas air mata, kita turun ke jalan—melontarkan ekspresi kemarahan di titik-titik aksi di DPR, Polda Metro Jaya, dan Markas Brimob di Kwitang.
Thesis yang berulang-ulang diserukan oleh para kontributor dalam seri NCS: Jakarta Whispers, bahwa gerakan komunitas musik bisa menjadi perwujudan resistensi, kembali terbukti seminggu kemudian. Di hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 September berbagai venue di penjuru kota Jakarta menjadi tuan rumah mendadak untuk acara-acara musik kecil, alternatif dari festival besar yang tercemar sponsor perusahaan tambang.
Hampir semua rekan kontributor NCS: Jakarta Whispers terlibat dalam munculnya konser-konser kecil itu: menjadi inisiator, organizer, band yang manggung, dan penonton. Aku datang ke konser dadakan di Krapela pada Sabtu siang sebagai penonton, mendapati tempat itu sudah penuh sesak dengan kawan-kawan kegelapan yang bersikeras untuk bersenang-senang di siang hari bolong. Ada yang hangat dari perasaan menolak dijajah bersama-sama, dan mengekspresikannya dalam suara.
View this post on Instagram
Tidak akan ada habisnya jika kita mencoba untuk terus-terusan merenungi dan memahami “suara”—baik dalam artian bunyi, musik, atau opini politik. Menggarap NCS: Jakarta Whispers, aku menyadari adalah mustahil untuk merekam dan menyajikan representasi menyeluruh bagi kota yang punya banyak wajah dan suara ini. Empat belas karya, ekstraksi dari berbagai komunitas gorong-gorong di sudut-sudut Jakarta yang terangkum dalam kolase ini adalah wajah dan suara Jakarta seperti yang kunikmati dari sudut pandangku: bisik-bisik yang lantang dan menggelegar dan menolak dibungkam.
—
NCS: Jakarta Whispers akan mengadakan release party-nya pada Sabtu, 27 September 2025, di Kios Ojo Keos.
Akan menghadirkan dua sesi Artist Talk:
1. Creating Safe Space for Women and Queers in Music Events: Gisela Swaragita with Anida Bajumi, Diedra Cavina, and Dymussaga;
2. A Guideline for Organizing Underground Touring Bands in Jakarta: Dymussaga Saifulhaq with Januar Kristianto.
Serta dua penampilan live dari Rabu dan Bin Idris. Sila berkunjung.












