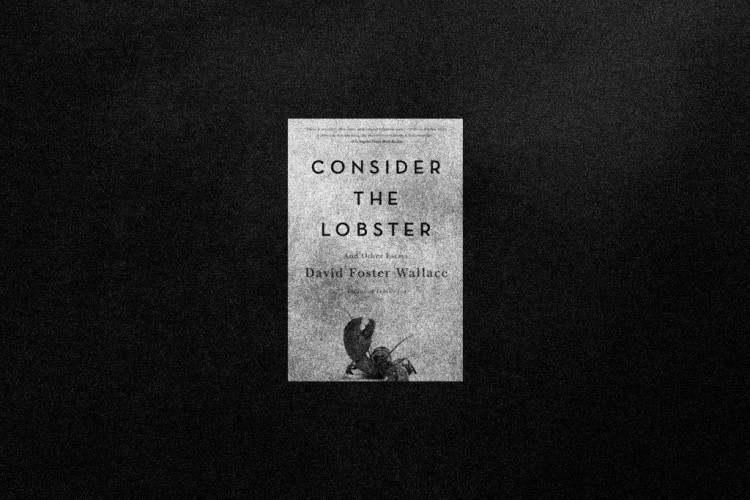Kepada Bapak
Pada submisi column kali ini, Dhibja Purwahananta menuangkan bagaimana kesempatan berdamai dengan duka oleh kematian dan perpisahan.
Words by Whiteboard Journal
Menyoal kehidupan dunia, banyak bab yang paling tidak pernah saya sukai. Seyogyanya manusia ketakutan pertama adalah kematian dan kedua perpisahan yang sama-sama merujuk pada termin ditinggal. Tentang kematian begitu jauh waktu berjalan ingatan tentang ujaran salah seorang kawan, yang harus mulai dibiasakan dengan seiring bertambanhnya usia adalah kehilangan sosok yang dekat atau hadir di pemakaman dan berdoa di nisan yang diberi nama. Begitu sial beberapa bulan kemudian seseorang yang sangat saya cintai pergi orang yang menurut saya segalanya di hidup, saat menerima kabar beliau sedang bertaruh di kehidupan kekal, yang bisa saya rasakan hanyalah sakit kepala “Masa sih, bapak udah ga ada lagi”. Rasanya aneh, gak sink in. Nalar seolah tidak bisa memproses the fact that he’s gone dan dalam rentang beberapa kala ke depan perubahan yang besar akan timbul.
Kematian merupakan duka dan pedih. Bukan hanya bagi mereka yang menjalani prosesnya (we all know the story of how painful death is according to religion) melainkan juga bagi mereka yang ditinggalkan. Maka jika ada yang berujar kematian adalah hikmah dan bagian perayaan dari hidup, telan bualan sampah itu! Cukup berhenti di sana tak ada tafsir yang harus didebatkan lagi. Ia merampas segala kesempatan berdamai dengan duka.
Seiringnya perpisahan hadir di hidup, membuat saya sadar bahwa kita hanyalah manusia yang fana dan seolah harus berjalan searah dengan yang dikangkangi kitab. Beberapa perpisahan memang harus dirayakan dengan suka cita, lantas sisanya? Getir, pilu jika harus diungkapkan. Jikapun mungkin sebagianya masih bisa bertatap ada kalanya juga suasana duka yang sama seperti melarung kematian dan sialnya suasana itu akan menjadi ajang panjang yang harus betah seumur hidup karena tak kunjung menemukan damai.
Rasanya memang banyak uncertenties, dimulai dengan pekan yang harusnya menyenangkan, berjalan buram sebab perihal yang tak akan saya tuliskan rincinya karena terlalu tengik dan anyir untuk dibaca. Kabar dari sebuh pesan WhatsApp tiba menghantarkan kepergian Bapak ke surga adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan dan harus saya hadapi di awal dekade kedua perkuliahan saya. Bagi saya Bapak adalah nyala dalam rumah, tanpanya semua gelap tak ada binar, tak ada bahana. Harusnya Bapak lestari di sana sebagai pengingat bahwa berpegang teguh dan berani memiliki sikap adalah sebuah kemewahan. Bapak adalah figur yang menjaga teguh integritas. Sayang mungkin Bapak terlalu berkilau untuk abadi di antara serakan kotoran anjing, sehingga anjing-anjing itu tak nyaman akan kehadiran Bapak.
Biarkan akal saya berjalan merepetisi lagi momen-momen bersama Bapak, saya masih ingat betul bagaimana dalamnya nurani beliau mendidik saya, daya upaya juga kucuran keringat yang melewati kening beliau untuk saya, saling mengingatkan saling beradu argumen. Tanpa beliau mungkin tak ada momen yang berkesan, saya juga melihat Bapak sebagai sosok luar biasa. Ia bisa hidup prasojo saat kumpulan anak adam lain fokus pada ego diri. Beliau keras, alot dalam pelbagai hal. Hingga hari berganti minggu berganti bulan sampai tahun, menjadi dewasa dengan kedekatan satu step dibawah dekat adalah penyesalan yang hingga kini membayang-bayangi, saya tidak terlalu dekat dengan Bapak. Ketidak dekatan itu berangkat dari tumbuh dewasa, kami hanya bersama namun jarang bercakap. Dulu problema mengenai hidup, beberapa hal pribadi sering saya ceritakan kepada Bapak dan tentu Bapak tidak pernah mengeluh atas cerita yang saya sampaikan, justru berpuluh saran Bapak sampaikan dan saya masih konsisten menjadi orang yang bebal. Seperti luka yang membekas, ingatan akan Bapak membuat saya merasa terkutuk dengan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan keluarga saya sendiri. Sedih menilik kenangan beliau, Bapak seolah tidak dituliskan abadi sentosanya temporer belaka, semua demi kami, saya, ibu dan adik-adik saya.
Mungkin ini hanya saya yang bebal dan terlampau banyak keluputan yang saya perbuat sebagai anak, mencoba membenarkan sesuatu dan malah merusaknya. Satu dari sekian kecerobohan yang harusnya membuat Bapak kesal, toh Bapak selalu memaafkan. Masih banyak seharusnya kecerobohan saya yang seharusnya bisa menjauhkan saya dari Bapak, kenyataanya Bapak selalu ada di sini . Luput dari benak saya, Bapak selalu diam jika mungkin memiliki masalah, Bapak selalu berhasil dalam memendam lara, seolah tak mau membebani anak-anaknya. Bapak selalu kuat.
Akan ada banyak hari berkelindan dengan kepura-puraan yang lekas membawa saya menjadi munafik kalau saya tidak pernah kesal bahkan marah dengan sikap atau perbuatan Bapak, selayaknya seorang anak. Hidup dalam kondisi saat ini sama sekali tidak mudah. Semuanya seperti perjudian. Apakah kita mendapat jackpot atau gagal. Namun kita masih harus melanjutkan ataupun lebih memilih tidak.
Setelah kepergian beliau, hari yang akan saya temui mungkin tidak akan lagi sama. Ada porsi yang harus diisi kembali, duka dan getir yang menetap, mungkin selamanya. Kehidupan harus tetap berjalan serta dendam yang tumbuh karena perpisahan akan saya semai tiap harinya, saya orang yang besar dan hidup di atas dendam.
Barangkali ada saatnya waktu terasa berjalan mundur, ingin saya kembali bertemu Bapak dan merenggut semua ilusi yang saya impikan. Kabarnya kembali seperti tafsir dendam menahun yang suarnya tak akan nyala. Saya akan sangat merindukan sosok Bapak. Di sini air mata saya bergelinang, untung sebelah saya kosong jadi saya tak harus malu menjadi cengeng.
Terakhir, sekiranya sudah cukup tak ada lagi yang harus saya sampaikan ke Bapak. Saya tak sanggup untuk larut lagi dalam rutinitas. Entah akan ada apa lagi setelah ketiga tahun ini, tapi sekali lagi saya harus terbiasa, saya harus kuat demi Ibu, adik-adik saya dan juga utamanya untuk Bapak.
–
Ditulis di antara perjalanan Surabaya-Malang, Bus Menggala jam 19:00, saya harap Malang hujan sehingga air mata bisa beradu dengan air hujan.