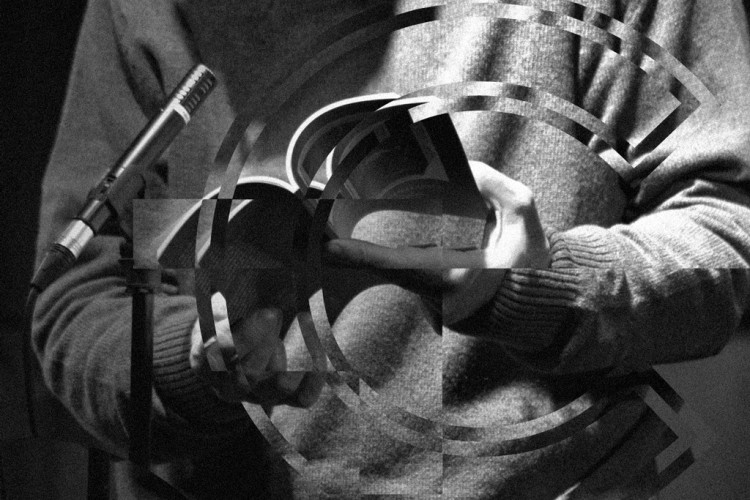Kegagalan Desain dan Segala Hal yang Membuat Kita Meninggalkan Rumah
Dalam submisi column ini, Adli Dzil Ikram menelusuri muasal keputusan orang-orang untuk pergi meninggalkan rumah. Selain ada faktor-faktor seperti ketidaksesuaian nilai, penelusurannya menunjukkan kegagalan desain arsitektur juga berperan bagi suasana rumah yang tidak nyaman.
Words by Whiteboard Journal
Pandemi membuat saya jadi banyak menonton drama Korea Selatan. Selain temanya yang sangat beragam, ceritanya unik dan terkadang juga susah ditebak. Serial yang terakhir saya tonton, “Our Beloved Summer”, bercerita tentang kisah sepasang mantan kekasih yang sebenarnya masih saling mencintai dan dipertemukan kembali dalam sebuah pembuatan film dokumenter.
Ceritanya sederhana namun begitu menarik. Karakter Choi Woong yang diperankan Choi Woo-shik, adalah seorang pelukis. Ia suka mengambar gedung-gedung yang didesain oleh arsitek kesukaannya. Dari gambar-gambar itu ia menghasilkan banyak uang. Si pelukis tinggal sendiri di sebuah rumah, dengan studio bawah tanah yang mewah. Padahal, rumah orang tuanya tidak jauh dari tempat itu. Ia adalah anak satu-satunya dan kedua orang tuanya bekerja di restoran milik mereka sendiri.
Keadaan itu membuat saya bertanya-bertanya, mengapa ia memilih tinggal sendiri? Mengapa banyak orang meninggalkan rumah dan kampung halamannya setelah tumbuh dewasa?
Beranjak dari situ, dalam setiap kesempatan, saya banyak bertanya kepada teman dan orang yang saya temui tentang keputusan mereka meninggalkan rumah. Rumah yang saya maksud adalah tempat kita dibesarkan atau rumah kedua orang tuanya beserta lingkungannya.
Sering kali orang-orang yang tinggal bersama kita (keluarga) tidak menerima kita apa adanya. Secara sadar atau tidak, mereka memaksa kita menjadi orang lain.
Teman saya Sintia (bukan nama asli) bercerita tentang dirinya yang tak pernah mau pulang ke rumah. Baginya, rumah adalah pengadilan yang tak pernah adil. Setiap perilaku dan keinginannya akan selalu dihakimi oleh orang tua dan di lingkungan tempat asalnya. Ia dipaksa untuk mengikuti kemauan mereka dan tak bisa menjadi diri sendiri. Bahkan, keluarganya akan menatap sinis saat ia membaca buku di dalam rumah.
“Kau tahu aku kan,” katanya sambil mengikat rambut panjangnya. “Saat di rumah aku tidak mungkin begini.”
Saat ini ia menyewa kamar kos bersama teman-temannya di perantauan. Ketika saya menanyakan kapan ia akan pulang ke rumah, dengan sedikit tertawa dan mengeluarkan asap dari mulutnya ia menjawab, “Lebaran!”
Apa yang dialami Sintia merupakan gambaran bagaimana ideologi bekerja di dalam rumah. Ia tertanam rapi di dalam kepala si pemilik. Karena punya kuasa, ia berhak mengatur apa saja. Misalnya, seorang ibu melarang anaknya membeli boneka atau patung dan membawanya masuk ke dalam rumah. Seorang kakek secara tiba-tiba menghancurkan kloset di kamar mandinya karena letaknya menghadap kiblat. Seorang ayah marah karena di meja makan tidak ada makanan kesukaanna.
Sebagai anak kecil mungkin kita akan mengikuti apa-apa yang dilarang, karena takut dimarahi. Namun, ketika tumbuh dewasa, masing-masing kita memiliki ideologi dan penilaian sendiri yang kita dapat dari luar rumah; sekolah, kampus, tongkrongan, pengajian. Hal itu bisa berseberangan dengan ideologi di dalam rumah. Semua tergantung lingkungan mana yang didatangi, di mana ia tinggal, atau apa-apa saja yang menyangkut di kepala si anak.
Tapi, hal ini tidak saja terjadi pada seorang anak, namun juga kepada seorang istri atau sebaliknya. Ada banyak sekali cerita di mana istri ketakutan ketika berada di rumah karena perilaku suaminya yang kasar. Benturan-benturan seperti itulah yang membuat si anak keluar dari rumah dan sekian banyak alasan perceraian terjadi.
Kepada Farhan, saya menanyakan mengapa ia menyewa rumah bersama anak-istrinya berdekatan dengan tempat kedua orang tuanya tinggal.
“Ada nilai berbeda antara yang aku anut dan ibu, dalam hal mendidik anak. Aku ingin belajar mendidik anak dengan baik, dan membiarkan dia tumbuh dengan percakapan ibu dan bapaknya. (Pindah) juga karena rumah orang tuaku terlalu dengan jalan raya, ribut,” jawab Farhan.
Jawaban Farhan menggambarkan keinginannya memiliki kenyamanan di dalam rumah dan berusaha memasukkan nilai-nilainya sendiri di dalam rumah. Farhan juga bercerita tentang adiknya yang memilih merantau agar bisa menganggap rumah sebagai tempat untuk pulang. Karena, jika di kampung halaman, ia hanya mengangap rumah sebagai tempat singgah. Pergi pagi, pulang malam untuk tidur.
Siapa saja bisa membangun rumah mewah, berlantai dua, keramik marmer, halaman luas, hingga kolam renang. Namun, tak banyak orang yang berhasil membangun keharmonisan di dalamnya. Pada akhirnya, rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat untuk pulang. Di dalam rumah, percakapan dan penerimaan terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam setiap individu harus terjadi. Jika para penguasa di dalamnya tak ingin ditinggalkan.
Selain ideologi, kegagalan desain adalah hal lain yang juga membuat kita menjauhi rumah. Awal tahun 2020, saya bertanya pada Paras, seorang teman yang menggiati seni dan budaya. Saya bertanya mengapa menghabiskan waktu berjam-jam di warung kopi? Ia menarik napas dan memandang dalam-dalam pada suatu sudut. “Rumahku panas, hawa panas membekas di dinding hingga malam.”
Suatu hari, saya berkesempatan berkunjung ke sana. Katanya, rumah yang ia tinggali sendirian itu didesain oleh seorang arsitek. Ada tiga kamar: kamar pertama dan kamar kedua serta mushola mengapit ruang keluarga. Sedangkan kamar ketiga bersebelahan dengan garasi, dapur dan kamar mandi. Rumah itu belum dicat sehingga ada bekas plesteran semen di beberapa sudut dinding.
Saya masuk ke rumahnya. Matahari cukup terik di luar dan telah melewati kepala manusia. Di atas ruang keluarga, tempat ia mempersilakan saya duduk, ada sepetak genteng yang sudah berkarat untuk menutupi ruang keluarga dari matahari. Saya bertanya soal genteng itu dan ia menjawab dengan cita-cita ibunya, “genteng itu hanya penutup sementara, nanti jika punya uang lebih akan dibangun lantai dua.” Artinya, tangga menuju lantai dua akan diletakkan di sana nanti.
Baru beberapa menit di dalam rumah Paras, leher saya sudah mengeluarkan keringat. Mata saya memandang ke arah dinding berlumut di dekat jendela yang menghadap ke pagar ketika ia membuka pintu kamarnya. Lumut di dinding itu berasal dari air hujan yang mengalir dari genangan di lantai dua. Kini, pengakuannya saat di warung kopi masuk akal. Wajar saja kamar itu panas karena tidak memiliki ventilasi udara meski ada kipas angin di sana. Mungkin, awalnya diniatkan menggunakan AC.
Selain tak pernah betah di rumah itu karena panas. Paras mengaku tak bisa bekerja ataupun beristirahat ketika siang hari. Ia akan pulang jika hari sudah gelap. Dan akan pergi lagi jika pagi tiba. Karena begitu, ia juga mengaku beberapa jadwalnya berantakan dan kesehatan tubuhnya terganggu. Ia tak mendapatkan istirahat yang layak.
Jocye Marcella dalam bukunya “Arsitektur dan Perilaku Manusia”, menulis bahwa sebuah desain arsitektur bisa menjadi salah satu fasilitator terjadinya perilaku, namun juga bisa menjadi penghalang terjadinya perilaku.
Di masa pandemi Covid-19 sedang ganas-ganasnya, rumah dijadikan tempat bekerja. Tapi rumah Paras melarangnya bekerja di sana. Seakan-akan beton raksasa itu menyuruh untuk selalu pergi, tak peduli virus di luar sana. Makanya, ketika bangun dari tidur ia akan langsung pergi dari sana, menuju kedai kopi langganannya. Pada akhirnya, Covid-19 pernah menyerang tubuhnya dua kali.
Romo Mangunwijaya dalam bukunya “Pengantar Fisika Bangunan” mengatakan, rumah yang kelihatannya mahal bisa saja tidak mahal. Sebaliknya, rumah yang kelihatan murah bisa saja lebih mahal dari pada rumah yang kelihatannya mahal. Para arsitek yang baik akan memperhitungkan segala persoalan dan kemungkinan buruk, lalu menyiapkan rencana untuk menghadapinya. Bukankah para perancang dibayar untuk itu? Seperti dokter, para arsitek dibayar untuk mengobati sebuah ruang, yang kadang berhasil dan kadang tidak sama sekali!
Namun, terkadang para klien, sebagai orang yang memiliki modal, sulit mendengarkan arsitek atas saran-saran untuk rumah mereka. Ini juga bentuk dari kuasa. Bagi saya, kegagalan desain juga menjadi alasan orang meninggalkan rumah dan hal itu sedikit banyak mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Siapa yang betah tinggal di rumah yang tak nyaman?
Di antara ideologi, kuasa, dan kegagalan desain yang menyebabkan orang meninggalkan rumah, barangkali, ada banyak alasan lain. Ketiga hal itu hanya bagian dari bermacam-macam yang berhasil saya tangkap.