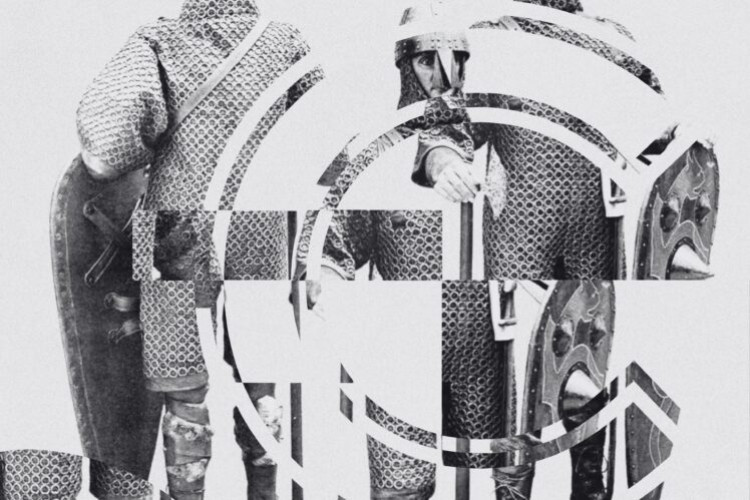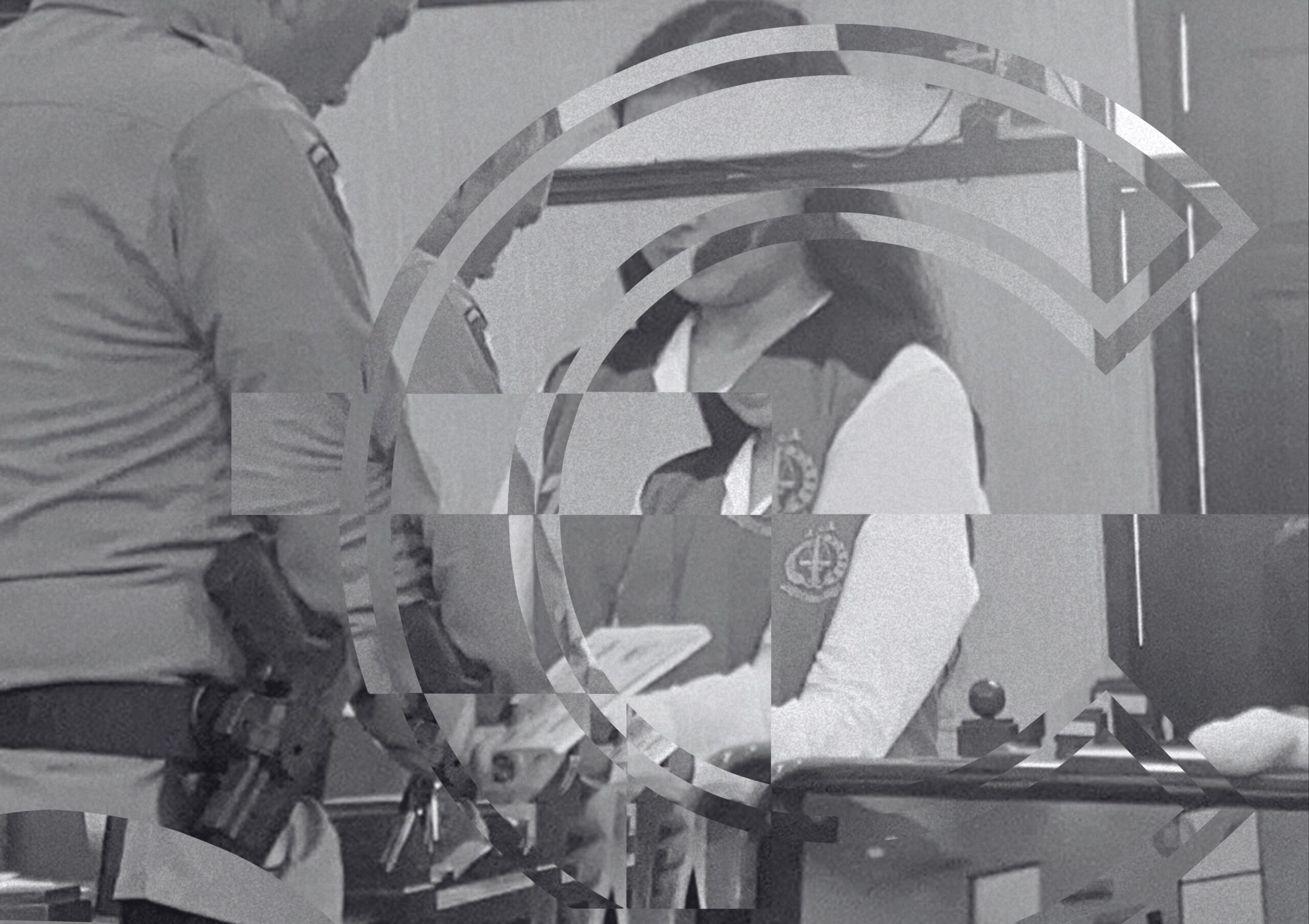
Jika Majelis Hakim Menjatuhkan Vonis Bersalah Pada 60 orang Tahanan Politik di Jakarta Utara
Dalam submisi Open Column ini, Eno Liska Walini menyibakkan realita di ruang sidang, realita yang dihadapi keluarga korban tahanan politik, yang mana memperjelas vonis-vonis yang memperlihatkan keberpihakan hukum yang selalu jauh dari kita.
Words by Whiteboard Journal
“Anak kecil tidak boleh masuk”, kalimat itu diucapkan dengan lugas oleh petugas di dalam ruang sidang perkara 60 (enam puluh) orang tahanan politik pasca Aksi Agustus Kelabu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Seorang Ibu yang sudah hampir lima bulan tidak tinggal serumah dengan suaminya hanya mengangguk, sambil menggendong bayinya yang baru berusia tiga bulan tanpa kehadiran seorang Ayah. Bayi itu ditinggalkan di luar, sementara ayahnya diadili di dalam.
Momen ini sebetulnya sudah cukup untuk menjelaskan persoalan perkara ini. Ketika seorang anak harus dijauhkan dari ruang sidang agar tidak melihat bagaimana ayahnya diadili, sementara negara tidak pernah sungguh-sungguh memeriksa cara penangkapan, penahanan, dan kekerasan yang menyertainya. Pikirku, mungkin memang sudah tepat anak-anak tidak boleh masuk ke ruang sidang. Bukan karena mereka belum cukup umur, melainkan karena kesucian hati mereka belum seharusnya dipaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa ruang sidang yang konon disebut tempat mencari keadilan justru kerap menjadi panggung telanjang tempat keburukan sistem yang sengaja dipelihara dipertontonkan tanpa rasa malu.
Dampak dari cara kerja sistem itu terlihat paling nyata pada orang-orang yang hadir di ruang persidangan, keluarga yang harus terhenti sumber penghidupannya pasca penangkapan. Setelah sebelumnya mereka juga dipaksa mencari sendiri informasi tentang nasib sanak keluarga mereka: menyusuri rumah sakit, mendatangi kantor polisi, menghubungi hotline bantuan hukum, dan berpindah dari satu kantor ke kantor lain tanpa pernah mendapat penjelasan yang utuh soal apa yang terjadi pada sanak keluarga.
Begitu pula setelah penangkapan, akses diputus; keluarga sempat tidak diizinkan menjenguk selama berminggu-minggu, tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan informasi yang sampai justru potongan-potongan paling menyakitkan: foto luka yang beredar dan kabar kondisi fisik yang memburuk. Bahkan tanpa memahami teori dan hukum sekalipun, mereka tahu satu hal yang pasti: anak mereka mengalami kekerasan, dan kekerasan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Saya ingat betul pertemuan pertama dengan beberapa keluarga di kantor kepolisian, yang terlihat bukan kemarahan yang meledak, melainkan kesadaran sunyi bahwa sesuatu yang salah telah terjadi, sementara sistem hukum memilih untuk tetap berjalan dan enggan dikoreksi.
Di persidangan, para terdakwa berkali-kali menyampaikan keterangan tentang apa yang mereka alami selama penangkapan dan pemeriksaan: pemukulan, ancaman, penyiksaan. Luka-luka itu tidak bersifat abstrak; ia tampak, terdokumentasi, dan dibawa ke ruang sidang. Bahkan ada satu terdakwa yang harus menjalani operasi berat akibat cedera serius dan memakai kursi roda dengan nanah yang terus mengalir dari kakinya pada saat sidang berlangsung.
Pada titik ini, perkara ini tidak lagi bisa dibaca sebagai kasus pidana biasa. Ia memperlihatkan cara kerja sistem peradilan pidana yang tidak memiliki mekanisme untuk berhenti dan mengoreksi dirinya sendiri. Kekerasan oleh aparat tidak menghentikan proses. Penahanan berkepanjangan tidak memicu evaluasi meski di depan mata ada ada pengakuan yang disampaikan begitu lantang oleh puluhan korban. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengoreksi kesaksian belasan anggota polisi yang terdengar tidak konsisten.
Hemat saya, perkara ini terus berjalan bukan karena kuat secara hukum, melainkan karena setiap institusi memilih tidak menghentikannya.
Ketika penyidikan bermasalah, polisi tidak menghentikan perkara dan justru melimpahkannya ke jaksa. Saat jaksa meragukan berkas perkara, ia tidak mengembalikannya melainkan memilih meneruskannya ke persidangan. Di pengadilan, hakim pun tetap melanjutkan pemeriksaan. Seolah-olah setiap institusi berasumsi bahwa kesalahan di tahap sebelumnya akan “diselesaikan” di tahap berikutnya, seolah-olah kekerasan itu harus dibuktikan dahulu oleh korban penangkapan yang sudah jelas tidak berdaya di bawah kuasa aparat. Tidak ada satu pun institusi yang benar-benar mengambil tanggung jawab untuk menghentikan proses peradilan, dan tidak satu pun yang berani menyatakan secara terbuka bahwa perkara ini sejak awal merupakan kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Kita semua barangkali sepakat bahwa Jaksa memegang peran yang tidak bisa dianggap pasif. Jaksa bukan sekadar tukang penerus berkas dari penyidik kepolisian ke pengadilan. Ia memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan perkara, termasuk ketika terdapat indikasi kuat penyiksaan dan keraguan serius atas keterlibatan terdakwa. Melanjutkan tuntutan dalam kondisi seperti ini bukanlah keharusan prosedural, melainkan keputusan institusional dan nurani dan setiap keputusan institusional membawa konsekuensi terhadap legitimasi hukum itu sendiri.
Dan hari ini, Kamis, 8 Januari 2026, keputusan itu akhirnya mengambil bentuk paling konkret: penuntut umum menuntut para terdakwa masing-masing satu tahun penjara. Tuntutan satu tahun ini memperlihatkan dengan terang bahwa jaksa memilih untuk tidak menggunakan kewenangannya sebagai penyaring terakhir sebelum keadilan benar-benar dikorbankan. Di hadapan fakta-fakta kekerasan yang disampaikan berulang kali di persidangan, jaksa tetap berdiri pada posisi menuntut, bukan mengoreksi. Pada titik ini, tuntutan pidana tidak lagi semata soal pembuktian unsur pasal, melainkan soal keberpihakan.
Pengadilan pun tidak berada di luar persoalan. Ketika keterangan tentang penyiksaan disampaikan di persidangan, ketika kondisi fisik terdakwa menunjukkan akibat nyata dari kekerasan, hakim tidak sedang berhadapan dengan perkara biasa. Ada kewajiban untuk membaca konteks secara keseluruhan, bukan sekadar memeriksa unsur pasal secara sempit saja. Namun selama ini sistem kita agaknya terlalu sering memperlakukan fakta-fakta semacam itu sebagai sebuah gangguan, bukan sebagai sinyal kegagalan yang menuntut untuk segera dikoreksi.
Selain itu, selama berbulan-bulan penahanan, permohonan penangguhan tidak kunjung dikabulkan. Para terdakwa tetap berada di balik jeruji, meskipun perkara mereka dipenuhi kejanggalan dan keraguan. Pada saat yang sama, pelaku kejahatan serius yang membunuh Affan Kurniawan, Iko Juliant Junior, Andika Lutfi Falah, Rheza Sendy Pratama, dan pelaku kekerasan terhadap ribuan massa aksi lainnya masih bisa bebas berkeliaran dan duduk manis di teras rumah. Sulit untuk menyangkal, bahwa dalam perkara ini hukum sedang salah memilih siapa yang seharusnya diseret ke ruang pengadilan dan siapa yang seharusnya butuh perlindungan dan pemenuhan hak.
Padahal prinsip hukum pidana sejak lama mengingatkan: lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Prinsip ini bukan slogan moral semata, melainkan pagar pembatas kekuasaan negara. Namun dalam perkara ini, prinsip tersebut tampak kehilangan daya kerjanya. Penyiksaan tidak menghentikan proses. Penahanan berkepanjangan tidak memicu evaluasi. Ketidakadilan tidak dianggap cukup serius untuk mengubah arah.
60 orang tahanan politik di Jakarta Utara tidak sedang meminta keistimewaan. Mereka tidak menuntut belas kasihan, apalagi kekebalan hukum. Yang mereka bawa ke ruang sidang hanyalah satu kenyataan: bahwa proses hukum yang mereka jalani sejak awal dipenuhi kekerasan, kejanggalan, dan penyangkalan terhadap hak-hak paling dasar. Fakta inilah yang sesungguhnya sedang diuji.
Jika majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan vonis bersalah, maka yang ditampilkan bukanlah wajah hukum yang berani jujur untuk mengoreksi diri, melainkan wajah lama yang kita kenal: yaitu hukum yang hanya tampak rapi dalam prosedur, tenang dalam menjatuhkan pidana, dan setia pada kekuasaan meski keadilan telah lama menjadi sebuah mitos.
Putusan semacam itu tidak hanya berbicara tentang 60 orang tahanan politik di Jakarta Utara, tetapi tentang pesan yang disampaikan negara kepada warganya: bahwa bersuara dapat berujung penjara, dan bahwa kekerasan dapat disucikan selama dibungkus oleh aturan dan perintah kekuasaan.