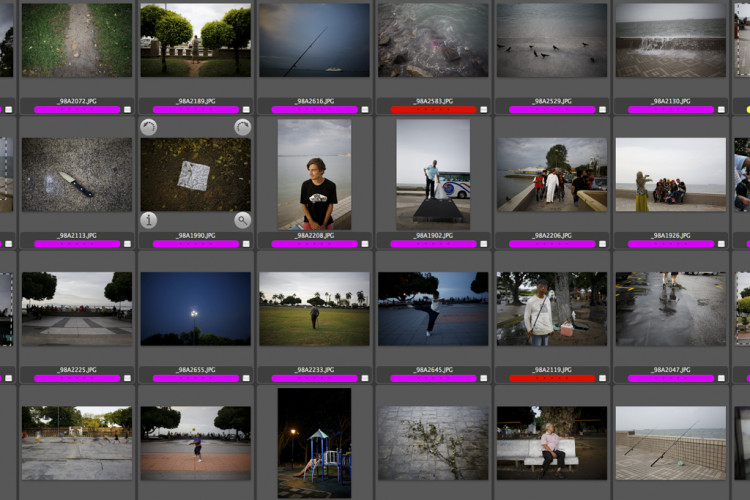Ada Logika Patriarkal di Balik Industri Ekstraktif
Dalam submisi Open Column ini, Cinta Marezi memperlihatkan bagaimana ada satu driving force dalam ekonomi dan industri ekstraktif yang, selain merusak ekologi, juga mempersempit ruang hidup perempuan: logika ketidakadilan gender yang berlandaskan patriarki dalam model tersebut.
Words by Whiteboard Journal
Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat belakangan ini kembali membuka mata publik. Peristiwa tersebut bukan semata-mata musibah alam, melainkan berkaitan erat dengan kerusakan ekologis akibat ekspansi perkebunan sawit yang masif di Pulau Sumatra. Kayu-kayu gelondongan yang terseret arus banjir menjadi penanda nyata bagaimana industri ekstraktif berkontribusi besar pada kehancuran lingkungan dengan manusia sebagai aktor utamanya. Tim Jurnalisme Data Kompas mengungkap hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat selama 1990–2024 hilang rata-rata 36.305 hektar per tahun.
Ada alasan utama industri ekstraktif terus didukung, yaitu motif pertumbuhan ekonomi. Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di poin kelima mendorong hilirisasi dan industrialisasi—sebuah upaya yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peneliti Senior Populi Center, Ratri Istania dan tim dari Institute for Advanced Research (IFAR) Atma Jaya dalam penelitian terbarunya yang masih berjalan mencatat bahwa saat ini terdapat 4.634 izin tambang yang mencakup wilayah seluas 9,1 juta hektar di Indonesia (Jurnal Perempuan, 2025).
Ratri juga menyatakan dalam pengantar di penelitiannya tersebut, ekspansi diperkuat saat masa pemerintahan Prabowo–Gibran yang mengedepankan hilirisasi tambang dengan mendorong ekspansi besar-besaran industri nikel, batubara, dan mineral lain. Industri pertambangan disebut-sebut sebagai penyumbang besar penerimaan negara dengan kontribusi mencapai Rp2,19 triliun. Ekspansi ini semakin diperkuat melalui agenda hilirisasi tambang melalui Asta Cita tersebut terutama nikel, batu bara, dan mineral lainnya yang diklaim sebagai jalan menuju target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut angka tersebut sebagai langkah awal menuju Indonesia sebagai negara maju.
Namun, apakah kita mengarah kepada kemajuan, atau malah kemunduran?
Jika berkaca dengan data dan kebijakan di atas tersebut, ekonomi Indonesia masih bertumpu besar pada proses kemampuan menghasilkan komoditas pasar global melalui hilirisasi. Pemerintah memang mengakui adanya tantangan dalam proses hilirisasi (yang tidak harus selalu hanya berfokus pada keuntungan ekonomi) tetapi juga memperhatikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola Environmental, Social, Governance (ESG) juga janji transisi energi dan pengurangan ketergantungan pada batu bara pun kerap digaungkan.
Sayangnya, dalam praktik menuju easy money ini justru sering memicu kerusakan ekologis serius dan menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat. Kerugian dalam konteks kekerasan ekologis nyaris tidak pernah masuk dalam perhitungan ekonomi negara.
Kerusakan ekologis dan menghilangkan sumber kehidupan seringkali menjadi sebuah kerugian yang tidak dipikirkan dalam sistem ekonomi negara. Hal ini sudah lama menjadi salah satu fokus kritik tokoh ekofeminis dari India, Vandana Shiva. Dalam karyanya Staying Alive: Women, Ecology, and Development, Shiva menilai pandangan mengenai produktivitas, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Barat telah dijadikan pakem universal yang kini juga dipakai di negara-negara Dunia Ketiga. Shiva juga mengkritik konsep dan kategori tentang pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang muncul dalam konteks spesifik industrialisasi dan pertumbuhan kapitalis dari Barat. Menurutnya penerapan dan konteks pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka sangatlah berbeda.
Pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai Shiva sebagai kolonialisme baru—menguras sumber daya dari mereka yang paling membutuhkannya. Selain karena produktivitas dan pembangunan dalam nilai ekonomi Barat selalu berfokus pada sebuah nilai yang menguntungkan, Shiva juga menekankan bahwa pembangunan kini merupakan penciptaan kekayaan dalam visi ekonomi patriarkal Barat modern yang selalu menyasar kepada eksploitasi dan peminggiran perempuan, eksploitasi dan degradasi alam, serta eksploitasi dan peminggiran budaya.
Logika patriarkal yang menganggap pekerjaan produktif menurut Shiva dalam konteks ekologis adalah produksi yang sangat merusak. Pembangunan dalam perspektif Barat menurutnya selalu membawa kehancuran bagi perempuan, alam, dan peminggiran budaya. Di banyak bagian Dunia Ketiga, perempuan, petani, dan masyarakat adat berjuang untuk pembebasan dari “motif pembangunan” sebagaimana mereka sebelumnya berjuang untuk pembebasan dari kolonialisme. Produktivitas saat ini dinilai oleh Shiva dengan banyaknya sesuatu yang lebih mekanis dan sebagai sesuatu yang mengantarkan kepada keuntungan dibandingkan kehidupan.
Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi = Kerusakan Ekologis dan Peminggiran Perempuan?
Industri ekstraksi sumber daya alam dalam kacamata ekofeminisme melihat bagaimana logika patriarkal berjalan—mengagungkan percepatan ada unsur dominasi, peminggiran, penindasan atas alam. Hal ini yang menjadi akar para pemikir ekofeminis lain seperti Karen J. Warren (Arivia, 2018) yang sangat yakin bahwa cara berpikir hierarkis, dualistik, dan menindas adalah cara berpikir maskulin yang telah mengancam keselamatan perempuan dan alam. Perempuan dan alam mempunyai kesamaan secara simbolik karena sama-sama ditindas oleh manusia yang berciri maskulin. Warren juga menilai bahwa selama ini alam selalu ‘difeminisasi’ dan perempuan selalu ‘dialamkan.’
Secara budaya, perempuan dan alam juga seringkali dikaitkan dengan fungsi biologis mereka dalam hal ‘penciptaan’. Sebelum abad ke-17, pengkritik environmentalisme (Tong, 1998) yang berorientasi manusia memikirkan alam secara organik—sebagai perempuan yang baik atau ibu yang mengasuh, sebagai seorang yang membagikan secara cuma-cuma yang dimilikinya secara melimpah kepada anak-anaknya. Setelah revolusi ilmu pengetahuan, kini manusia memandang alam sebagai sebuah objek pasif yang tidak hidup. Sama halnya dalam konsep subjektivitas, perempuan seringkali hanya dianggap objek pasif yang dapat ditindas.
Logika patriarkal dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini menempatkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang tunggal. Saya mencoba melihat beberapa contoh kasus yang terjadi dalam laporan Down to Earth (2003) dan Oxfam Australia (2009) mengenai Women, Communities, and Mining. Dalam laporan itu dicatat, beberapa aktivitas ekstraksi membuat perempuan dapat menderita dua kali lipat di tangan perusahaan. Mereka tidak hanya digusur dari tanah mereka, sumber daya yang menjadi dasar penghidupan mereka pun terdegradasi atau hancur, tetapi kompensasi yang ditawarkan perusahaan biasanya hanya dibayarkan kepada laki-laki, yang menyebabkan marginalisasi perempuan semakin parah.
Perempuan juga cenderung terdorong masuk ke pasar kerja berupah rendah atau bergantung pada suami yang bekerja di tambang memperkuat ketimpangan gender. Kerusakan ekologis dapat memperkuat beban kerja perempuan, mempersempit ruang hidup perempuan, mengikis kemandirian ekonomi perempuan, hingga mengarah kepada kekerasan berbasis gender.
Contoh di Nusa Tenggara, Sumbawa telah mencegah produksi gula aren, kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan oleh perempuan menyebabkan hilangnya pendapatan sekitar Rp20.000 per hari. Penambangan batu bara di Kalimantan Selatan telah mencegah perempuan memperoleh penghasilan dari perkebunan karet. Perempuan yang tinggal di dekat tambang emas Sulawesi Utara, telah menyaksikan penurunan jumlah ikan bandeng muda, sumber utama pendapatan mereka, di Teluk Buyat tempat perusahaan tambang membuang tailing tambang di dasar laut. Perempuan Amungme yang tinggal di dekat tambang di Papua Barat, menurut laporan tersebut membuat hanya laki-laki yang menerima pembayaran kompensasi dan mengakibatkan peningkatan konsumsi alkohol, bar dan pekerja seks komersial, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Pekerjaan yang didominasi oleh perempuan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari melalui alam tidak pernah masuk hitungan ekonomi negara. Fenomena ini yang disebut oleh Shiva sebagai kurangnya pengakuan terhadap proses alam untuk bertahan hidup sebagai faktor dalam proses pembangunan ekonomi. Fenomena ini juga menjadi pengaburan isu-isu politik yang muncul dari transfer dan perusakan sumber daya, dan menciptakan senjata ideologis untuk meningkatkan kendali atas sumber daya alam dalam konsep produktivitas yang lazim digunakan. Akibatnya, semua biaya lain dari proses ekonomi menjadi tidak terlihat.
Lalu, apakah kita perlu melihat ekonomi dalam perspektif baru? Dalam lensa ekonomi politik feminis (Riley, 2008) ekonomi perlu berfokus pada penyediaan kebutuhan dan kesejahteraan manusia juga menantang model ekonomi yang hanya berfokus pada pasar dengan pertumbuhan dan akumulasi sebagai tujuan utama. Lensa ini menekankan bagaimana konsep ekonomi juga perlu berperspektif gender misal dalam tingkat makroekonomi—pembagian kerja, skala upah, kekuasaan ekonomi, dan pengambilan keputusan.
Selain itu juga dalam tingkat mikroekonomi perlu melihat berbagai aktivitas ekonomi individu dan institusional termasuk rumah tangga, pembagian kerja, peran dan tanggung jawab, akses ke sumber daya, dan pengambilan keputusan yang dipengaruhi gender. Kita perlu mendorong model pembangunan yang berlandaskan perawatan, keberlanjutan, dan keadilan gender. Jika tidak, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi nama lain dari kekerasan ekologis, peminggiran perempuan dan masyarakat adat yang terus berulang.