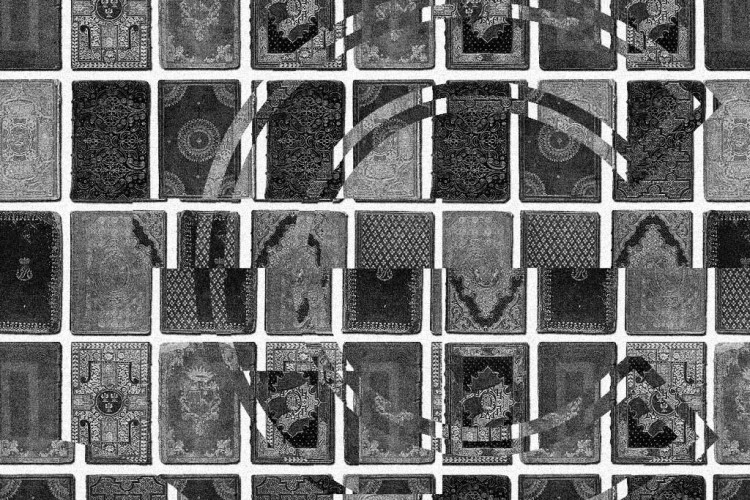Gaji DPR Selangit, Kepercayaan Kita Jeblos ke Gorong-Gorong
Dalam submisi Open Column ini, Adinan Rizfauzi menanggapi bagaimana amarah dan rasa kecewa publik terhadap pejabat publik (tak lupa juga rasio perbandingan upah antara keduanya) di hari ini tidak jauh berbeda dari apa yang dirasa oleh Serikat Buruh Kereta Api, beberapa bulan setelah Hari Kemerdekaan.
Words by Whiteboard Journal
Belum genap setahun setelah Hari Kemerdekaan, sepucuk surat bertanggal 2 Juli 1946 mendarat di meja menteri keuangan yang kala itu diemban oleh Soerachman Tjokroadisoerjo. Isinya berupa protes dari para buruh kereta api yang bernaung di bawah Serikat Buruh Kereta Api (SBKA). Mereka keberatan dengan kebijakan pemerintah yang baru saja menaikan gaji pegawai negeri golongan atas, termasuk pegawai tinggi kereta api, sebesar 45 persen.
“Menurut hemat kami, jika pemerintah mengadakan kenaikan gaji hendaklah perubahan itu merata mengenai semua golongan, dan kalau tidak mungkin, maka gologan yang paling rendahlah yang seharusnya didahulukan, tidak sebaliknya,” demikian pernyataan dalam surat yang ditandatangani Ketua SBKA Moenadi, seperti dikutip dalam buku Serikat Buruh 1945–1948: Menduduki Stasiun, Menguasai Perkebunan, Menjalankan Pabrik (2024).
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri kala itu beralasan. Pemerintah khawatir gelombang perpindahan pegawai yang kompeten di bidangnya dari wilayah republik ke wilayah yang masih diduduki pemerintah kolonial Belanda terus berlanjut. Perpindahan itu terjadi lantaran pemerintah kolonial Belanda memberi upah tinggi ke para pegawainya, jauh di atas upah yang diterima pegawai di wilayah republik.
Saat itu, ekonomi republik muda masih gonjang-ganjing. Suasana perang mempertahankan kemerdekaan juga membuat situasi makin sulit. Semua kena imbasnya, tak terkecuali para buruh kereta api, dengan pangkat tinggi maupun rendah.
Namun, kondisi kerja yang dialami tiap lapisan pekerja tentu berbeda. Buruh rendah berhadapan dengan kondisi kerja fisik yang keras, berbahaya, juga berat. Sementara pekerja menengah dan atas bekerja di kantor dengan kondisi kerja yang lebih baik. Itulah mengapa SBKA, yang anggotanya kebanyakan adalah buruh rendahan, tidak puas dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Delapan puluh tahun setelah republik merdeka, bukan hanya buruh yang menggugat keabsahan kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji, tapi juga warga dari berbagai kalangan. Kenaikan gaji kali ini menyasar ke pejabat publik, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kenaikan itu berupa tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah yang diberikan setiap bulan. Konon tunjangan itu ada karena rumah dinas yang sebelumnya bisa ditempati pada anggota dewan sudah tidak layak huni.
Bukan satu hal yang sulit dibayangkan kebanyakan orang bahwa anggota DPR punya gaji yang fantastis. Di atas kertas, pendapatan anggota DPR yang meliputi gaji pokok dan berbagai tunjangannya adalah sekitar 104 juta per bulan. Tetapi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) baru-baru ini mengungkap bahwa total penghasilan anggota DPR bisa mencapai 230 juta per bulan. Sulit mengetahui besaran pasti gaji DPR sebab tak pernah ada laporan yang transparan.
Dengan gaji sebesar itu, sialnya, mereka tetap berhasrat melakukan praktik korup. Data yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 mencatat ada 87 kasus anggota DPR yang terseret kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kebanyakan yang tersandung kasus korupsi merupakan anggota dewan yang juga berlatar belakang pebisnis.
Selain korupsi, hal lain yang patut dipersoalkan adalah tak tampaknya fungsi anggota dewan itu sendiri. Secara umum DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran. Tetapi, DPR belakangan lebih tampak menjadi tukang stempel kekuasaan alih-alih mengawasi kinerja lembaga lain. Produk undang-undang yang jauh dari aspirasi publik bisa ketok palu begitu saja. Main pangkas anggaran oleh pemerintah pun lolos tanpa perdebatan yang berarti.
Ya, kenaikan pendapatan DPR kali ini memang dilakukan ketika pemerintah baru saja melakukan “efisiensi”. Pemangkasan anggaran itu berimbas pada layanan publik. Dana transfer ke pemerintah daerah pun juga menyusut. Juga yang sulit untuk tidak geleng-geleng kepala adalah kenaikan gaji itu terjadi di tengah kelesuan ekonomi. Meski pemerintah mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi masih berada di angka 5,12 persen, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menyempitnya lapangan pekerjaan menjadi topik berita harian publik.
Namun, kita mesti berhati-hati dalam menyikapi silang sengkarut ini. Sebab, sayup-sayup ada pendapat yang menghendaki pembubaran DPR. Bukannya menyelesaikan masalah, pembubaran DPR malah berpotensi membuat kekuasaan makin terpusat. Usulan pembubaran DPR sebenarnya tidak mengagetkan. Survei yang dirilis oleh Indikator menempatkan DPR di urutan bawah sebagai lembaga negara yang dipercaya publik. Maka, usulan pembubaran DPR bisa dilihat sebagai akumulasi dari runtuhnya kepercayaan publik dan berbagai kekecewaan lain.
Walau demikian, betapapun mandul kinerja DPR dan betapapun rendah kepercayaan kita pada lembaga ini, yang dibutuhkan sebenarnya bukanlah pembubaran, tapi reformasi sistemik mulai dari demokratisasi internal partai politik tempat kader bernaung sampai perombakan sistem pemilihan umum yang saat ini menguntungkan kelompok-kelompok predatoris. Agar tak salah pilih calon, penguatan kapasitas pemilih juga tak kalah penting.
Beberapa pekan setelah surat dari SBKA dikirim, tanggapan dari menteri keuangan belum juga muncul. SBKA mencari cara lain supaya suaranya didengar, yaitu lewat Konferensi Kementerian Sosial yang berlangsung pada 27–29 Juli 1946 di Yogyakarta. Pada forum tersebut, SBKA berpendapat bahwa sebaiknya perbandingan buruh yang terendah dengan yang tertinggi adalah 1:5.
Melihat perbandingan upah yang ditawarkan oleh SBKA, kita patut bergidik ngeri ketika melihat perbandingan upah anggota DPR saat ini dengan warga kebanyakan.