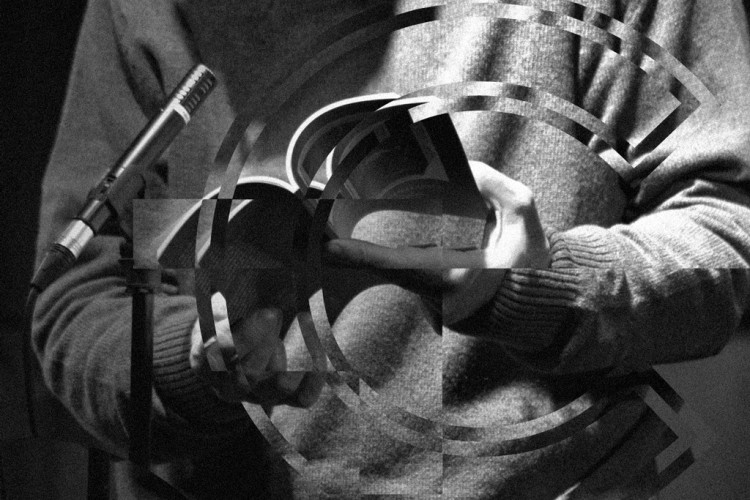Ternyata Angkuh yang Membuat Raja Lalim itu Jatuh
Dalam submisi Open Column kali ini, Muhammad Rizki Ardhana merenungkan mengenai nepotisme, kondisi politik dan runtuhnya demokrasi negara kita saat ini yang merugikan seluruh rakyat.
Words by Whiteboard Journal
Siang tadi, aku melakukan tamasya ke situs Candi Gedong Songo bersama pacarku. Kebetulan pacarku adalah seorang perempuan Sunda asal Bandung dan aku seorang Jawa tulen yang lahir di Ungaran, tempat Candi Gedong Songo ini berada. Aku mengajaknya ke sana untuk ingin mengenalkannya kepada jejak-jejak sejarah nenek moyangku (yang mungkin berbeda puluhan generasi) dan bekas-bekas kejayaan kerajaan raja-raja Jawa di zaman Mataram Kuno yang mencapai puncak keemasannya berabad-abad lalu.
Di sepanjang perjalanan yang menanjak dan disinari oleh matahari yang terik itu kami mengobrol “Kok bisa ya orang-orang zaman dulu membangun candi-candi seperti ini dengan teknologi, pengetahuan, dan akal yang serba terbatas dan ala kadarnya?” Kami kebingungan bagaimana cara mereka membangunnya dengan presisi, memakai batu-batu yang sejenis, membawa batu berton-ton tersebut ke lereng gunung, membawanya ke sembilan tempat dengan ketinggian berbeda, memahat relief dengan detail, dan menatanya dengan kokoh tanpa adanya semen dan perekat lain. Candi-candi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-7 hingga ke-9 ini masih berdiri kokoh dan kuat selama berabad-abad. Begitu juga keajaiban-keajaiban lainnya seperti Piramida Mesir, Piramida Matahari di Meksiko, Stonehenge di Inggris (yang santer dibahas oleh orang-orang merupakan buatan alien, but let’s not get into it, shall we?).
Pada saat duduk untuk beristirahat aku bilang, “Keren juga ya Raja-raja Jawa ini, seniat itu untuk membuat tempat peribadatan. Mereka membangun candi-candi ini jauh-jauh dari pusat kerajaannya yang ada di Yogyakarta sampai ke daerah sini. Membangunnya di dataran tinggi agar doa-doa mereka lebih mudah sampai ke Tuhan. Membangunnya di tempat yang sepi, suci, tempat bersemayamnya roh leluhur, agar mereka dapat berdoa dengan khusyuk.” Yah begitulah, kalau dipikir-pikir, seorang manusia jika telah memiliki keinginan yang kuat, maka segala cara pun akan ia halalkan untuk dapat mencapai keinginan tersebut, entah dengan berupaya sendiri, memanfaatkan orang lain, atau merubah sistem pun akan mereka jabani.
Singkat cerita, sesampainya di rumah, aku pun membuka hp dan membuka Instagram. Pada postingan pertama, langsung muncul warta tentang adanya upaya seseorang yang sedang melakukan aksi playing god dan berkelakuan layaknya raja dengan melakukan siasat dan jurus-jurusnya untuk mengatur dan membolakbalikkan negara sedemikian rupa. Ia layaknya seorang feodal yang hidup di negara (yang harusnya) demokrasi. Berbagai upaya telah ia lakukan untuk mendapatkan apa yang ia mau: membentuk konsolidasi elit, melanggengkan oligarki, menerabas konstitusi, mencederai demokrasi, dan menjajah saudaranya sendiri. Karena semua sudah berada di genggamannya, maka aksi yang semena-mena pun membuat ia keasyikan dan keblinger. Parahnya, sampai-sampai ada salah satu kroninya yang memanggilnya “Raja Jawa”. Dan yang lebih buruk adalah ia mengatakannya dengan bangga seolah-olah disertai dengan ancaman, seperti mengatakan, “Saya mau kasih tahu saja, jangan sekali-sekali main-main dengan Raja Jawa. Kalau kita main-main barang ini, celaka kita.”
Entah apa motif yang “raja-rajaan” ini inginkan: Membuat legacy berupa megaproyek yang megah dan mewah untuk dinikmati segelintir orang dan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat? Untuk memastikan megaproyeknya berlanjut agar tidak kepalang malu jika berujung mangkrak? Sebuah paternal instinct dari seorang ayah yang ingin memastikan keluarganya hidup enak dan anak-anaknya mendapat pekerjaan? Atau memang ego pribadi saja yang terus haus akan kekuasaan? Bagaimanapun juga, semua alasan tersebut tentunya tidak bisa dibenarkan, apalagi setelah melihat semua tindak-tanduknya dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai hal dikorbankan untuk melanggengkan kekuasaannya dan menjaga agar kepentingan pribadinya berada pada tingkat tertinggi di negara ini, lebih tinggi daripada yang katanya “kepentingan rakyat adalah yang utama.”
A man cannot play god without being acquainted with the devil. Kelakuan-kelakuan absurdnya telah membuat rakyat makin menderita. Dan sekarang ia melakukannya terang-terangan, tanpa rasa sungkan. Ia merasa berada di atas segalanya. Ia dan kroninya terlalu lama tinggal di menara gading yang membuat mereka melihat kita-kita yang tinggal di bawahnya dengan menundukan kepala dan memakai teropong, melihat kita layaknya melihat semut-semut yang sedang berebut makanan dan sekonyong-konyong bisa ia injak-injak kapan saja. Sayangnya, sekarang ia sedang melakukannya. Untungnya, kita masih bisa mencegahnya.
Tidak, kita tidak perlu sampai membaca buku The Anarchist Cookbook lalu mempraktikan dan membuat “resep-resep” yang diajarkan di dalamnya. The least thing we can do adalah dengan merapatkan barisan di media sosial kita, mengawal proses penegakan konstitusi dan penegakan hukum yang sedang berupaya digoyahkan oleh mereka, dan menjaga agar tingkah mereka on check. Sepele memang, tapi jika dilakukan oleh semua orang, maka semuanya akan terakumulasi dan terbentuk sebuah barikade yang akan menjaga semangat demokrasi dan kebebasan terus tegak di tanah air kita ini. Mari kita semua berpegangan tangan guna membentuk jembatan kebersamaan, layaknya para semut yang saling menopang satu sama lain untuk membuat sebuah jembatan yang dapat mewujudkan keinginan bersama: untuk dapat melanjutkan hidup dengan mencapai kebahagiaan kolektif dan damai antara satu sama lain.
…
Dari dua kejadian dalam sehari tersebut, saya jadi teringat sebuah puisi dari seorang penyair termasyhur dari Inggris bernama Percy Bysshe Shelley. Pada tahun 1818, ia menulis sebuah puisi berjudul Ozymandias:
“I met a traveler from an antique land
Who said: “Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert… Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them, and the heart that fed
And on the pedestal these words appear:
‘My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!’
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.”

Patung Ozymandias
Ozymandias menceritakan tentang pengalaman penulis saat bertemu seorang pengembara di sebuah gurun pasir yang menceritakan pengalamannya saat berkelana. Pengembara itu menemukan sebuah reruntuhan berupa patung raksasa yang hanya tersisa kaki saja dan kepala yang tergeletak. Wajahnya tersungkur dan terbenam separuh. Badan dan tangannya tak tahu di mana. Pada bagian tumpuannya tertulis:
“Namaku Ozymandias, Raja dari segala raja; Lihatlah hasil karyaku, wahai yang perkasa, dan berputusasalah!”
Namun, sekarang kata-kata itu hanya omong-omong belaka. Sebab, tak ada lagi kemasyhurannya, tak ada lagi kedigdayaannya. Yang tersisa hanya reruntuhan. Sebuah kepala buntung layaknya kepala Raja Louis XVI dan Maria Antoinette yg terpisah dari badannya karena mendapat sentuhan lembut dari bilah pisau guillotine kala Revolusi Prancis. Sisa-sisa kehancuran dari yang adikuasa, yang tak terbatas, dan yang paling berjaya. Tak ada lagi seruan gagah dan menggelegar sebagaimana yang terpahat pada tumpuan yang menjadi prasasti. Dan yang tersisa kini hanyalah hamparan pasir yang membentang sejauh mata memandang.
Puisi sonet ini mengingatkan para pembacanya untuk tidak menyombongkan diri. Bermakna bahwa sesuatu yang kita bangun dengan megah dan mewah sudah barang tentu akan musnah juga. Semua peninggalan yang sifatnya duniawi itu hanya akan menyisakan nama. Segala yang fana berujung menjadi omong kosong semata. Segala tetek-bengek kekuasaan bersifat sementara, tidak peduli seberapa sombong atau tiraninya seorang penguasa. Sebesar dan semasyhur apapun karya yang kita hasilkan, waktu akan merusaknya—menghancurkannya perlahan. Akhirnya, semua milik kita hanya akan terpendam dan terkubur oleh pasir menuju tempat yang amat dalam: menuju yang tak terbatas, menuju jurang kehampaan.
Pada akhirnya, keangkuhan akan memakan diri kita.
Pada akhirnya, keangkuhan akan memakan semuanya.