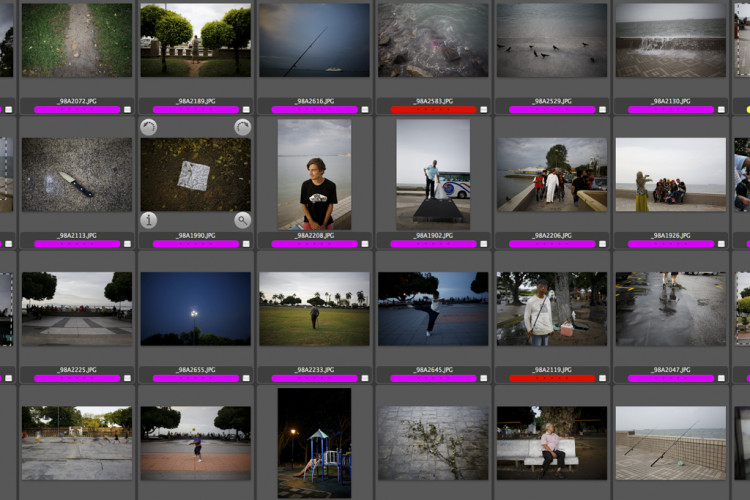Jelita,
Ingin rasanya kubuka surat ini dengan untaian kata yang indah. Mungkin dengan sebait prosa atau seuntai doa.
Percayalah jelita, maksud hati bukan untuk berkabar saat aku ingin saja. Namun apa daya, saat surat ini hendak ku tulis, jadi sudah bagian tengahnya, tanpa penutup dan pembuka. Sebab, aku merasa berdusta jika aku tanyakan, ‘Apa kabarmu?’, sedang kusaksikan sendiri ia dari ketinggian, di warung-warung makan, atau di tengah deru mesin angkutan. Meski begitu, tetap kulantunkan beribu harapan agar elok slalu paras dan jiwamu.
Sadarkah kau, jelita?
Keelokanmu selalu menjadi pusat perhatian. Baik oleh sebagian kecil yang (merasa) memilikimu, maupun sebagian besar yang tidak. Aku maklum, kemolekanmu memang membutakan bagi sebagian pemuja. Kau terlihat elok dari kejauhan, meskipun kau tak luput juga dari kekurangan.
Untuk ini, aku menyalahkan mereka, yang terlalu sempurna memuja keelokanmu hingga buta pada sisi kelam dari setiap keindahan. Bukankah cinta berarti menerima keadaanmu seutuhnya, termasuk cantik paras dan kelam lukamu? Mungkin aku naif. Tapi apa dayaku, jelita? Surat ini hendak ku tunjukkan untuk memujamu. Tak pantas kiranya aku isi dengan cerminan diri.
Jelita,
percayalah, di balik sebagian yang kecil dan sebagian yang besar, ada aku. Aku, si besar yang kecil; si kecil yang besar. Aku maklum kiranya kau tak sering mendengar namaku tersiar. Tak seperti sebagian yang kecil yang mencintaimu dengan suara, aku memilih untuk mencintaimu dalam diam.
Mengapa?
Karena, jelita, cintaku menembus elok paras dan tubuhmu (percayalah saat aku mengatakannya). Sekiranya kau anggap cintaku adalah omong kosong, percayalah wahai jelita, omong kosongku lebih besar dari omong besar sebagian mereka yang kecil.
Sadarkah kau, jelita? Elokmu membuta.
Maafkan aku, jelita.
Sungguhpun ku tak sampai hati untuk menjadikan kau seakan pengadu domba. Hanya saja, aku dan mereka, terdengar cukup konyol adanya.
Terlepas dari perbedaan yang ada, aku dan mereka, jelas sama-sama mencintaimu. Namun, mengapa sulit rasanya untuk mengakui itu? Mengapa sulit sekali rasanya untuk sadar bahwa aku dan mereka, adalah kami, kami yang mencintaimu, dengan sepenuh omongan.
Ingatkah kau jelita, bahwa cinta berarti ketulusan tanpa memiliki? Bukankah cinta berarti apapun untuk kebahagiaanmu, termasuk tanpa aku, mereka, atau siapapun tetek bengek lainnya yang dengan sengaja dibesarkan untuk mengaburkan cinta untukmu? Mengapa cinta harus memiliki? Mengapa cinta menjadi sebuah panggung retorika semata? Mengapa cinta menjadi permasalahan aku, mereka, kamu, dan bukan cinta?
Jelita,
percayalah, surat cinta ini aku tulis di bawah segala keragu-raguan. Sebab, apalah tahuku tentang cinta? Aku hanya gemar menjadi melankolis, cenderung sinis. Lantas, pantaskah aku berbicara tentang cinta? Saat aku tak mengerti sejarah, tak ikut angkat senjata, dan tak pernah ikut turun meneriaki para pendusta? Masihkah ku harus bicara tentang cinta? Saat hal yang aku khawatirkan adalah waktu gajian, biaya tagihan, dan angsuran?
Jawab aku, jelita,
apakah cinta memiliki kepantasan? untuk kami yang mengaku cinta walau sesungguhnya hanya ingin memiliki?
Dari aku, yang mencintaimu (setiap lima tahun sekali), kaum menegah ngehek ibu kota.
“Surat Cinta Untuk Siapa” ditulis oleh:
Yessi Nurita
Working her way into adulthood by pouring her last bit of teenage angst as a sociology student on her Instagram, @ynlabas.