Gimme 5: Rekomendasi Buku oleh Teddy W. Kusuma untuk Memulai 2019
Dari “Insomniac City” hingga “Seribu Kunang-Kunang di Manhattan”.

POST Bookshop adalah salah satu toko buku sekaligus penerbit independen di Jakarta dengan seleksi buku-buku yang jarang ditemukan di toko lainnya. Hal itu pun hasil dari kurasi para pemiliknya, Maesy Ang dan Teddy W. Kusuma, beserta sosok-sosok terpercaya lainnya dengan selera membaca sama. Tidak hanya sebagai toko, POST juga merupakan suatu wadah bagi para pecinta buku untuk saling berbagi dan berdialog menyangkut hal-hal relevan, dengan digelarnya sederet workshop dan talks dalam toko.
Sebagai toko buku independen, POST terbilang cukup aktif dalam memberikan rekomendasi mengenai buku-buku baru ataupun yang menarik untuk dibaca. Oleh karena itu, pada episode “Gimme 5” kali ini, kami menanyakan Teddy untuk memberikan rekomendasi buku bagi yang ingin memasuki tahun 2019 dengan mulai membaca.
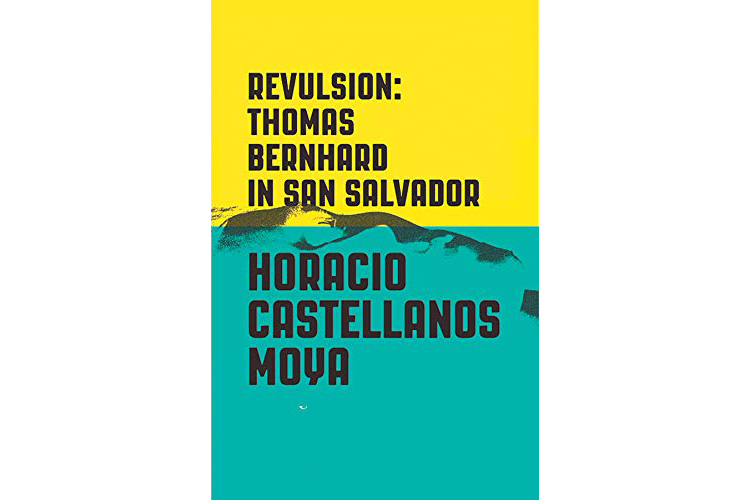
Revulsion: Thomas Bernhard in San Salvador – Horacio Castellanos Moya
Edgardo Vega pulang ke San Salvador untuk menghadiri pemakaman ibunya setelah lama mengasingkan diri di Kanada. Suatu sore ia duduk di bar dan mengomel tanpa henti tentang betapa El Salvador adalah tempat paling putus asa di dunia; tentang bir lokal yang membuatnya mencret, tentara dan para pedagang yang menciumi tangan mereka, lagu-lagu cengeng pegunungan Andes yang dinyanyikan pria-pria berponco, selera seni yang menyedihkan, nasionalisme yang cuma temuan para politisi, hingga monumen di tengah kota yang lebih menyerupai tempat pipis. Horacio Castellano Moya menemaninya minum wiski dan menulis semua omelan Edgardo Vega dalam satu paragraf panjang yang akan membuatmu takjub. Buku ini saya baca di pagi pertama 2019, dan ia langsung menjadi pagi yang asyik. Bagaimana tidak, omelannya seperti petasan yang muncrat tanpa henti. Ini cerita dari orang di pengasingan dengan narasi yang jarang saya baca. Ia tidak berisi nostalgia, kerinduan akan masa kecil, atau ikatan dengan budaya leluhur. Ia seperti seorang intelektual yang sakit hati, dan mabuk, dan marah, lalu mengayunkan tinju ke sana ke mari. Beberapa bulan setelah buku ini terbit, ibu Horacio Castellano Moya menerima telepon dari orang tak dikenal yang mengancam akan membunuh anaknya. Seorang kawan Moya melempar buku ini dari jendela kamar mandi karena “Revulsion” juga menghina pupusas, makanan kebanggaan warga El Salvador.
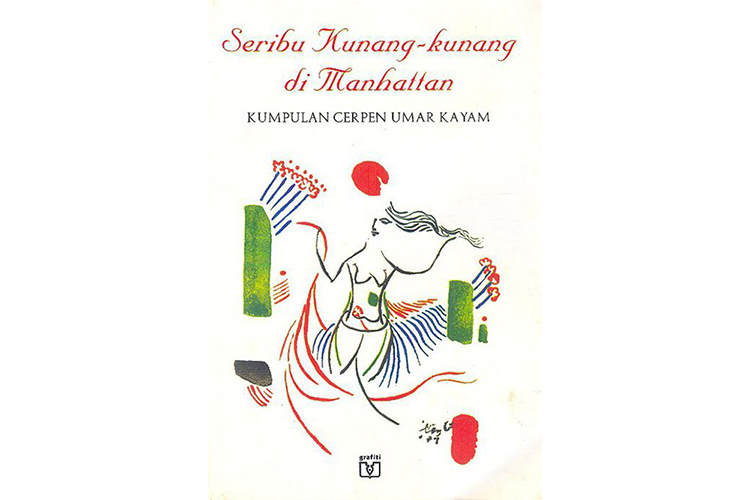
Seribu Kunang-Kunang di Manhattan – Umar Kayam
Di masa ketika dunia kerap terobsesi akan hal-hal yang baru, segala yang serba cepat, (bayangkan, ada lebih dari seribu judul buku terbit di Indonesia setiap bulannya!), selalu menyenangkan untuk membaca kembali karya-karya lama yang dapat tetap tegak berdiri bersama waktu. Cerita-cerita pendek Umar Kayam ini saya baca pertama kali lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Saat baru-baru ini membacanya kembali, ia tetap menjadi karya dengan kualitas kepenulisan yang bagus sekali. Tokoh-tokohnya, juga percakapan-percakapannya, juga adegan-adegannya, ternyata masih terpatri kuat. Adegan percakapan Marno dan Jane sambil memandang keluar jendela, atau cerita New York yang diibaratkan raksasa yang menelan manusia. Saya masih merasakan pahit saat membaca cerita si tua Charlie yang setiap hari menaiki komidi putar di taman, membayangkan dirinya Chief Sitting Bull, atau cerita Sybil yang membiarkan tangan dan kaki si kecil Susan terikat di taman. Senang rasanya kisah-kisah ini baru saja diterbitkan kembali oleh penerbit Pojok Cerpen untuk bisa menemui lebih banyak pembaca.
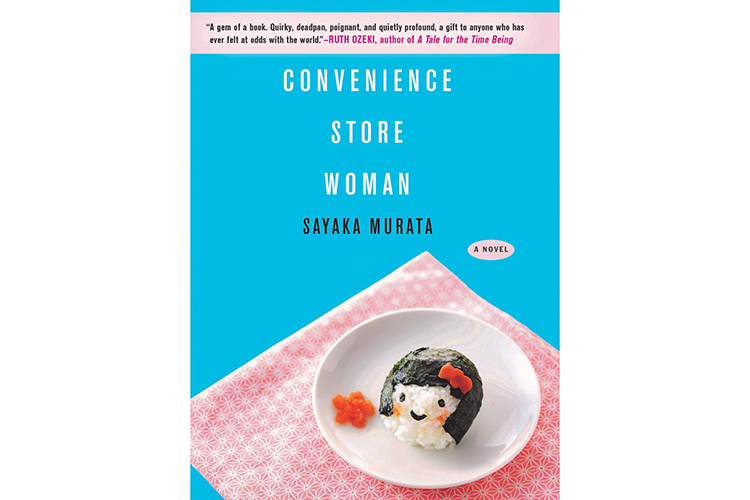
Convenience Store Woman – Sayaka Murata
Ketika Keiko tak bisa memahami bagaimana dunia bekerja, dan dunia tidak bisa memahaminya, ia menemukan tempat yang memberikan rasa tenteram: Smile Mart, sebuah minimart di stasiun Hiromachi. Dengan seragam dan aturan main yang telah digariskan, Keiko paham apa yang harus dilakukannya. Maka ia menghabiskan usia dewasanya bekerja di sana, menjalankan tugasnya dengan patuh, menerima permintaan lembur dengan gembira. Delapan belas tahun berjalan dan kini Keiko berusia 36, dan ia masih makan makanan yang dijual di Smile Mart. Karenanya ia merasa menjadi bagian yang utuh dari tempat itu, bersama penyeduh kopi, atau rak majalah, atau mesin pendingin minuman kaleng. Novel tipis ini menyajikan narasi segar tentang pencarian seseorang akan tempatnya di dunia, sekaligus kritik subtil pada norma dan ekspektasi masyarakat pada perempuan di pertengahan usia tiga puluhan.
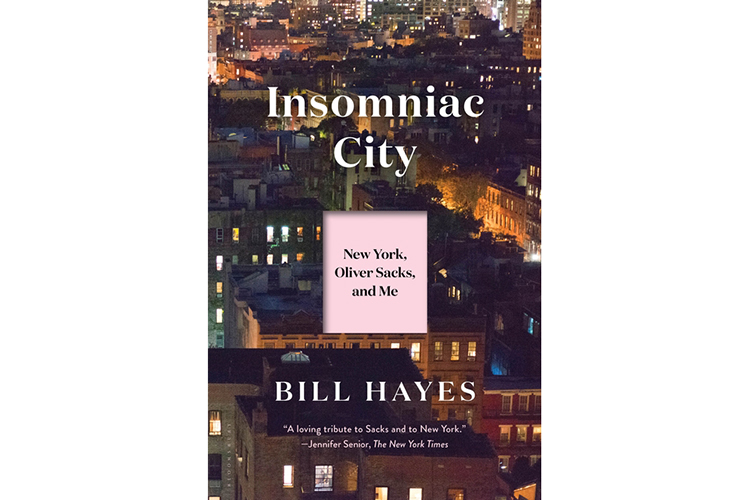
Insomniac City – Bill Hayes
Bill Hayes – seorang insomnia yang patah hati – pindah ke New York untuk memulai kembali hidupnya. Ia menghabiskan hari dengan berjalan, mengambil gambar, dan berbicara dengan orang-orang yang ditemui; pemadat, foto model, bocah bernama Cube yang mengajarinya bermain skateboard, atau pria yang menangis tersedu-sedu di kereta. Di sana Hayes menemukan kembali dirinya dan – saat bertemu ilmuwan Oliver Sacks – cintanya. Tentang hubungannya dengan Sacks, Hayes menuturkan dalam fragmen-fragmen keseharian yang lembut. Tentang Sacks yang baru menemukan cinta di usia 75 tahun, yang menggunakan kaca mata renang saat membuka botol sampanye, yang menyimpan tabel periodik di dompetnya, yang selalu dipenuhi rasa ingin tahu (suatu malam Sacks terjaga dan berkata, “wouldn’t it be nice if we could dream together?”). Buku ini adalah ungkapan cinta Bill Hayes pada New York, juga pada Oliver. Ia menjadi salah satu kisah paling hangat yang saya baca. Kisah cinta antara sesama manusia, juga kepada sebuah kota.
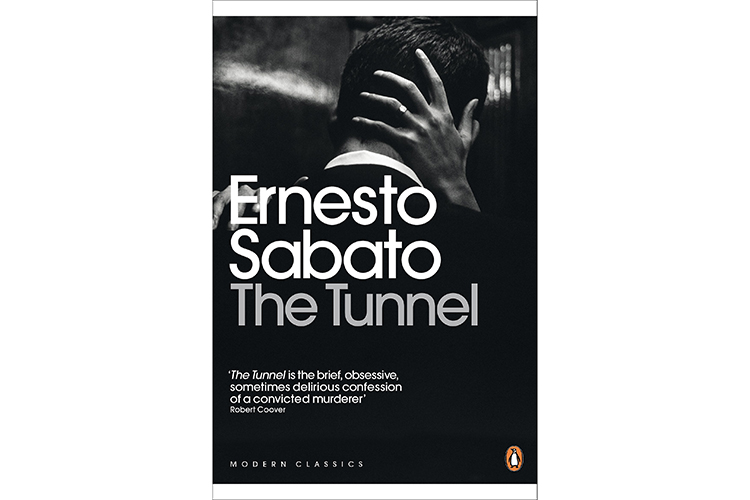
The Tunnel – Ernesto Sabato
Cerita dituturkan oleh tokoh Juan Pablo Castel, pelukis yang dipenjara karena membunuh kekasihnya, Maria Iribarne. Castel mengenang kali pertama ia melihat Iribarne, satu-satunya pengunjung pameran lukisannya yang menurutnya bisa memahami esensi karyanya, dan karena itu diyakini bisa pula memahami jiwanya. Maka dimulailah kisah cinta Castel dan Iribarne yang obsesif hingga akhir saat Castel menancapkan belati ke jantung kekasihnya. Akhir cerita bukan misteri dalam kisah ini (Castel sudah menuturkan di awal), tapi bagaimana Sabato membangun narasinya adalah yang membuat “The Tunnel” menjadi novel yang sulit saya lupakan. Cerita dituturkan dengan tenang, dengan prosa terukur. Narasi Sabato tidak mengajak kita memahami apa yang dilakukan Juan Pablo Castel, tapi ia mengajak kita melongok ke sisi-sisi tergelap jiwanya, dan pada saat yang sama sisi-sisi tergelap kita sendiri.











