Cerita Visual bersama Hikmat Darmawan
Amelia Vindy (V) berbincang dengan Hikmat Darmawan (H).









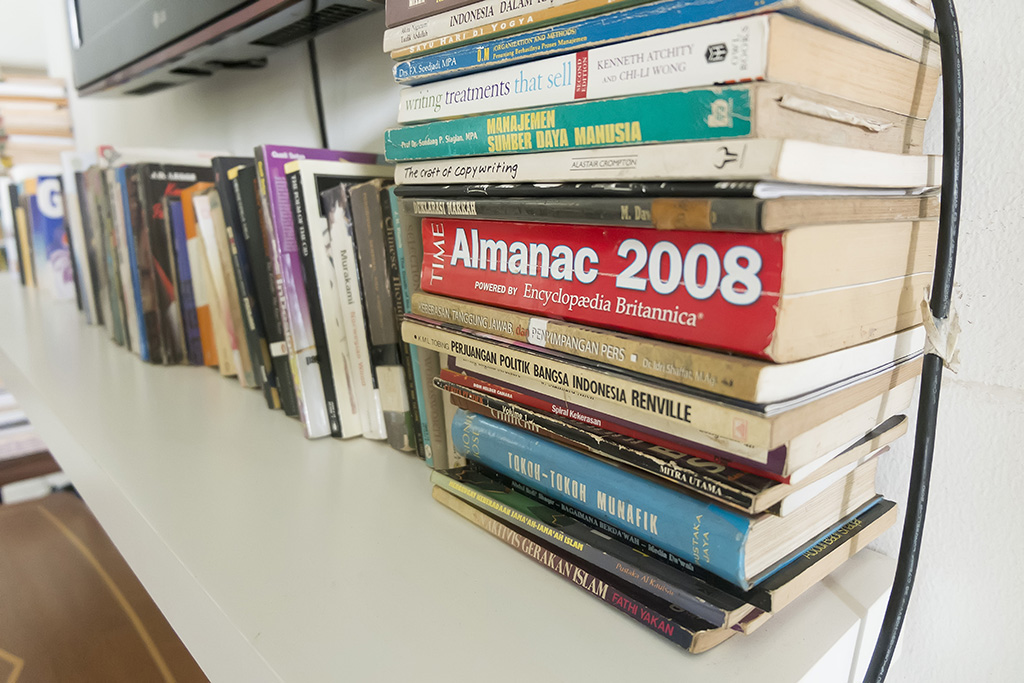















V
Bagaimana awal mula perkenalan Anda dengan komik?
H
Sudah dari kecil, seperti kebanyakan orang. Dulu di awal 2000-an Arswendo Atmowiloto pernah membuka sebuah pameran dengan ungkapan yang masih sangat saya ingat sampai sekarang, “Kalau Anda ingin berbohong, mengakulah tidak pernah baca komik” begitu katanya. Praktis manusia modern itu sejak abad 20, kebanyakan pasti memiliki pengalaman dengan komik. Masalahnya 1. Komiknya yang macamnya apa, 2. Apakah kemudian komik ditinggalkan ketika “beranjak dewasa?”
Tidak hanya di Indonesia atau Amerika tahun 50-an yang memandang komik sebagai sesuatu yang harmful dan berbahaya terhadap anak-anak dan harus ditinggalkan. Tapi di Jepang yang kita tahu adalah sebagai negeri manga atau sangat identik dengan komik, di sanapun ada semacam nilai bahwa komik anak-anak yang sebenarnya komik untuk orang dewasa pun ada, tapi tidak lagi dianggap sebagai bacaan “resmi.” Jadi dalam praktek sebetulnya sampai tua orang-orang baca komik, tapi belum tentu semua mengaku atau nilai budaya yang ada mengakui kalau bahwa hal tersebut bisa dilakukan.
Jadi sejak kapan akrab dengan komik? Ya dari kecil. Saya beruntung karena waktu itu punya akses dengan komik, walaupun saya bukan kelas menengah makmur, tapi tahun 70-an akhir saya bisa baca sebelum masuk sekolah, dan akses pertama saya dengan tulisan adalah lewat majalah. Seperti misalnya majalah Bobo, di sana ada komik dan prosa, sehingga sejak awal saya tidak pernah membedakan atau memberi hirearki, misalnya bahwa komik lebih rendah dari sastra contohnya, tidak juga karena semua sama saja dan hadir berbarengan. Jadi waktu saya berkenalan dengan komik, sama dengan waktu saya berkenalan dengan cerpen atau prosa.
Saya bisa baca bukan karena sekolah, tapi karena saya baca majalah. Ketika saat itu saya mendapatkan sebuah stiker, dari sanalah saya tahu cara kerjanya huruf, kemudian saya tulis nama saya “Hikmat” dan memperlihatkannya kepada ibu saya. Ini menjadi kredit juga untuk ibu saya, karena saya jadi bisa membaca karena dilangganankan majalah Bobo oleh beliau, dan di majalah itu pun sana ada komik yang gambar-gambarnya menarik.
Ketika saya SD saya juga dilangganankan buku dari Pustaka Alam Life, jadi cara mendidik ibu saya pun tidak mengira-ngira karena tidak ada teorinya, pokoknya kalau senang dengan buku ya dia kasih meskipun belum bisa membaca. Buat saya, komik dan prosa hadir di saat bersamaan sekitar tahun ‘76. Tapi kemudian berkenalan lebih intim dengan komik Amerika, karena membagi tugas di saat teman-teman saya mengoleksi komik-komik Indonesia, saya mengoleksi komik Amerika yang pada saat itu ada terbitan Sipress. Dan itulah pertama kalinya saya menjadi seorang pengumpul.
V
Di saat buku-buku tentang komik membahas gambar-gambar komik itu sendiri, salah satu buku Anda yang berjudul “How to Make Comics” justru membahas cara membuat komik atau menulis komik yang juga mengambil referensi dari buku Scott McCloud yang berjudul “Understanding Comic”. Apa yang mendasari Anda untuk membuat buku seperti itu dan apa yang ingin Anda sampaikan lewat buku tersebut?
H
Ada semacam kegemasan, karena saya lihat capaian bentuk atau naratif dari komik yang dihasilkan oleh anak-anak muda di Indonesia ada saat buku itu dibuat, sebetulnya sejak tahun 2000-an saya memiliki kegemasan serupa, itu kebanyakan hanya bertumpu kepada gambar. Asumsi dasarnya adalah jadi komikus itu kalau seseorang bisa jago gambar, padahal tidak begitu, karena cerita di dalamnya juga sangat esensial. Komik itu medium cerita, jadi sebetulnya meskipun ia merupakan medium artistik juga, tapi sebagai medium artistik toh teman-teman muda kebanyakan memperlakukannya bukan dengan pemahaman atau gagasan artistik yang lengkap juga. Kita biasanya berpikir pokoknya gambar bagus saja, sebenarnya pertanyaannya gambar bagus itu apa? Banyak pertanyaan kalau menjadi komikus hanya karena bisa menggambar bagus, lalu muncul juga pertanyaan memangnya mediumnya hanya gambar saja?
Kalau kita melihat komik, sebetulnya pesonanya kan pada cerita, atau kalau tidak pada cerita, pesonanya pada bahasa visual. Jadi sebenarnya medium ekspresi maupun cerita. Gagasan ekspresi dan artistik apakah yang ada? Itu yang kurang digali. Tapi lebih-lebih lagi tools-nya untuk menjadikan komik agar bisa bercerita, itu tidak banyak digali. Jadi orang punya asumsi hanya penggambar yang bisa bikin komik, padahal tidak seperti itu. Kenyataannya adalah Alan Moore (pengarang Watchmen, V for Vendetta hingga Batman) tidak bisa menggambar, sebenarnya dia bisa tapi kemudian ia lebih dikenal sebagai komikus karena aktivitasnya menulis cerita. Grant Morrison (Swamp Thing, hingga Batman vs Robin) juga menulis cerita. Banyak sekali penulis yang hanya menulis, di Jepang juga ada. “Valerian” misalnya, itu penulis ceritanya sendiri Pierre Christin, adalah doktor sosiologi, jadi ada keseriusan terhadap penulisan cerita. Pada dasarnya orang terpikat pada cerita, bahwa misalnya seorang penggambar punya kemampuan bercerita, itu bagus, tapi dia akan berangkat dari cerita bukan dari (yang terutama) gambar, tapi kalaupun ada yang berangkat dari gambar dia akan berusaha mencapai apa yang disebut bahasa visual.
Inilah bedanya antara banyak komikus dengan para perupa yang lain. Intinya lewat buku tersebut saya ingin mendorong agar orang tidak harus menunggu untuk menjadi seorang penggambar yang bagus dulu untuk bisa jadi komik. Misi dasar saya adalah mendorong banyak orang untuk bikin cerita, misi besarnya adalah karena kita sebagai bangsa membutuhkan banyak sekali cerita saat ini. Kita entah kehilangan cerita atau semakin sedikit cerita, atau cerita yang ada keracunan.
Kalau kata Ben Okri “to poison a nation poison its stories” kita punya berapa banyak racun di sekeliling kita yang masuk lewat cerita, seperti rumor, hoax, semakin lama semakin banyak. Dulu saya merasa bahwa komik merupakan alat atau medium yang sangat asik kalau dipakai untuk menggali cerita-cerita kita sendiri. Maka yang penting adalah bahasa visual untuk menjadikan cerita itu terwujud atau bentuk komik. Karena itulah saya merasa mengalami kecocokan dengan apa yang dikembangkan oleh Scott McCloud karena dia juga membahas komik tidak dari segi gambar atau style-nya, melainkan membongkar, misalnya hubungan antar panel seperti apa, kalau kita membaca komik secara menyeluruh kita akan dapat apa? Lalu jika satu per satu akan dapat apa?
Dia tidak hanya bicara soal garis. Kalau pun bicara soal garis, ia membicarakan bagaimana cara garis itu membawa emosi, bagaimana garis itu membawa informasi dan ekspresi tertentu. Jadi lebih dari sekedar “Ini gambar bagus”, yang sebenarnya hanya selera. Orang yang dibesarkan dengan rujukan manga, shonen manga, shoujo manga, bagi mereka yang dibilang bagus yang seperti itu, sedangkan orang lain yang dibesarkan dengan tradisi realisime klasik dalam ilustrasi mengatakan “jelek sekali sih manga”, jadi bagus itu apa? Standarnya tidak bisa diandalkan. Itu sikap saya juga dalam mengkritik film atau sastra, tidak lagi berdasarkan bagus atau jelek karena itu selera dan selera itu dibentuk oleh situasi dan kelas, kelas sosial menentukan selera.
V
Anda adalah seorang pakar komik yang memilih untuk tidak membuat komik, lalu seperti apa proses Anda dalam mengamati dan memahami sebuah komik?
H
Sebenarnya saya juga membuat komik, tetapi memilih untuk lebih banyak menuliskan tentang komik. Kalau Anda tahunya saya tidak membuat komik, berarti saya berhasil menipu (tertawa). Saya pernah membuat salah satu komik yang saya buat bersama teman-teman berangkat dari kegemasan saya dengan “Jum’atan” untuk majalah Madina. Kemudian saya bentuk komik tadi jadi selebaran dan saya sebarkan di mesjid-mesjid yang tentu saja banyak ditolak, tapi beruntungnya Masjid Cut Meutia mau menerimanya. Lucu, sehabis Jum’atan kemudian memberikan selembaran ini. Formatnya jadi “Buletin Komik Jumat” karena saya memang sebetulnya ingin melakukan pendekatan seperti saat memberikan lembaran Jum’atan, yang terbit setiap hari Jum’at. Meskipun tidak memiliki banyak volume, karena ternyata cukup melelahkan juga. Mengisi salah satu kolom di Madina karena heran kenapa majalah ini serius sekali, kenapa tidak membuat komik? Kemudian daripada lama menunggu komikus betulan, dan deadline terus berjalan akhirnya saya saja yang mengisi. Jadi di tengah pekerjaan lain, saya ada satu halaman membuat komik dan sempat ada beberapa yang terbit. Tetapi sayangnya saya tidak menyimpan arsipnya, jadi terlihat seperti tidak terlalu sayang dengan hasil kerja sendiri.
Di pertengahan tahun 2000 saya yang tidak mengaku sebagai komikus, justru punya jumlah komik yang saya hasilnya lebih banyak daripada teman-teman yang mengaku sebagai komikus. Sebutan komikus terlihat seperti konsep, yang sudah membuat karakter lalu menganggap dirinya sebagai komikus, membuat semacam poster atau sampul dengan merancang ini dan itu kemudian sudah merasa membuat komik lalu dipamerkan. Hal ini sudah menjadi penyakit sejak tahun 98 sampai 2000-an, sehingga membuat saya, “Yuk, hitung banyaknya jumlah komik yang sudah dihasilkan” (tertawa).
Saya sebetulnya memandang komik sebagai bagian dari minat saya terhadap budaya populer. Di tahun 90-an saya banyak menulis tentang film, tapi pada saat itu saya pun tidak pernah meninggalkan komik. Karena pada tahun 90-an saya juga menemukan bahwa komik bisa sangat eksploratif, seperti saat saya membaca “Sandman” di tahun 1994 sehingga membuat saya berpikir, “Ternyata komik bisa seperti ini ya.” Memang sudah sejak semula saya tidak melihat komik hanya sebagai hiburan yang hanya hiburan, jadi kalau saya melihat komik dan komik itu sebagai medium hiburan dalam arti ada komik yang dengan sengaja dibuat sebagai hiburan, saya tidak bisa membacanya hanya agar bisa terhibur.
Saya mengukuhkan diri sebagai pembaca. Dan dengan posisi ini, saya mempertanyakan tentang apa yang saya lihat dari komik? Tentu saja melihat teks, jadi saya memperlakukan komik sebagai teks. Saya melihatnya sebagai hal yang menarik dalam komik, saya menemukan bahwa adalah gambar yang lebih dulu dilihat, teks dulu dibaca, yang sebenarnya dari dulu pun tidak seperti itu, hanya saya mencoba untuk mempermudahnya saja. Jadi begini, gambar itu dilihat ketika melihat komik kita melihat gambarnya, lalu kita membaca teksnya tetapi di dalam komik sangat terasa bahwa gambar juga bisa dibaca dan teks bisa dilihat. Contohnya, sound effect itu bisa menambah emosinya dengan cara memperlakukan teks sebagai sebuah imaji, maka jadilah teks itu menjadi sesuatu yang kita lihat, salah satu komik yang merepresentasikan hal tersebut misalnya komik series “Cerebus” oleh Dave Sim, yang merupakan salah satu komik indie di Kanada. Bekal itulah yang membuat saya semakin mengeksplorasi dan memang komik sebagai seni sekuensial. Apa yang menyebabkan atau membedakan komik lain berbeda dengan komik lainnya? Karena sekuensialnya, tetapi sekuensial itu bukan sekadar mengurutkan satu gambar dengan gambar yang lain untuk membentuk sebuah pesan atau cerita.
Ada banyak dinamika antara satu panel dengan panel lainnya, dan dinamika itu harus ditemukan. Upaya awal yang dilakukan oleh McCloud untuk mensistemasi pengetahuan membaca komik itu dengan lebih teoritis tentu sangat membantu, meskipun menurut saya ada juga banyak hal terlalu gegabah dari beliau. Namun tidak masalah, karena paling tidak ia memberikan petunjuk bahwa kita bisa menggali potensi-potensi bacaan komik itu sampai ke hubungan antar panelnya. Ada banyak hal yang terjadi ketika panel satu dipisahkan dengan panel lainnya oleh garis, kejadian-kejadian tersebut adanya di dalam kepala kita karena kepala kepala kitalah yang berimajinasi dalam mengaitkan satu cerita antara panel yang ada di dalam komik, itulah yang saya gali.
Kemudian minat terhadap budaya populer itu sendiri adalah bagian dari minat saya terhadap kebudayaan. Saya juga melihat letaknya komik dalam kebudayaan, secara mudahnya dapat dikatakan saya melihat komik, pertama sebagai teks kemudian sebagai sarana ekspresi. Kalau membaca teks itu kan menemukan konstruksi tekstual, saya sendiri pun saat ini tidak mau mengabaikan pengalamannya jadi tidak melulu sebagai teks, namun juga sebagai pengalaman estetik dan artistik. Kenapa kita bisa menyukai gambar-gambar tertentu? Hal itu juga menarik, jadi tidak hanya membaca konstruksi ideologi apa yang ada di sebuah gambar atau sebuah imaji? Tapi juga mengapa kita bisa sangat menyukai komik tersebut? Mungkinkah itu ada di level psikologis, psikologi sosial, kimia atau tubuh kita dan cara kerja otak kita, dari hal-hal tesebut masih banyak yang bisa kita kembangkan. Gambar menjadi sesuatu yang menarik bagi saya, bukan sekadar berhenti digambar yang bagus tapi definisinya apa atau kalau tidak bicara soal definisi bisa juga soal rasa. Ada banyak metode yang saya gunakan, teori yang ambil, padu, ramai dan kemudian saya racik, menjadi semacam cara pembacaan saya terhadap komik.
V
Scott McCloud mempertanyakan mengapa karya komik di Amerika tidak diberlakukan seperti karya seni lainnya seperti contohnya karya lukisan, patung dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda peran komik di Indonesia, tidakkah hal itu juga terjadi di negara kita bahwa rasanya karya komik bukan sebuah karya “high art”?
H
Saya tidak terlalu keberatan dengan peran komik yang tidak diberlakukan sama seperti misalnya seni kontemporer. Walaupun pada kenyataannya seni kontemporer banyak “nyolong” dari komik, mulai dari pop art sampai sekarang. Kalau Anda lihat di pameran seni rupa kontemporer pasti ada saja apropriasi, pencurian atau peminjaman bahasa komik menjadi bahasa seni rupa tetapi kemudian komiknya ditinggalkan. Bahkan terkadang seorang seniman memulai karirnya sebagai komikus atau tetap membuat komik, ketika ia berapa di pelataran seni rupa kontemporer komiknya sendiri diabaikan, hal ini terjadi di Amerika dan juga di Indonesia, tidak masalah kalau menurut saya. Karena saya lebih percaya bahwa komik memiliki kelebihannya sendiri sebagai bahasa vernakular.
Menurut saya komik adalah salah satu hal yang vernakular yang ada di masyarakat, baik di Amerika atau pun Indonesia. Saya berani mengatakan bahwa komik adalah hal vernakular atau ada di dalam masyarakat itu sendiri karena dalam sejarah komik Indonesia yang mengalami periode, di mana komik menjadi bagian yang integral dari masyarakat. Tidak perlu diwajibkan untuk membacanya, contohnya ketika bangun tidur membaca komik adalah hal yang biasa. Pada penelitian Marcel Bonneff mengenai komik Indonesia pada periode tahun 1968-1971 ada satu gambaran sebuah taman baca di sebuah terminal justru didatangi oleh orang-orang yang ingin berangkat kerja dan memilih komik untuk dipinjam yang kemudian hari selanjutnya dikembalikan dan meminjam lagi yang baru. Sosok orang-orang yang ada anggota TNI, karyawan, pekerja biasa dan justru sangat jarang ada anak-anak yang mana memang pada saat itu produk komik di Indonesia tidak banyak untuk anak-anak, dalam artian lagi ada banyak juga yang membuat komik untuk anak-anak, tetapi tersendiri.
Jadi banyak komik yang diperuntukkan bagi orang dewasa dan merupakan bagian dari keseharian, sama seperti musik. Tentu kemudian disanggah oleh industri yang berhasil, tetapi sebagai bahasa atau narasi visual, komik adalah sebuah narasi yang vernakular dari mulai zaman candi hingga sekarang, bahasa visual yang sekuensial sangat lekat dengan keseharian kita. Jadi kalau kita sudah dapat yang vernakular saya memperjuangkan agar vernakularitasnya itu dikenal kembali menjadi bagian dari kita juga. Jangan sampai kita menutupi kenyataan bahwa komik itu tidak menjadi bagian dari kita, sehingga disisihkan karena dianggap seperti cela, aib dan sebagainya.
Saya lebih berkepentingan agar orang memiliki presepsi yang lebih positif terhadap komik, ketimbang komik masuk ke lembaga seni rupa kontemporer, saya tidak terlalu risau. Walaupun saya memanfaatkan semua peluang yang ada, toh saya juga menginisiasi atau mengampu pameran komik di lembaga seni rupa. Contohnya dulu saya membuat pameran berjudul “DIY” (Daerah Istimewa Yourself). Eksibisi ini mengulik komik-komik DIY yang berkembang diranah komik indie dan itu atas inisiatif yang bekerja sama dengan DKJ yang merupakan lembaga seni yang resmi. Selain itu ada juga, pada saat CP Biennale yang kemudian di geruduk FPI karena ada karya yang dianggap mengandung unsur pornografi oleh Davy Linggar dengan modelnya yaitu Anjasmara. Di situ pun ada Akademi Samali dan ada Taring Padi yang jelas-jelas komik. Kembali pada vernakularitas tadi yang mana merupakan hal penting, apakah masuknya lewat lembaga seni atau lewat komik-komik surga neraka yang ada di pinggir jalan ketika jama’ah berkumpul? Ya tidak masalah yang terpenting adalah hidup terus bahasa vernakularnya.
V
Juga sebagai orang jurnalis, bahasa visual seperti apakah yang diperlukan seorang komikus agar bisa efektif dalam menyampaikan pesan?
H
Bahasa yang tidak mementingkan gaya. Jadi sekarang, tidak hanya komikus, contohnya seperti sastrawan, filmmaker atau bahkan perupa, banyak yang lebih mementingan “wow” faktor atau keren-kerenan. Itulah kenapa ada banyak orang yang lebih mementingkan aspek teknis agar bisa membuat orang terpukau atau terkadang terlalu banyak menggunakan teori. Teori urusan saya sebagai kritikus; seharusnya, meskipun sebetulnya sah-sah saja jika ingin bertele-tele atau sampai terlihat pada deskripsi karyanya bahwa karya ini ruwet. Entah gagasan atau teorinya yang muncul pada gambar yang juga jadi ruwet, tapi justru itu membuat senimannya merasa keren. Saya merasa bahwa kita harus kembali kepada gagasan dan pesan. Pesan itu sering kali di dalam karya seni di Indonesia banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang cemar, takut jadi “ini sastra bertendens ya?” Apa itu? Sastra bertendens adalah sebuah sastra yang tidak berangkat dari rasa, padahal pembedaan-pembedaan seperti ini sudah basi.
Kalau tadi pertanyaan bagaimana dengan pendekatan jurnalistik, jangan salah Indonesia barangkali menjadi salah satu negara yang cukup dini mengenali potensi jurnalistik di dalam komik, paling tidak dalam sosok Delsy Syamsumar. Beliau banyak membuat reportasi sehari-hari di dunia hiburan hingga dunia seniman Pasar Senen yang merupakan tempat pertama kali ia memulai komik reportasi. Menggunakan bahasa sekuensial dan strip, beliau bisa menginformasikan banyak sekali percakapan yang berlangsung di Pasar Senen, lalu beliau melanjutkan ke dunia hiburan. Meskipun dengan bekerja di tabloid murahan menurunkan posisinya, tapi beliau tetap seorang Delsy Syamsumar, yang berbasiskan laporan jurnalistik dalam membuat gosip-gosip terkini tentang artis. Jadi kita lebih dulu dari Joe Sacco, orang Palestina yang belajar jurnalistik namun lebih dikenal sebagai komikus, sisi displin jurnalistiknya itulah yang belum dimiliki dan diterapkan oleh Indonesia.
Saya mendengar meskipun belum sampai melihat barangnya, bahwa ada satu laporan jurnalistik di buat dengan gaya komik. Sangat disayangkan laporan tersebut dimuat di koran PKI, sehingga sulit bagi saya untuk mendapatkannya sekarang. Saya mendapat informasi dari Martin Alameda bahwa Amarzan Lubis pernah membuat reportase tentang kemarau di daerah-daerah, lalu bentuk reportasenya kemudian dibahasakan secara naratif di tahun 1964. Pada tahun itu juga seniman Pasar Senen masih banyak berkumpul. Sisa-sisa kejayaan Pasar Senen tahun 50-an atau pada zamannya Chairil Anwar, Delsy yang sebagai salah satu orang yang sering berkumpul di sana dan merekamnya secara visual. Jadi saya kira, cirinya di situ, dia punya gaya pribadi tetapi tidak menjadikan gaya tersebut membatasi informasinya. Bahasa jurnalistik apa yang dibutuhkan? Bahasa yang mampu mengundang pembaca untuk masuk ke dalam pesan maupun fakta yang hendak di ungkapkan.
V
Dari banyaknya koleksi komik yang Anda punya, Anda nampak lebih menyukai graphic novel. Apa yang membedakannya dengan komik lainnya sehingga membuatnya lebih spesial?
H
Sebenarnya sama aja, karena keduanya sama-sama komik, itu kan hanya istilah orang saja menyebutnya graphic novel. Saya sederhananya membagi dua penggunaan utama dari istilah graphic novel 1. Secara estetika, apa itu graphic novel. 2. Secara marketing – dan inilah yang sebenarnya lebih penting. Dari awal orang yang sangat getol mempopulerkan istilah graphic novel adalah Will Eisner dan dari awal orang tersebut memang sudah memiliki kesadaran marketing. Dia berkata seperti ini, “Saya mau membuat komik untuk orang dewasa, tetapi penerbit komik rasanya tidak cocok karena waktu itu isi komik kebanyakan orang yang memakai kostum kemudian berkelahi.” Karena itu ia menginginkan sebuah penerbit yang “serius.”
Di dalam kepalanya ada pemikiran seperti itu, namun penerbit “serius” tidak akan menerima komik, karena itu supaya mendapatkan penerimaan atau lebih terbuka Eisner menggunakan istilah graphic novel. Graphic itu lebih terhormat dari komik, novel pun demikian, jadi dimunculkannya istilah tersebut olehnya. Eisner serius pada karya komik untuk orang dewasa, dalam artian mengulik sisi tergelap dari sisi manusia yang ia gambarkan lewat salah satu karyanya berjudul “Contract with God.” Jadi tercampur kan, secara estetika dan pasar menjadi satu meskipun sebelumnya orang-orang banyak yang menggunakan istilah graphic novel sebagai gimmick dan setelahnya menjadi kepentingan untuk menciptakan jalur distribusi sendiri.
Dalam konteks sebagai bagian dari kebudayaan populer, komik di Amerika pernah menikmati peran sebagai “mass market” di tahun 40-an. Saat itu, satu buah komik bisa terjual 1,2 juta kopi per bulan untuk komik superhero dan action. Mungkin kenapa komik bisa laku sebegitu kerasnya, karena orang-orang sedang frustasi dengan perang atau karena para ayah sedang pergi ke seberang lautan dan ibu pergi ke pabrik, sebab itu komik dijadikan hiburan untuk anak-anak, pokoknya ada konteks sosiologisnya. Tahun 50-an komik dihajar oleh kelas menengah Amerika, akhirnya surut dan industrinya terpukul sehingga menyebabkan komik mengembangkan jalur ritelnya sendiri atau khusus, yang kemudian memunculkan komik-komik yang dijual di toko komik khusus.
Kalau mainstream, seperti toko buku atau supermarket tidak lagi menerima komik kecuali Mad Magazine yang awalnya komik berubah menjadi majalah dan akhirnya melenggang di antara majalah TIME dan sebagainya karena memang penjualan terjaga sampai tahun 90-an – oplahnya paling besar. Meskipun sudah menjadi bagian dari imajinasi kultural Amerika, pasarnya tetap terbatas, bentuknya pun semakin menyerupai pamflet dengan 32 halaman, penuh warna, tiap bulan ada. Setelah baca dibuang, jadi tidak terlalu berharga, bahkan orang yang mengerjakannya mungkin saja asal-asalan. Meskipun asal-asalan tetapi tetap memiliki makna kulturalnya sendiri. Lama-kelamaan jalurnya toko khusus komik semakin sempit dan istilah graphic novel menyebabkan tersedianya peluang dari para toko/ritell buku umum untuk membuka rak khusus graphic novel dengan syarat bukunya harus tebal seperti novel.
Secara istilah marketing, tentu sekarang hal tersebut sudah mengalami inflasi. Tetapi yang menarik di tahun 2000-an, omzetnya bisa mencapai 1 juta Dolar AS, meskipun mayoritasnya adalah terjemahan komik Jepang. Menariknya adalah di belahan bumi yang lain tanpa disebut dengan graphic novel justru formatnya sudah graphic novel, seperti contohnya Jepang dan Indonesia. Lalu kembali pada estetikanya, yakni “Apa bedanya graphic novel?” Format longform storytelling atau cerita panjang. Seberapa panjang? Kalau menurut saya di atas 48 halaman; walaupun saya memiliki yang berisikan 16 halaman, tapi saya masukan sebagai kategori graphic novel karena setiap panel seperti seni rupa, sulit dibacanya dan itu adalah hal lain yang menjadi kategori.
Selain itu, juga memiliki ambisi sastrawi dan artistik yang kuat, tidak hanya sekadar ingin memenuhi setoran bulanan atau hanya untuk bersenang-senang dan berambisi ingin menggambar sesosok perempuan yang sangat seksi. Itu kan bisa saja ada di kepala para komikus dan buat saya menganggapnya sebagai ambisi artistik. Yang disebut sebagai ambisi artistik secara estetika adalah misalnya menemukan bahasa pengucapan baru atau ekplorasi bentuk. Kalau secara marketing, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya itu hanya sebuah gimmick agar komik bisa mendapatkan ruang di tempat mainstream. Bentuk tebal, sejajar dengan novel dan bisa dijual dengan harga mahal sehingga kemudian orang-orang bisa menghidupkan industri buku lebih lanjut.
V
Menurut Anda seberapa besar peran bentuk fisik sebuah bacaan menyikapi era yang sekarang ini sudah serba digital? Termasuk hingga menjadikannya sebuah medium untuk berkarya. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?
H
Saya sering dituduh romantik dalam hal ini dan mungkin itu benar karena saya orang kuno. Saya punya relasi romantik dalam artian punya idealisasi terhadap nikmatnya membaca bacaan fisik, sehingga saya tidak akan menutupi sisi tersebut. Masih merasa nikmat sekali menggenggam sesuatu. Saya punya argumen, bahwa gagasan ketika diwujudkan secara fisik kemudian akan menjadi artefak dan penting bagi sebuah gagasan untuk memiliki artefak, jadi orang bisa menjamahnya secara fisik terlebih dahulu. Dalam keseharian saya dulu punya satu pengalaman bersama keponakan saya ketika ia masih bayi, saya dan mantan istri dulunya adalah seorang penterjemah, lalu kami membelikan kamus visual yang harganya mahal yang ternyata tidak terlalu terpakai. Meskipun mewah dan memiliki banyak gambar, kamus ini pemalas karena tidak banyak memiliki banyak kata padanan dan yang ada malah serapan, pokoknya di “sasi-sasi” saja sehingga tidak terpakai. Tapi sebagai bentuk fisik, sangat indah dan kemudian berguna untuk keponakan saya yang masih bayi.
Di saat berumur 2 tahun ketika sedang rewel, saya kasih lihat gambar yang ada di kamus tersebut dan terhibur. Jadi di umur 3 tahun ia sudah terbiasa dengan bentuk fisik buku. Saya pun mengenal komik seperti Tintin dan sebagainya. Saya ajak jalan-jalan ke Gramedia Matraman, keponakan saya ini kemudian sangat karib, gembira dan berteriak sepanjang alur rak buku, terkadang berhenti di rak tertentu seperti mengenali karakter-karakter tertentu seperti Captain Haddock misalnya. Wah, itu saya bangganya luar biasa sekali karena memiliki wawasan internasional di saat kakak-kakaknya membaca manga-manga tidak jelas dan hingga sekarang jadi gemar membaca.
Jadi awalnya fisik itu memang membawa kita ke dalam dunia gagasan, karena sebagai artefak mereka membetot kita. Tetapi ada juga sisi tidak romantiknya, dalam arti saya tidak keberatan jika zaman beralih menjadi lebih mementingkan informasi secara digital, tidak apa-apa. Bagi saya, buku harus tetap ada meskipun jumlahnya hanya ada sedikit saja. Sekarang ini kan pergeserannya kan belum terjadi secara signifikan atau menguntungkan. Bahkan trennya pun rilisan; baik di musik atau pun buku, sedang naik. Jadi sekarang di negara-negara maju, tren buku naik lagi dan penyanggahnya bukan lagi ritel toko buku besar karena mereka banyak yang tutup, tetapi toko-toko neighborhood atau independen ini.
Kalau pernah melihat film You’ve Got Mail, karakter wanitanya pemiliki toko buku anak-anak yang independen atau neighborhood store sementara Tom Hanks mewakili koorporasi yang membuat ritel. Film itu seolah-olah menyatakan bahwa zaman sudah beralih, toko neighborhood yang terlihat hangat dan cute harus menyingkir dan film itu menerima. Sekarang justru sebenarnya terbalik dengan kenyataan di film tersebut, yang mana ritel banyak yang runtuh karena diambil alih oleh, misalnya Amazon dan orang-orang lebih mudah memesan dalam kamar kemudian buku akan datang ke depan pintu.
Tapi kalau sampai mendorong diri kita untuk pergi apa yang kira-kira masih menarik? Ya buku-buku lama atau loakan, juga buku-buku yang seni cetaknya diperhatikan dan bisa diceritakan makna dan isinya oleh penjual sehingga ada interaksi langsung antara penjual dan pembelinya, saya rasa film itu harus di revisi (tertawa). Intinya saya tidak keberatan dengan kehadiran era digital karena saya pun sekarang menggunakan secara optimal bentuk-bentuk digital. Jadi bukannya saya tidak membaca bentuk digital ya, justru saya pun merasa banyak terbantu dengan kehadiran era tersebut.
V
Sebagai kritikus film, pernahkah Anda justru mendapat kritik dari para pelaku atau penikmatnya?
H
Sering dong, karena kritikus apa sih gunanya. Buat saya yang paling sangat istimewa adalah ketika saya menulis kritik panjang tentang “99 Cahaya di Atas Langit Eropa”. Film ini kan menceritakan tentang seseorang bernama Rangga yang setelah saya tulis kritik itu, Rangga-nya sendiri yang menyapa saya di inbox Facebook. Rangga ingin membenarkan pemikiran saya. Ya saya jawab, “Tulis saja.” Lalu akhirnya ia memberikan tulisannya dan mengasumsikan saya bahwa tulisan saya lahir karena saya resah melihat sudah banyak orang yang menggunakan jilbab. Jadinya saya berpikir, tolong lah hargai kritikus dengan membuat kritik yang benar karena apa yang ditulis bukan kritik namanya, melainkan prasangka. Ya sudah, kemudian saya jawab juga dengan serius karena minimal dia sudah menulis.
Banyak sekali teman-teman kritikus saya mengalaminya, dan saya pun begitu. Hanya saja saya beruntung karena walaupun saya banyak menulis film dan kemudian saya banyak bersirkulasi di kalangan filmmaker, khususnya yang muda, tetapi saya tidak memiliki hubungan personal dengan banyak orang film. Banyak wartawan menjadi dekat dengan banyak orang film tapi saya memilih beberapa saja dan itu pun karena pertemanan yang natural sehingga tidak terpengaruh oleh omongan orang karena tidak tahu apa yang mereka bicarakan tentang saya. Kalau sudah berbentuk tulisan ya biarkan saja mau ada yang masuk ke inbox saya atau membalas tulisan saya.
Justru lebih terganggu dengan sesama kritikus yang menurut saya kemudian tidak mengembangkan kritik dengan displin. Seperti halnya apa yang saya lakukan dengan komik, saya juga memperlakukan film sebagai teks atau sebagai pengalaman sinematik, itu pendekatan yang terbaru sehingga totalitas pengalamannya konteksnya menjadi lebih hidup. Tapi kalau sebagai teks kan artinya kita mencari tafsir, sempat ada masanya atau satu aliran berkata Susan Sontag “against interpretation” karena tafsiran bisa jadi overreading.
Saya menjaga hal tersebut lewat metode juga kembali pada pengalaman sinematik itu sendiri. Itu semua kan ada metode dan dasar teorinya, orang tuh susah membuat film, jadi hargailah dengan membuat kritik yang tidak asal ucap atau komentar, parahnya berdasarkan selera. Kalau benar seleranya terasah, kalau tidak? Buat saya basis selera itu lemah sekali karena selera itu adalah hasil dari bentukan kelas biasanya. Sebuah standar bagus yang dominan itu bisa jadi karena selera kelas yang dominan.
Contohnya Basuki Abdulah, bagus sekali karyanya dan memang bagus, jika diperhatikan secara teknik sering kali ada yang off karena bagus secara teknis misalnya, walaupun dia punya tempat sendiri dalam sejarah seni rupa. Tapi orang kaya di negeri ini saat awal memiliki Basuki Abdulah yang berjaya pada masa itu senang sekali, karena mereka menjadi lebih cantik atau tampan ketika dilukis olehnya dan itulah yang disiapkannya dan itulah tempatnya. Tapi kemudian bila dikatakan dia jauh melebihi Affandi atau S. Sudjojono itu kan cerminan atau selera kelas. Jadi kesimpulannya saya lebih terganggu oleh kritikus yang mengkritik tidak dengan displinnya dibanding orang yang mengkritik tulisan saya. Tentu saja terkadang saya sewot. Contohnya saya pernah sewot karena saya merasa dinista orang yang sehari-harinya mengaku sebagai jurnalis film, kemudian meremehkan metode. Padahal metode tidak yang berat, yang penting rasional saja jangan berdasarkan suka atau tidak. Jadi seperti apa bedanya dengan gosip tetangga?
V
Sekarang ini, sudah sulit menemukan sebuah ulasan film yang ditulis secara kritis oleh orang yang benar-benar menguasainya dan rasanya penonton pun tidak terlalu mempedulikan ulasan panjang, kalau pun ada mungkin hanya beberapa. Sebagai seorang kritikus film, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Pentingkah peran sebuah ulasan untuk para penonton film?
H
Panjang atau pendek, toh para penonton tidak peduli kok sama kritik. Tapi saya tidak melihat ada masalah dengan tulisan panjang, mau mediumnya berupa blog pribadi atau situs tidak ada bedanya bagi saya. Bahkan mungkin lebih memuaskan tulisan online karena bisa mendapatkan reaksi dan respon langsung, ya paling tidak tulisannya dibaca. Dari pengalaman saya justru tulisan-tulisan panjang yang lebih banyak dibaca, contohnya di Facebook atau di situs Rumah Film.
Rumah Film berisi beberapa pengulas kritikus atau yang ingin jadi kritikus film memang tidak merasa puas dengan media cetak yang ada. Coba sandingkan kedua media cetak dan elektronik. Lewat media elektronik pesan kita tersampaikan, tetapi belum tentu kita terpanggil karena secara visual tidak menarik. Jangan salah, gagasan bisa kalah dengan rupa. Media cetak, halamannya sangat terbatas, kita bisa bilang apa? Sering kali juga redaksinya tidak punya wawasan karena film tidak dianggap penting. Jadi tidak perlu penontonnya dulu deh, rubrik film saja tidak dianggap penting oleh redaksi pada umumnya. Asumsinya seperti ini, paling sulit adalah berita politik jadinya para penulis baru diberikan bobot ringan dan diberilah tugas untuk menulis film.
Film itu masuknya hiburan, padahal ada banyak film yang membuat saya tersiksa, bukan hiburan. Maksud saya medianya sendiri tidak menganggap penting ulasan film, makanya film sering tidak punya ruang untuk diberikan ulasan yang serius. Akhirnya kita sering bersiasat menulis tulisan pendek tapi sangat berdisiplin tapi juga jarang yang bisa menguasai itu. Karena secara attitude keseluruhan kritik film memang bukan sesuatu yang penting, tapi kritik apa sih yang penting buat kita sekarang?
Tidak banyak, memangnya kritik seni rupa penting buat kita? Tidak, penting untuk para kolektor untuk mengetahui nilai sebuah karya, sehingga ada jalinan antara pasar kolektor dan kritiknya. Tapi kan pasar seni rupa berbeda dengan budaya populer, seperti film dan musik. Dulu kritikus musik yang serius juga hanya beberapa salah satunya, adalah almarhum Denny Sakrie. Kita bisa lihat dia memiliki wawasan, pengalaman dan gairah untuk merujuk tapi pendekatannya masih jurnalistik saja. Cuma ya, itu saja sudah bagus.
Sekarang bicara film, infrastruktur perfilman atau ekosistem perfilman memang sebagaimana banyaknya ekosistem kesenian yang ada di Indonesia, belum terbentuk dengan baik. Jadi kalau kita bayangkan ekosistem itu ada produksi, distribusi, eksibisi, apresiasi dan pendidikan, maka ranah apresiasi ini kan yang seharusnya hidup dengan melimpah ruahnya kritik yang serius? Itulah yang dari dulu tidak terlalu terbentuk. Walaupun dulu banyak orang di tahun 80-an yang bukan dari “insan” film, masih mau melakukan kritik terhadap film seperti yang majalah Jakarta Jakarta lakukan. Ada Seno Gumira Ajidarma dan Danarto yang sebenarnya sehari-hari adalah sastrawan dan budayawan, menganggap film secara serius. Itulah yang hilang sekarang ini. Mereka menulis ulasan pendek, namun berdasarkan posisi sastra dan budaya mereka. Ada juga Putu Wijaya di Tempo, Salim Said seorang akademisi dan ahli politik. Jadi orang-orang yang punya wawasan di luar film saja dan di luar kenikmatan membuat film. Jadi walaupun belum ada disiplin ilmu film yang terlalu jelas, paling tidak orang-orang yang menulis punya displin kebudayaan dan punya kecenderungan memandang kegiatan kritik sebagai kegiatan menegakkan tanggapan rasional terhadap karya pada saat itu.
Menariknya pada tahun 2000-an, sebetulnya yang disebut banyak itu apa? Banyak orang yang secara serius menulis film dalam arti setiap hari menulis film dan secara serius sudah merasa sungguh-sungguh, yang mana biasanya adalah para blogger. Tapi sebetulnya mereka masih berkutat atau berangkat sebagai movie buff yang memang senang dengan film dan tentu saja senang dengan film adalah sebuah modal, tetapi sama sekali tidak cukup. Jika tidak bisa keluar dari situ, derajatnya sama saja seperti gosip kalau menurut saya. Jadi apa guna kritik? Menurut feedback yang saya dapat dari pembuat film; contohnya Joko Anwar yang dulunya juga seorang kritikus yang bagus saat itu, gunanya adalah sebagai penyeimbang atau memberi sisi lain. Si pembuat film itu kan sudah sibuk membuat film dan bagaimana memecahkan persoalan-persoalan artistik yang berhubungan dengan camera man, adegan dan sebagainya, dan seorang pembuat kritik akan datang dengan mata dan feedback lain yang tidak hanya sekadar teknis, walaupun sebaiknya lebih menguasai aspek tersebut sehingga menciptakan sebuah dialektik.
Jadi gunanya di situ, saya juga menawarkan guna yang lain, sebenarnya kritik itu adalah karya dan tidak banyak orang yang memberlakukan hal tersebut. Ada beberapa pendapat ranah sastra, misalnya Sapardi Djoko Damono. Banyak orang lupa sebenarnya beliau adalah seorang akademisi sastra yang sangat baik dan kalau membuat kritik sama semangatnya seperti ketika membuat puisi, tidak dengan gaya bahasanya tetapi kesungguhannya. Saya menganggap itulah yang seharusnya menjadi semangat seorang kritikus, jadi saya menawarkan gunanya sebagai hiburan atau membuka wawasan juga sebagaimana film mampu memberikan wawasan dan menggugah sebagaimana film bisa menggugah, itulah guna yang bisa ditawarkan dari sebuah kritik. Dia memiliki potensi untuk menghibur pembacanya, bukan untuk bisa mendapatkan tiket dan kemudian berguna dalam ekonomi kreatif sekarang, tetapi dia bisa menyumbang apresiasi sehingga meningkatkan wawasan audiens atau khalayak dan menumbuhkan budaya menonton yang sehat.
Poin-poin tersebut bukan peran ideal lho, melainkan peran-peran yang konkret dan menjadi tidak konkret karena ekosistemnya belum hidup. Jadi itu yang saya kira perlu dikembangkan, contohnya ketika saya mengajak teman saya, “Oh kamu tertarik menulis kritik? Kritik itu bukan tentang celaan ya dan bukanlah kerjaan di mana orang membuat film sampai ke gunung sedangkan kita di kamar kemudian melihat hasilnya.” Tidak seperti itu, karena kritik itu tanggapan rasional.
V
Peran kritikus sampai saat ini masih dianggap menjadi sebatas teman diskusi bagi para pelaku di industri film. Sehingga apa yang dituliskan justru lebih berpengaruh ke publik. Sebenarnya kepada siapa ulasan atau tulisan itu dibuat?
H
Ditujukan untuk publik juga, sebenarnya banyak juga filmmaker yang tidak terlalu peduli dan punya kepentingan untuk berdialog dengan hal tersebut. Kita menulis entah kritik atau karya seni tentu punya bayangan khalayak, tetapi bukan berarti kita menulis untuk mereka saja. Dalam hal ini saya membedakan kritikus dengan market guide atau orang yang menentukan apa yang harus kita beli, bukan seperti itu. Kalau kritikus sama seperti ketika seniman membuat karya yang mana sama-sama ingin menyampaikan sebuah gagasan tanpa terlalu terpaku apakah nanti gagasan tersebut akan dikonsumsi oleh khalayak luas atau tidak, tetapi pasti sudah memiliki bayang khalayak yang mana.
Misalnya di titik mempertanyakan siapa khalayaknya, pasti bayangan orang-orang yang bisa diajak berpikir secara rasional, itu saja. Mau banyak atau sedikit itu tidak masalah, intinya jika tertarik untuk melihat film secara rasional dan lebih jauh dan daripada sekadar, “Ah takut melihat film horror.” Bacalah kritik, dan itu selalu ada meskipun minoritas tapi minoritas tak terpermanai itu adalah istilah dari Goenawan Mohamad untuk publik sastra. Seringkali publik sastra itu sangat kecil, tapi cinta mereka keras kepala terhadap sastra. Jadi meskipun kecil tapi mereka ada di mana-mana dan selalu ada. Sama saja, jadi orang membuat kritik itu untuk publik yang tak terpermanai. Kenapa? Karena terserah mau banyak atau tidak, ajakan ini untuk berpikir bersama.
Pasti ada yang tidak setuju dengan isi kritiknya, tapi tentu mereka menggunakan kapasitas rasionalnya, jangan sampai tidak setuju karena, “Wah ini banyak orang pakai jilbab pasti resah.” Tahu dari mana? Itu kan tidak rasional, tapi kalau misalnya, “Menarik juga ya, memangnya konstruksi Islam dalam film relegi kita seperti itu ya? Kok saya tidak setuju ya, menurut saya konstruksinya begini.” Nah, itu kan jadi perbincangan rasional, karena tujuan dari kritik film atau karya seni yang lain adalah untuk menciptakan dialog dan percakapan rasional.
V
Proyek apa yang tengah dipersiapkan?
H
Saya sehari-hari di Komite Film, sehingga ada banyak program di komite film yang disiapkan. Konsentrasi saya sebetulnya adalah advokasi kebijakan film di Jakarta dan nasional, yang dilakukan bersama teman-teman Dewan Kesenian Jakarta sampai tahun 2018. Tapi saya juga punya perhatian khusus untuk produksi pengetahuan, saya ingin Kineforum benar-benar dioptimalkan fungsinya sebagai wahana produksi pengetahuan film maupun yang bersinggungan dengan film di masyarakat atau hal-hal umum. Film bisa kita baca sebagai wahana untuk narrating direction, tetapi narasi macam apa yang ada saat ini di film-film kita itu kan bisa diolah. Film bisa berkomentar juga menjadi salah satu konsentrasi saya. Tapi yang paling sibuk saat ini adalah tengah mempersiapkan program komik di Eropalia yang akan dimulai bulan Oktober 2017 sampai Januari 2018.
Sebenarnya saya ingin lebih memanfaatkan Eropalia, sebagai acara seni budaya yang biasanya memperlihatkan seni pertunjukan dan karena tahun ini fokus adalah Indonesia, maka kemudian akan ada banyak bentuk kesenian dan bentuk kebudayaan yang dihadirkan. Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud pun ingin memanfaatkan momen ini untuk mengenalkan Indonesia secara lebih jauh kepada Eropa. Acara ini akan ada di lebih dari 15 kota. untuk program komik ada salah satu fokus kotanya adalah Brussels dan seniman-senimannya antara lain Moki seniman komik dari Yogyakarta dan Yudha Sandy. Selain itu saya juga sedang mempersiapkan pameran Komik Indonesia tahun 1929 -2017. Jadi ini adalah sejarah. Sebagai kurator, saya banyak mendapatkan banyak bantuan dari Seno Gumira yang juga akan memberikan pengetahuan tentang budaya komik Indonesia di Muntpunt pada bulan November.
Sebagai salah satu kolektor yang kuat, Seno Gumira membantu saya dalam segi pemikiran maupun dari segi data dan arsip, kemudian juga bantuan dari Iwan Gunawan sebagai ketua jurusan di IKJ yang juga merupakan kolektor senior. Jadi saya mempunyai akses terhadap koleksi beliau sehingga sangat membantu saya dalam menyusun sejarah komik Indonesia secara praktis dan akan dituliskan secara lengkap nantinya. Kami bertiga memang memiliki keinginan untuk membuat sejarah komik Indonesia secara benar dan punya metode. Selanjutnya ada Adyaksa yang membantu desain yang mana adalah seorang kolektor juga dan masih banyak kolektor-kolektor lainnya yang terlibat atau membantu pameran ini. Dan saya ingin menjadikan ini sebagai momentum untuk komik Indonesia agar bisa masuk ke dalam petak komik dunia melalui pintu Eropa.
Sejauh ini tanggapan di sana sudah mulai banyak yang tertarik atau paling tidak kaget ternyata Indonesia punya sejarah komik yang sangat kaya. Kenapa program komik di sana menjadi sangat menggairahkan karena secara trinity, negeri komik di Eropa, Perancis, Belanda dan Belgia, ya cuma Belgia yang masih hidup. Brussels masih ibukota komik karena Belanda mulai sepi dan kering, Perancis tidak sebesar Brussels atau Belgia komunitas komiknya, sehingga tepat untuk membuat program komik di sana agar memperkenalkan komik Indonesia di negeri komik. Yang jelas dengan kesibukan itu saya seperti kuliah lagi tentang komik Indonesia karena memiliki banyak akses terhadap hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain, sehingga menghadirkan sekeping Indonesia yang cukup penting dan semoga nantinya bisa menjadi museum komik.











