Sinema dan Cerita bersama Wregas Bhanuteja
Muhammad Hilmi (H) berbincang dengan Wregas Bhanuteja (W).

























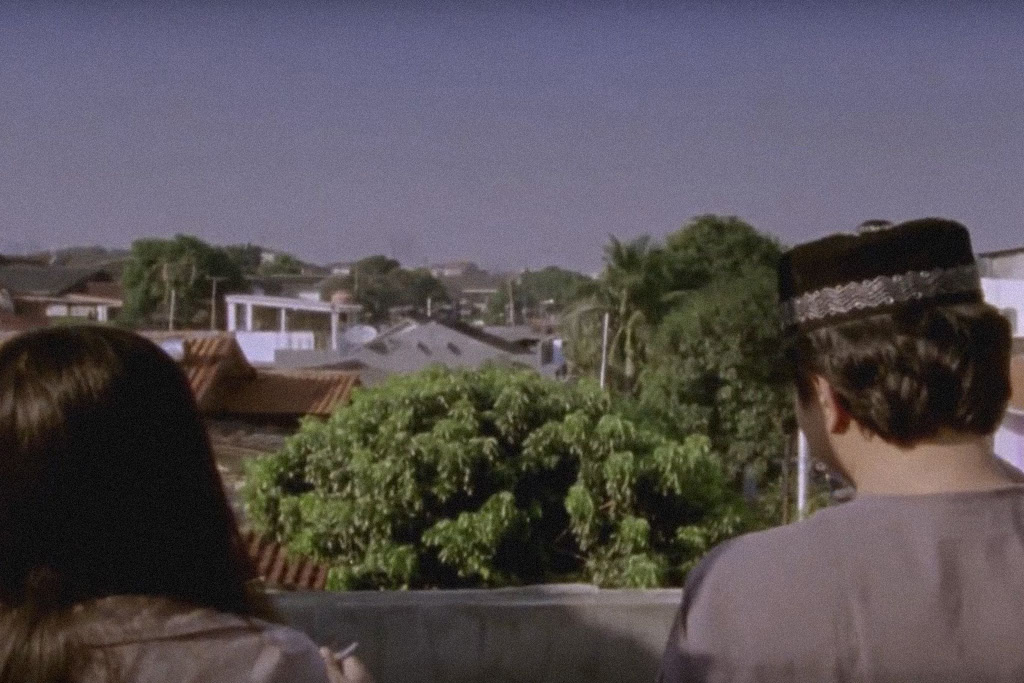
H
Film apa yang membuat Wregas terjun ke dunia sinema?
W
Gie. Karya Riri Riza ini sangat membekas di benak saya sejak saya menontonnya pada kelas dua SMP. Secara sinematografi, penyutradaraan, pesan dan cerita, film itu lengkap. Saking membekasnya, saya lalu membuktikan dan memamerkannya pada jahitan patch di bagian belakang jaket jeans ketika saya SMA. Sejak itu, saya tertarik dengan film.
Sebelumnya, saya hanya mengkonsumsi film Hollywood atau film lokal yang struktur penceritannya hanya tiga babak. Namun ketika kemudian menekuni dan terjun di dunia film saat kuliah di IKJ, saya menemukan bentuk lain dari sinema. Mata saya lantas terbuka melalui film-film Lars von Trier dari Denmark, hingga film karya Kim Ki-duk dari Korea Selatan. Dalam merubah cara pandang saya terhadap sinema, film Lars von Trier lah yang memiliki peran paling besar. Melalui filmnya, saya belajar bahwa film tak harus selalu naratif, bahwa kita juga bisa bereksperimen dengan berbagai elemennya, mulai dari sinematografi, hingga cara penuturannya.
H
Dari pengagum, Wregas kemudian bekerja bersama Riri Riza pada film Ada Apa Dengan Cinta 2, bagaimana ceritanya? Dan apa yang dipelajari dari kesempatan bekerja sama dengan Riri Riza itu?
W
Awal pertemuan kami sangat janggal. Antara tahun 2007 atau 2008, pas setelah film Laskar Pelangi rilis, saya liburan ke Belitung, tanpa ada niatan apapun. Di pantai saya mengenali sosok Riri Riza dengan rambut keritingnya yang khas, saya lantas menyapa dan mengajak foto bersama. Setelah itu, bertahun-tahun kami tidak ada kontak sama sekali.
Pertemuan kedua kami pun tak sengaja. Saat menonton sebuah pertunjukan teater di Salihara, saya melihat sosoknya lagi. Kebetulan saat itu saya sedang mencari tempat untuk magang. Saya lantas menghampirinya dan bertanya tentang produksi film yang sedang ia kerjakan. Ternyata sedang jalan produksi film Sokola Rimba di Jambi. Dengan modal nekat, saya lantas mengajukan diri untuk magang bersamanya. Riri Riza kemudian meminta portfolio saya, dan saya lantas mengirimkan film-film pendek saya. Ternyata saya diterima magang sebagai asisten sutradara ketiga, inilah titik pertama saya bisa bekerja bersama Riri Riza. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, dimana saya yang dulunya hanya merupakan penggemar filmnya, kini bisa melihat dapur di mana film itu dibuat. Saya bisa melihat langsung bagaimana Riri Riza menyutradarai pemain dan mengatur sinematografinya.
Beliau adalah guru saya. Salah satu hal yang saya pelajari dari kesempatan tersebut adalah mengenai perhatian Riri Riza terhadap detail, terutama pada pengaturan akting pemain. Dalam produksinya, Riri Riza bahkan sampai mengatur ke mana mata aktor harus melirik. Karena baginya, hal kecil seperti lirikan mata, kalau tidak diarahkan ke tempat yang tepat akan menciptakan mood yang berbeda. Aksi-reaksi, juga gestur pemain sangat diperhatikan olehnya. Secara cerita, Mas Riri lebih santai justru.
H
Tahun 2016 adalah tahun yang spesial bagi Wregas, terlibat di bagian dari kesuksesan AADC 2, juga prestasi Prenjak di level internasional. Bagaimana bisa seimbang di dua dunia yang lumayan berseberangan ini?
W
Di Ada Apa dengan Cinta 2 saya terlibat sebagai behind the scene director, dimana saya mengkonsepkan bagaimana alur cerita dan interview yang akan saya lakukan di sana. Saya melihat ini sebagai kesempatan berharga untuk belajar. Saya selalu menganggap bahwa dunia film mainstream dengan pola penceritaan yang sangat komersil adalah tempat saya untuk mencari pengalaman berbeda selain juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu di sini tentu bukan untuk mempelajari pola penceritaan yang ada di sana. Tapi lebih ke belajar mengenai workflow sebuah produksi yang baik itu seperti apa. Dan, dari sepengetahuan saya, tak ada yang lebih baik dari Miles Production dalam hal itu. Mereka adalah production house yang masih mempertimbangkan jam shooting yang manusiawi.
Jadi bidang komersil ini bukan berarti saya ingin ke sana nantinya. Tidak ada niatan sama sekali bagi saya untuk suatu saat nanti membuat film yang menuruti selera pasar. Tapi saya merasa perlu untuk menambah ilmu tentang alur produksi, keuangan, cara bekerja bersama investor, serta hal teknis lainnya.
Nah, Prenjak bagi saya adalah usaha supaya karya pribadi saya bisa seimbang dengan aktivitas di area komersil. Kalau saya terlalu lama dan terlalu dalam beraktivitas di komersil, saya tak akan punya waktu dan bahkan mungkin lupa untuk merefleksikan karya, ide dan gagasan pribadi saya.
H
Bagaimana hasil belajar Wregas di area komersil membantu pengembangan karya personal?
W
Yang paling bisa saya rasakan adalah saya bisa mengatur produksi jadi lebih efisien. Saya juga jadi lebih bisa berkomunikasi dengan kru, mengatur attitude dalam bekerja, dan ini adalah hal yang penting. Apapun gagasan yang diangkat sebuah film, kalau ada ketidaklancaran dalam proses shooting dan produksi, pasti akan ada penurunan kualitas. Dari Mbak Mira Lesmana, dan Mas Riri Riza, saya belajar mengenai bagaimana produksi yang baik berjalan.
H
Bagaimana rasanya mendapat prestasi internasional, namun publik lokal justru asing dan bahkan belum bisa menonton film Anda?
W
Saya menerima hal itu. Bahkan ketika saya membuat Prenjak, saya sadar bahwa film ini tidak mungkin tayang di bioskop, televisi atau YouTube, karena ada sensor di sana. Tapi prinsip yang selalu saya yakini setiap kali saya membuat film adalah setiap film memiliki penontonnya masing-masing. Untuk film ini, jika orang Eropa menonton film ini, maka saya sudah merasa sangat cukup. Memang di situlah tempat bagi film ini. Saya tidak ingin memaksakan bahwa orang Indonesia harus menonton dan harus suka terhadap film ini. Film itu tentang selera, layaknya kopi. Ada yang suka kopi susu, kopi dengan gula, tapi ada pula yang suka kopinya pahit. Kita tentu tidak bisa memaksakan kepada semua orang untuk menyukai kopi pahit.
Tentang film saya yang belum ditonton, saya menerima saja. Mungkin publik lokal juga belum siap untuk menonton film saya. Jika suatu saat nanti publik lokal bisa lebih terbuka terhadap literasi sinema, mungkin film saya akan dinikmati. Dan ini menjadi bonus bagi saya.
H
Kalau publik Eropa yang menjadi tujuan dalam berkarya, bagaimana Wregas memposisikan eksotisme kebudayaan timur-barat dalam film Wregas? Karena beberapa film, Wregas seperti bermain-main di posisi tersebut.
W
Kalau mengamati apa yang terjadi di festival internasional beberapa tahun belakangan, Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Thailand, memang cenderung menampilkan eksotisme lokal. Dari Thailand, Apichatpong Weerasethakul menunjukkan bahwa di Thailand itu ada roh, juga hutan. Atau juga Brilante Mendoza dari Filipina, yang menonjolkan area slump dan kemiskinan di negaranya.
Ke depan, saya ingin untuk tak terlalu menampilkan elemen eksotisme pada film saya. Di Prenjak, Lemantun, dan Lembusura, saya memang bermain di situ. Di karya yang akan datang, saya merasa perlu untuk menampilkan wajah Indonesia yang sebenarnya tidak se-miskin dan se-tradisional itu. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang modern, punya band-band keren, juga seniman dengan karya yang bagus. Ke depan saya ingin menunjukkan itu kepada dunia melalui festival film. Karena bagi saya, festival film adalah sebuah medium bagi kita untuk menceritakan seperti apa kondisi negara kita. Kalau saya hanya menampilkan eksotisme, kemiskinan, dan elemen-elemen yang disukai oleh orang bule, maka selamanya perspektif orang luar terhadap kita akan seperti itu. Bahwa Indonesia itu masih penuh dengan hutan, dan semua lelakinya memakai blankon.
H
Dalam sebuah interview, Wregas bercerita bahwa sejak awal berkarya, Cannes merupakan motivasi utama yang dituju. Kenapa tidak Piala Citra misalnya? Apakah menilai ada kekurangan di Piala Citra?
W
Ah… (tertawa). Saya mulai suka Cannes itu saat kuliah semester dua. Sejak itu, saya selalu memantau film apa yang masuk seleksi Cannes, dan dari seleksi film Cannes itulah saya lalu menonton setiap judulnya. Hampir semua film seleksi mereka saya suka. Setiap sutradara diberi kebebasan dalam mengekspresikan film sesuai dengan gayanya sendiri. Keberagaman style dijunjung dan dihargai di sana. Jadinya, Cannes merupakan ajang bagi sutradara untuk memberikan sumbangsih dalam bahasa sinema yang baru.
Piala Citra bukan tujuan utama bagi saya karena di ajang tersebut bahasa penceritaannya cenderung seragam. Hampir semua modelnya naratif, dan masih terjebak di konsep tiga babak. Dengan begitu, Piala Citra belum bisa menjadi gambaran atau wajah dari perkembangan sinema sekarang. Saya ingin memberikan sumbangan baru bagi bahasan sinema lokal. Dan itu belum bisa terakomodir pada Piala Citra.
H
Padahal sebenarnya kalau secara gaya, ada banyak yang berkembang di luar sana. Tapi masih sedikit yang diakui.
W
Bagi saya, ini mungkin ada hubungannya dengan pengetahuan masyarakat tentang sinema yang masih belum terlalu banyak. Ada banyak tawaran bahasa yang muncul di dunia sinema Indonesia. Seperti film Edwin yang Postcard from The Zoo atau Babibuta yang Ingin Terbang, atau Mouly Surya dengan What They Don’t Talk When They Talk About Love, ini adalah bentuk art sinema, tetapi film-film itu tidak bisa awet di bioskop karena harus disensor dan penontonnya tidak banyak. Ini karena masyarakat kita belum bisa memahami diversity dalam bentuk sinema.
Filmmaker adalah kumpulan orang yang sangat mencintai sinema, tapi tentu saja kecintaan masyarakat tentu tak sedemikian, dan filmmaker tidak bisa memaksakan itu. Analogi kali ini adalah tentang lukisan. Misalnya seorang kurator membawa karya abstrak Affandi ke publik, namun publik tak menyukainya, karena lebih suka yang realis seperti karya Basuki Abdullah, sang kurator tentu tidak bisa memaksakan seleranya. Ini mungkin ada hubungannya dengan sejarah sinema kita yang tidak sepanjang sejarah sinema Perancis, Italia atau Amerika misalnya.
H
Tentang aktor. Di bioskop, film Indonesia terasa seperti milik aktor/aktris tertentu saja karena hanya dia-dia lagi yang bermain film, dan ini semakin terasa belakangan ini. Bagaimana Wregas melihat kondisi yang demikian?
W
Kalau film bioskop, biasanya para produser punya kepentingan bahwa filmnya bisa balik modal dan untung. Kita sudah mengenal star system, dimana untuk menjual film, mereka butuh untuk menampilkan bintang, seperti Reza Rahadian, Lukman Sardi, atau Dian Sastrowardoyo. Meski sebenarnya kalau mau melihat lebih jauh, ada aktor dan aktris dengan talenta yang luar biasa. Seperti Sekar Sari yang bermain di Siti, misalnya. Atau pemain di film Vakansi Yang Janggal karya Yosep Anggi Noen, Joned Suryatmoko itu juga bagus sekali.
Meski mungkin nama-nama tersebut tentu akan diacuhkan oleh produser yang misi utamanya adalah balik modal. Karena mereka tak mau ambil resiko untuk bereksperimen kepada publik yang pandangan utama terhadap film adalah melalui wajah siapa yang dipajang di poster. Mereka lebih yakin untuk memasang muka Chico Jericho dan Tara Basro daripada Sekar Sari, misalnya. Pemikiran seperti ini masih sangat kental di industri film lokal.
H
Film Wregas, terutama film pendeknya, mulai dari Senyawa, Lemantun hingga Prenjak terasa mengambil inspirasi dari kejadian nyata, yang lantas dibuat seolah menjadi cerita fiksi. Apakah ini disengaja? Dan apa yang ingin disampaikan dengan gaya yang demikian?
W
Kisah pada film saya memang kebanyakan saya ambil dari pengalaman yang dekat dengan keseharian saya. Dengan mengambil pengalaman yang paling dekat, saya tahu betul mengenai apa yang terjadi di situ. Tentang modifikasi yang saya lakukan, itu betul sekali. Contohnya adalah pada film Lemantun, saya mengambil ide cerita dari kisah nenek saya, namun ending-nya saya ubah sedemikian rupa. Hal yang sama juga saya lakukan di Prenjak. Modifikasi ini saya lakukan for the sake of fiction, dalam artian dalam film saya, yang ingin saya sampaikan adalah cerita di dalamnya, tanpa ada misi-misi tertentu di dalamnya.
H
Yogyakarta terasa memiliki tempat yang spesial di karya-karya Wregas, bagaimana pengaruh kota ini terhadap karya dan pola berpikir Wregas?
W
Saya tumbuh besar di sana, keluarga dan sahabat saya hidup dan tinggal di sana. Namun, Yogya baru terasa istimewa ketika saya meninggalkannya. Saat kuliah di Jakarta, saya baru merasakan itu. Disini, ritmenya serba cepat, temperamen lebih meningkat, dan di antara suasana baru Jakarta ini, saya jadi kangen dengan suasana Yogya. Mungkin akan berbeda bila saya tak pernah meninggalkan Yogya sama sekali, saya mungkin akan merasa bahwa Yogya itu biasa saja, dan mungkin justru film saya tak akan bercerita tentang Yogya.
H
Bagaimana bila misalnya Wregas membuat film tentang Jakarta?
W
Mungkin jadinya akan lebih sarat emosi. Mulai dari cerita dan tokohnya mungkin akan terhubung dengan kemarahan. Yang jelas tone-nya akan berbeda dengan film Lemantun yang hangat itu. Kamera lebih hand-held, dengan editing yang lebih cepat. Style-nya akan lebih keras. Kenapa demikian? Ya karena itulah yang saya rasakan di kota ini.
H
Selain film pendek yang berbasis pada narasi, Wregas juga beberapa kali membuat film yang pendekatannya lebih eksperimental. Apakah ada perbedaan metode ketika mengerjakan dua yang gaya berbeda ini?
W
Untuk film eksperimental, saya membuat dua judul, satunya adalah Lembusura, dan The Floating Chopin. Pada kedua film itu, saya bermain dengan elemen unconsciousness. Alur kerjanya tidak dimulai dengan skenario yang kita rancang, polanya diawali dari respon saya terhadap peristiwa yang sedang saya hadapi. Contohnya Lembusura, kalau saat itu Gunung Kelud tidak meletus dan tak ada hujan abu di Yogya, maka film itu tak akan ada. Saat itu saya sedang di tengah proses shooting, namun tiba-tiba hujan abu turun, membuat saya tak bisa beraktifitas. Untuk mengisi waktu, saya mengambil gambar hujan abu itu, mengumpulkannya dan menggabungkannya dengan tarian teman yang berperan sebagai tokoh Lembusura-nya. Tanpa skenario atau apapun, jatuhnya lebih ke spontan saja. The Floating Chopin pun demikian. Saat liburan ke Paris, saya mengunjungi makam Frederic Chopin, dari pengalaman itu saya kembangkan jadi cerita fiksi dan jadilah film tersebut.
Di film eksperimental, skenario dan kisah baru tercipta di meja editing. Tak ada penjelasan teknis kenapa saya mengambil dengan angle tertentu untuk menggambarkan suatu adegan. Keputusan diambil berdasar unconsciousness, semuanya terjadi secara spontan.
H
Jadi kalau boleh menggarisbawahi, baik di karya film naratif maupun eksperimental, pendekatan atau karakter utama Wregas dalam membuat film adalah merespon sekitar?
W
Bisa dibilang begitu, beberapa teman juga sempat menyatakan demikian. Saya cenderung tergerak untuk membikin film kalau ada peristiwa yang mengganggu benak saya. Lemantun saya buat karena saya tergerak dari kisah Pakde saya, Prenjak itu karena saya melihat teman SMA saya yang hamil di luar nikah, Lembusura karena hujan abu, dan seterusnya. Jadi mesti ada sebuah peristiwa yang terngiang di kepala saya hingga berminggu-minggu untuk kemudian bisa saya filmkan.
H
Saya ingat nama Wregas pertama kali muncul pada video klip dari Efek Rumah Kaca, terakhir Wregas juga membuat video klip untuk Rabu, Bagaimana Wregas memposisikan musik dalam film?
W
Kok tahu? (tertawa). Di film, saya melihat musik adalah medium untuk memberi penekanan pada cerita yang ingin saya bangun. Sebagai filmmaker saya tidak terlalu suka dengan film yang setiap scene-nya diisi musik. Saat pemerannya sedih, musiknya sedih, saat senang, musiknya berbunga-bunga. Bagi saya fungsi musik pada film mirip dengan opsi bold/underline di word processor, tidak lucu kan kalau artikel semua font-nya di bold? Kecuali kalau kita bikin sinetron, semua memang harus ada efek suara “jeng..jeng..jeeeng”-nya. Untuk film, tentu kita tidak bisa begitu. Musik disini membantu saat akting dan adegan tak bisa melukiskan suasana yang ingin kita ciptakan pada film.
H
Siapa kira-kira band yang ingin Wregas kerjakan videonya?
W
Keinginan selalu ada untuk membuat video klip. Tapi untuk membuat video klip, saya harus mendengar lagunya terlebih dahulu. Dan, lebih dari itu, lagunya harus terngiang di kepala saya. Seperti layaknya ketika saya membuat film, saya membuat video klip Efek Rumah Kaca dan Rabu karena lagu mereka terus terngiang dan terbayang visualnya.
Ada musisi dari Yogya, namanya Gardika Gigih. Ia beberapa kali membuat musik untuk film saya. Nah, barusan ia membuat album baru. Biasanya ia membuat komposisi tanpa vokal, kali ini ada lagu yang bervokal, dan nyangkut di kepala saya. Jadi mungkin yang terdekat bagi saya adalah Gardika Gigih.
H
Tentang Studio Batu yang dulu Wregas gagas bersama teman-teman, apa misinya dan apakah Wregas masih aktif di situ?
W
Studio Batu adalah komunitas yang terdiri dari berbagai aktivitas, tak hanya film saja, senirupa, musik, dan teater. Justru yang film di situ cuma saya. Tapi tak jarang ketika saya bikin film, saya meminta bantuan mereka. Saat saya di Jakarta, mereka di Yogya akan aktif dengan kegiatannya masing-masing. Mulai dari bikin pameran, berpartisipasi dalam Festival Kesenian Yogyakarta, hingga bikin merchandise. Jadi tak ada saling menunggu. Saya berkegiatan, merekapun begitu.
Studio Batu merupakan kumpulan teman-teman saya sejak SMA, dan kami berkumpul karena memiliki satu kesamaan, kami suka ketika berbagai orang berkumpul, lalu berdiskusi di sana dalam sebuah forum. Kami sangat menikmati ketika kami bersama-sama mendiskusikan film, puisi, dan sebagainya. Kami ingin menciptakan ruang dimana diskusi-diskusi semacam itu hidup dan berlangsung secara kontinyu. Mungkin contoh riilnya adalah Komunitas Salihara. Dimana kita bisa membuat pemutaran film, teater, pameran seni rupa dan mendiskusikannya bersama-sama.
H
Sejauh ini, film Wregas kebanyakan formatnya film pendek. Bagaimana kira-kira bentuk film panjang karya Wregas?
W
Sebenarnya saya sedang mempersiapkan itu. Karena menang Cannes kemarin, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti development lab yang berfokus pada skenario. Akan ada mentor yang memberi masukan soal penyutradaraan dan secara skenario. Kalau boleh jujur, saya belum terbayang seperti apa nantinya film panjang saya, tapi yang jelas film saya tidak akan membuat film yang bermain-main dengan eksotisme lagi. Di film panjang pertama, saya ingin menunjukkan anak muda berusia 20-an di tahun 2016 dengan segala problematikanya. Saya ingin film panjang pertama saya menjadi penanda zaman yang merangkum era sekarang. Tentang McDonalds, sepatu New Balance, Vespa matic. Unsur-unsur itu ingin saya rekam dan abadikan, supaya kelak ketika di masa yang akan datang orang menonton film saya, orang akan tahu bagaimana situasi zaman yang sedang kita alami sekarang.
Ceritanya seperti apa, saya belum tahu. Yang sudah terbayang di kepala saya adalah tokoh berusia dua puluh lima-an, hidup di tahun 2016, dan sedang menghadapi problematika kehidupannya.
H
Tapi yang jelas, pemainnya bukan Reza Rahadian ‘kan?
W
Tentu saja bukan (tertawa).
H
Sebagai representasi generasi baru di dunia sinema, apakah Wregas memiliki manifesto yang berbeda dengan generasi sebelumnya?
W
Kita melihat negara-negara seperti Iran, Thailand, dan Korea memiliki figur atau filmmaker dengan bahasa sinema yang khas. Sehingga dengan hanya menonton sekilas kita akan tahu, siapa sutradaranya. Di Indonesia, saya rasa belum ada satu sutradara yang dipandang dunia memiliki bahasa sinema yang khas. Mungkin yang mendekati adalah Mas Garin Nugroho dengan arthouse-nya. Meski begitu, Mas Garin belum memiliki karya sebanyak Kim Ki-duk atau Abbas Kiarostami yang konsisten pada style-nya dan penampilan di film festival, seperti Cannes atau Berlin.
Saya ingin mencoba untuk konsisten dengan gaya saya, dan mengusahakannya di level internasional, sebagai sumbangan saya kepada bahasa sinema Indonesia kepada dunia.
H
Bagaimana melihat kajian film bisa memasuki berbagai dimensi seperti pada acara Ubud Writers & Readers Festival yang lebih dekat dengan bahasan sastra dan literatur?
W
Saya merasa ini adalah perkembangan yang positif. Film adalah cabang seni yang lahir terakhir. Film lahir karena sastra, teater, hingga seni rupa. Tanpa hal-hal itu, film tak akan ada. Mungkin, melalui Ubud Writers & Readers Festival akan membawa kita untuk menelisik roots dari film itu sendiri, yakni sastra. Menelusuri akar sebuah kebudayaan, adalah aktivitas yang penting. Apalagi ketika konteksnya sastra dan literatur. Kita semua tahu kalau tulang punggung sebuah film adalah cerita. Secanggih apapun sinematografi, jika roots cerita tak kuat, maka film tersebut akan terlewatkan begitu saja.
Di Ubud Writers & Readers Festival, saya diajak untuk berbicara tentang konteks perempuan di Prenjak. Walaupun sejujurnya, saya tidak terlalu memahami teori feminisme dan pergerakannya, saya belum mempelajari konsep ini. Jadi di sana saya akan membagi perspektif tentang bagaimana perempuan bagi saya adalah sosok yang kuat. Saya yakin akan terjadi diskusi yang menarik di sana.
H
Besar di scene film festival, bagaimana kira-kira karya Wregas jika suatu saat nanti membuat karya untuk bioskop?
W
Yang paling dekat bagi saya adalah produksi film panjang yang saya ceritakan tadi. Tapi, bioskop bukan tujuan utama saya, saya lebih fokus pada festival internasional. Prinsipnya film saya harus sudah mencukupi diri sendiri sebelum naik ke bioskop. Jadi saya tidak memiliki kekhawatiran bahwa film saya harus mencapai sekian juta penonton atau saya bangkrut. Proses yang demikian akan mengganggu proses kreatif saya. Jadi penonton di bioskop lebih ke bonus saja.
Mungkin jika film saya meraih prestasi yang mengesankan di festival internasional, akan ada produser atau distributor yang menayangkannya di bioskop. Kalau begitu mungkin film saya akan bisa ditonton di bisokop.



