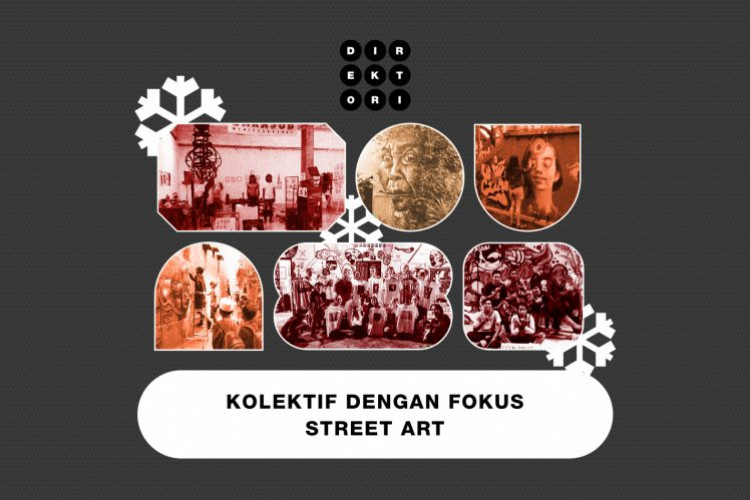The Popo Tidak Anonim bersama Riyan Riyadi
Ken Jenie (K) berbincang dengan seniman Riyan Riyadi aka The Popo (P).
by Ken Jenie





















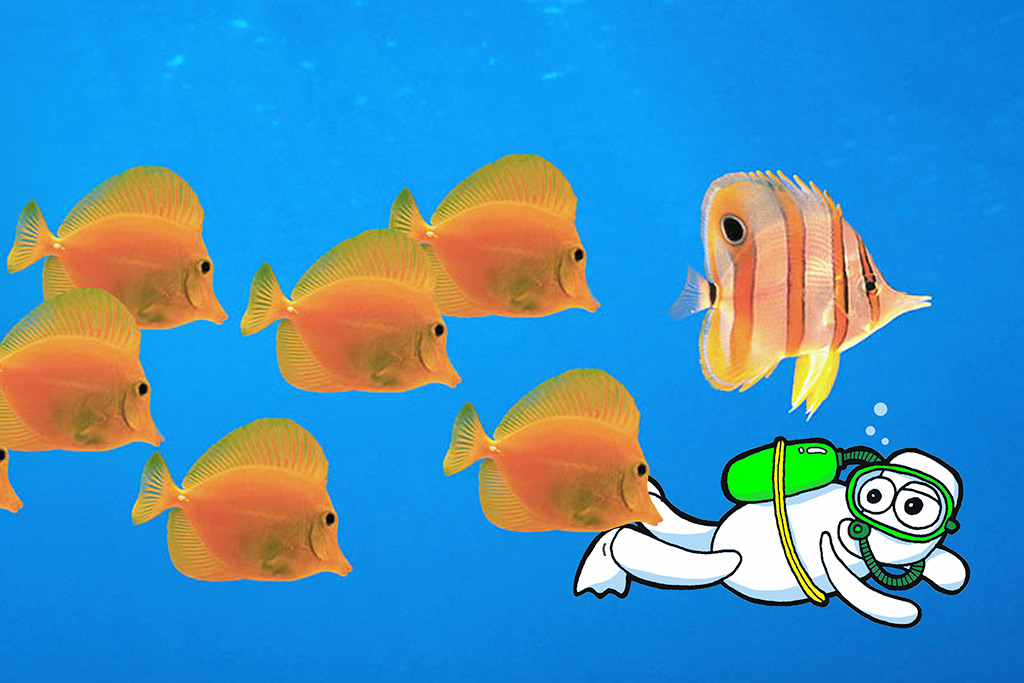


K
Kalau tidak salah, Popo mulai gemar menggambar sejak SD, seperti apa awal mula perkenalan Popo dengan dunia gambar ini?
P
Benar sekali. Saya mulai menggambar memang sejak SD. Sebenarnya, saya jadi suka dan sering menggambar sebagai cara saya berkomunikasi dengan ayah saya. Saya tidak terlalu dekat dengan beliau. Jika biasanya anak-anak ketika ingin punya mainan baru bisa langsung meminta ke ayahnya, entah kenapa saya tidak bisa seperti itu. Ayah saya cukup galak, dan tegas. Maka dari itu, jika saya ingin punya mainan baru saya “meminta” nya melalui gambar di tembok rumah. Misalnya saya ingin punya tamiya, saya lalu menggambar mobil tamiya di tembok kamar saya. Awalnya, ayah saya selalu menutupi gambar saya dengan cat baru, tapi saya selalu menggambar keinginan saya lagi sampai ayah saya membelikan mainan yang saya inginkan.
Saat itu, saya belum menyadari bahwa saya melakukan aktivitas menggambar untuk tujuan komunikasi non-verbal. Selain sebagai cara untuk meminta mainan, saya juga menggambar untuk menceritakan apa yang saya rasakan. Ketika saya senang, saya menggambar, begitupun ketika saya marah. Ini pilihan yang lebih menyenangkan daripada untuk menangis ketika sedih atau marah, karena jatuhnya saya bisa jadi dihukum oleh ayah saya. Kesenangan ini berlanjut hingga sekarang. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan ayah saya yang membelikan satu set spidol berwarna sebagai hadiah ulang tahun kepada saya, sebuah hal yang mungkin membuat beliau menyesali keputusannya itu. Melihat bagaimana spidol yang beliau hadiahkan kepada saya membuat dinding rumah, buku pelajaran sampai ijazah SD, SMP, SMA saya penuh coretan. Beliau akhirnya merebut dan kemudian membuang spidol warna tersebut. Tapi ternyata saya terus menggambar sampai sekarang (tertawa).
K
Apa saja bentuk coretan Popo saat itu?
P
Masih sama saja sebenarnya, saya menggambar untuk menceritakan tentang apa yang saya rasakan. Jika suatu saat saya kesal dengan salah satu guru yang galak dan menyebalkan, maka saya akan menuangkan kegelisahan saya tersebut dalam coretan di buku pelajaran. Mungkin sama posisinya dengan twitter di jaman sekarang.
Ketika masuk SMP, saya mulai terpapar dengan MTV dengan video musiknya. Saya lantas mulai menggambar instrumen musik, dan segala macam hal yang saya lihat di channel tersebut seperti skateboard dan lain-lain. Selain itu, ada juga masanya ketika sedang tren sepeda balap, saya jadi sering menggambar sepeda. Saya sempat mengumpulkan gambar-gambar saya dari SD, jadinya arsip saya ini seperti rekaman apa yang terjadi di setiap era, misalnya era skateboard, sepeda dan lain-lain. Gambar yang saya buat untuk model komunikasi di keluarga ternyata bisa menjadi dokumentasi apa yang terjadi di sekitar saya. Tapi sayang, arsip ini lalu hilang entah kemana.
K
Gemar menggambar sejak kecil, tapi ketika kuliah Popo justru mengambil jurusan komunikasi. Kenapa?
P
Sebenarnya keputusan ini berdasar pada ketidaksengajaan. Saya lulus SMA dan mulai mencari kampus untuk kuliah. Saya sempat lolos seleksi di IKJ, tapi ayah saya tidak menyanggupi biaya kuliahnya yang mahal. Lolos di ISI Jogja, tapi saya dicegah karena jaraknya yang jauh, sedangkan saya anak laki-laki yang selalu diandalkan di rumah. Lolos di ITB, tapi ayah saya juga mencegah. Ternyata, alasan utama ayah saya untuk mencegah saya kuliah di kampus-kampus seni tersebut adalah beliau kurang suka kalau saya kuliah di jurusan seni. Tapi beliau selalu menutupi ini dengan berbagai alasan lain.
Ketika beberapa teman saya setelah SMA kemudian masuk ke Institut Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, saya ikut-ikutan mendaftar saja. Ternyata masuk dan saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi dengan pendalaman media massa. Di masa kuliah, saya jarang menikmati kelas-kelas saya. Saya merasa materi yang diajarkan dosen di kelas telah saya pelajari dan dalami di kehidupan sehari-hari saya. Jadinya kelas terasa mubazir, selain teori akademisnya mungkin. Kuliah saya jadi terbengkalai, saya lebih suka nongkrong, saat itu saya juga mulai kenal dengan teman-teman di IKJ, ITB dan ISI. Saya juga mulai ikut lomba mural, dan masuk ke dalam scene seni rupa yang seumuran dengan saya.
Saat saya mulai tidak konsentrasi kuliah, ayah saya lalu bercerita bahwa alasan utama kenapa beliau mencegah saya untuk masuk kuliah seni adalah supaya jika nantinya saya jadi seniman, saya memiliki perspektif yang berbeda dengan tipikal seniman yang kuliah seni. Ternyata, visi ayah saya tersebut cukup berharga buat saya, dalam berkarya saya kini merasa bahwa saya bisa mengangkat isu sosial dalam karya saya dengan perspektif yang berbeda.
K
Ini cukup menarik, jadi Popo melihat perspektif berkarya dari seniman yang kuliah seni dan seniman yang kuliah komunikasi menghasilkan karya yang berbeda? Dimana letak perbedaannya?
P
Banyak dari teman saya yang kuliah seni, berkarya sesuai materi atau acuan dosen yang diajarkan di kelas seni. Karena saya tidak mendapatkan arahan dalam berkesenian di kampus, maka saya berkarya berdasarkan apa yang saya lihat di lingkungan sosial saya. Saya secara tidak langsung melakukan riset terhadap kondisi sosial untuk saya olah jadi karya visual.
Jadi ketika seniman lain berangkat dengan bekal teori kesenian dalam berkarya, maka satu-satunya bekal saya dalam berkesenian adalah apa yang saya alami di sekitar. Itu yang saya selalu ceritakan di karya saya. Ini mungkin juga awal lahirnya konsep sosial yang cukup kuat pada karya saya.
Yang saya lihat di jaman saya kuliah, awal tahun 2000an, sedang terjadi demam penggunaan komputer dalam berkarya. Maka dari itu, sedang gencar pengajaran berbasis komputer, dan para dosen sedang berusaha menyesuaikan materi mereka dengan teknologi baru ini. Jadinya materi mereka cenderung kaku. Kalaupun ada materi di luar itu, kebanyakan hanya menceritakan aliran lukis seperti realis, surealis atau dadaisme. Saya berkarya tanpa modal pengetahuan semacam itu. Apapun yang saya buat atau lakukan, saya tidak tahu nama atau definisinya. Mungkin justru jika saya tahu tentang aliran-aliran tersebut, apa yang saya lakukan justru terbatas sesuai definisi aliran yang sudah ada.
Ini juga terjadi dalam konteks aktivitas saya di dunia graffiti. Di tahun 2005 sedang booming seni graffiti. Tapi kebanyakan teman saya hanya memahami graffiti sebagai teknik berkarya dengan cat semprot, pylox, vandalisme, budaya New York atau Brooklyn, Hip-Hop dan semacamnya. Saya sendiri lebih suka memahami graffiti dari apa yang saya lihat di tempat saya hidup. Bahkan ketika saya mencoret tembok di jalanan, itupun sebenarnya bentuk graffiti juga sejatinya. Pemahaman pribadi saya ini membuat saya bebas untuk berkarya dengan apapun yang ada di tangan saya.
K
Popo juga berprofesi sebagai dosen, bagaimana cerita dibalik profesi ini?
P
Saya adalah dosen praktisi di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta meskipun kuliah saya di jurusan Komunikasi tidak selesai. Untuk menjadi seorang dosen praktisi, seseorang harus intens di dalam bidangnya selama kurang-lebih 10 tahun. Dosen praktisi bukan dosen tetap, tetapi bisa membuat silabus sendiri. Pertimbangan kampus IISIP untuk mengajak saya sebagai dosen praktisi berdasarkan mereka mengikuti karya saya, dan menurut mereka keahlian saya bisa dibagikan kepada teman-teman di kampus.
Mata kuliah yang saya ajarkan adalah Komunikasi Visual, dan sebenarnya sudah ada silabus yang dibikin oleh dosen-dosen yang lebih paham. Tetapi saya diberi keistimewaan untuk bikin silabus sendiri – saya membawa perspektif saya ke dalam kelas. Sebenarnya saya tidak tahu cara membuat silabus – saya presentasi karya saya saja.
Misalnya murid-murid fotografi ke Jogja, saya memberi mereka tugas seperti ini: saya memberi mereka tugas untuk mengambil foto yang bercerita mengenai Jogja. Sebelum mereka mengerjakan tugas, saya membuat sebuah list 10 item yang mereka tidak boleh foto, tetapi saya tidak kasih lihat mereka. Saat mereka membawa hasil tugas mereka ke kelas, saya membukakan catatannya yang berisi item seperti gudeg, Keraton, dan lainnya. Saya berkata bahwa jika mereka telah foto item yang ada di catatan ini, mereka tidak mendapatkan nilai. Yang saya ingin kasih tahu mereka ini: kalau ingin bercerita melalui foto mengenai Jogja, orang harus lebih peka tentang kehidupan penduduk di luar sisi wisatanya. Dari 40 murid, yang mendapatkan nilai hanya satu orang.
K
Oh ya? Dia bercerita tentang apa?
P
Dia membahas mengenai Trans Jogja, yang serupa dengan Trans Jakarta. Dia menjelaskan lokasi-lokasi rute Trans Jogja yang sampai ke Borobudur, dan ia berkata bahwa sebenarnya Jogja tidak perlu menciptakan Trans Jogja – dia meriset sendiri mengenai transportasi ini. Trans Jakarta kan dibikin sebagai solusi mengurai tentang kemacetan, dan Jogja semacet-macetnya masih jalan.
Sebenarnya ini licik saja kepada adik kelas, mungkin lebih bagus ilmunya dia. Berhubung di kelas dia membahas risetnya, saya juga jadi lebih tahu mengenai sebuah topik (tertawa).
Ketika mereka di Jogja saya juga memberi mereka list tempat untuk mereka datangi seperti Cemeti Art House dan Kunci Cultural Studies Center. Mereka bertanya tempat-tempat ini apa, dan saya menjawab bahwa mereka yang harus mencari tahu apa tempat-tempat ini. Kalau ke Jogja tidak harus ke Malioboro – gila banyak banget foto Malioboronya (tertawa). Hubungan antara Jogja dan Malioboro sudah tidak perlu di ceritakan lagi, Malioboro sudah identik dengan Jogja.
Ini cara saya mengajar karena saya sedih melihat ilmu-ilmu dasar jurnalistik di kampus saya berkutat kepada foto kecelakaan, dan harus berbasis di kantor polisi. Kalau diceritakan menyedihkan banget. Contohnya teman saya yang cum laude menjadi wartawan infotainment… kalau menjadi wartawan infotainment tidak perlu kuliah – ini menjadi beban moral buat saya sebagai pengajar. Menurut saya, bagus atau tidak, harus ada cara lain untuk mengajarkan ilmu jurnalistik. Sekolah saya (IISIP) adalah sekolah jurnalistik tertua, dan saya sedih melihat teman saya tidak bisa memakai ilmu mereka.
K
Apa yang membuat Popo akhirnya berkarya sebagai seniman jalanan?
P
Pada awal saya berkarya di bidang ini, sebenarnya saya tidak tahu apa itu seni jalanan. Saya terjun di bidang ini karena kebetulan teman nongkrong saya banyak yang berkarya sebagai seniman jalanan. Jadi mereka cukup berperan dalam membentuk karakter saya. Mungkin, jika saya nongkrong di tempat berbeda, saya bisa jadi pribadi yang berbeda. Misalnya jika saya nongkrong di Taman Ismail Marzuki atau Ancol, saya akan tampil dengan rambut gondrong dan tidak seperti sekarang (tertawa). Bisa jadi, jika saya bermain di tempat yang berbeda, pola pikir saya akan jadi klenik, hanya berkarya di kanvas, dan mengagung-agungkan seni di atas segalanya. Jadi, meski saya secara kebetulan terjerumus berkarya sebagai seniman jalanan, saya bersyukur.
K
Di sisi lain, Popo juga tak jarang berpartisipasi di event “seni murni”, sedangkan pemahaman umum tentang seni jalanan adalah lawan kata dari seni di galeri dan semacamnya. Sebagai seniman yang berkarya pada dua dunia tersebut, bagaimana Popo melihat pemahaman yang demikian. Apakah Popo menggunakan teknik yang berbeda ketika berkarya di jalanan dan di galeri?
P
Dalam aktivitas saya berkesenian, saya mempraktekkan berbagai pendekatan, mulai dari fine art, kontemporer hingga urban art. Saya memasuki dan berinteraksi pada berbagai ruang tersebut. Saya lebih suka memahami berbagai konsep seni tersebut sebagai media saya dalam berkesenian. Tentu saja ada pendekatan yang berbeda untuk berkarya pada medium yang berbeda.
Pertanyaan semacam ini pernah muncul dari teman saya sesama street artist. Dia mempertanyakan keputusan saya untuk memajang karya di galeri, padahal saya adalah seniman jalanan. Saya menjawabnya dengan menjelaskan bahwa sebenarnya street art, setidaknya menurut pemahaman saya tidak terbatas pada konteks jalanan sebagai tempat memamerkannya, tetapi lebih ke memamerkan karya di public space. Dan, bagi saya galeri adalah salah satunya. Dan saya tidak melihat ini sebagai masalah. Asalkan saya tetap memiliki strategi yang disesuaikan dengan tempat dimana saya berkarya. Ini membawa saya ke berbagai kemungkinan dan kesempatan. Salah satunya adalah untuk berkarya di ruang edukatif, dimana saya harus membatasi karya saya supaya tidak rancu maknanya di ruang tersebut. Berkarya di tempat seperti galeri seni bukan masalah bagi saya, selama saya masih memiliki kebebasan dalam berkarya dan menuangkan apa yang ingin saya sampaikan. Sama halnya dengan ketika saya bekerja dengan proyek iklan, saya justru melihat itu sebagai kesempatan untuk mengadu idealisme saya dengan pihak pengiklan. Dan itu seru karena selain saya bisa berkarya, saya juga bisa melakukan riset di dalamnya.
Saya sendiri melihat diri saya sebagai seniman yang serakah. Karena semua jenis media, kesempatan selalu saya terima dan kerjakan.
K
Dari pengamatan saya, awalnya ketika seniman jalanan pameran di galeri seni, yang ditampilkan hanya sebatas eksotisme saja. Dimana galeri seni komersil tersebut cenderung hanya mengeksploitasi aspek jalalan untuk dipamerkan di ruang putih mereka. Apakah Popo juga melihat hal yang sama?
P
Banyak diantara galeri seni yang mengundang saya memiliki pemahaman yang persis sama dengan apa yang diceritakan tadi. Mereka mengajak seniman jalanan untuk berkarya di galeri komersil karena mereka melihat bahwa tampilan street art di galeri menciptakan keunikan tersendiri. Sesederhana itu. Tapi saya tidak melihat ini sebagai masalah.
Bahkan ketika saya berkarya di pameran galeri seni komersil, saya tidak menghindari komersialitas itu. Yang paling penting bagi saya adalah ketika berpameran di galeri komersil, saya tidak lantas mempermanis karya saya supaya lebih mudah laku. Dimanapun tempatnya, bentuk karya saya akan sama. Jadi karya saya di galeri komersil tersebut tidak akan lebih “indah” dan lebih “rapi” dibanding karya saya di jalanan. Tidak jarang ketika saya berpartisipasi pada sebuah pameran, karya yang saya tampilkan justru menyindir dan mentertawakan pameran itu sendiri.
K
Satir cukup sering muncul di karya Popo, dan sepertinya Popo melihat sebagai cara yang pas untuk menyampaikan realitas hidup atau kritik kepada masyarakat. Saat tragedi di Sarinah terjadi, ada beberapa artikel online yang menulis tentang bagaimana masyarakat menjadikan tragedi tersebut sebagai bahan candaan melalui akun sosial media, adalah cara dari orang Indonesia untuk menghadapi keresahan hidup dengan meringankannya. Namun ada juga yang melihatnya sebagai bentuk apatisisme masyarakat Indonesia terhadap apa yang terjadi di negaranya. Menurut Popo, apa sebenarnya peran humor dalam keseharian masyarakat Indonesia?
P
Yang perlu dipahami dalam menempatkan humor di masyarakat kita adalah bahwa setiap orang memiliki batasan masing-masing dalam menertawakan sebuah komedi. Apalagi kalau kita membahas humor dalam konteks tragedi. Untuk itu kita mesti tahu angle apa yang bisa diangkat dalam membuat sebuah meme mengenai kejadian kurang mengenakkan. Dalam keadaan yang seperti ini, saya biasanya lebih menikmati untuk mengambil perspektif dari apa yang terjadi di sekitar kejadian tadi, ketimbang misalnya untuk membuat meme mengenai pelaku teror atau korban yang akan justru menyakitkan ketimbang untuk memancing tawa. Kita harus peka dalam melakukannya.
Bagi saya, sebuah humor atau komedi yang baik adalah yang bisa mengambil sudut yang pas. Humor seperti inilah yang tidak akan garing.
Dalam menciptakan karya yang humor, saya selalu lebih berhati-hati. Ketimbang misalnya ketika saya sedang menyampaikan kekesalan. Kekesalan itu lebih sederhana dan bisa disampaikan dengan dengan cara yang lebih direct, lebih langsung. Dalam menceritakan humor, seperti yang saya ceritakan tadi, semua orang memiliki level masing-masing. Saya juga pernah gagal dalam berkarya dalam koridor humor ini, dimana orang-orang menegur saya atas gambar atau teks saya yang menyinggung. Tapi saya justru belajar banyak dari momen humor yang gagal seperti ini. Tentang apa saja yang bisa saya lakukan dan apa yang harus saya hindari dalam berkarya.
Tapi yang saya lihat adalah memang pada dasarnya masyarakat Indonesia itu sangat humoris. Meski kadang, sekarang pada beberapa kasus, masyarakat juga semakin sensitif. Itu kuncinya disitu. Mencari jalan tengah diantaranya.
Sebagai seniman, dengan karakter masyarakat yang demikian, saya sangat menikmati berkarya dan menyampaikan gagasan melalui komedi. Karena saya sebagai personal juga pada dasarnya bukan pribadi yang serius. Jadi pada level tertentu, karya yang humoris adalah cara saya dalam berkarya secara jujur. Toh, kita hidup di antara banyak kejadian yang bahkan sudah lucu tanpa harus kita menjadikannya sebagai meme. Banyak karya saya yang sifatnya tinggal re-post dari apa yang terjadi di keseharian. Dan tipe re-post seperti ini justru yang bisa menyentuh orang banyak.
K
Meskipun berbasis satir dan humor, pada sebuah artikel disebutkan bahwa dalam berkarya, Popo selalu menjalankan riset. Seperti apa bentuk riset versi Popo ini?
P
Riset saya lakukan diantara aktivitas keseharian. Misalnya tentang sebuah karya saya di salah satu tembok di jalan TB Simatupang. Saya hampir setiap hari melewati jalan tersebut, dan selalu macet banget. Akhirnya pada satu kesempatan saya menuliskan, “Jangan pucet lihat Jakarta macet” di sebuah tembok tol disana. Secara tidak langsung proses saya melewati jalanan tersebut setiap hari dan merasakan kemacetan di sepanjang perjalanan adalah riset buat saya, yang melahirkan karya saya tersebut.
Ini kenapa karya saya selalu memiliki konteks lokalitas di dalamnya. Karya saya kebanyakan selalu site specific. Saya akan lebih memilih untuk menulis tentang kemacetan di tembok jalanan Jakarta ketimbang untuk menggambar konflik Palestina disana, karena bagi saya itu terlalu jauh dan jadinya tidak relevan dengan apa yang ada disana. Mungkin, saya akan menggambar tentang Israel – Palestina jika saya berangkat ke Gaza.
Saya selalu berusaha untuk bekerja sama dengan ruang dimana karya saya akan hidup. Dalam berkarya, saya ingin mengangkat cerita yang ada disana. Jadi nyata dan tidak mengada-ada. Inilah yang mungkin membuat karya saya tersebut kemudian banyak tersebar di sosial media. Orang-orang merasa terwakilkan atas apa yang saya gambar dan tuliskan.
Hal yang sama terjadi juga dengan karya saya di daerah Antasari ketika sedang ada pembangunan flyover. Demi pembangunan fondasi jalan tersebut, banyak pohon kemudian ditebangi. Saya meresponnya dengan menggambar dan menuliskan tagline, “Demi Flyover, Pohon Game Over” di salah satu temboknya.
K
Dalam mengumpulkan cerita ini, apakah terjadi interaksi dengan warga sekitar? Karena saya sempat membaca bahwa Popo juga berkolaborasi dengan warga dalam berkarya…
P
Nah, ini ada hubungannya dengan karya saya di Antasari tadi. Ketika suatu saat petugas jalanan mau menghapus karya saya tersebut, ternyata warga sekitar mencegah mereka. Warga sekitar merasa tagline “Demi Flyover, Pohon Game Over” tersebut sangat pas dalam menangkap cerita di area itu. Mereka jadi ikut merasa memiliki dan ini membuat mereka ikut menjaga karya itu. Apa yang saya rasakan sama persis dengan apa yang mereka rasakan.
Tapi diluar itu, saya juga cukup sering bekerja sama dengan masyarakat dalam berkarya. Seperti misalnya pada Jakarta Biennale 2013, saya yang saat itu kebagian untuk berkarya di daerah Asemka. Di Jakarta, daerah tersebut identik dengan lokasi jual-beli mainan. Ketika saya harus berkarya di Asemka, saya lalu banyak berbincang dengan warga disana. Tentang apa aktivitas mereka dan kenapa daerah tersebut bisa dikenal sebagai tempat jual mainan. Ternyata memang disana banyak penjual mainan dan entah bagaimana, penjual mainan bisa berkumpul disana. Para penjual juga bercerita bahwa jualan mainan adalah cara mereka untuk menopang kehidupan. Dari interaksi dengan para penjual mainan disana, saya lalu punya ide untuk membuat mural bertuliskan “Hidup Adalah Mainan”. Karya ini ternyata bertahan cukup lama, dan baru saja dihapus di awal 2016. Sebelumnya mural tersebut sempat akan dihapus tapi ternyata orang-orang di sekitar situ mencegahnya.
K
Dari sekian kali bekerja di ruang publik, apakah Popo pernah mendapat penolakan dari warga sekitar?
P
Seringnya sih warga menerima gagasan saya. Perbandingannya mungkin kalau dari 10 kali menggambar, cuma satu kali saja warga tidak sepakat dengan apa yang ingin saya sampaikan. Ini sepertinya tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan dengan warga. Biasanya yang saya lakukan adalah untuk mengajukan desain gambar saya terhadap pemilik area dahulu sebelum melukisnya sembari menjelaskan konsep dan pesan di dalamnya. Karena karya saya selalu merupakan bentuk dari realita yang ada di sana, orang biasanya akan paham dan memberikan izin. Tak jarang, saya jadi belajar, berdiskusi dan melakukan riset dalam proses bernegosiasi ini. Kalau penolakan, biasanya dari preman lokal yang meminta jatah uang rokok dari aktivitas saya.
Tak banyak dari teman-teman street artist yang menjalani proses ini. Karena mereka melihat street art harus dilakukan sembunyi-sembunyi, pakai jaket tertutup, anonim, lompat pagar dan dikejar-kejar Polisi. Padahal bagi saya tidak begitu harusnya. Tapi tanpa proses negosiasi ini, proses berkarya jadi semakin sempit. Bukan saya tidak pernah ditangkap Polisi, saya pernah ditanyai ketika sedang menggambar, saya juga pernah ditangkap, tapi saya tidak pernah lari dari mereka. Inilah posisi negosiasi bagi street artist.
Proses meminta izin kepada pemilik bagi saya adalah bagian penting di proses berkesenian saya. Dengan mendapatkan izin dari sang pemilik lahan, saya berarti bisa menaklukkan tempat itu, dan membuat saya bisa berkarya secara lebih bebas. Ini bagi saya adalah kemenangan tersendiri.
Pada sebuah kesempatan, saya mengunjungi sebuah daerah di Sleman dimana ada bangunan anti gempa yang sangat menarik, bernama Kampung Teletubbies karena bentuknya yang menyerupai gundukan bukit Teletubbies. Dengan ketertarikan saya terhadap bangunan tersebut, timbul keinginan untuk menggambar disana. Saya lalu mengajukan ide untuk menggambar disana dan untuk itu saya berhubungan dengan pengelola tempat tersebut. Dari obrolan, lalu saya tahu bahwa di tempat tersebut penghuninya beraktivitas sebagai petani. Saya lalu membuat karakter saya bermain gitar dengan buah-buahan dengan tagline, “Berjuang adalah Bercocok Tanam”. Setelah saya jelaskan kepada pemilik lahan, orang tersebut ternyata suka dan saya diizinkan untuk menggambar disana.
Yang lucu dari pengalaman ini adalah ketika saya akan mulai menggambar, sang pemilik lahan berkata bahwa akan ada ongkos untuk menggambar di tempatnya. Saya memahami bahwa di beberapa tempat saya memang harus membayar kepada pemilik tempat, dan saya sudah menyediakan budget khusus untuk itu. Saya lantas mengiyakannya. Ketika gambar hampir selesai, sang pemilik lantas mengampiri saya lagi dan menyinggung soal ongkos gambar tadi. Saya lalu mengambil uang saya di tas dan menyerahkannya pada si pemilik. Tapi ternyata kami salah paham. Ongkos yang dibicarakan tadi ternyata adalah ongkos dari sang pemilik untuk membayar saya yang telah mendekorasi tempatnya. Jadi kami sama-sama dalam posisi mau menyerahkan uang, tak ada yang siap untuk menerima uang (tertawa). Ternyata satu kampung patungan untuk membayar saya, karena mereka melihat saya sebagai seniman yang hidup dari bayaran atas lukisannya. Ini antara saya terharu tapi juga ingin ketawa. Tentu uangnya tidak bisa saya terima, karena saya menggambar disitu bukan untuk cari uang, tapi lebih karena suka dengan lokasinya.
Tapi dari situ, saya jadi terus berhubungan dengan pemilik tempat dan warga disana sampai sekarang. Mereka selalu mengabari dan menanyakan kapan saya bisa kesana lagi untuk menggambar. Katanya mereka bahkan telah menyiapkan space khusus untuk saya gambari. Ada 80 rumah yang ingin saya gambari. Jadinya kampung itu punya ikatan batin dengan saya. Saya rasa, karya saya yang ada disana tidak terlalu penting, justru proses dan jaringan persaudaraan yang saya bangun dengan mereka inilah yang lebih berkesan bagi saya.
Yang saya agak aneh, sebenarnya Sleman ‘kan cukup dekat dengan Jogja, dan di Jogja banyak sekali seniman hebat yang karyanya keren. Tempat itu tadi juga sebenarnya bisa sangat dieksplor untuk dijadikan karya. Tapi sepertinya sampai sekarang belum ada seniman yang mau untuk mencoba berproses dengan mereka. Sayang saja.
K
Tapi dengan melakukan negosiasi dalam berkarya, apakah itu membuat Popo harus berkompromi dengan publik?
P
Bagi saya, kompromi itu penting. Bahkan ketika seorang seniman masuk galeri sebenarnya kita sudah berkompromi dengan ruang itu sendiri. Toh, kompromi ini juga kontekstual. Asal kita tidak mengalah sepenuhnya dengan ruang yang kita ajak negosiasi, itu sama sekali bukan masalah. Jikapun sebagai seniman kita anti sistem, bukan berarti kita lalu menentang sistem yang ada, karena kalau demikian kita masih berpikir dan bertindak dalam koridor sistem itu sendiri. Jika kita benar-benar anti dengan sistem yang ada, maka harusnya kita menciptakan sistem baru sesuai dengan apa yang kita yakini.
Dengan tataran kompromi yang pas, saya rasa ini akan melahirkan bentuk karya yang lebih positif bagi sang seniman. Bagi saya, seorang seniman jalanan manapun akan selalu lebih suka kalau karyanya bisa lebih awet di jalanan, dan ini bisa dicapai dengan kompromi kepada publik dan ruang yang ada.
Proses negosiasi dan kompromi ini juga bisa membuat seniman sadar bahwa seniman itu tidak selalu yang paling benar. Padahal kan kenyataannya tidak demikian. Seniman dan karyanya hanyalah bagian kecil dari publik, kekuatan utamanya tetap ada pada ruang dan masyarakat di dalamnya.
K
Bagaimana Popo melihat bahasa visual di Jakarta atau mungkin di Indonesia?
P
Di Amerika, ada istilah low brow untuk sebuah gaya visual. Di Indonesia kita punya bahasa sendiri. Jika kita membahas low brow di Indonesia, mungkin bentuknya yang paling umum adalah spanduk pecel lele. Meskipun mereka tidak memiliki kesepakatan tertulis mengenai hal ini, semua spanduk pecel lele memiliki gaya yang distingtif. Warnanya selalu mencolok, eye catchy. Ini hal yang juga sama dengan kasus merek makanan dari Jawa, biasanya branding merk mereka selalu ada fotonya. Seperti bisa dilihat di Mbok Berek, Ayam Suharti dan semacamnya. Ini juga unik, sebenarnya kan foto mereka tidak ada korelasinya dengan produk jualannya, tapi mereka selalu memajang foto di branding mereka. Apakah ini bentuk narsisme mereka? Gila juga kalau mereka ternyata se-megalomania itu (tertawa).
Secara pribadi, saya selalu tertarik dengan visual yang ada di keseharian. Spanduk makanan, lukisan di truk, itu saya lihat sebagai cara mereka dalam berkomunikasi. Ini sering saya jadikan bahasan saya di kelas ketika mengajar. Dan ini selalu menarik juga bagi mahasiswa saya. Saya justru dapat banyak pengetahuan dengan interaksi saya dengan teman-teman mahasiswa. Yang jelas, dari pengamatan saya, Indonesia memiliki bahasa visual yang kaya. Meski mereka tidak memiliki sistem tertulis mengenai hal ini, mereka ternyata memiliki guidance masing-masing dalam berkomunikasi secara visual. Tak jarang karena kepolosan mereka, ada yang memancing tawa juga. Bahkan tukang becak di rumah saya memiliki sistem tersebut. Kebanyakan dari mereka selalu melukiskan pemandangan di bodi becak mereka, ketika saya tanya alasan dibalik visual ini, mereka menjawab bahwa lukisan pemandangan yang ada di becak mereka sebenarnya adalah simbol bahwa mereka selalu merindukan rumah mereka di kampung. Hal-hal seperti ini selalu menarik bagi saya.
K
Karakter gambar Popo cukup sederhana, ini membuat gambar Popo sering diimitasi oleh publik dan muncul gambar-gambar Popo yang aspal, bagaimana Popo menanggapi fenomena ini?
P
Saya sendiri tidak masalah bila karya saya ditiru. Tapi uniknya adalah banyak karya saya direproduksi oleh orang lain, tapi bahkan pada hasil reproduksi tersebut, mereka masih menampilkan signature saya disana. Bahwa meski aspal, mereka masih memberi kredit pada saya. Suatu ketika saya menemukan karya saya sedang dilukis di daerah Candi Borobudur oleh remaja setempat. Ketika saya tanyai alasannya, mereka ternyata berkarya dengan karakter saya karena mereka memang suka dengan karakter Popo ini, bahkan mereka tahu bahwa saya tinggal di Bekasi (tertawa).
Yang menarik kejadian seperti ini cukup sering saya temui. Dimana pesan atau tagline saya kemudian direproduksi dan disesuaikan dengan masalah yang mereka hadapi disana. Seperti misalnya, yang dulunya saya bikin “Jangan Pucet Lihat Jakarta Macet” mereka ubah jadi “Jangan Pucet Lihat Bogor Macet”. Merekapun tidak berkeberatan jika saya meminta lukisan itu dihapus, tapi saya sama sekali tidak merasa bahwa mereka membajak karya saya. Jadi saya tidak melihat ini sebagai masalah. Justru saya percaya bahwa kejadian seperti ini seperti meneruskan spirit karya saya ke tempat-tempat baru. Tak peduli itu karya asli saya atau bukan.
K
Di awal kemunculannya, Popo dikenal dengan karakter satir, komedi, tapi belakangan mulai menampilkan cerita personal, dengan munculnya gambar buah alpukat yang mengambil inspirasi dari keseharian Popo, apa alasan dibalik transisi ini?
P
Agak panjang sebenarnya cerita dibalik alpukat ini. Dan ini berhubungan dengan kisah ayah saya. Jadi tiga atau empat tahun lalu, saya sempat kena sakit asam lambung karena pola hidup saya yang berantakan. Saya akhirnya masuk rumah sakit selama seminggu. Dan selama di rumah sakit, saya jadi dekat dengan ayah saya. Sebelum masuk rumah sakit, saya sudah agak lama tidak berhubungan dengan beliau. Dengan saya masuk rumah sakit, saya jadi intens berkomunikasi dengan beliau. Beliau sempat menyindir saya, bahwa saya dibuat sakit supaya bisa ngobrol bareng ayahnya.
Saat itu, beliau yang biasanya sangat anti dengan karya saya-bahkan beliau sempat membakar beberapa karya saya, semingguan itu tiba-tiba mau untuk membicarakan karya seni, khususnya karya saya bersama saya. Saya sampai merinding sendiri, bisa tiba-tiba intens membahas karya seni dengan beliau. Dalam obrolan saya, saya lantas dibuat sadar bahwa ternyata ayah saya, dibalik keacuhannya selama ini, ternyata paling hafal dengan hampir semua karya saya.
Suatu ketika beliau membawa sebuah majalah yang membahas salah satu karya saya, sembari membaca, beliau sempat berkata, “wah, seru juga ya”. Ini cukup mengagetkan, beliau yang biasanya mencela-cela karya saya, tiba-tiba bilang bahwa karya saya seru. Jadilah selama seminggu itu saya semakin intens dalam membicarakan kesenian bersama beliau.
Hingga di sebuah pagi, beliau berkata kepada saya, “Kamu boleh saja bersenang-senang, bekerja sebagai seniman. Tapi kamu harus menjaga kesehatan. Dengan tubuh yang sehat, ide-ide kamu sebagai seniman bisa berkembang lebih baik, kamu juga bisa lebih optimal dalam berkarya. Tubuh adalah satu-satunya senjatamu sebagai seniman, jadi kamu harus sehat. Kalau tubuhmu sehat, karyamu juga akan semakin sehat.” Saat itu, saya mengiyakannya saja. Beberapa hari kemudian saya pulang ke rumah. Dua hari kemudian, ayah saya meninggal. Tidak sakit apapun, tiba-tiba jatuh tidur, koma dua hari, lalu meninggal begitu saja. Dokter pun tidak bisa memberikan penjelasan spesifik mengenai keadaan beliau, yang jelas ayah saya tidak sakit, tekanan darah, jantung, pembuluh darah semuanya aman.
Setelah itu, saya masih belum sepenuhnya pulih dan ibu saya tiba-tiba juga jatuh sakit. Saya semakin sedih dan termotivasi untuk sembuh, sudah saya sakit, saya juga tidak bisa merawat ibu saya yang sedang kehilangan. Akhirnya saya memburu obat yang bisa membuat asam lambung saya sembuh dengan segera. Dari penelusuran di internet, saya lalu baca bahwa yang paling mujarat untuk menyembuhkan asam lambung adalah buat alpukat. Dan ternyata alpukat ini juga bisa menyembuhkan serangan panik yang sering saya alami semenjak ayah saya meninggal. Ternyata setelah saya ingat-ingat, sejak kecil, alpukat adalah salah satu buah favorit saya, meski memang saya tidak terlalu sering mengkonsumsinya. Dan ketika saya mulai mengkonsumsinya lagi, serangan panik dan asam lambung saya langsung reda dan hilang begitu saja. Saya lalu jadi rutin mengkonsumsi alpukat lagi. Dan alpukat ini menjadi bagian dari keseharian saya. Ternyata saya jadi semakin sehat, begitu juga dengan ibu saya. Berat saya turun sekitar 20 kilo, dan saya jadi seperti memiliki energi tambahan untuk berkarya. Entah ini sugesti saja, atau memang khasiatnya, saya lalu mengagung-agungkan buah ini.
Suatu saat, saya teringat bahwa ketika menjenguk saya di rumah sakit, ayah saya sempat membawakan saya alpukat untuk saya makan. Ini membuat saya jadi merinding ketika saya mengingat-ingatnya kembali. Seolah beliau berpamit pada saya, dan berkata bahwa alpukat yang akan menggantikan posisi beliau di keluarga. Saya jadi sering bercanda dengan ibu saya bahwa jangan-jangan ayah saya reinkarnasi dalam bentuk buah alpukat ini. Dengan semua cerita tadi. Buah ini jadi seperti katarsis bagi saya. Dan ini turun ke karya saya.
Tapi diantara semua cerita, saya paling tersentuh ketika saya membereskan sebuah tas milik ayah saya dan di dalamnya saya menemukan arsip semua karya saya dari tahun 2005. Semua media cetak yang menampilkan profil saya ada di arsip beliau dan semua tertata rapi. Saya bahkan banyak yang belum tahu bahwa ada profil saya di beberapa media yang beliau koleksi. Ayah saya yang selama ini selalu anti dengan karya saya, ternyata menaruh perhatian yang sedemikian mendalam kepada saya. Kalau jadi FTV ini bisa jadi mengharukan banget ya, asal jangan jadi kayak sinetron aja (tertawa).
K
Apa rencana Popo ke depan?
P
Pertengahan April 2016 ini saya diminta warga Penjaringan untuk melukis tembok sepanjang 250 meter dengan karya saya. Ini proyek lama yang sudah sering saya tunda, tapi sepertinya akan saya segera kerjakan. Tidak enak, warga sana sudah sering menanyakan kabar proyek ini. Di dalamnya saya akan melukiskan mengenai berbagai tema, termasuk isu-isu yang saya angkat di artwork album Efek Rumah Kaca – Sinestesia kemarin itu. Termasuk masalah masyarakat Jakarta, karena nantinya jalanan tersebut akan jadi jalur yang dilalui oleh gubernur Jakarta. Di tengah tahun, saya sepertinya akan menggambar lagi di Kampung Teletubbies Sleman itu.