
Perspektif Alternatif untuk Stagnansi Praktik Desain Grafis
Kami berbincang dengan Januar Rianto dan Almer Mikhail dari Further Reading mengenai artbook, intensi di balik konsistensi penerbitan mereka, stagnansi yang menjangkiti praktik desain grafis di Indonesia, hingga pandangan mereka tentang desain vernakular.
Words by Whiteboard Journal
Bermula sebagai platform independen yang mempublikasikan berbagai perspektif alternatif mengenai desain dengan beragam format pada 2017, Further Reading kini telah memanifestasikan wacana tersebut melalui publikasi fisik dan juga pendistribusian artbook yang mereka kurasi secara independen.
Perhatian mereka terhadap praktik desain di Asia, khususnya Indonesia, membuat mereka memformulasikan berbagai cara untuk membagikan aneka bacaan dan referensi yang belum dikenal secara luas–bahkan oleh kebanyakan pelakunya.
Simak perbincangan kami bersama Januar Rianto dan Almer Mikhail dari Further Reading mengenai artbook, intensi di balik konsistensi penerbitan mereka, stagnansi yang menjangkiti praktik desain grafis di Indonesia, hingga pandangan mereka tentang desain vernakular.
Further Reading dikenal sebagai publikasi yang berfokus pada penerbitan artbook. Untuk orang-orang yang belum tahu, apa sih yang membedakan artbook dengan komik atau novel grafis?
Januar: Sebenarnya kalau artbook itu kan umbrella term ya. Jadi, di bawah artbook ini ada beragam buku atau publikasi, dari yang bentuknya teori atau lebih text-based sampai yang visual-based. Jadi, sebenarnya agak sulit di-pinpoint apa sih sebenarnya definisi artbook. Tapi, mungkin lebih ke arah itu: sebuah publikasi yang bentuknya bisa buku bisa jurnal, tapi memang secara konten spektrumnya itu dari yang teori banget (teks) sampai yang visual. Maknanya sendiri sebenarnya bakal terus berubah dengan seiring berkembangnya [pemaknaan] art dan book itu sendiri. Kalau ngikutin definisi ini, berarti komik dan novel termasuk di dalam artbook. Bukan apa yang membedakan (artbook dengan komik atau novel grafis), tapi justru komik dan novel grafis adalah salah sekian dari genre-genre artbook.
Berarti, zine yang diproduksi dan didistribusikan secara independen juga termasuk di bawah umbrella artbook ya?
Januar: Termasuk. Bukan hanya yang diterbitkan dan didistribusikan secara independen, tapi yang secara komersil pun masih bisa dibilang artbook. Misalkan Phaidon, itu kan buku-buku tentang art juga. Jadi, bukan caranya seperti apa (bentukannya), tapi lebih ke kontennya. Dan, cara-cara independen (seperti zine) itu yang memperkaya definisi artbook itu sendiri.
Almer: Menurut gue sih nggak bisa dibedakan secara clean cut apa itu artbook, komik, atau novel grafis. Tapi, menurut gue yang membedakan adalah intensi si kreatornya. Artbook sendiri kan umbrella term tapi kalo kita ngambil definisinya yang secara broad, bisa dibilang artbook itu adalah karya/artwork dan bentuknya buku, dan itu bisa mencakup apapun formatnya. Kalau intensi si pembuatnya adalah ingin menyampaikan kekaryaannya dalam format buku, itu sudah bisa jadi artbook. Misalkan mengambil contoh komik US, bahkan di antara kreator-kreatornya dulu, mereka sendiri nggak punya persetujuan antara apakah yang mereka buat adalah karya seni ataukah bagian dari literasi. Sedangkan, komikus-komikus dari beberapa generasi ke belakang menganggap [diri] mereka adalah vaudevillian, bukan artist ataupun writer. Jadi, kalau soal itu sih pasti nggak pernah ada persetujuan. Di Jepang pun ada dikotomi antara manga dan gekiga. Kayak yang dibilang tadi, nggak akan ada persetujuan antara apa itu artbook atau bukan, kecuali dari intensi si kreatornya
Kalau ngomongin definisi nggak ada habisnya, ya?
Kurang lebih, akan selalu bekembang ya.
Untuk pembaca awam yang mungkin tertarik untuk membeli buku Further Reading, bisakah kamu mendeskripsikan secara sederhana apa yang dimuat di dalamnya?
A: Further Reading itu publikasi desain, yang nggak strictly tentang desain. Yang kita sorot justru kayak free-usenya gitu.
J: Kalau dari formatnya sendiri orang kadang masih bingung, ini majalah, zine, atau buku. Cuma kalau mau disederhanakan, bisa disebut buku. Jadi, menurut gue, [Further Reading adalah] buku yang berisikan aneka ragam pembahasan seputar desain, dalam artian di dalamnya ada artikel atau konten yang formatnya tulisan (esai), dan itu paling dominan. Tapi, ada juga yang bentuknya visual: bisa foto, macam-macam graphic treatment, observasi; hingga mixtape.
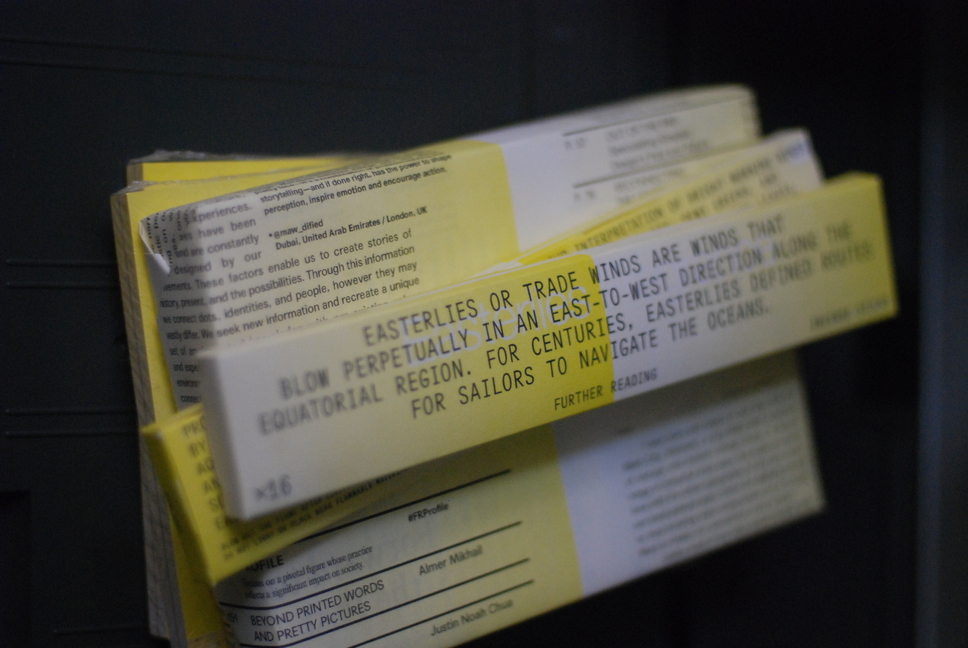
Further Reading Easterlies Incense Sticks (Foto: Further Reading)
“Seputar desain” ini juga dalam artian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan desain. Jadi, nggak secara direct majalah desain, tapi bisa juga hal-hal mengenai/yang berhubungan dengan desain, serta hal-hal di sekeliling desain–apa saja yang dipengaruhi atau mempengaruhinya. Dan, desainnya juga lebih ke arah pemikiran: berupa teks, teori, dan ragam disiplin; arsitektur, grafis, desain, dan dalam definisi metode/cara dan/atau sebagai output.
A: Mungkin lebih ke interseksi antara creative cultures di mana desainnya jadi benang merah yang present di semuanya.
Kenapa menitikberatkan desain Further Reading dengan format typographic? Apakah ada alasan tertentu?
J: Mungkin itu juga tidak secara sengaja direncanakan. Keputusan yang tidak disadari karena secara personal saya ada interest ke tipografi, jadi berangkat dari situ. Karena memang terbiasa ngulik tipografi. Tapi, kalau mau dirasionalkan,Further Reading ini kan buku berisi tulisan untuk dibaca oleh pembaca, jadi bisa dibilang secara direct ini memang untuk kasih “hint” kalau isinya untuk dibaca.
Apakah ada hubungannya dengan zeitgeist dunia desain saat ini?
J: Kalau ke sana, kayaknya di awal kita nggak mikirin ke sana. Tapi, mungkin sekarang jadi berbarengan dengan itu. Intensinya sih, ini publikasi untuk dibaca. Bisa dibilang juga untuk memfamiliarkan tulisan lewat desain yang nggak intimidating dan nggak perlu gimmic-gimmick. Sederhananya lebih ke sisi practicalnya. Misalkan di issue pertama, covernya berisi cuplikan-cuplikan teks dari masing-masing artikel. Issue kedua, isinya pertanyaan besar tentang buku ini. Lebih ngasih clue. Jadi, ketika orang ngambil bukunya dan ngeliat cover, dan ketika orang baca udah mentrigger argumen. Supaya orang-orang bisa judge the book by its cover aja
Kalian kan cukup konsisten dan terlihat semangat untuk memproduksi Further Reading. Apa sih tujuan yang ingin dicapai dengan memproduksi dan mendistribusikan Further Reading?
J: Nggak terlalu muluk-muluk: untuk menyediakan alternatif bacaan seputar desain. Further Reading-nya sendiri dimulai dari 2017. Tapi waktu itu masih di Instagram dan isinya kompilasi referensi bacaan. Jadi, dari tim kita pernah baca apa aja, kita kumpulin dan bikinin sinopsisnya. Jadi kita share bacaan yang di Indonesia mungkin nggak terlalu populer atau familiar. Jadi, kita melihat kalau disiplin ilmu desain grafis atau DKV di Indonesia hampir selalu maknanya ke branding dan iklan. Padahal, kalau di luar Indonesia, bahkan kayak di Singapura aja, secara definisi dan disiplinnya terus dikembangkan. Nah, kita melihatnya kalau di sini (Indonesia) begitu-gitu saja. Jadi, kita pengen kasih tau kalau ada alternatif-alternatif lain yang menurut kami penting untuk diketahui.
Bisa elaborasi bagaimana yang kalian maksud “gini-gini aja”?
J: Kita lihat saja, misalkan sejak pertama kali ada sekolah desain grafis, sampai sekarang ya masih itu saja, paling-paling berkembang jadi DKV. Stagnan. Sedangkan di luar–kalau mau bicara yang agak progresif–katakanlah Belanda, di sana ada jurusan-jurusan seperti Applied Graphic Design atau misalkan dari Graphic Design jadi cultural entrepreneurship, hingga experiential graphic design. Kalau di sini, kan, graphic design masih berkutat pada artian branding atau iklan. Paling jauh mungkin jadi product seperti clothing. Padahal definisi desain grafis kan bisa: 1. Sebagai cara (metode). 2. Sebagai output
Nah, yang branding, clothing, atau iklan itu kan outputnya. Untuk disiplinnya sendiri kan metodenya banyak banget. Ada yang desain grafis sebagai researcher, curator, bahkan kalau yang sekarang lagi ngetren sebagai type designer.
A: Mungkin kalo ngambil contoh practicalnya di keseharian. Kalau misalnya ditanya sama tante atau keluarga kerja di industri apa dan jawab desain grafis. Paling mentok-mentoknya direspons “oh, advertising?” Jadi, desain grafisnya [dianggap] sebagai instrumen untuk branding atau advertising doang. Buat gue yang bukan kuliah desain grafis dan basicnya nulis, setelah beberapa tahun di industri ini perspektif tentang desain tuh shifting banget. Desain in general bukan sekadar praktik branding/advertising untuk campaign satu brand atau apalah. Ini tuh (desain grafis) present di banyak banget aspek keseharian yang bisa kita lihat sebagai metodologi hingga way of thinking.
Berarti, tujuan awalnya adalah menyediakan alternatif dan bukan secara gamblang mengkritik praktik desain grafis di Indonesia, begitu ya?
Desain in general bukan sekadar praktik branding/advertising untuk campaign satu brand atau apalah. Ini tuh (desain grafis) present di banyak banget aspek keseharian yang bisa kita lihat sebagai metodologi hingga way of thinking.
J: Kurang lebih gitu sih. Lebih ke kasih alternatif ya. Kalo kritik mungkin di sini agak tabu. Sensitif. Konotasinya tuh kayak, oh lu ngatain gue. Padahal, dulu waktu kuliah setiap seminggu sekali di mata kuliah tertentu ada sesi kritik (crit session): di mana kita presentasi ide, presentasi progres, dan akan dikritik oleh satu kelas. Dan sebenarnya di situ kritik bukan untuk menjelekkan, tapi lebih memberi alternatif pemikiran. Menurut gue begini, menurut dia begitu. Jadi, bukan untuk serta merta diikuti. Misal kita ngikutin salah satu (dari sepuluh), kan masih akan dianggap salah oleh sembilan orang yang lain.
Jadi, sebenarnya lebih menyediakan alternatif pandangan yang mungkin nggak kelihatan oleh kita sebelumnya. Mungkin, [Further Reading] kritiknya dalam hal itu, dan bentuknya bukan secara gamblang. Jadi, ketika lo baca akan muncul argumen lo sendiri.
A: Apa yang kita lakukan di Further Reading ini bukan terang-terangan mengkritik. Kita lebih memperlihatkan perspektif lain, approach lain, tapi di dalamnya itu bisa jadi ada kritik dari kontributor kita, yang juga bisa mengarah ke industri secara luas. Misalnya, di Further Reading #2 ada yang menulis tentang bagaimana semakin kita menormalisasi penggunaan teknologi, imajinasi kita justru makin terbatasi. Contohnya format e-book: cuma kayak buku fisik, tapi bentuknya digital. Itu kan dia kritik secara luas, tapi nggak sekadar kritik semata—lebih mengkritik kenapa sih kita sampai ke titik ini. Di mana harusnya ada cara alternatif untuk moving forward atau ngeliat editorial design di era digital ini.
Waktu kalian memutuskan membuat Further Reading, apakah sebelumnya ada riset dulu terhadap seberapa banyak orang yang berprofesi sebagai graphic designer dan punya keinginan untuk membaca lebih jauh? Kalau melihat secara agak pesimistis, kan, disiplinnya memang seperti disiapkan untuk industri advertising.
J: Dengan kita melihat bentukan atau kestagnansian DKV yang dari dulu sampai sekarang fakultasnya begitu, yang diajarin juga sama aja. Sebenarnya itu nggak salah. Cuma menurut gue itu hanya salah satu atau sepersekian porsi dari disiplin desain grafis itu sendiri. Jadi, bisa dibilang overly-simplyfied. Sebenarnya, disiplin ini luas banget. Jadi, keliatannya gitu-gitu aja jadinya. Orang habis lulus bikin studio desain atau kerja di agency iklan. Sedangkan disiplin ini seharusnya atau by nature terus berkembang. Jadi, kalau di awal kita riset seberapa banyak yang butuh bacaan alternatif sih enggak. Tapi, kita bisa melihat berapa jumlah kampus yang ada program DKV. Tiap angkatannya saja ada berapa ratus orang. Jadi, tiap tahun pasti ada ribuan lulusan DKV.
Omong-omong soal pembaca dan audiens kalian yang mayoritas lulusan DKV. Menurut kalian seberapa urgent untuk menerjemahkan bacaan-bacaan yang memang penting?
J: Kalau bahasa, sebenarnya menurut gue, mungkin lebih subjektif. Misalkan gue sendiri lebih terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris kalau dalam bentuk tulisan. Berangkatnya dari situ. Kan tujuan sebenarnya untuk menyampaikan gagasan. Jadi, kita pakai yang paling terbiasa, yang paling nyaman. Kita tetap menggunakan bahasa Inggris sampai sekarang juga sebenernya karena waktu kita sempat terlibat bikin pameran di London Book Fair, di mana di sela-sela pamerannya gue menyempatkan untuk datengin toko-toko buku di sana untuk riset. Pengen ngeliat buku-bukunya kayak apa. Dan dari semua toko buku, sangat sedikit buku-buku desain yang ngobrolin tentang desain di Indonesia atau Asia Tenggara. Dari situ kita melihat masih dikit banget. Padahal di sini banyak banget sekolah desain. Terus, sempat juga ke Graphic Design Biennale di Sharjah dan ngobrol sama kuratornya, dan mereka kayak “Oh, ada desain grafis ya di Indonesia? Kayak apa sih? Kita nggak pernah dengar.”
Jadi, di sini [sisi] inklusifnya lebih ke kasih liat bahwa setiap orang bisa baca Further Reading, termasuk orang-orang dari luar Indonesia supaya mereka bisa melihat bahwa di sini ada pemikiran-pemikiran atau praktik-praktik seperti ini. Jadi, aimnya lebih ke arah sana.
A: Sebenarnya ini sempet kita bercandain juga, bahwa kita di Further Reading banyak ngebahas tentang subyek-subyek dekolonisasi, tapi kita malah pake bahasa Inggris, udah gitu pake British [English] cara penulisannya. Hahaha. Kita pake bahasa colonizer untuk menyampaikan subyek-subyek dekolonisasi. Tapi itu, ya…
J: Biar mereka ngerti juga. Hahaha.
Seandainya ada orang yang punya ketertarikan untuk mentranslasikan apa yang ada di Further Reading ke bahasa Indonesia. Apa kalian terbuka pada kemungkinan tersebut?
J: Kalau kesempatan sebenarnya ada. Nggak menutup kemungkinan juga. Tapi, contohnya di issue pertama dan kedua, ada satu artikel dalam bahasa Indonesia yang ditulis Mas Ayos (Ayos Purwoaji) dan Mas Iwang (Irwan Ahmett). Awalnya sejak mereka submit memang dalam bahasa Indonesia dan kita minta izin ke dia untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Tapi, setelah diterjemahkan dan dibaca ulang kok maknanya banyak yang lepas, jadi nggak akurat. Jadi, balik lagi bahasa Inggris memang lebih sederhana dan Mas Ayos juga di situ banyak menggunakan kata serapan dari bahasa Jawa dan bahasa daerah. Jadi, kami tetap putuskan untuk pakai bahasa Indonesia. Yang di Issue #2 juga dari performancenya Mas Iwang, dan dia praktekkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, karena konteksnya masih dalam bingkai karya seninya dia, ya udah kita keep juga dalam bahasa Indonesia.
Jadi, untuk penerjemahan memang terbuka tapi mungkin ada beberapa kasus yang tidak bisa diterjemahkan secara langsung.
A: Dalam kasus-kasus sebaliknya pun misalkan kita ngerasa lebih baik present dalam bahasa Indonesia untuk audience internasional, ya udah aja, nggak apa-apa kalau mereka nggak ngerti, karena memang editorial decision kita merasa bahwa ini harus di-present dalam format tersebut.
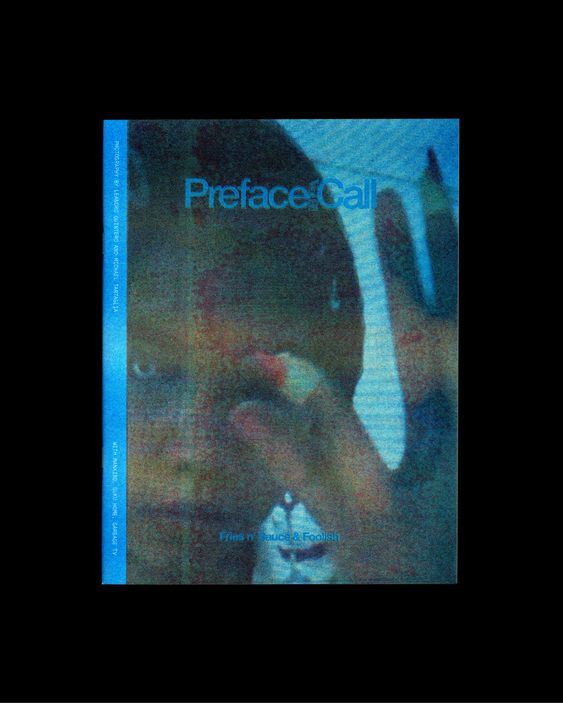
Further Reading Zine Series: Preface Call (Foto: Further Reading)

Further Reading Print No. 1

Further Reading Print No. 2

Further Reading Print No. 3
Belakangan saya sering mendengar penggunaan istilah “desain vernakular” dan sering kali dikaitkan dengan eksotisme. Apa sebenarnya makna desain vernakular buat kamu?
A: Kalau by definition, kan, desain vernakular itu adalah desain yang tumbuh dari kondisi kultural di sekitarnya, dan konotasinya lebih kepada desain yang lahir bukan dari perspektif profesional. Misalkan, desain yang bukan dibuat oleh orang-orang yang secara formal mempelajari sesuatu. Contohnya arsitektur vernakular, implikasinya adalah [arsitektur] yang lahir dari kebutuhan lingkungannya, kondisi kulturalnya, dan bukan orang yang mempelajari arsitektur secara formal.
Misalkan desain secara luas desain vernakular dipandang eksotis, ya itu untuk outsidernya saja sih. Ini tuh balik lagi ke canon-nya desain adanya di Barat. Karena mereka yang dilihat sebagai canon-nya, sebagai mainstreamnya, kita melihat desain dari Global South tuh jadinya kayak eksotis. Padahal, buat orang-orang yang menghidupinya sih sebenarnya itu hal yang biasa saja dalam kesehariannya. Contohnya, di Further Reading Print #3 ada yang membahas lukisan di warung-warung makan. Itu kan bisa dibilang desain vernakular yang sudah tepat sama audiensnya dan kebutuhannya, sudah bisa mengkomunikasikan apa yang butuh dikomunikasikan. Buat kita kan itu sudah part of our reality aja, tapi kalau orang dari luar mungkin melihatnya eksotis karena melihatnya dengan westerner-gaze.
J: Sebenarnya kalau menurut gue, contrary to popular belief, menurut gue nggak ada yang namanya desain vernakular. Kita melihatnya itu [sebagai] desain vernakular, mungkin, dari kacamata kita sebagai praktisi desain. Misalkan tulisan pecel lele atau tulisan gorengan di gerobak, sebenarnya itu lettering aja. Mereka menulis seperti itu karena bisanya begitu atau mediumnya begitu. Tapi, kita punya background pendidikan desain melihatnya “ini desain vernakular”, orang-orang ini mendesain tulisan itu. Seperti tadi Almer bilang, itu kan sebenernya cara domestiknya mereka sendiri.
Jadi, desain vernakular menurut gue nggak ada. Adanya ya vernakularnya aja. Misalnya orang bikin rumah adat, di sana mereka nganggapnya rumah aja. Tapi, ketika arsitek atau desainer yang melihat, “oh ini desain vernakular”. Perspektif mereka memang secara pendidikan atau keahlian memang diajarkan seperti itu. Jadi, ketika melihat hal-hal itu mereka menganggapnya begitu, ini desain vernakular, ini arsitektur vernakular.
Untuk eksotisme ini adalah soal jarak. Untuk mereka yang menghidupi, ya itu keseharian saja. Tapi, ketika kita melihat spanduk pecel lele dan dijadikan tshirt dan memakainya ke kantor di SCBD, itu jadi eksotis. Bahkan dari kacamata Barat, itu adalah hal yang eksotis.
Contrary to popular belief, menurut gue nggak ada yang namanya desain vernakular.
A: Ini sebenarnya nyambung sama poin tadi, bahwa desain tuh nggak strictly soal apa yang ditampilkan di industrinya atau dipelajari secara formal. Orang bikin rumah panggung secara historis untuk menghindari hewan buas di bawah, secara prinsip kan itu desain. Ada banyak banget di aspek kehidupan.
J: Bahkan kayak lettering, ada digital jadi type design. Padahal berangkatnya dari tukang gambar huruf yang bukan desainer (profesional). Kalau kita sekolah type design itu kan jadi reference. Bahkan hingga ke batu nisan, bagaimana carving-nya. Jadi, hal-hal itu memang vernakulernya. Dan desain itu disiplin modernnya.
Secara pragmatis bagaimana cara kerja/mekanisme Further Reading untuk memperkuat impact dari tujuannya?
A: Dari kayak bikin pop up Kiosk di Footurama itu salah satu bentuk usaha kita mengamplifikasi. Kan kita nggak strictly nerbitin buku doang.
J: Cara kita meng-amplify lebih dengan cara ke gimana supaya buku-buku atau objek/produk desain yang berhubungan dengan Further Reading itu pelan-pelan jadi bagian dari keseharian si pembacanya. Karena kalau kita bicara soal kritik dan counter-argument kan memang agak susah untuk jadi mainstream. Mungkin cara-caranya bisa dengan pendekatan yang lebih lunak, yang lebih pop dengan bikin pop up, masuk-masukin buku dari luar, terutama yang memang sudah didapatkan di sini atau mahal kalau dibeli di sini. Tapi, yang masih sejalan dengan Further Reading. Terus juga, beberapa kali kami coba buat merchandise. Lebih ke gimana caranya menginkorporasikan Further Reading dan programnya ke keseharian. Sebenarnya masih terus-menerus kita coba sih cara-caranya, apakah kira-kira relevan dan gak hanya jadi sekadar gimmick aja.
A: Kita pun nggak pengen berhenti di Further Reading Print doang. Itu kan sebenarnya flagship publication dari payungnya Further Reading Press. Ada pula Further Reading Riso Zine series kayak yang Jan bilang tadi, di mana kolaborator bisa mengeksplor medium risograf. Kita pun nggak pengen nerbitin editorial dari internal saja, ke depannya mungkin kita bisa eksplor publikasi lain dengan subjek yang berbeda tapi dengan approach dan curiosity yang sama.
J: Sebenarnya bisa dibilang kita lagi siapin series of publication yang baru. Jadi, selain ada Further Reading Print sebagai flagshipnya, terus ada zine series, terus nanti bakal ada satu lagi. Secara curiosity berangkatnya dari Further Reading, tapi melalui sarana atau subyek yang berbeda, di mana kita akan mengeksplor subyek yang lebih dekat dengan keseharian. Tapi, tetap masih berkutat dengan kultur desain, tulisan, dan ada kritiknya juga. Jadi, selain flagship publication itu, kami juga akan bikin publikasi-publikasi lain yang lebih beragam.
Berarti, Bookshop by Whiteboard Journal ini sejalan dengan aim kalian untuk menyediakan alternatif bacaan?
J: Iya, betul. Apalagi seperti Footurama yang menjadi konseptor lifestyle dan Whiteboard Journal juga media online yang menjadi tempat pelaku-pelaku creative culture. Jadi, masih align, masih resonate lah sama kita. Jadi, buku, desain, atau pemikiran-pemikiran ini adalah bagian dari keseharian yang relevan dengan Footurama dan Whiteboard Journal. Jadi, artbook ini sebenarnya bukan benda asing.
Beberapa buku hasil kurasi kalian (seperti CAPS LOCK) menawarkan perspektif kritis terhadap desain grafis yang berorientasi pada pasar/kepentingan kapitalisme. Apakah memang ada celah untuk melepaskan desain grafis dari kapitalisme?
J: Mungkin pertama, kami pilihnya buku-buku yang masih resonate sama Further Reading. Terus kedua, [buku-buku] yang menawarkan perspektif alternatif yang udah lebih dulu dibahas/diolah sama orang lain. Bisa nggak melepaskan grafis desain melepaskan diri dari kapitalisme? Sebenarnya buku tersebut (CAPS LOCK) memang jadi perspektif mereka di dunia Barat. Sekali lagi, kita ngasih buku bukan untuk mengajarkan step 1, 2, 3 atau caranya untuk terlepas dari belenggu kapitalisme. Bukan. Tapi lebih ngasih liat pandangan alternatif. Kalau secara praktis jawabannya, bisa sih bisa tapi balik lagi ke definisi desain grafis yang seperti apa? Jadi, kalau definisinya masih branding lagi, itu pasti akan berkutat di situ, di market. Tapi kan ada juga disiplin-disiplin desain grafis yang lain, yang mungkin tidak secara gamblang menawarkan cara-cara melawan kapitalisme.
A: Kalau gue melihatnya, ya desain grafis kan cuma satu bagian dari konstelasi industri yang lebih luas. Kalau misalkan kapitalisme masih jadi sistem yang berlaku, desain grafis nggak berada dalam vakum, kita masih harus berinteraksi dengan industri lain secara luas yang membutuhkan desain grafis sebagai solusi. Jadi, dari sisi itu sih bisa, tapi perubahannya pun mesti secara luas. Kita nggak bisa melepaskan diri secara sendirian saja. Mungkin kalau secara industri, for the time being, belum bisa ya melepaskan diri. Tapi, secara praktik desain grafis kan nggak harus selalu diaplikasikan untuk kebutuhan-kebutuhan komersil doang. Bisa juga misalkan kita pakai desain sebagai metodologi, sebagai way of thinking dan diaplikasikan dalam output-output lain. Nggak harus selalu dikomodifikasi. Sederhananya kalau secara profesional berpraktik sebagai desainer grafis–yang nggak bisa bohong harus berinteraksi dengan industri lain–di luar itu kan bisa bikin output lain.
J: Bedanya kalau kita melihat CAPS LOCK itu subversif banget, tapi kan juga kalau kita melihat buku ini dari perspektif penulisnya, Ruben Pater, dia orang Belanda dan pasti pengetahuannya sedikit banyak pengaruhnya dari situ juga. Kalau mau kita bandingin praktik/disiplin desain di sana dan di sini itu beda banget. Di sana kan progressing terus, sedangkan di sini stagnan.
Sama aja kayak 20 tahun lalu. Jadi, treatmennya pun, cara mereka berpraktik sekarang juga beda. Kayak misalkan di sana itu banyak banget desainer grafis yang mau bikin proyek ini-itu ada pendanaan dari pemerintah atau cultural institutionnya. Kalau di sini kan kayak begitu setengah mati. Jadi, mau nggak mau seniman di sini susah banget untuk jadi fulltime seniman. Tetep harus hustling untuk memenuhi kebutuhan primer. Jadi, sebenarnya lebih ke arah bagaimana menyikapi kapitalisme itu juga. Bisa aja misalkan seniman atau desainer idealis di sini yang masih ngerjain proyek-proyek komersil tapi untuk mendukung proyek-proyek mereka yang lebih bertujuan luhur. Intinya nggak bisa ditelan mentah-mentah kalau orang luar bisa kayak gini, kita juga harus bisa kayak gini.
Desain grafis atau desain pada umumnya tidak bekerja dalam vakum. Kalau kita mau melepaskan belenggu kapitalisme ini harus ramai-ramai. Dan kalau pertanyaannya bisa dan mungkinkah? Ya, jawabannya bisa dan mungkin. Tapi, harus mengukur berapa banyak effort yang harus ditempuh.
A: Sama halnya dengan kita di Asia nggak bisa ngambil mentah-mentah metodologi desain dari Barat yang merupakan canon-nya untuk permasalahan dan realitas sehari-hari kita.
J: Di Issue #1 pernah dibahas juga tuh. Ada artikel yang isinya interview judulnya ‘Other Review: Navigating Practice with …’ Di artikel itu kita interview tiga kolektif/instansi: Eropa Timur, Filipina, dan Amerika. Kita interview untuk mengetahui progres di daerah mereka seperti apa, apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi, setiap daerah itu punya permasalahan dan kebutuhannya masing-masing. Nggak bisa kita pukul rata bahwa desain grafis seperti ini, standar internasionalnya seperti ini. Jadi, pasti ada inisiatif, solusi, atau pergerakan untuk menjawab kebutuhannya masing-masing. Justru harus dibalikin lagi ke tiap-tiap praktisinya.

Kurasi buku Kiosk oleh Further Reading (Foto: Further Reading)
Bagaimana pendapat kalian tentang kanonisasi karya desain grafis?
A: Nggak masalah sih menurut gue. Sama halnya dengan kita yang existing outside the canon, nggak masalah.
J: Kalau desain itu kan memang disiplin yang lahirnya dari sana. Perspektifnya seperti itu secara formal dan kebetulan yang dipopulerkan itu: Modernism, Swiss Typography, dan lain-lain. Mau kita sebelin juga akan tetap ada. Mungkin lebih condong ke bagaimana kita memahami itu untuk mempraktikkan apa yang bisa dan sesuai [untuk dipraktikkan] di sini.
Pertanyaan gue sebagai outsider desain grafis: desain kan ada identitasnya, di Indonesia sendiri ada nggak sih identitas desainnya?
J: Ini agak tricky. Desain itu kan [disiplinnya] dari Barat, sedangkan kita di sini sebelum disiplin itu masuk sudah punya vernakular-vernakularnya. Kayak tipografi aja, misalkan kita mau bahas, ada tulisan Aditya Bayu di Further Reading yang membahas macam-macam skrip tradisional di Indonesia. Jadi, agak susah untuk di-pinpoint bahwa desain grafis Indonesia adalah batik, adalah tipografi yang agak cursive. Padahal belum tentu satu pakem itu mewakili yang lain. Jadi, mungkin kalau bicara identitas Indonesia, ya justru lebih ke keberagamannya. Misalkan, di Jawa seperti ini, di Papua seperti itu. Jadi, kalau bicara identitas desain Indonesia balik lagi ke identitas masing-masing pelakunya di tiap-tiap tempat. Kalau merujuk ke Barat, kita melihat desain seolah untuk membuat sesuatu lebih simpel, makanya ada Modernism, Swiss Typography, dll–itu kan memang seperti itu [fungsinya] di awal. Tapi, kalau kita aplikasikan di sini kan nggak bisa sesederhana itu. Justru kompleksitasnya yang penting. Itu yang menurut gue lebih penting ketimbang terus menerus menyederhanakan.
Kalau memaksakan desain Indonesia itu cuma sekadar batik, aksara, atau wayang semata, ya sama konyolnya seperti bikin standar bahwa membentuk identitas Indonesia yang baru mesti mengarah ke Modernism. Mau jadi fundamentalis banget atau maksain jadi modernis banget itu sama konyolnya.
A: Kalau menurut gue, itu hal yang nggak perlu dicari karena ke depannya akan terus terbentuk sendiri. Di Indonesia kan desain itu diformalisasikannya terhitung masih muda, masih baru. Walaupun sebelum itu diformalisasikan pun, apa yang orang lakukan, misal bikin rumah panggung, melukis spanduk pecel lele pun itu udah secara prinsip merupakan praktik desain. Jadi, menurut gue nggak perlu kita paksakan identitasnya apa dan perlu dicari, karena nantinya akan jadi nggak natural. Kalau memaksakan desain Indonesia itu cuma sekadar batik, aksara, atau wayang semata, ya sama konyolnya seperti bikin standar bahwa membentuk identitas Indonesia yang baru mesti mengarah ke Modernism. Mau jadi fundamentalis banget atau maksain jadi modernis banget itu sama konyolnya.
Contohnya, Jepang secara desain kan lumayan distinctive. Orang-orang suka men-describe desain Jepang tuh sebagai sparse, minimalistic, padahal mereka pun nggak ada intensi ke sana.
Kenapa output kekaryaan/desain mereka seperti itu? karena mereka punya konsep yang disebut “Ma”, dan ini hadir di semua aspek kehidupan mereka. “Ma” ini berarti emptiness (dapat juga diartikan sebagai gap, interval, atau negative space), dan buat masyarakat Jepang emptiness ini yang memberi makna terhadap berbagai hal.
Kayak kenapa di Jepang ada format puisi kayak Haiku, yang sebenarnya secara format benar-benar limiting—cuma tiga line gitu. Soalnya, buat mereka, apa yang tidak tersampaikan secara eksplisit sama pentingnya dengan apa yang tersampaikan secara eksplisit. Hal ini bahkan sampai ada dalam praktik kehidupan seperti waktu memberi salam, ada jeda sepersekian detik. Jadi, konsep ini tertuang juga dalam desainnya: banyak empty space. Kalau secara kasat mata kita akan menganggap karakternya minimalistik. Padahal intensi mereka bukan ke sana, mereka hanya menerapkan apa yang mereka praktikkan sehari-hari ke dalam desainnya.
Nah, menurut gue Indonesia pun nggak perlu nyari-nyari. Kalau udah mature pun akan ketemu sendiri.
J: Super sekali, hahaha. Bahkan kalau mau disederhanakan, di Jepang ada [desain] yang minimalis dan ada Harajuku yang ramai banget. Dua-duanya benar, nggak harus milih.
A: Nggak bikin salah satunya less-Japanese than the other.
Berarti, apa pesan yang mau kalian sampaikan untuk pelaku desain grafis muda yang suka mengikuti kecenderungan tren?
J: Mungkin paling klise dan sederhana ya: looking inwards. Lihat lo kayak gimana. Lo sesuaikan aja: kemampuan lo kayak gini, kebutuhan lo kayak gini, ya itu yang harusnya lo kerjakan. Secara luas seperti itu. Tapi, kalau dalam konteks seperti pekerjaan, ada kebutuhannya masing-masing lagi. Tapi, kalau secara luas kayak gitu sih: nggak perlu ngikut-ngikutin orang lain.
Tidak seperti buku cetak pada umumnya, artbook independen seperti Further Reading didistribusikan dengan cara yang unik, artinya ini berada di luar radar “otoritas”. Apakah menurutmu masa depan distribusi pengetahuan subversif berada di dalam zine?
J: Kalau melihat dari perspektif Further Reading, kita nggak menekankan subversivitas dan menurut kita untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan seperti ini memang cocoknya lewat media cetak daripada media online. Media online mungkin kesannya lebih cepat dan terburu-buru. Dengan media cetak ini yang ingin kita dapatkan adalah less-distraction-nya ketika orang baca, dia fokus di buku ini. Selain itu, lebih ke arah penyusunannya. Media cetak kan cenderung lambat, tapi kita somehow punya luxury of time buat revisit lagi tulisannya. Jadi, kalau bicara masa depan zine ini cuma zine cetak, sebenarnya cuma salah satu dari sekian banyak pilihan medium. Sebenarnya balik lagi ke intensi masing-masing untuk membahas apa. Kalau merasa print lebih cocok ya silakan, kalau merasa online atau suara (podcast) lebih cocok ya silakan juga.
A: Ada satu potongan dari Further Reading Print #3 yang resonate banget di bagian Bookshelf di mana kita mengundang kontributor untuk memberikan daftar sejumlah buku yang important buat mereka. Dia bilang bahwa, “self-publishing is sometimes the only means of self-representation.“
Jadi, memang most of the time, self-publishing itu merupakan satu-satunya cara untuk kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Dan itu bentuknya bisa apapun. Untuk kita represent diri kita se-singular mungkin dengan intensi kita, ini tuh (self-publishing) menurut gue masih salah satu jalan terbaik. Soalnya, dari puluhan tahun lalu sampai sekarang, ini praktik yang masih ada dan akan terus ada.













