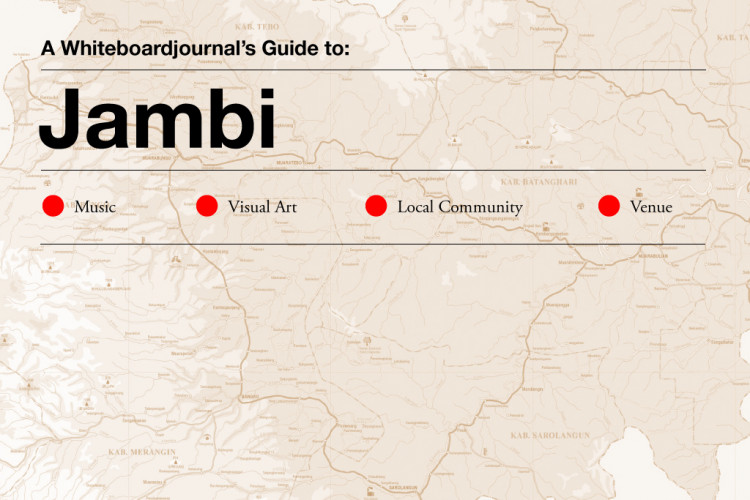Saat Stagnasi Mengancam Skena, Sorge Records Mengingatkan Cara untuk Membalikkannya
Ulasan acara Tukar Suara, persembahan Sorge Records yang menampilkan konsep kolaborasi berbagai musisi dan sajian acara pemuas panca indera.
Words by Whiteboard Journal
Teks: M. Hilmi
Foto: Kevin Fadillah (@vinfadillah)
Ada fenomena menarik yang terjadi paska pandemi. Kita yang seperti dipaksa puasa keriaan dalam kegiatan sosial, kemudian berbuka dengan kalap ketika pagebluk ternyata bisa tenggelam juga. Terkhusus dalam hal panggung musik, kalap itu nyata adanya. Konser, gigs, hingga festival musik – yang seringnya itu-itu saja penampilnya – diserbu oleh banyak di antara kita.
Jika dulunya musik adalah selingan, more than ever, musik berkembang menjadi menu besar di piring hiburan masyarakat, tak lagi jadi konsumsi anak skena saja. Saya cukup yakin kalau banyak di antara kita belum mengenal term “war-ticket” sebelum ini semua terjadi, tapi kini, itu sudah menjadi kosakata dan fenomena sehari-hari. Dan ternyata, kalap ini bukan cuma kita yang punya, dalam tulisannya yang berjudul “Post-Pandemic and Beyond: Looking Ahead to the Future of Live Concerts” di Rollingstone.com, Victoria Kennedy bercerita tentang bagaimana kehausan ini juga merupakan fenomena global, “One thing is certain: If we loved live events before they were stripped from our lives, we appreciate them with a fiery passion now. All over the world, musicians are selling out stadiums, music halls, parks and boutique venues.”
Tapi, layaknya hal-hal baik yang kita lihat, semua kemudian rusak saat kapitalisma menyeruak sekelebat. Antusiasme yang tinggi ini kemudian dikomodifikasi dan direduksi oleh industri menjadi semata kesempatan untuk memperkaya diri. Momentum yang sebenarnya bisa kita manfaatkan menjadi titik tolak untuk membangkitkan ekosistem, justru mendekatkan kita ke pinggir jurang tragedi: konser musik jadi modus operandi penipuan tiket, pengelolaan acara musik yang amatir beberapa kali bermain mata dengan kekacauan massa, tumpulnya kurasi membuat banyak acara berkali-kali menampilkan line-up yang sama. Oke, mungkin tragedi adalah diksi yang agak hiperbola, tapi jika terus begini, maka stagnasi akan jadi momok yang nyata.
Untungnya, suram dan muram masa depan ini bisa dibalik dengan hal sederhana yang sebenarnya kita semua punya: keberanian.
Dan inilah yang membuat inisiatif berjudul “Tukar Suara” dari Sorge Records menjadi hal yang penting digarisbawahi tebal di sepertiga pertama tahun 2023 ini. Keberanian menyeruak pekat sedari pertama: secara konsep mereka membuat konsep yang tak mudah, mini konser dengan konsep kolaboratif dengan tiga babak. Di setiap babaknya, mereka mengajak beberapa musisi untuk saling merespon karya.
Sejatinya konsep kolaborasi bukan hal yang unik. Cuma, kita terbiasa dengan konsep kolaboratif yang ditunggangi kepentingan brand yang sering menutupi keunikan karyanya. Belum lagi soal pemilihan talent yang melulu cuma mempertimbangkan angka dan algoritma. Dan di segi penampil ini pula, “Tukar Suara” punya nyali. Mereka seperti tak mengenal algoritma saat menyusun line-up. Tak ada nama-nama populer yang menjadi langganan, alih-alih, didatangkan nama-nama yang juga menunjukkan keberanian saat berkarya: Fuzzy, I berkolaborasi dengan Merry Kasiman di babak satu, Frau, Ananda Badudu dan Tomy Herseta di babak dua, serta Flukeminimix bertemu Bin Idris di babak tiga. Beberapa yang sinis mungkin akan melihat bagaimana lineup ini terkesan Bandung-sentris, subjektif, karena Sorge Records lahir juga dari bumi pasundan. Tapi justru subjektivitas penyelenggara acara adalah hal yang harus terasa, karena dengan begitu, satu acara akan punya karakteristik yang berbeda dengan acara yang lainnya.

Tak berhenti di situ, keberanian “Tukar Suara” juga hadir dalam bentuk penyelenggaraan acara. Mereka dengan serius dan profesional memberi contoh tentang bagaimana hal yang subjektif itu juga patut diperjuangkan dan diseriusi. Secara venue keseriusan itu terlihat pada bagaimana mereka memilih Teater Salihara. Tak hanya bergengsi, venue ini juga proper secara tata suara, memberikan kanvas yang sempurna bagi masing-masing penampil untuk unjuk suara. Dilibatkan pula penata suara Ahmad “Adun” Ramadan sebagai pemuas telinga. Keseriusan ini berlanjut untuk panca indra yang lain. Di visual, mereka melibatkan seniman Wulang Sunu sebagai ilustrator untuk poster acara dan Zamzam Mubarok sebagai penata cahaya, dan untuk indra pengecap, mereka mengajak Bimo Wicaksono serta Lampitan untuk meramu sajian yang dihidangkan ketika panggung jeda. Selain menunjukkan level profesionalitas, keterlibatan nama-nama di atas juga menjadi pengingat yang baik tentang bagaimana panggung musik adalah kerja kolektif – tak selamanya tentang musisi di panggung dan penonton saja.

Hasilnya, adalah salah satu pengalaman menonton konser yang paling menyenangkan yang pernah saya datangi. Jika di ranah festival Joyland menjadi brand yang paling kami percaya, maka di ranah konser, Sorge adalah nama di mana yakin kami berada. Semua terasa sejak babak pertama. Dari dulu, saya punya tempat spesial untuk Fuzzy, I. Sejak mereka masih bermain di ranah grunge/noise-rock, nama ini sudah mencuri perhatian dengan panggung yang intens. Kualitas ini kemudian berkali lipat saat mereka membelokkan arah musiknya ke ranah post-punk (dan belakangan jadi menyerempet eksperimental?). Kebetulan beberapa waktu yang lalu, Fuzzy, I merilis album “IONS II” – sebuah pencapaian artistik yang cukup monumental di mana mereka menarik komposisi lagu yang mereka punya pada batasan-batasan yang jarang dijelajahi di lanskap musikal kita. Agak sulit membayangkan bagaimana komposisi musikal mereka yang kompleks di album tersebut bisa dibawakan secara live. Tapi “Tukar Suara” menunjukkan bahwa personil Fuzzy, I cukup kompeten untuk menghidupkan album tersebut di panggung. Sulit untuk tidak terpukau dengan bagaimana set double drum yang mereka bawa bisa saling mengisi ganjil ketukan yang ada di setiap komposisi mereka. Memberikan pakem yang mantap untuk isian personil lain yang tak kalah jenial. Di beberapa lagu di mana mereka dipertemukan dengan Merry Kasiman, musisi jazz senior yang juga kini tergabung bersama Potret, mereka bisa cukup saling mengisi dan menimpali dengan relatif baik.

Setelah set yang memukau dan intens di babak pertama, panggung kemudian dilanjut dengan ketulusan dan kejujuran di panggung kolaborasi Ananda Badudu, Frau dan Tomy Herseta. Babak kedua menyentuh sejak lagu pertama, “Hiruplah Hidup”. Jika di album lagu ini bernafaskan optimisme, sabtu itu, gamang adalah nuansa yang datang. Goyah tarikan suara Ananda Badudu menjadi kontras yang sendu di atas soundscape Tomy Herseta dan iringan pemain piano dan cello. Jika babak pertama menunjukkan kompleksitas, maka babak kedua menjadi antitesisnya: betapa indahnya kesederhanaan. Tomy yang biasanya bermain dengan palet soundscape yang luas dan tak jarang menderu dan bising, hari itu tampak menahan diri untuk memberikan cakrawala yang luas pada indah komposisi musik Ananda Badudu juga Frau. Malam itu, Ananda memainkan lagu-lagu dari proyek solonya (yang harusnya menghentikan pertanyaan membosankan, kapan Banda Neira reunian) dan Frau memainkan beberapa lagu miliknya serta satu lagu karya Sri Wahyuni, seniman korban G30SPKI. Yang menarik adalah bagaimana Sorge bisa mempertemukan Nanda dengan Frau – sebuah ide jenius yang entah kenapa baru bisa terwujud kemarin.

Set ketiga sejujurnya tak terlalu istimewa. Flukeminimix yang bermain musik post-rock dipertemukan dengan Bin Idris, kombinasi yang juga sebenarnya cukup unik secara gagasan. Tapi, setelah dua babak yang memecahkan ekspektasi di kepala, pembawaan post-rock Flukeminimix yang repetitif terasa sedikit menurunkan mood yang telah terbangun sebelumnya. Jika ada hal yang cukup membayar kekurangan babak ketiga adalah kualitas suara yang sangat memuaskan di penutup acara ini. Tiga gitar, satu bass, satu drum plus satu gitar dan vokal (serta empat pengisi paduan suara di satu lagu) masing-masing terdengar sangat jelas dan balance. Menunjukkan bahwa keputusan mereka dalam membuat gigs di venue Teater Salihara bukan cuma mengejar gengsi, tapi juga kualitas.
Di tengah jeda antara babak, ada satu moment yang cukup menarik. Announcer mengumumkan bahwa acara “Tukar Suara” ini adalah hasil dari ikhtiar Koperasi Sorge – kumpulan individu yang dimulai sekitar tahun 2011 ini memutuskan untuk mengambil bentuk koperasi untuk mendemokratisasi segala usaha yang dilakukan bersama termasuk dalam pengelolaan ekonominya. Kemudian disebutkan juga bahwa Koperasi Sorge sendiri menaungi beberapa unit seperti Sorgemagz, Sorge Records, dan Sorge Visual. Menarik bagaimana sebuah kolektif yang lahir dari kumpulan mahasiswa kampus (Universitas Parahyangan, Bandung) bisa mengambil posisi sebagai koperasi dan berjalan cukup konsisten belasan tahun setelah mereka lahir. Pilihan menjadi koperasi (bentuk usaha yang dekat dengan gagasan sosialis) mengingatkan kita pada gagasan tentang kolektif yang lebih egaliter sembari tetap memegang misi bersama.
Berbeda dengan kebanyakan bentuk usaha lain yang cenderung berfokuskan pada kapital, koperasi adalah bentuk usaha yang lebih ideologis dan karena itu mulia adanya. Yang membuat ini juga perlu diapresiasi adalah bagaimana Koperasi Sorge, juga punya sikap politis yang jelas dan konsisten. Mereka aktif dalam gerakan sosial dan pemberdayaan, sembari punya sikap yang tegas pada kekuasaan. Melihat bagaimana sebuah organisasi dengan angle sepolitikal ini, bisa membuat panggung dengan konsep yang keren dan delivery yang mantap adalah catatan sejarah sendiri di saat gagasan tentang ekosistem semakin tenggelam dalam gerus industri kapitalis. Dan dengan begitu, kita harusnya berterima kasih pada Koperasi Sorge, juga semua pihak yang terlibat, karena telah mengingatkan bahwa sikap dan karya perlu dihidupkan dan bisa diwujudkan. Yang kita butuhkan cuma keberanian.