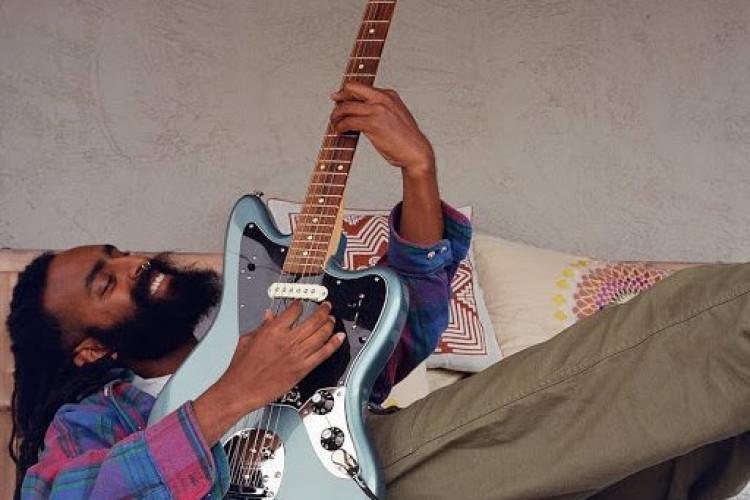I Wayan Sudirana: “Saat melakukan musik itu kita harus berpikir melampaui zamannya.”
Bagaimana perjalanan sang etnomusikolog ketika disandingkan dengan musik elektronik untuk melatari narasi surreal khas Garin Nugroho?
Words by Whiteboard Journal
Teks: MM Ridho
Foto: Film Samsara
Dalam proyek film bisu sekaligus cine-concert-nya yang berlatar Bali di awal abad 20, Garin Nugroho mengambil langkah tepat untuk menggandeng Etnomusikolog/Komposer I Wayan Sudirana. Selain latar akademisnya, ia juga punya pemahaman yang luas dan mendalam terhadap tradisi musik di tanah kelahirannya tersebut. Tapi, siapa sangka ia bakal disandingkan dengan duo musisi elektronik Gabber Modus Operandi?
Film Samsara jelas mempunyai visi artistik yang bisa dibilang nyebrang. Ia adalah proyek yang keras kepala namun ultra-rasional. Hal ini tergambar dari pemilihan gamelan ensemble dari Gamelan Yuganada dan musik elektronik sebagai pengiring cerita sci-fi mistis tersebut—jika boleh disebut demikian. Kita tahu betul kekhasan poliritmik dari musik tradisi itu dan musik elektronik “keras” adalah entitas yang jauh berbeda, namun bukan berarti tidak bisa dipersatukan. Buktinya, mereka berhasil membuat pengunjung Esplanade Concert Hall, Singapura, terbelalak menyaksikan penampilan mereka.
Sesaat setelah berbincang dengan Gabber Modus Operandi, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan perspektif I Wayan Sudirana tentang tantangan (atau justru kesenangan?) yang dihadapinya ketika mengomposisikan gamelan dan musik elektronik dalam proyek ini.
Dari sisimu, apa sih tantangan terbesar dalam menyelaraskan gamelan dengan bebunyian khasnya Gabber Modus Operandi?
I Wayan Sudirana: Sebenarnya untuk synchronizing. karena dalam konteks membuat komposisi saya merasa sangat enjoy dengan kalian berdua (Gabber Modus Operandi), dengan vokal juga langsung nge-click. Tapi yang paling menantang dalam produksi film ini menurut saya adalah sinkronisasi antara gamelan dengan kode timing di film itu, itu yang paling susah. Jadi kalau dengan musik saya tidak mau bilang tidak ada tantangan, tapi prosesnya bagus. Karena apa yang kita lakukan… Bagaimana ya, Mas Kas?
Kasimyn: Mungkin ini sih, tantangan kolektif waktu itu kan kita musisi, bahasanya bahasa musik, tiba-tiba harus berubah jadi bahasa film gitu loh. Lagu belum selesai dipotong. Itu kayak kadang-kadang ada feeling belum jadi, tapi udah harus dicut. Bahasa film, bahasa musik dan bahasa film itu yang menjadi tantangan besar
I Wayan Sudirana: Jadi ini, kalau dari vokal ada aural cue, di film ada visual cues. Itu yang perlu perhatian khusus. Kemudian sesuatu yang kita lakukan ini kan sebenarnya real time. Jadi, kita langsung merespon sesuatu yang sangat fix. Sesuatu yang tidak bisa diubah. Sesuatu yang saya bilang, tidak punya rasa. Film itu sudah fix seperti itu, tidak bisa merespons apa yang kita lakukan. Nah, tantangannya di sana.
Mengingat latar akademismu sebagai etnomusikolog, saya ingin bertanya tentang musik Bali di awal abad 20: Sebenarnya, ada nggak sih alat musik tradisional yang digunakan di sana selain gamelan??
I Wayan Sudirana: Alat musik? Itu namanya Semarandana, perpaduan antara Gong Kebyar dan Semar Pegulingan. Ini adalah identitas musik yang ada di keraton. Jadi, ensemble yang kita pakai sebenarnya sudah merepresentasikan musik keraton dan musik awal abad 20. Saya juga menggunakan beberapa instrumen bambu. Walaupun tidak full, tapi itu inspirasinya dari Bumbang. Nah, itu alat musiknya lebih awal lagi sebelum abad 20.
Di antara 8 babak di film Samsara, babak mana sih yang paling seru atau menantang untuk kalian terjemahkan menjadi musik?
I Wayan Sudirana: Kalau saya sih babak 4, karena itu perjalanan mistis. Dan musik yang saya buat itu memang musik yang perlu perhitungan banget. Ada satu kesalahan maka musik itu akan hancur, tidak sesuai dengan apa yang saya tulis. Jadi, fix banget, tetapi dalam konteks ini dia harus dimainkan pada sesuatu perjalanan yang tidak pasti. Itu yang paling sulit bagi saya dan juga bagi musisi. Musisi itu memainkan beberapa multi layer tempo ritmik yang berbeda-beda. Nah, waktu latihan saya coba lepas tanpa conducting mereka tidak bisa sama sekali memainkan. Kemudian, musik yang dimainkan oleh Mas Kas di sana juga mistis, pokoknya tidak fix dalam konteks ritmik, tidak ajeg gitu. Nah, itu yang paling menarik bagi saya. Lalu saya memutuskan untuk meng-conduct. Saya membuat tempo walaupun yang mereka mainkan itu kelihayannya tidak sesuai tempo, padahal mereka memainkan pola ritme yang memang berlawanan dengan tempo yang saya mainkan. Tetapi, mereka memerlukan tempo ajeg itu untuk bisa memastikan mereka memainkannya dengan solid.
Kasimyn: Di situ juga, ketika kita dapat babak keempat itu baru mulai agak clear. Oke, ini ceritanya gelap, ya udahlah kita bikin yang indah-indah dulu dari awal.Yang cantik-cantik dulu, ntar endingnya pasti kan sengsara nih. Kalau dari kami di GMO sih, karena kekayaan ritmis dari musik gamelan itu sendiri kan sangat kompleks untuk dipaksa masuk ke dalam ranah elektronik yang strict 4/4, atau hitungannya lumayan fix. Kami nggak pengen coba tabrakin sampai akhir. Karena bisa sangat kacau. Terus, menghilangkan kualitas poliritmik dari gamelan itu sendiri, yang bisa ke mana-mana. Kalau di musik GMO kan lumayan fix tuh. Sampai akhir-akhir baru kami benturkan. Jadi, ada titik ketika menyatu, misalnya gamelan di babak kedua dan ketiga tuh ada drone yang ngikutin laras dari gamelan. Terus, mulai pelan-pelan menyatu. Babak keempat sudah mulai kita full o,n sering bareng, dengan tetap membuat polirithmik di Bali itu jadi yang utama—karena “kaya”-nya ada di situ.
I Wayan Sudirana: Jadi secara umum gitu ya, dari awal itu kita main: ini gamelan, ini GMO. Jadi, pas Darta mencari pesugihan, kita menunjukkan diri identitas dulu, kemudian mencoba untuk mulai berdialog dari babak tiga itu kita, masuk dikit. Akhirnya di babak empat itu sudah mulai main bareng sampai akhir. Gitu sih. Jadi, menunjukkan identitas, terus berkenalan, nanti mencoba untuk berinteraksi bersama. Hasilnya nanti apakah itu bisa bersama atau tidak terserah pendengar.
Adakah pertimbangan ketika pertama kali diajak mengisi musik di film Samsara? Apakah karena kamu tahu akan bekerja sama dengan Gabber Modus Operandi, menimbang storyline-nya, atau karena ini adalah film Garin Nugroho—yang jelas sutradada besar?
I Wayan Sudirana: Kalau saya sih jujur semuanya. Jadi, saya senang tantangan. Hal yang baru itu pasti saya senang. Kemudian, ditambah dengan ini film Mas Garin. Jadi, kalau saya diberikan kesempatan, ini sebuah kehormatan bagi saya. Nah, setelah jalan sama Mbak Gita dibilang mau sama Mas Kasymin dari GMO. Wah, ini makin menarik lagi gitu.
Kasimyn: Kalau saya sih takut awalnya. Maksudnya, kalau ada yang jelek nih pasti kami hahaha.
ini kan juga ada legacy-nya Pak Panggah juga di sini. Terus, kalau di lingkaran pertemananku itu sebenarnya murid-muridnya Bli Sudirana: Kadapat, Putu Septa. Bukan ngomongin hierarki ya, tapi mereka memang murid Bli Sudirana di kampus. Biasanya, kami kolaborasi sama muridnya sekarang langsung sama gurunya. Kan bikin deg-degan, jujur aja.
Tapi, Mbak Gita dan Mas Garin juga bikin projectnya menyenangkan. Lumayan fluid untuk membuat kami juga nggak takut, nggak sungkan satu sama lain. Dari awal itu sudah cair. Waktu itu yang lucu juga, meeting pertama kita kan langsung menentukan empat vokalis. Dan mengeluarkan tiga nama yang sudah pasti: Ican, Pak Gusti, dan Thaly. Pas kita ngobrolin tentang vokalis perempuan kontemporer yang bisa mewakili karakter Sinta ketika dia menjadi terdistorsi itu siapa ya? Terus nggak sengaja kita ngeluarin nama yang sama: Dinar—memang jagoan kita. Padahal, enggak janjian gitu. Dari awal mungkin memang sudah ada bayangan yang agak mirip.
Indonesia memiliki beragam musik eksperimental dan beberapa darinya menggunakan instrumentasi alat musik tradisional. Bagaimana pandanganmu mengenai fenomena ini?
I Wayan Sudirana: Pertama, saat melakukan musik itu kita harus berpikir melampaui zamannya. Saya ambil contoh, dulu, satu orang Bali yang dinobatkan sebagai komposer it pertama itu namanya Wayan Lotring. Di awal abad 20, dia sudah memikirkan membuat musik yang melampaui zamannya pada waktu itu. Jadi, musik yang ia hasilkan waktu itu sampai bikin orang berpikir: ini musik apa?
Nah, justru musiknya Lotring itu sampai sekarang masih digandrungi. Saya berpikir sama terhadap musik eksperimental. Musik eksperimental itu kan melakukan percobaan cara kerja baru, cara kerja penggabungan yang berbeda. Jadi, saya kira hal-hal seperti itu tidak berbenturan dengan tradisi. Dia punya jalurnya masing-masing. Bagi saya, kelompok saya, dan kelompok yang berada di Ubud, kita mempelajari musik tradisi dalam konteks ritual itu masih jalan. Kalau kita disuruh perform di temple atau di pura untuk ritual, kita bisa. Jadi, kita berusaha sebisa mungkin fondasi tradisional gamelan itu kita pahami, sebelum kita bisa melakukan percobaan-percobaan baru.
Intinya, sebelum kita mengetahui yang lama, kita tidak mungkin bisa melakukan hal baru. Jadi, menurut saya eksperimental dalam musik itu sangat penting, terutama yang khusus dalam gamelan misalnya (yang belum menggunakan perangkat elektronik) itu sudah ada wadahnya sekarang, namanya New Music for Gamelan, atau musik baru untuk gamelan. Orang-orang seperti I Wayan Yudane, Dewa Alit dan saya sendiri mempergunakan perangkat gamelan tradisional dalam konteks barunya. Jadi, berusaha mempertahankan tradisi gamelan tetapi mengaplikasikan cara kerja baru di dalam gamelan—yang saya pahami seperti apa yang Lotring lakukan pada awal abad 20.
Harapannya nanti musik yang kita canangkan dari sekarang ini pada zamannya nanti, di masa depan, itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Sama halnya dengan musik elektro-akustik atau elektronik.eksperimental seperti yang dilakukan oleh Mas Kas dan Kadapat itu bagus menurut saya. Saya mendukung hal itu, karena Kadapat menguasai betul tradisinya. Mereka menguasai pakem musik Bali; tradisi jegog; hingga gender wayang. Dari sana, dia bisa memainkan instrumen itu sesuai dengan tekniknya. Dalam konteks Kadapat, dia mengembangkannya berdasarkan fondasi itu. Pengetahuan terhadap apa sih cultural upbringing dari instrumen ini? Itu yang dibawa. Itu bisa memiliki makna yang luar biasa, daripada orang yang mengambil mencomot satu-satu [tapi] belum mengetahui cultural upbringing-nya, teknik bermainnya, terus menempel-nempel. Menurut saya itu yang berbahaya.
Tapi yang memang mengkaji betul dari tradisinya, kemudian intisarinya dia terapkan dalam bentuk eksperimen, itu luar biasa nanti hasilnya. Itu akan beyond era, melampaui zamannya.