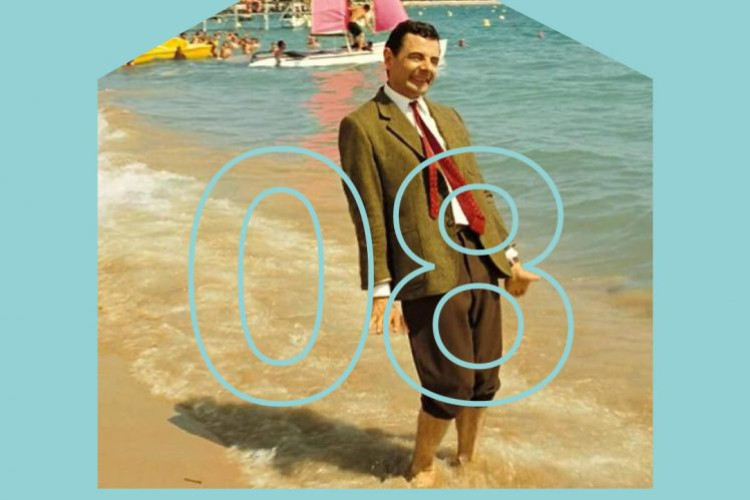“Cancel Culture” di Indonesia: Kesadaran Sosial atau Sekedar Ikut-Ikutan?
Berbincang dengan pelawak hingga co-founder organisasi online tentang “cancel culture” dan posisinya dalam iklim sosial Indonesia
Words by Emma Primastiwi
Ilustrasi & Desain: Mardhi Lu
Dalam 5 tahun terakhir ini, kita telah dipertemukan dengan fenomena-fenomena baru. Rasanya, kesadaran masyarakat akan topik-topik sensitif semakin meningkat. Banyak sekali kelakuan juga pemikiran problematik yang biasa kita diamkan kini menjadi suatu masalah yang bahkan bisa mengakhiri karier seseorang. Dengan kesadaran ini, kita menjadi semakin sadar akan iklim sosial kita, tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negeri. Namun, dengan kesadaran ini, terdapat pula argumen tentang hipersensitivitas yang semakin lama semakin menghambat orang-orang untuk membicarakan topik kontroversial atau mengutarakan opini yang tidak sesuai dengan standar masyarakat. Dengan itu, kami berbincang dengan beberapa figur mulai dari pelawak, videografer hingga co-founder organisasi online mengenai “cancel culture” dan posisinya dalam iklim sosial di Indonesia sekarang ini.

Foto: Ernest Prakasa
Ernest Prakasa
Pelawak, Filmmaker
Dalam perspektif pribadi, apa definisi “Cancel Culture” bagi Anda?
Sepanjang pengetahuan gue, cancel culture adalah sebuah fenomena di mana orang jaman sekarang di era informasi bisa digugat atau dijatuhkan karena kesalahan masa lalu yang pernah ia perbuat yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang.
Bagaimana Anda melihat dampak-dampak ganasnya “Cancel Culture” di media sosial?
Cancel culture di media sosial dampaknya bisa sangat fatal buat public figure yang menjadi sasaran. Atau, bukan hanya public figure sebenernya ya, dalam kasus ini bisa jadi pejabat, apapun yang dalam position of power gitu. Orang yang ada di position of power bisa kehilangan power-nya karena menjadi target dari si campaign cancel culture tertentu.
Sebagai pengamat, menurut Anda impact “Cancel Culture” lebih banyak positif atau negatif?
Kalo dibilang positif atau negatif, gak bisa digeneralisir sepertinya. Kita harus lihat case by case. Karena, kadang-kadang kayak misalnya waktu Kevin Hart diserang dan gak jadi nge-host Academy Awards waktu itu karena dia pernah nge-tweet jokes yang offensive. Menurut gue itu berlebihan karena batasan moral kita itu berevolusi. Kalo kita liat, misalnya bicara konteksnya jokes, dulu jokes-jokes-nya Warkop DKI seksis dan objectifying women, gak ada yang ribut gitu. Sekarang, tentu kita tidak bisa lagi mengenakan jokes-jokes seperti itu. Artinya apa? Artinya batasan itu berevolusi. Kalo misalnya ada orang, komedian, dalam contoh Kevin Hart tadi ya, diungkit misalnya, atau komedian siapapun deh, diungkit jokes lamanya yang pernah menyinggung, tapi menyinggung dalam fenomena kultural sekarang pada saat itu, itu masih acceptable. Nah ini kan menjadi sesuatu yang harusnya bisa dipahami dan bisa dimaafkan gitu. Jadi, tidak semuanya cancel culture bener juga, tapi mau dibilang negatif juga gak juga. Karena kadang-kadang ya memang benar ada orang-orang jahat yang berbuat hal-hal buruk yang tidak diketahui dan orang segan untuk membongkar karena dia terlalu berkuasa.
Terdapat argumen bahwa “Cancel Culture” menjadikan media sosial sebagai tempat yang menolak kebebasan berpendapat. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan tersebut?
Kalau soal kebebasan berpendapat ya public figure kalau mau bebas berpendapat memang resikonya tinggi. Jadi kalau dia bebas berpendapat dan ada orang yang ngomong cancel, itu bagian dari dinamika media sosial, gak bisa naif gitu. Orang yang followers-nya banyak, yang dapet spotlight, memang sulit untuk berpendapat bebas karena dia punya beban untuk menjangkau dan agreeable untuk semua orang. Not me, maksudnya I don’t really care, tapi kan orang yang dalam posisi yang jauh lebih populer (misalnya jauh lebih punya power gitu) pasti kalau dia bicara tentang sesuatu yang kontroversial, yang terlalu memihak pihak tertentu pasti akan membuat pihak yang berseberangan dengan itu jadi gak senang gitu kan. Jadi, kalau dibilang menjadikan media sosial tempat menolak pembebasan berpendapat, gak juga, sebenarnya lebih simple banget, kalau itu fenomena adalah public figure gak bisa ngomong seenaknya. Kalau dia mau ngomong seenaknya, mau ngomong sejujur dan sebebas dia, ya siap menanggung konsekuensinya, se-simple itu sih kalau yang itu.
Menurut Anda, apakah “Cancel Culture” kini telah berubah menjadi mob mentality atau mentalitas ingin “ikut-ikutan” saja?
Kalau soal mob mentality, apalagi di era Covid ini ya, people have so much stress and anger to lash out gitu. Jadi, kalau ada orang yang dirasa berbuat salah kita mendapatkan validasi untuk mem-bully atau menyerang karena kan jadinya salah, maka dia harus dimarahi, jadi ya mentalitas ikut-ikutan ini juga bisa jadi alasan kenapa begitu banyak dan begitu ramai. Tapi, it’s not entirely bad, karena kadang-kadang untuk mem-pressure power tertentu kita butuh banyak orang. Untuk bisa meng-cancel misalnya ada tokoh yang memang seharusnya di-call out dan dijatuhkan karena kejahatan yang dia lakukan misalnya, gak cukup hanya segelintir orang, kan harus banyak orang gitu, jadi, mob mentality ini, umm, I don’t think it’s entirely bad juga gitu.

Foto: Putu Aditya Nugraha
Putu Aditya Nugraha
Videographer Content Creator
Dalam perspektif pribadi, apa definisi “Cancel Culture” bagi Anda?
Saya melihat Cancel Culture sebagai sebuah gerakan yang terorganisir dalam menghentikan dukungan terhadap seorang publik figur atau orang terkenal setelah melakukan atau mengatakan hal-hal yang ofensif atau menyinggung kelompok tertentu.
Bagaimana Anda melihat dampak-dampak ganasnya “Cancel Culture” di media sosial?
Dampaknya kurang lebih saya lihat hanya di durasi yang tidak cukup panjang ya. Jadi seringnya hanya terlihat pada saat itu saja, kemudian beberapa waktu berlalu tidak lagi ramai.
Sebagai pengamat, menurut Anda impact “Cancel Culture” lebih banyak positif atau negatif?
Negatif sih yang saya lihat, dan sudah itu saja.
Terdapat argumen bahwa “Cancel Culture” menjadikan media sosial sebagai tempat yang menolak kebebasan berpendapat. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan tersebut?
Yang saya tahu, kebebasan berpendapat kita sendiri selalu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Jadi, ketersinggungan itu sebaiknya tidak dianggap sebagai baperan atau lemah, karena pengalaman orang itu berbeda-beda. Tapi, sebaiknya itu bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk diskusi dan berusaha saling mengerti point of view masing-masing. Kuncinya empati, dan kalau misalnya menyinggung, ada baiknya minta maaf, belajar, lalu melanjutkan hidup dengan pengalaman baru.
Menurut Anda, apakah “Cancel Culture” kini telah berubah menjadi mob mentality atau mentalitas ingin “ikut-ikutan” saja?
Iya, bisa jadi. Tapi saya yakin banyak orang lain yang juga menyadari bahwa hal ini sangat kontra produktif, karena kultur ini nyaris tidak memberi ruang untuk diskusi, apalagi sekadar membela diri atau menjelaskan maksud sebenarnya. Saya takutnya malah suatu hari ini jadi semacam kalau di Bali istilahnya Suryak Siu. Di mana satu orang meneriakkan “maling”, satu desa langsung percaya, mengejar, dan mengeksekusi. Semoga ke depannya kita semua bisa jadi lebih baik.

Foto: Margianta Surahman
Margianta Surahman
Founder Emancipate Indonesia
Dalam perspektif pribadi, apa definisi “Cancel Culture” bagi Anda?
Bagi saya pribadi, cancel culture adalah wujud mentalitas kerumunan atau mob mentality di mana sekumpulan orang secara serentak dan reaktif menarik dukungan terhadap individu maupun badan tertentu yang dianggap telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang disepakati bersama.
Bagaimana Anda melihat dampak-dampak ganasnya “Cancel Culture” di media sosial?
Dampak cancel culture tidak bisa diremehkan. Banyak orang yang kehilangan reputasinya, jabatannya, dan bahkan pekerjaannya dalam hitungan jam maupun hitungan hari saja. Jadi memang dampaknya cukup signifikan dan ini bisa menimpa siapa saja, terutama di era media sosial seperti sekarang.
Sebagai pengamat, menurut Anda impact “Cancel Culture” lebih banyak positif atau negatif?
Cancel culture memiliki dua sisi. Di satu sisi, cancel culture menyoroti pentingnya akuntabilitas, bagaimana para korban dan penyintas ketidakadilan bersuara bersama-sama secara kolektif demi tercapainya keadilan. Di satu sisi lainnya, cancel culture juga merupakan wujud ekspresi yang reaktif di mana seringkali juga tidak jarang banyak fenomenanya yang melanda orang yang salah. Banyak fenomenanya yang justru tidak memberikan diskursus lebih luas terkait pentingnya isu ketidakadilan tersebut. Jadi lebih fokus kepada demonisasi individu daripada melihat permasalahannya secara lebih luas lagi dan kompleksitas isunya yang tidak selalu hitam putih.
Terdapat argumen bahwa “Cancel Culture” menjadikan media sosial sebagai tempat yang menolak kebebasan berpendapat. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan tersebut?
Justru cancel culture memberikan kita pembelajaran bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban sangatlah penting dalam kebebasan berpendapat. Saat seseorang berpendapat seenaknya, bertindak seenaknya, dan menjadi opresi bagi kalangan tertentu, tentu perlu ada pertanggungjawaban. Tapi, apakah bentuknya harus seperti yang ditunjukkan cancel culture? Orang beramai-ramai menghancurkan karakter seseorang seketika secara reaktif tanpa memberikan ruang lebih luas untuk memahami diskursus tersebut atau tidak, ini harus dicermati. Maka dari itu, mungkin maksudnya baik, ingin memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam kebebasan berpendapat. Tapi, caranya yang terlalu reaktif telah membuat cancel culture justru mengalahkan tujuannya sendiri.
Menurut Anda, apakah “Cancel Culture” kini telah berubah menjadi mob mentality atau mentalitas ingin “ikut-ikutan” saja?
Cancel culture yang ditemukan pada umumnya sekarang lebih mencerminkan mob mentality, fokusnya lebih ke denominasi daripada refleksi, balas dendam daripada koreksi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, saya pun pernah dalam posisi tersebut. Tetapi, kita selalu bisa belajar. Sebelum kita belajar, kita harus mengakui kesalahan kita, menerima ganjaran atas kesalahan kita, dan menghabiskan seluruh sisa hidup kita belajar kembali untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Sangat mudah bagi kita untuk melakukan cancel culture. Tapi, yang susah adalah sama-sama berproses dan saling mengingatkan satu sama lain, saling menjaga satu sama lain agar kita tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan bersama. Jadi, proses refleksi yang kolektif itu adalah alternatif yang lebih baik daripada cancel culture yang hanya berfokus kepada satu momen tertentu saja untuk mendemonisasi orang, alih-alih memberikan ruang diskursus yang lebih luas untuk memahami isu yang kompleks tersebut dan memberikan kesempatan untuk orang yang melakukan kesalahan, menebus kesalahannya dengan berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Itu yang lebih susah, dan itu yang sebetulnya harus kita lakukan bersama-sama secara reflektif.