
Bintaro Design District dan Usaha Membumikan Arsitektur bersama Budi Pradono
Memaknai inklusivitas arsitektur bersama salah satu penggerak Bintaro Design District.
Words by Whiteboard Journal
Teks: Wintang Warastri
Foto: Budi Pradono
“Inklusif itu mengajak semua ikut serta,” tegas Budi Pradono saat ditanya tentang makna inklusivitas. Mengajak semua berarti mengajak seluruh lapisan masyarakat terlepas dari perbedaan kalangan dan generasi, olehnya dibuktikan lewat gelaran Bintaro Design District tahun ini. Memasuki kali kedua penyelenggaraan, Budi bercerita lebih dalam tentang upayanya membumikan dunia arsitektur dengan masyarakat sekitar, membawa tanggung jawab sosial dan lingkungan agar dunia kreatif dapat bersikap responsif terhadap yang terjadi di sekitarnya.
Bagaimana awalnya bisa menggeluti dunia arsitektur?
Dulu awalnya saya belum tahu, saya belum cinta arsitektur, inginnya jadi seniman. Ibu saya yang mengarahkan untuk kuliah arsitektur, setelah berjalan 2-3 tahun, baru cinta mati. Saya kuliah di Jogja, di Duta Wacana. Selepas lulus saya langsung meninggalkan Indonesia, saya kerja di luar bersama arsitek Australia, Inggris, Jepang, Belanda, baru lanjut S2 setelah keliling itu. Saya melanjutkan kuliah di Belanda di 2002. Kemudian pulang di 2005, dan karena teman-teman banyak yang di Bintaro ya sudah, saya juga akhirnya menetap di Bintaro.
Waktu itu saya berkeliling dunia dengan modal cekak, zaman dulu tidak ada internet, jadi sebelum berangkat penting sekali untuk meriset dulu. Mau ke Cina, harus riset dulu desa-desanya seperti apa, disana naik apa, jadi sudah terbiasa dengan kebiasaan meriset. Masuk Jepang, ke Hokkaido dan lain-lainnya saya membuat riset sebelumnya. Waktu kembali masuk ke Indonesia lagi, saat masuk Jakarta saya merasa penting sekali untuk riset cari tempat tinggal, lalu saya lihat bahwa ternyata saya tidak mampu lagi [di Jakarta]. Waktu di Tokyo, Jepang saya terbiasa naik angkutan umum, terbiasa tepat waktu dan nyaman, sementara di Jakarta waktu itu kebalikannya, jadi sempat stres dan merasa tidak mampu, apalagi seperti di Blok M yang penuh asap. Berpikir mau dimana ya? Lalu saya lihat Bintaro itu sepi, karena orang kerja di Jakarta, disana juga berbagai kelengkapan ada, kalau sudah di Bintaro tidak perlu kemana-mana. Juga ternyata prediksi saya benar, karena dia sebetulnya sudah dibangun sejak 1979 jadi sudah mengalami siklus 30 tahun, yang lahir besar di situ sudah pergi, yang tersisa sudah berumur, sehingga sudah ganti generasi. Sementara generasi yang baru ini tidak mau tinggal di sana, semua pindah ke apartemen, pindah ke luar negeri. Jadi itu salah satu alasan kenapa banyak artis yang tinggal di Bintaro, karena pagi-pagi kita tidak perlu berdesak-desakan, di pagi hari otak kita bisa digunakan untuk berpikir jernih dulu, bisa santai minum kopi.
Bintaro Design District kembali hadir tahun ini untuk kedua kalinya. Mengapa memilih wilayah distrik dan Bintaro, adakah karakter tersendiri dari Bintaro yang membuatnya menarik diangkat sebagai identitas pameran?
Energi kreatif di Bintaro sangat besar, dan mereka pada awalnya saya lihat bekerja sendiri-sendiri.
Studio saya sejak sebelum Bintaro Design District (BDD) berlangsung sudah membuat riset, dan dari membuat mapping itu ternyata hasilnya banyak sekali studio kreatif di sana. Di sisi lain, saya setiap tahun selalu ikut acara internasional, Milan Design Week, Maison Objet Paris, London Design Festival, dalam satu tahun saya rutin mengikuti dan saya berpikir kapan Indonesia punya seperti ini dalam arti merayakan desain selama periode tertentu. Jadi sebenarnya ide itu hadir karena pertama, ada ekosistem di dalam Bintaro, misalnya ada arsitek, desainer interior, desainer fashion, filmmaker, bahkan sekelas Ratna Riantiarno, sekelas Teater Koma itu ada di Bintaro. Energi kreatif di Bintaro sangat besar, dan mereka pada awalnya saya lihat bekerja sendiri-sendiri. Suatu kali, misalkan saya punya klien yang mau merancang hotel kapasitas 200 kamar. Satu hotel itu membutuhkan upaya kreatif yang banyak sekali, misal membuat baju seragamnya berarti mengajak desainer fashion, buku tamu dan menu berarti desainer grafis turun, merancang penerangan berarti lighting designer, nah ternyata mereka semua ada di Bintaro. Jadi kalau kita membuat acara kreatif akan gampang sekali, kalau kita berkolaborasi dalam satu proyek dikumpulkan saja semua, sudah bisa. Energi kreatif kalau berkolaborasi bisa menjadi satu kekuatan yang menurut saya super besar. Di satu sisi, kalau dari desain, ada kalanya dia stagnan, ada kalanya menjadi trendsetter, dan dengan adanya acara tahunan hal itu bisa menjadi trigger, pemicu untuk inovasi kreatif. Tahun lalu sudah temanya itu, tahun ini apa lagi. Penting sekali untuk saya kita belajar dari Milan, Milan Design Week itu rutin dilakukan setiap tahun, itu menurut saya bagus sekali. Saya tadinya bercita-cita bikin Jakarta Design Festival mirip dengan London, atau Jakarta Design Week, tidak usah langsung festival juga bisa. Tapi ternyata sulit tanpa satu demi satu distriknya dibangun dulu, setiap distrik harus dikuatkan supaya mendorong nanti masing-masing. Bisa bikin Kemang Design District, Kebayoran Design District, yang di Bintaro kan sudah berjalan, nanti itu semua digabung menjadi Jakarta Design Festival. Itu yang saya pelajari dari Milan, di Milan itu ada Ventura Lambrate yang mencakup satu bagian sendiri, ada Brera Design District, itu juga satu distrik sendiri, begitu, yang semuanya bergabung menjadi Milan Design Week. Itu sudah sejak tahun 90an.
Lewat tema ini, semua generasi bisa mengajukan usulan dan ide desain.
Jadi memilih Bintaro karena ekosistemnya sudah ada, tinggal saya datangi satu-persatu, mau tidak ikut BDD. Apa itu BDD? Saya jelaskan dulu, satu demi satu saya datangi sampai mereka paham. Karena kalau yang belum pernah datang atau tahu yang seperti ini itu sulit. Teman saya dari Jepang, dari Italia, dari Rusia langsung datang, ikut selama 10 hari karena mereka sudah pernah jalan ke Milan Design Week dan sudah ada bayangan. Bicara soal karakter wilayah, saya rasa Bintaro itu seksi. Dari segi aksesibilitas, dari bandara hanya setengah jam, saya ke kota juga hanya setengah jam naik kereta. Apalagi sekarang dengan MRT, Lebak Bulus ke Bundaran HI 25 menit saja. Daerahnya sudah dikembangkan sejak 1979 dan ada area-area misalkan sektor 1, 2 yang sudah mapan secara komunitas, lalu nanti ada generasi-generasi baru di sektor 7, 8, 9. Juga kalau saya lihat ukuran lahannya itu di sektor awal-awal lebih besar, sementara kalau di sektor 9 dan lain-lain itu hanya 400 meter, 500 meter, makin kesana makin kecil karena lahannya makin mahal, lalu tetangganya Bintaro itu apa? Ada BSD, Serpong, Summarecon, di sekitar Bintaro itu terlalu kaku. Saya bawa tamu dari luar negeri 5 orang, mereka saya bawa jalan-jalan di Bintaro dari ujung sampai ke ujung, setelah itu saya tanya pendapatnya. Kesimpulannya sama, bahwa yang di BSD terlalu rigid karena ada jalur truk masuk, sehingga jalannya lebar dan otomatis membuat chaos. Rigid dalam arti cat tidak boleh diubah, ada standar sendiri dari developer. Sementara Bintaro ini karena diserahkan kepada Pemda, kadang-kadang ada yang terlupa jadi pasarnya makin kotor, banyak rumah jelek dikontrakkan dan dijual, itu memberi peluang untuk desainer berpikir “ini kalau dibeginikan jadi bagus, jadi keren,” ada fleksibilitas untuk berkreasi di sana. Tamu saya saja melihatnya gatal, ingin berkreasi macam-macam. Sebenarnya selama ini banyak acara, tapi semuanya dikontrol Pemda. Seperti dulu BEKRAF pernah membuat acara yang trennya adalah semuanya dikumpulkan di satu titik, misal di JHCC. Kemarin terjadi kekacauan ketika ada demo, padahal sedang ada 5 acara disana, langsung tidak ada pengunjung. Berkaca dari sini, BDD saya putuskan untuk dipecah agar titiknya banyak, sekarang ada di 90 titik. Sejarahnya arsitektur dari Indonesia, Yori Antar, Andra Matin dan lain-lain memang mereka selalu mengadakan open house, generasi muda kapan tampilnya? Sehingga waktu BDD berlangsung, saya menawarkan satu opsi dimana lewat tema ini, semua generasi bisa mengajukan usulan dan ide desain. Yang tidak berkantor di Bintaro ya bisa menggunakan taman, ruang publik manapun.
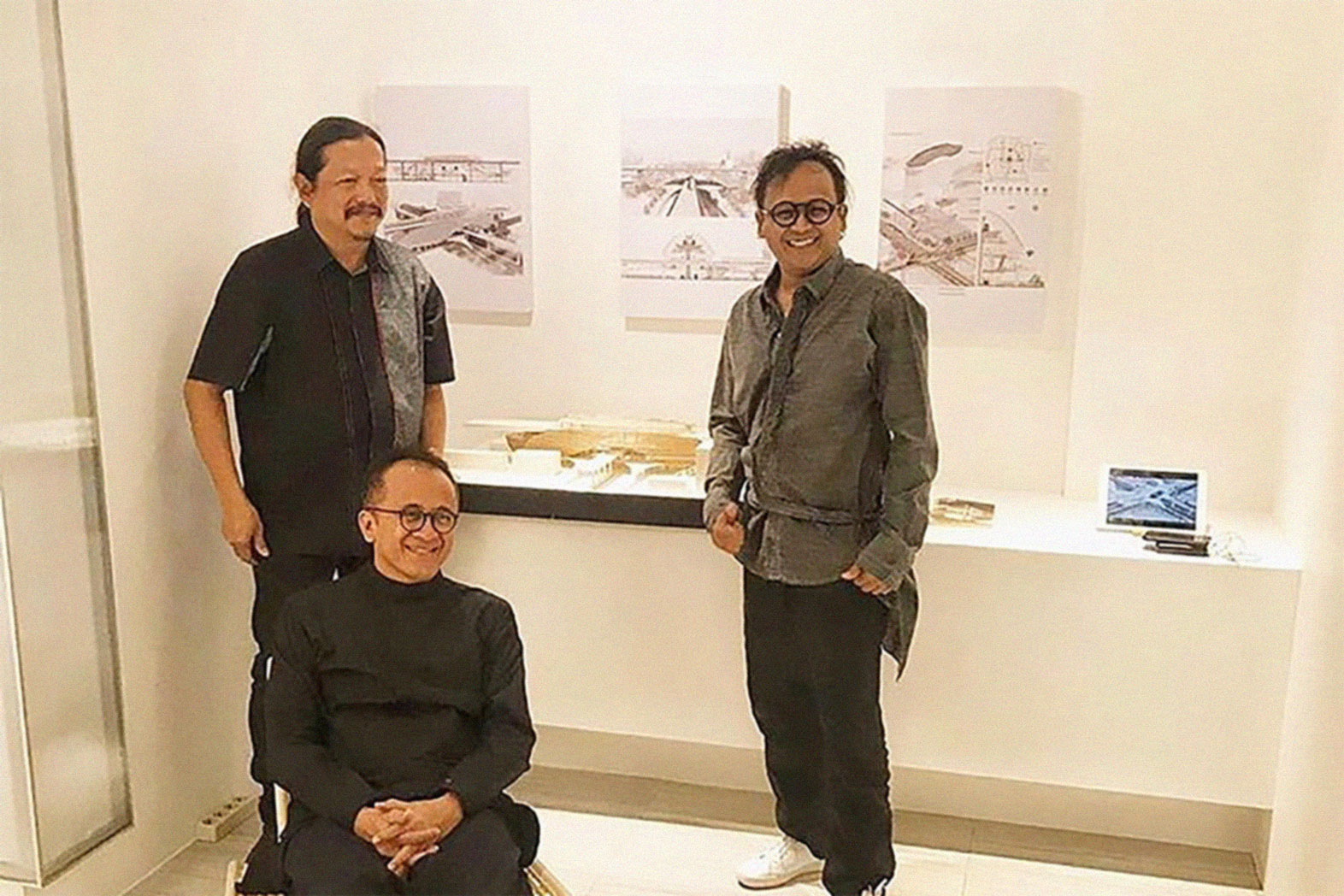
Bagaimana agar tetap menjaga identitas Bintaro terutama bagi acara-acara yang diadakan di luar wilayah tersebut?
Yang diluar Bintaro kami menyebutnya sebagai collateral events, saya belajar dari pengalaman di Venice. Setiap dua tahun itu ada Venice Biennale of Architecture dan disana ada dua lokasi utama, sekarang bagaimana caranya Paolo Baratta [Presiden Venice Biennale] bisa menjadikan seluruh kota happening. Dia tawarkan ke semua galeri yang ada disana untuk mengambil tema yang sama, semua bisa mengangkat dengan label collateral events. Jadi saya berpikir karena kemarin sekalian dengan Andra Matin yang ingin memperingati 21 tahun berkarya, dia ingin membuat pameran besar di Galeri Nasional, juga Dia.lo.gue yang punya acara Seek a Seek yang ada hampir 50 desainer grafis berpameran, kemudian saya usul BDD dibuat segitiga dengan dua collateral events diluar yang mendukung BDD.
Inklusif itu mengajak semuanya untuk ikut serta
BDD tahun ini mengambil tema Inclusivity. Apa makna inklusivitas menurut Anda pribadi, dan bagaimana aplikasinya dalam dunia arsitektur dan desain/kreatif?
Inklusif itu mengajak semuanya untuk ikut serta, satu misalnya dalam konteks kita bertetangga sehari-hari. Tetangga tidak setuju kalau tembok antara rumah kita terlalu tinggi, berarti kita harus mau bernegosiasi. Yang kedua, kalau dari sisi desain misal untuk arsitek atau desainer interior, mereka umumnya direkrut oleh perusahaan atau individu yang sudah mapan, sementara pengusaha atau orang marginal, kadang meskipun mereka punya modal banyak mereka tidak kenal namanya arsitek itu apa. Dia membuka warung, berjualan beras, bisa mengumpulkan banyak juga padahal. Disini saya rasa kita harus memperkenalkan desain kepada mereka. Inklusif itu adalah juga memperkenalkan desain kepada masyarakat yang lebih luas dengan cara itu tadi.
Anda menyatakan bahwa ingin “membumikan arsitektur dan desain” melalui tema Inclusivity ini. Adakah citra arsitektur sebagai bidang yang elit mempengaruhi pendekatan ini?
Arsitek diberi kesempatan untuk mendesain langsung demi kepentingan publik
Pasti, karena kebijakan pemerintah untuk bidang perumahan kan dia autopilot, serahkan saja kepada developer. Perumahan rakyat kan tidak disiapkan oleh pemerintah, sementara kalau di luar negeri yang namanya rumah susun saja itu dikompetisikan desainnya, dipilih desain terbaik hasil arsitek top. Dengan begitu, arsitek diberi kesempatan untuk mendesain langsung demi kepentingan publik, sementara kalau disini kan rumah susun dianggap rumah sisa, kemarin sempat ketahuan kalau ada developer berjanji membuat rumah susun, berhutang ke pemerintah tapi tidak ditindaklanjuti karena dianggap sisa, rugi kalau membikin rumah susun. Masalahnya seperti itu, mindset yang seperti itu masih sangat kuat disini.

Clay House Selong Blanak. Foto: Instagram / Budi Pradono
Berbicara tentang membumikan, seberapa jauh menurut Anda arsitektur memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam konteks masyarakat awam?
Merespon lingkungan sekitar. Itu menurut saya adalah strategi inklusivitas supaya bisa diterima masyarakat.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu tantangannya, artinya waktu penyelenggaraan BDD tahun lalu, kali pertama pelaksanaannya saya stres, karena membuat macet Bintaro. Akhirnya yang kedua ini dibuat lebih strategis, jadi kapasitas penonton dikurangi, ada ojek online juga. Saya simpulkan kalau mendapat tentangan dari RT/RW dan lingkungan sekitar, itu berarti acara ini belum inklusif. Belum berhasil membumi. Akhirnya tahun ini, banyak Pak RT dan RW yang bertemu saya, berterima kasih karena saya mendorong peserta untuk bereaksi pada lingkungan selebar 1 km. Jadi dalam rentang satu kilometer mengevaluasi, oh ada tong sampah jelek, oh ada taman yang kurang bagus, oh ada gardu satpam yang perlu diperbaiki. Itu semua bagian dari sisi responsif sebagai desainer, merespon lingkungan sekitar. Itu menurut saya adalah strategi inklusivitas supaya bisa diterima masyarakat. Coba kalau itu dilakukan setiap tahun, dalam tiga tahun ke depan Bintaro makin keren.
Mulai dari pos satpam hingga kedai mie ayam, karya-karya yang ditampilkan dalam Bintaro Design District terbilang sangatlah beragam. Boleh diceritakan tentang proses mengkurasi BDD?
Kami berpikir kalau kami mendesain yang namanya kafe sudah banyak, tapi kalau mendesain warung mie ayam, warung burjo siapa yang mau?
Semua adalah hasil dari tantangan merespon satu kilometer itu. Misalnya yang mie ayam, itu adalah kedai Mie Ayam Tirta, itu ceritanya dia berada di rentang satu kilometer dari rumah Andra Matin. Mie ayam ini bersejarah, karena mie ayam ini jadi makanan tiga kantor, Arkonin, Andra Matin, dan studio saya, BPA [Budi Pradono Architects]. Pagi dia mangkal di BPA, siang di Andra Matin, kemudian malam di Arkonin. Semua makannya mie ayam, pagi siang malam [tertawa]. Sampai anaknya Andra Matin dari kecil juga makan disitu, jadi terasa ada sejarahnya. Kami berpikir ini semacam sedekah desain, mau mendesain mie ayam saja berebut. Dekat studio saya juga ada lagi, namanya Warung Burjo MM. Itu sudah lama sekali, dan dia buka 24 jam, tahun lalu rapat membahas acara ini sampai jam dua, tiga pagi, istirahat perginya ya kesitu. Itu yang termasuk dalam rentang satu kilometer studio saya. Itu dikerjakan juga oleh desainer grafis Thinking Form, instalasinya juga, semua karena kami berpikir kalau kami mendesain yang namanya kafe sudah banyak, tapi kalau mendesain warung mie ayam, warung burjo siapa yang mau?
Satu instalasi yang mengajak suku adat, itu ide dari studionya Yori [Antar], Han Awal and Partners. Jadi setiap studio berhak mengajukan ide untuk open studio mereka. Mereka merayakan satu rumah panjang yang ada di Kalimantan, baru saja mendapatkan penghargaan di New York. Dia mengajak komunitas Dayak itu supaya sekalian membuat presentasi di BDD, memberikan pengetahuan dasar tentang apa itu rumah panjang mereka. Banyak sekali yang mengunjungi, sehingga memperkuat jejaring mereka juga. Tentang reaksi mereka pada rentang satu kilometer, ada di SD Pucung yang di dekat sana. HAP akhirnya berkolaborasi dengan SD tersebut untuk membuat instalasi, membuat presentasi pengetahuan kepada satu sekolah.
Ada aspek interaktif juga ya disini, kalau boleh disimpulkan.
Iya, jadi kalau misalnya di studio saya karena kantor kami berbasis riset, kita menceritakan riset kita. Ada proyek yang baru saja menang dengan perusahaan Belanda, kita jelaskan riset tentang arak dari seluruh Indonesia, proses membuatnya seperti apa, juga riset tentang Bintaro sendiri itu seperti apa. Jadi pengunjung mendapat cerita, yang datang ke studio kami kurang lebih ada total 800 orang selama durasi acara. Di kantor Mas Yori mungkin ada 1.000 lebih, belum kami kalkulasi juga dengan collateral events-nya, mungkin ada diatas 20/30.000.
Kedepannya, mungkin ini bisa menjadi kegiatan komunitas terbesar di Indonesia. Bagi komunitas kami, yang penting modal balik saja sudah terima kasih. Misalkan ada si A yang punya ide seperti ini, seperti kemarin Mira Lesmana dan Riri Riza punya ide, kami persilahkan. Bagi semua yang idenya disetujui, mereka juga harus sanggup membiayai itu. Kami melihatnya saweran skala nasional, kalau berhasil tiap tahun berarti Bintaro semakin bagus, karena desainnya otomatis semakin bagus-bagus, dan kalau bisa melebar misalnya menjadi ada Kemang Design District, saya akan mendorong teman-teman yang di Kemang. Harus ada satu pionir seperti saya untuk bisa maju, mulai dari situ baru kita bisa kerjasama untuk mencocokkan. Harus muncul orang-orang yang mau berjibaku di kawasan masing-masing, misalnya Hermawan Tanzil dari Dia.lo.gue bisa mengajak seluruh Kemang, tapi semangatnya harus sama, visinya harus sama terlebih dulu. Kebetulan tema tahun depan sudah ada, judulnya “Berbagi Masa Depan”. Setelah bersama-sama lewat “Inclusivity”, nanti diajak “Berbagi Masa Depan”. Sekali-kali menggunakan Bahasa Indonesia, tidak Inggris.

Foto: Slanted House

Foto: Dezeen
Selama berjalan dengan Budi Pradono Architects, adakah perubahan yang dirasakan dari awal hingga sekarang terutama tentang karakter dan proses berkarya?
Kita konsisten saja membuktikan bahwa ternyata desain berbasis riset bisa bertahan dan berkembang.
Tidak ada sebenarnya, cuma kita konsisten saja membuktikan bahwa ternyata desain berbasis riset bisa bertahan dan berkembang. Banyak firma yang tidak punya dasar itu, jadi mereka mengerjakan apa saja, klien minta apa mereka ada. Kalau saya tidak begitu, selalu menawarkan dulu, “mau diriset tidak?” hasilnya pasti tidak biasa memang. Semua desain kami dasarnya adalah riset. Hasilnya klien kami sekarang banyak yang asing, dari Belanda, Inggris, Australia, Perancis, itu karena basis desain itu tadi. Kebetulan kalau klien dalam negeri kita masih belum bisa bicara riset terlalu serius, meskipun metodenya tetap kami gunakan riset yang sama, cuma ya begitulah. Kemarin saya meluncurkan satu kursi di Maison Objet Paris, itu dasarnya dari riset bahwa generasi sekarang suka jalan-jalan, jadi membuat kursi yang bisa dibongkar, itu apresiasinya memang di luar. Sekarang saya sibuk mengerjakan BDD sambil saya juga menyiapkan untuk Milan Design Week. Karya saya kebetulan sudah terpilih oleh kuratornya, sedang disiapkan satu plot untuk pameran tunggal Budi Pradono. Saya juga sedang menyiapkan summer course di daerah di Indonesia, nanti entah di Lombok atau di Sumba, karena saya selama tiga tahun belakangan menjadi pengajar tamu di Praha, daripada saya yang pergi kesana terus kali ini saya ajak kesini, rencananya memang membuat pondokan sementara di pulau. Mahasiswanya tidak hanya dari Praha, dari macam-macam negara lain juga.
Beberapa karya Anda seperti Rumah Miring dan Dancing Mountain House mengintegrasikan aspek alam di dalam ruangan. Boleh diceritakan tentang inspirasi dari pendekatan tersebut, terutama dari sudut pandang lingkungan?
Tentang Rumah Miring, rumah itu juga hadir dari hasil riset. Jadi pertama, riset di Pondok Indah itu banyak artis dan politisi yang tinggal di sana, dan mereka umumnya ingin menunjukkan eksistensi mereka kalau mereka sudah sukses dan berhasil. Jadi rumahnya dibuat dengan kolom-kolom besar warnanya emas. Besar dan mewah jadi terlihat kesuksesannya. Hampir semua rumah artis dan politisi di sana seperti itu. Begitu saya dapat proyek ini, saya bilang, menurut saya biasanya kalau orang sukses tidak perlu ditunjukkan lagi [kesuksesannya], kalau dia menyombong berarti sebenarnya dia orang yang tidak punya. Misalkan seseorang mau datang ke pernikahan, berpikir bagaimana supaya terlihat kaya? Pinjam baju, aksesoris sana sini, karena tidak percaya diri. Saya kemudian mengusulkan untuk membuat rumah bentuk kotak saja, lalu saya pikir kalau dimiringkan seperti sedang gempa bumi, itu secara implisit mempertanyakan pameran kesuksesan itu. Mempertanyakan kesuksesan, kalau rumahnya ambruk apakah kesuksesannya juga ikut ambruk? Orang yang sudah benar-benar merasa sukses harusnya tidak akan merasa seperti itu.
Kalau yang rumah Dancing Mountain itu juga sama, berbasis riset juga. Orang tua saya sekarang sudah tiada, tapi waktu itu saya bangun Dancing Mountain House untuk orang tua saya sendiri. Mereka digusur dari rumah dinas setelah pensiun, waktu itu posisinya saya sedang di luar negeri. Ya sudah, terpikir untuk membangun rumah untuk mereka yang sustainable, tetangganya banyak memakai bahan bambu, jadi berpikir untuk memakai yang sama saja. Kebetulan di sekitar Salatiga banyak gunung, Merbabu, Merapi, Telomoyo, ada lima totalnya, jadi muncul ide menamainya Dancing Mountain. Bentuknya menyimbolkan kelima gunung tersebut. Makna sustainability itu untuk saya ya ramah lingkungan, banyak bambu yang bisa diolah, dan ada juga satu air terjun di gunung di dekat sana yaitu Sekar Langit, penduduk disana sudah ratusan tahun punya metode mengawetkan bambu. Bambu dipotong dan dimasukkan ke dalam sungai selama setahun, itu teknik pengawetan tradisional dari nenek moyang kita. Teknik itu menghilangkan kandungan glukosanya, jadi tidak cepat busuk dan dimakan rayap atau ngengat.

Foto: Budi Pradono
Belajar di Indonesia itu jelas belajar tentang budayanya.
Anda pernah menyatakan bahwa pendidikan arsitektur di Belanda membuat Anda “belajar dalam kilometer,” sementara di Jepang “belajar dalam milimeter.” Bagaimana dengan pengalaman/pendidikan di Indonesia dan pengaruhnya pada Anda?
Belajar di Indonesia itu jelas belajar tentang budayanya. Budaya setiap daerah itu kaya sekali, saya pernah ke Papua dengan Mas Yori, mereka sangat bersemangat bertemu dan menjamu kami. Di tengah hutan disuguhi buah-buahan sementara tidak ada kulkas, cara penyimpanan mereka yaitu buah-buahannya ditaruh di pohon yang dikelilingi lumut yang sudah beku, jadi dia bisa menjadi pendingin. Itu menarik sekali menurut saya. Sekarang ini saya sedang di Lombok, kemarin kami mengunjungi satu desa yang kebetulan sedang ada acara pernikahan. Dihadiri ribuan orang, mereka memasak nasi sampai 200 kilogram, alat pengaduknya mirip dengan yang untuk mengaduk pasir [tertawa]. Saya suka sekali mengamati yang seperti itu, yang dipelajari dari Indonesia adalah kekayaan-kekayaan seperti itu, adaptasi dengan alam dan lingkungan sekitar dan manusianya juga.
Tentang posisi desain dalam masyarakat, menurut Anda apa sebenarnya tanggung jawab sosial seorang arsitektur terutama lewat dunia kreatif?
Tanggung jawab sosial itu menurut saya menjaga etika lingkungan sekitar, menyerap kebudayaan lokal setempat, semua dituangkan saat proses mendesain jadi rancangannya itu akan mengapresiasi lingkungan sekitarnya sendiri.
Bergeser ke bahasan desain di era digital, bagaimana agar seorang kreatif tetap bisa memiliki/menunjukkan karakter yang distingtif di tengah akibat efek bubble dan echo chamber?
Kami berbasis riset, ia akan menjadi dasar yang galiannya bisa tiada habisnya.
Kalau saya kembali ke metode kerja saya, kalau kami berbasis riset, ia akan menjadi dasar yang galiannya bisa tiada habisnya. Keluarannya bisa banyak sekali, dan nantinya dia juga akan bisa mengantisipasi tren masa depan. Kalau di BPA menentukan karakter itu selalu dengan konteks dan berjalannya waktu. Selalu kita membahas setiap proyek dengan metode riset itu dan selalu dilakukan dalam tim, bisa berdelapan, bersepuluh, nanti setiap orang – seperti kita mau memasak, bumbu-bumbunya macam-macam, yang satu riset bumbu A, yang satunya lagi riset bumbu B, digabungkan dan akhirnya menjadi sesuatu.
Adakah prinsip-prinsip tertentu yang Anda bawa dalam setiap karya, dan bagaimana mengkompromikannya terutama dalam hal fungsi versus estetika?
Kreatif tidak melulu lekat dengan estetika, bisa dari pendekatan lainnya juga.
Menurut saya, style is dead. Jadi kalau orang hanya berpaku pada gaya, dia tidak akan bertahan lama dan pasti mati, karena dia membatasi waktunya sendiri. Itu bedanya kami dengan dunia fashion, menurut saya. Fashion bergantung dengan pergantian musim, sementara arsitektur harus timeless. Jadi misal menginterpretasikan yang tradisi itu tadi, ada satu proyek saya yaitu Villa Casablancka di Tabanan yang mentransformasikan tradisi Bali, namanya Akasa. “Akasa” itu maksudnya ruang kosong di tengah ruangan, bentuk bangunan bisa bermacam-macam tapi kita mempertahankan si ruang kosong itu tadi. Maksud saya dengan menjauh dari style itu tadi, adalah bahwa konsepsi Bali itu tidak hanya lewat ukir-ukiran, lewat motif-motif tertentu yang bisa diaplikasikan. Kreatif tidak melulu lekat dengan estetika, bisa dari pendekatan lainnya juga.











