
Berbincang tentang Arsitektur sebagai Solusi dengan Stephanie Larassati
Kami berbincang dengan arsitek Stephanie Larassati tentang ruang publik, proyek Misbar Kayong, hingga posisi perempuan dalam dunia arsitektur.
Words by Ghina Sabrina
Bermula dari keinginan untuk membuat museum memorial yang mendokumentasikan momen penting dalam sejarah Indonesia, Stephanie Larassati pun memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk melanjutkan praktiknya sebagai seorang arsitek. Pengalaman sekaligus pendidikan yang ia dapatkan dari Berlin juga membawa perspektif baru terhadap bagaimana ia meng-approach arsitektur lewat desain dan konsep yang ia bangun. Banyak dari karyanya berpusat pada aspek ruang publik dengan pesan sosial yang kuat, seperti proyek Misbar di daerah-daerah berkembang di Indonesia. Kami berbincang dengan Stephanie mengenai arsitektur sebagai solusi, perannya dalam membangun temporary outdoor cinema di Kalimantan hingga keinginannya untuk membangun museum di Indonesia.
Apa yang membuat Anda memilih untuk fokus pada bidang arsitektur?
Saya memutuskan untuk sekolah arsitektur mungkin sedikit terinspirasi sama nyokap. Dia adalah seorang arsitek juga, lalu dia pernah bilang kalau saya itu campuran antara orang seni dan technical – dan dia bilang bahwa arsitektur adalah ilmu yang cocok untuk itu. Awalnya saya tidak begitu mengerti maksudnya karena pada semester 1 dan 2 kuliah, saya benar-benar clueless. Nilai saya kurang bagus dan pada waktu itu saya tidak mengerti ketika ada yang menyuruh saya untuk membuat konsep. Tapi, akhirnya saya melihat bahwa arsitektur itu sebagai ilmu yang menarik banget karena dia itu ilmu yang menggabungkan semua hal. Tidak hanya seni, tapi technical, managerial dan kadang filosofis juga. Saya merasa bahwa saya bertambah dewasa karena arsitektur juga.
Dengan pengalaman yang didapat lewat pendidikan arsitektur di Jerman, apa yang membedakan perspektif Anda dengan arsitek-arsitek yang mengenyam pendidikan di Indonesia?
Sebetulnya agak sulit untuk membandingkan saya dengan teman-teman sejawat saya. Cuma yang bisa saya lihat mungkin malah junior-junior arsitek yang kerja dengan saya – mereka kan cerminan langsung dari produk pendidikan arsitektur di Indonesia. Perbedaan yang saya lihat paling mencolok itu, mungkin kalau misalnya di Jerman, kita dibebaskan untuk mencoba hal-hal yang di luar kebiasaan. Kalau di sini, saya melihat ada tendensi bahwa mereka agak khawatir, apakah itu untuk mencoba desain ataupun menuangkan konsep. Ada terlalu banyak kekhawatiran formal yang sudah ada di awal proses. Formalitas itu penting apalagi dalam membangun karena kita berurusan dengan regulasi dan manusia, tapi itulah arsitektur, kita harus tahu sweet spot antara desain dan formalitas itu. Itu sih salah satu yang saya lihat sangat signifikan.
Dan mungkin yang paling terlihat juga adalah ketika saya sekolah di Jerman, setiap harinya saya dihadapkan oleh kehidupan kota yang sudah advanced. Infrastruktur yang advanced yang di balik itu ada layer-layer pengambilan keputusan yang sudah advanced, demokratis, dan segala macam. Dan akhirnya itu menghasilkan sebuah bangunan yang berkualitas tinggi. Di sini, kita kekurangan referensi itu, sehingga agak sulit untuk menyampaikan apa yang saya maksud ketika ingin menciptakan desain atau ingin menyatakan pendapat tentang sebuah karya. Ada aspek-aspek yang mungkin memang kita yang di Indonesia tidak terbiasa untuk melihat. Kekurangan referensi itu mempengaruhi banget bagaimana cara pandang kita dalam approaching desain atau menilai sebuah karya.
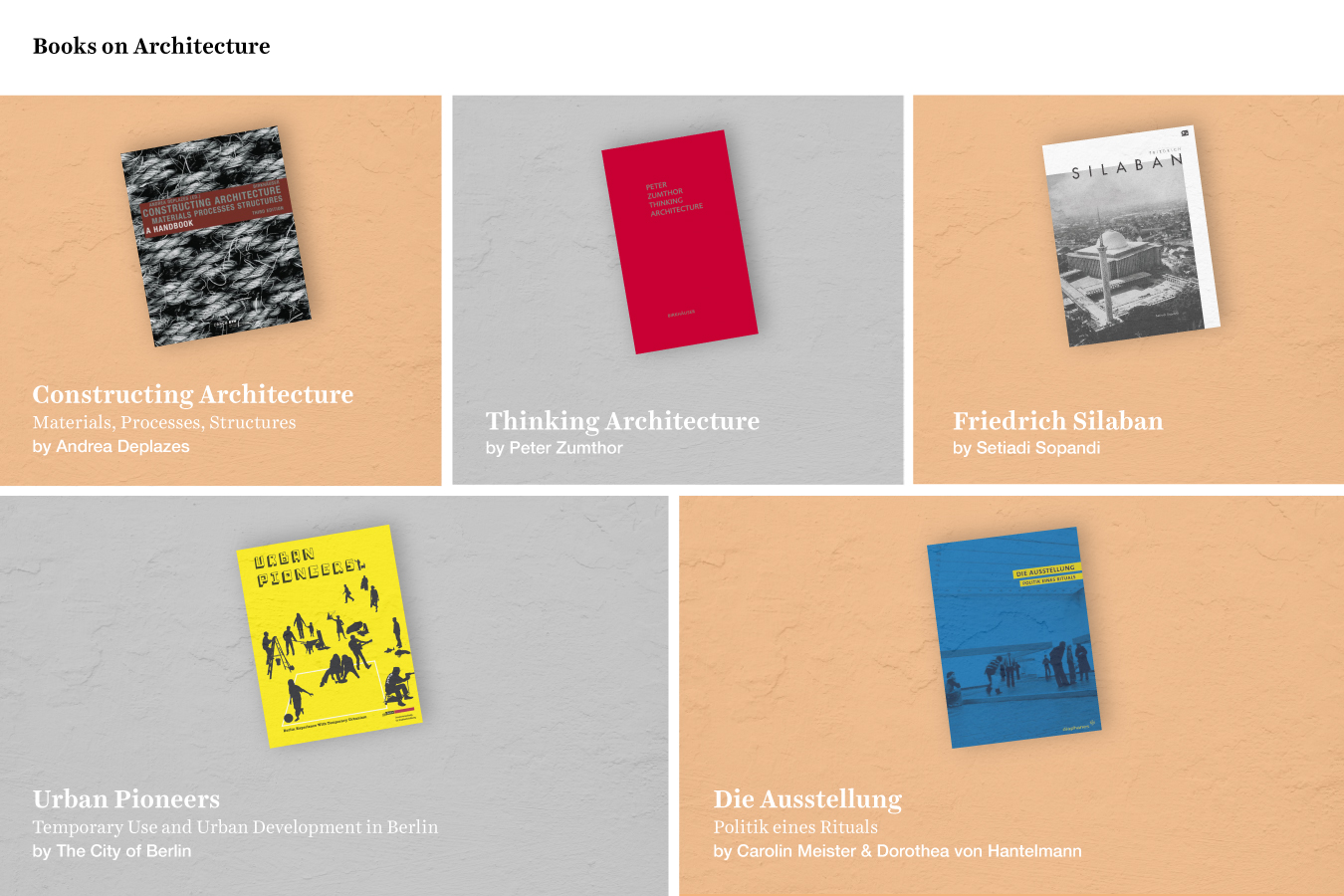
Terlihat bahwa desain-desain Anda memiliki esensi yang mengedepankan hubungan emosional antara para pengguna dengan lingkungannya. Apa alasan di balik hal ini?
Menurut saya, setiap arsitektur itu berhubungan dengan memori. Ruang itu tidak pernah tiba-tiba muncul. Dia pernah ada ceritanya, dia pernah ada, lalu dia sekarang seperti ini dan dia akan menjadi apa. Dan arsitektur itu sebetulnya apa yang kita jumpai setiap hari. Sekarang kita berada di sebuah arsitektur. Yang kita lihat dan yang mengingatkan kita sama masa kecil, atau bau-bauan yang mengingatkan kita sama pengalaman yang manis, itu akan menjadi sebuah tempat yang sukses, dan itu sebetulnya apa yang ingin kita capai dalam sebuah bangunan. Sebuah bangunan di mana orang merasa nyaman dan mempunyai relasi terhadap space di sana.
Penting juga untuk sebuah bangunan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya, yang berarti dengan orangnya, dengan bangunan sekitarnya dan juga lingkungan alamnya juga. Dan ketika kita bicara tentang arsitektur, kita membangun sesuatu yang tanggung jawabnya itu untuk 20 tahun ke depan. Jadi mungkin lebih dari hanya sekadar emosional. Hubungan emosional yang saya maksud itu lebih ke bagaimana dia bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar dan bagaimana dia memberikan rasa familiar dengan penggunanya.
Arsitektur bisa menjadi solusi tapi bisa menjadi sesuatu yang destruktif sebenarnya.
Tidak hanya berbentuk bangunan, arsitektur juga mempengaruhi kehidupan sosial para penggunanya. Bagaimana Anda melihat arsitektur sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi di kota-kota besar?
Arsitektur bisa menjadi solusi tapi bisa menjadi sesuatu yang destruktif sebenarnya. Whether we like it or not, arsitektur adalah sebuah ilmu yang dari dulu sampai sekarang dibutuhkan karena kita pasti butuh ruang tertutup untuk tinggal, kerja dan sebagainya. Ketika kita melihat rumah, itu adalah suatu solid object yang bisa kita kotak-katik semau kita. Tapi ketika kita melihat itu dalam perspektif yang lebih besar, ketika terdapat 1 juta rumah dan itu membentuk sebuah kota, bukankah kita jadi berpikir bagaimana rumah itu harus dibangun agar kotanya menjadi livable? Rumah adalah kota, kota adalah rumah. Jadi sebenarnya kalau mau membicarakan mengenai sebuah kota yang baik, memang harus mulai dari satu rumah. Sayangnya di Indonesia sama sekali belum bisa diterapkan karena sistemnya belum berfungsi.
Ada satu contoh menarik mengenai arsitektur yang menjadi solusi, yang sebetulnya juga menyangkut tema yang sekarang sedang saya coba kulik. Specifically, arsitektur di tempat-tempat yang tidak terpakai. Seperti kita lihat, di kota-kota besar banyak masalah bangungan-bangunan yang terlantar dan membuat celah-celah mati. Dan itu sebetulnya berpengaruh negatif pada sebuah kota. Dia bisa menurunkan nilai dari lingkungan sekitar dan meningkatkan kriminalitas. Orang-orang terus membangun gedung-gedung baru dan space-space yang kosong malah tidak terpakai. Ada satu strategi desain di arsitektur yang kadang suka dipandang sebelah mata tapi sebetulnya menarik, yaitu bagaimana caranya untuk reactivate tempat-tempat yang kosong di kota. Dia bisa trigger pelaku-pelaku ekonomi kreatif atau pemerintah tentang apa sih yang bisa dikerjakan di tempat kosong ini? Karena kadang-kadang orang itu punya uang tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, atau investor mempunyai uang tapi malah dijadikan sebuah mall. Itu real, dan tidak hanya terjadi di Jakarta, di Berlin juga.
Berlin adalah contoh yang paling cocok untuk proyek-proyek temporer di tempat-tempat yang temporer juga. Jadi tempat yang dulu terbengkalai, yang tidak ada nilainya, akhirnya value-nya naik karena ada anak-anak muda yang memasukan fungsi-fungsi baru di tempat itu, misalnya membuat club dadakan atau space di pinggir sungai dijadikan beach bar dadakan. Itu sangat berguna untuk kota itu dan pada akhirnya kota tersebut akan memiliki identitas baru. Berlin pada waktu itu dapat identitas sebagai “the hype city” karena kegiatan-kegiatan seperti itu. Akhirnya pemerintah menganggap serius kegiatan itu dan dijadikan sebagai program pemerintah. Dan kemudian, menjadi win-win solution untuk para investor yang mempunyai tanah di sana. Mereka tidak perlu membuat apa-apa, tapi tanahnya dirawat oleh para anak-anak muda itu. Konfliknya akan ada ketika nanti investor sudah punya uang, lalu yang punya tanah sudah keburu bikin cult di lahan itu dan akhirnya timbul konflik. Tapi itu adalah dinamika di perkotaan. Banyak tempat-tempat yang pada akhirnya jadi milik masyarakat lagi karena ada pergerakan seperti itu. Placemaking in a transient space itu menurut saya salah satu strategi yang menarik banget untuk di kulik, terutama di kota-kota besar.
Placemaking in a transient space itu menurut saya salah satu strategi yang menarik banget untuk di kulik, terutama di kota-kota besar.
Waktu itu saya pergi ke Kota Lama di Semarang, bagus banget. Bangunan-bangunannya itu rotten seperti di venice. Venice juga seperti itu, super rotten dan pada awalnya tidak ada yang mau ke sana, tapi disuntik dengan kegiatan-kegiatan high class. Semua biennale yang nomor satu ada disana, dan pada akhirnya kota itu memiliki charm-nya sendiri. Padahal bangunannya tetap rotten.

Foto: Ardi Widja

Foto: Ardi Widja

Foto: Ardi Widja

Foto: Ardi Widja

Foto: Ardi Widja
Anda pernah terlibat dalam proyek Misbar yang merupakan inisiasi oleh Bekraf di tahun 2016 lalu. Boleh ceritakan tentang proyek tersebut?
Proyek itu bermula dari ketika program directornya, Mas Totot Indrarto approach saya untuk membuat Misbar ini. Dia tahu saya dari proyek Rekoleksi Memori di Taman Ismail Marzuki yang merupakan instalasi temporer sebesar 287 meter persegi dan dibangun dalam 3 hari menyangkut museum temporer untuk Hak Asasi Manusia. Dan ternyata, di Jakarta saat itu, atau mungkin sampai saat ini masih sedikit proyek-proyek temporer seperti itu yang mengusung topik-topik kultural. Akhirnya mungkin gara-gara proyek itu, orang-orang langsung refer ke saya tentang Misbar karena waktu itu brief-nya adalah suatu project temporary outdoor cinema di daerah-daerah berkembang.
Saya pun baru tahu juga ternyata di Indonesia penyebaran bioskop itu sangat tidak merata, bahkan ada daerah yang tidak ada sama sekali. Dan salah satu tujuan dari Bekraf adalah ingin meningkatkan ekonomi kreatif di daerah berkembang, selain itu mungkin juga ingin orang-orang di luar Jawa agar dapat membicarakan tentang hal-hal lain. Akhirnya saya di-approach, terus proyek itu adalah proyek nekat karena selain kita cuma dapat waktu satu bulan dari sejak penugasan sampai opening, itu adalah proyek pertama saya di Indonesia setelah for good, dan itu bertempat di Kalimantan. Saya tidak pernah ke Kalimantan sebelumnya. So, nekat tapi seru banget jadinya.

Foto: Ardi Widja

Foto: Bekraf

Foto: At-Lars
Kita memutuskan untuk bikin pier-like structure di atas laut dan struktur itu sebetulnya infrastruktur yang normally ditemukan di daerah dekat pantai. Jadi, geladak yang menghubungkan antara rumah penduduk dengan pantai dan geladak itu terbuat dari kayu yang mempunyai sifat sangat horizontal dan linear. Kita menggunakan infrastruktur itu sebagai elemen utama di Misbar Kayong dan kita mencoba untuk menggabungkan struktur horizontal itu dan kita shifting sehingga terbentuk space-space baru disitu. Cukup berhasil saat itu karena pembangunannya harus cepat dan kita menggunakan struktur geladak yang sudah sering dibuat oleh penduduk setempat. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak berkomunikasi lagi dalam segi konstruksinya, kita tinggal bilang kepanjangan dan ketinggian yang sekian dan tinggal mereka susun. Dan di Kalimantan pula, mereka punya source kayu yang luar biasa, craftsmanship kayu mereka juga gila banget dan proyek itu akhirnya berubah menjadi sebuah proyek bersama.
Proyek itu berlokasi di tengah desa dan para penduduk sekitar pun pada awalnya bingung, “ini ada apa rame-rame buat bioskop?” Akhirnya orang-orang lokal datang dan menyemangati kita. Proyek itu juga bertransformasi tidak cuma menjadi outdoor cinema saja, tapi berubah menjadi sebuah tempat yang digunakan oleh orang lokal untuk docking kapal nelayannya dan jadi tempat main untuk anak-anak. So it transformed into something more beautiful than expected.
Tantangan apa yang Anda hadapi saat mengerjakan proyek ini?
Tantangan yang pertama mungkin saya mengalami culture shock, itu pertama kalinya saya sadar akan perkembangan di luar Jawa yang jauh berbeda. Lalu, karena harus selesai dengan cepat – ini lebih technical, koordinasi dengan kontraktornya tidak begitu smooth seperti seharusnya walaupun itu bisa diperkirakan dengan waktu proyeknya yang hanya satu bulan. Tapi, sebetulnya saya tidak ingat adanya sebuah kesulitan yang signifikan. I think the landscape was too beautiful.
Seperti bidang desain lainnya, arsitektur juga memiliki tren tahunan seperti unfinished interiors hingga kemunculan co-working spaces. Bagaimana Anda melihat hal ini?
Well, I don’t believe in trends, that’s the thing. Saya lebih percaya ke konteks, kontekstual sebuah bangungan terhadap lingkungan sekitarnya dan bagaimana dia mempengaruhi lingkungan sekitar secara mikro maupun makro. Ketika kita melihat dari perspektif itu, tren, style atau apapun itu buat saya pribadi jadi nomor ke sekian. Of course kita akan mengikuti tren dalam arti apa yang sekarang sering dijumpai supaya familiar sama penggunanya. Atau tren dalam arti material mana yang sekarang paling adaptable sama climate. Of course itu akan menjadi sebuah tren karena sering dipakai dan diproduksi. Atau ketika kita ada di lingkungan tertentu, ada material-material yang tidak bisa didapatkan, akhirnya kita pakai material tertentu. So, I think arsitektur dan tren itu tidak selaras, malah agak contradicting sama esensi arsitektur sendiri.
I think arsitektur dan tren itu tidak selaras, malah agak contradicting sama esensi arsitektur sendiri.
Misalnya, kita harus tahu kenapa gaya Minimalist itu ada. Minimalis tidak datang karena tiba-tiba orang bangun pagi ingin menggambar garis dan kotak. Renaissance, Baroque, Avant-garde datang karena ada sebuah movement, sebuah kebutuhan yang sangat esensial. Apalagi zaman dulu – tahun depan Bauhaus 100 tahun, Minimalist salah satunya lahir dari semangatnya Bauhaus – Bauhaus itu bukan style. Bauhaus itu sebuah pergerakan, institusi, yang intinya adalah sekolah. Untuk mengerti Bauhaus, kita harus mengerti kenapa Bauhaus bisa terbentuk. Bauhaus itu terbentuk sejak zaman Industrialisasi, di saat itu mereka bertemu dengan material steel dan langsung menggila.
Saat itu habis Perang Dunia 1, ekonomi sedang tidak baik tapi dalam segi manufacturing terbilang tinggi dan untuk sehari-hari itu barangnya tidak ada yang relatable. Lalu pendirinya Bauhaus, Walter Gropius, melihat bahwa kita harus mengembangkan cara pikir desainer yang berbeda, tidak lagi yang penuh dengan dekorasi, tapi kita harus membuat sesuatu yang lightweight, bisa di mass-produced, modular, supaya bisa dipakai oleh orang banyak. So that’s why mereka harus membuat sesuatu yang istilahnya itu Minimalist atau fungsional. Jadi kita harus melihat ini dari empat dimensi.
Jika berbicara tentang karakter arsitektur Indonesia, apakah Anda dapat menjelaskan tentang lebih lanjut tentang hal itu? Dan bagaimana Anda melihat keadaannya sekarang?
Sebetulnya saya beruntung balik ke Indonesia di saat-saat ini karena lagi banyak banget kantor-kantor muda yang karyanya lagi gila banget sekarang, baik dari memang yang sudah lama di sini sampai yang dari luar Indonesia dan kembali membawa pandangan yang fresh. Sekarang lagi terwadahi banget dengan banyak keikutsertaan Indonesia dalam festival arsitektur internasional, karena sekarang dunia arsitektur lagi terekspos banget.
Agak susah sebenarnya untuk kita mencari karakter arsitektur Indonesia karena pengaruh sejarah kita yang terlalu banyak, namun tidak semua di preserve. Kemudian, jika dihubungkan dengan politik, ada usaha untuk menghapus sejarah itu. Kalau ada penghapusan, berarti ada replacement. Di-replace dengan intensi untuk mendatangkan modal asing. Jadi memang tidak bisa di pinpoint dan mungkin itu adalah the beauty of Indonesian architecture.
Saya rasa hal ini adalah sesuatu yang sering ditanyakan tapi malah menjadi pertanyaan sendiri pada akhirnya.
Top 5 Buildings in Indonesia





Di tengah naiknya kesadaran secara global atas gender imbalance, bagaimana Anda melihat posisi perempuan dalam dunia arsitektur?
Kalau kita membicarakan angka, memang masih sedikit sekali arsitek perempuan di Indonesia dan alasannya itu, saya sempat baca, adalah faktor sosial. Masih banyak banget di Indonesia yang menganggap perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi dan sampai present time masih banget kayak menerapkan hal itu ternyata. Atau sudah sekolah terus pada akhirnya malah berpikir, “santai saja nanti juga nikah terus di rumah”. Masih banyak omongan seperti itu dan para perempuan muda pun masih mempercayai itu.
Kedua, ada juga mitologi – well, saya tidak bisa bilang mitologi karena saya belum menikah dan belum punya anak juga – tapi saya baca ada mitologi bahwa kalau perempuan dan arsitek itu tidak akan bisa. Maksudnya, bagaimana caranya membagi waktu antara kehidupan pribadi dengan waktu untuk anak? Tapi ada beberapa teman-teman arsitek perempuan yang jadi panutan saya, misalnya Daliana Suryawinata, dia bilang bahwa kunci itu adalah time management. Dia punya anak, dan studio arsiteknya pun berjalan dengan sangat baik. Pada akhirnya, terlepas dari perempuan atau laki-laki, kita memang punya kewajiban masing-masing dan kadang saya melihat perempuan di Indonesia tidak bisa maju sebagaimana seharusnya dia bisa maju lebih karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa. That’s the saddest part about it.
Tapi in a positive light, saya pernah diundang menjadi pembicara, specifically karena saya adalah perempuan, untuk meng-encourage mahasiswa perempuan bahwa kita bisa berkarir dalam arsitektur. Saya melihat antusiasmenya sangat tinggi, mereka ingin dan butuh role model supaya percaya bahwa mereka bisa. Tapi kalau wanita dalam industri arsitektur, saya tidak pernah melihat – kadang saya tidak menyadari kalau diri saya itu di antara laki-laki sampai ada orang lain yang memberi tahu. Being a successful female architect, salah satu caranya adalah don’t remind yourself that you are a female. Lucu aja kalau melihat term “female architect”, kenapa kita tidak disebut “architect” aja?

Foto: Ardi Widja

Foto: Ardi Widja

Foto: Ardi Widja

Foto: Ardi Widja

Foto: Ardi Widja
Jika Anda dapat membangun salah satu desain Anda yang belum terealisasikan, apa yang akan Anda bangun?
Impian saya adalah membangun museum untuk hak asasi manusia di Indonesia terutama di Jakarta karena itu adalah ibu kota. Hal ini berakar dari master thesis saya tentang museum memorial Mei 98. Itu adalah sebuah museum yang sesuai namanya ingin mencoba mendokumentasikan sejarah Mei 98 yang masih sangat dekat banget sama kita dan mempengaruhi jiwa banyak orang. Berawal dari master thesis yang sudah jadi dan dinilai, lalu saya berinisiatif untuk membuat proyek itu jadi sebuah inisiatif yang ingin trigger dialog terutama di kalangan orang muda tentang sejarah hak asasi manusia yang mana kita tahu di Indonesia tidak pernah dibicarakan.
Sebenarnya sekarang sudah jauh lebih baik, dulu, anak muda bahkan tidak Lucu aja kalau melihat term “female architect”, kenapa kita tidak disebut “architect” aja?
tahu apa yang terjadi pada tahun itu, mereka cuma ingat dulu sekolah itu libur (tertawa). Dan agak bahaya ketika kita tidak tahu sejarah yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti itu. Sejarah itu pasti terulang dan ketika punya sense akan sesuatu yang benar atau tidak benar, kita akan mencegah hal yang tidak baik tersebut terjadi di society. Itu mulai dari hal-hal kecil seperti komentar-komentar rasis. Ketika kita tahu bahwa ada efek yang lebih besar dari itu, kita akan berpikir dua kali saat melihat kejadian-kejadian seperti itu.
Proyek itu akhirnya membuahkan hasil, yaitu Rekoleksi Memori di Taman Ismail Marzuki. Dari proyek itu, saya banyak bertemu dengan pihak-pihak yang cukup relevan seperti Komnas HAM atau DKJ yang ternyata punya impian yang sama. Kita butuh satu institusi yang mendokumentasikan ini semua, tidak cuma sekadar untuk diingat tapi untuk memberi tahu bahwa ini itu penting. Kita sudah tidak bisa lagi pura-pura tidak mengerti dan tidak tahu – hal itu sudah terlalu ketinggalan jaman. Semua negara sekarang sudah mengerti tentang hal itu. Jadi dari inisiatif saya sekaligus juga melihat energi dari orang-orang sekitar, itu yang membuat saya semakin merasa bahwa I think this is one of my purpose, membuat bangunan yang ada hubungannya dengan HAM di Indonesia.
Saya rasa hal ini juga memiliki hubungan erat dengan saya yang tumbuh dewasa di Berlin. Di Berlin, kota itu penuh dengan sejarah, museum dan penghormatan terhadap korban-korban Nationalsozialistische. Kita tiap hari dikonfrontasi dengan itu dan diajarkan, setiap tahun selalu ada interview survivor holocaust karena memang bukan untuk hiburan, tapi untuk terus mengingatkan kita saja. Kalau saya tidak sekolah di Berlin, saya mungkin tidak akan terjun ke topik-topik itu. Itu benar-benar salah satu milestone di hidup saya yang membuat saya sadar bahwa saya pernah berada di tengah-tengah kejadian pelanggaran HAM dan ternyata bisa dihubungkan dengan arsitektur dan bisa merubah hidup orang banyak. Dengan proyek ini, kita bisa memaksa bagaimana sebuah negara melihat kejadian itu. Karena kalau kita membuat museum, tidak mungkin tiba-tiba ada private owner yang membuatnya, tapi harus ada hubungan sama pemerintah dan institusi lainnya. So it’s a big job and a big dream, tapi why not.
Video: Youtube: Aam Kusuma
Untuk proyek Rekoleksi Memori, bagaimana prosesnya?
Jadi saya punya inisiatif yaitu Museum Mei 98, saya sempat presentasi di Berlin dan di Komnas Perempuan saat saya sedang di Jakarta. Saya lalu menerima email dari dua orang yang kini menjadi kawan saya. Mereka semua itu penggiat film dan punya concern besar di topik HAM, dan sangat tertarik dengan ide Museum Memorial Mei 98 dan mereka punya visi-misi yang sama karena mereka banyak bekerja sama dengan seniman-seniman muda yang memang suka membuat karya-karya nyeleneh. Mereka lalu menghubungi saya dan mengatakan bahwa mereka bisa menggalang dana untuk proyek ini, walaupun secara desain tidak bisa sama persis, melainkan hanya sebuah museum temporer. Lucunya, pada saat itu di Berlin saya sedang berpikir untuk menghabiskan tahun ini dengan santai. Tapi, tentu saya tidak bisa ignore email itu. Itu bulan Agustus dan museum temporer itu berdiri pada awal bulan Desember pada akhir tahun 2015.
Hampir di setiap skena seni pastinya ada sekumpulan sosok yang termasuk dalam kolektif masing-masing, apakah hal ini juga terlihat dalam skena arsitek lokal?
Particularly tentang ini, saya tidak menjawabnya, mungkin karena saya belum lama di sini dan saya masih menjalankan apa yang saya punya. Saya memiliki beberapa kenalan arsitek tapi kita tidak sampai menjadi kolektif gitu sih. Saya kenal beberapa inisiatif yang membuat forum-forum diskusi tapi jatuhnya masih di tahap informal. Sebetulnya ada juga yang menarik, Muhammad Kamil, inisiatif dia itu sangat socially-driven.
Selain bergerak di bidang arsitektur, Anda juga sempat menunjukkan ketertarikan di bidang film dengan membentuk Pidjar. Bisakah Anda menceritakan awal mula terbentuknya Pidjar dan minat Anda terhadap film?
Pidjar bermula dari inisiatif saya dan teman baik saya, Audrey Juanda, di Jerman, kita sama-sama sangat menyukai film. Waktu itu kita membuat film pendek, lucu-lucuan tapi sempat masuk festival kecil-kecilan juga. Pada saat itu, Indonesia sedang banyak berpartisipasi di Berlinale, lalu saya mulai banyak mengobrol dengan beberapa teman terus melihat nuansa Berlinale yang seru banget. Lalu, film dari Indonesia itu mulai kedengeran, tapi kita-kita yang di Jerman itu tidak pernah tahu film-film Indonesia itu seperti apa dan ketika saya melihat film yang ditayangkan di Berlinale, saya cukup kaget, masa kita tidak pernah tahu tentang film ini? Saya jadi mulai banyak research dan ternyata film-film ini pun tidak banyak diketahui. Akhirnya, karena saya sangat excited sama film itu, Pidjar pun dimulai dari keinginan saya untuk menampilkan film tersebut. Kita juga akhirnya bertemu dengan beberapa sutradaranya, seperti Aditya Ahmad yang sekarang baru saja menang di Venice International Film Festival 2018, waktu itu dia baru membuat film “Sepatu Baru”, film pertamanya yang di Berlinale masuk dalam kategori Short Film, kita banyak mengobrol sama dia. Bermula dari small events di mana kita buat screening kecil di bar-bar di Berlin, sampai akhirnya bisa membuat screening di bioskop independen di Berlin dan masuk dalam program area setempat. So it went on very organically aja. Tapi, sejak saya sudah pindah ke Indonesia, sayangnya sudah tidak bisa terlalu aktif di sana.
Apa proyek yang sedang Anda kerjakan untuk kedepannya?
Ada beberapa. Saya belum bisa memberi tahu terlalu banyak, tapi ada yang hubungannya sama Jerman, masih berhubungan dengan public space dan installations.











