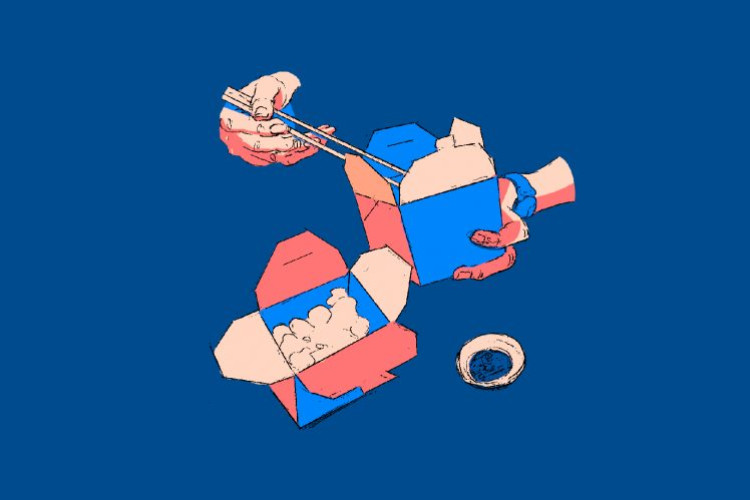Melihat Posisi dan Perkembangan Museum Hari Ini
Beberapa kurator dan seniman Indonesia berbagi pandangan tentang dinamika definisi dan peran museum saat ini.
Words by Whiteboard Journal
Teks: Wintang Warastri
Desain: Tiana Olivia
Jika dulu pengunjung datang ke museum untuk berfokus pada karya/artefak, saat ini kebanyakan datang juga untuk eksistensi di media sosial dengan mengunggah foto kunjungan. Perubahan tersebut mau tidak mau berpengaruh terhadap definisi dan peran museum dewasa ini. Mulai dari elemen interaktif hingga integrasi teknologi, bermacam konten dan metode hadir sehingga mengubah cara menikmati museum saat ini. Di sisi lain, mau tidak mau para kurator dan seniman sebagai aktor di balik layar pun ikut terekspos pada perubahan ini. Adakah dinamika tersebut mempengaruhi mereka? Kami mengajak bicara beberapa penggiat seni tersebut untuk mengulik sudut pandang mereka tentang museum hari ini.

Foto: Febrina Anindita
Rebellionik
Seniman, Founder ONX Idea Studio
Museum identik dengan peran edukatifnya untuk menyimpan/memamerkan benda berharga dari suatu masa kehidupan manusia. Adakah pergeseran fungsi museum saat ini?
Pergeseran fungsi menurut saya tidak, hanya cara penyajian dari kontennya yang mengalami pengembangan.
Museum juga dipandang sebagai tempat hiburan yang terjangkau. Menurut Anda mengapa popularitasnya masih lebih sedikit dibandingkan destinasi lainnya seperti mall/bioskop?
Jika dibandingkan dengan mall pasti akan sangat berbeda, secara konten dan fungsinya pun sudah berbeda. Ketika di mall sangat banyak hal yang ditawarkan dari mulai belanja, hiburan, sampai kuliner, sehingga banyak pilihan dalam satu tempat. Tetapi beberapa museum yang saya kunjungi sudah menarik, dengan variasi aktivitas di dalamnya dan program-program yang menarik.
Berbicara tentang museum tidak bisa dilepaskan dari pengunjung dan interaksinya lewat media sosial baik secara langsung atau tidak. Apakah ini menggeser persepsi kurator/seniman saat menyiapkan sebuah pameran di museum hari ini?
Tergantung tipe museumnya. Tetapi interaksi pengunjung lewat media sosial menjadi pertimbangan saat saya (dari kacamata seniman) berpameran, misalkan jenis dan durabilitas karya agar sesuai dengan karakter pameran dan fungsinya. Kalau pergeseran kurator saya kurang tahu, karena belum pernah jadi kurator.
Jika dulu berkunjung ke museum adalah untuk menikmati karya, saat ini fokus kunjungan kerap kali berubah menjadi tentang eksistensi si pengunjung sendiri lewat datang ke karya/pameran yang viral. Apa tanggapan Anda akan hal ini?
Apapun alasannya menurut saya tidak ada masalah, selama museum jadi ramai dikunjungi sehingga bisa menjadi salah satu trigger “kebiasaan berkunjung” ke museum.
Di samping media sosial, integrasi teknologi di dalam museum juga semakin menjamur (virtual reality tour/works, dll). Menurut Anda apakah ini mengubah cara pandang seseorang saat berkunjung ke museum/pameran dan menikmati sebuah karya?
Integrasi teknologi akan sedikit banyak mempengaruhi motivasi dan experience.

Foto: Febrina Anindita
Ardi Gunawan
Seniman, Pengajar
Museum identik dengan peran edukatifnya untuk menyimpan/memamerkan benda berharga dari suatu masa kehidupan manusia. Adakah pergeseran fungsi museum saat ini?
Tergantung museum macam apa ya, museum kan banyak macam-macamnya. Ada museum penerbangan, marinir, seni, sejarah alam, geologi, sampai museum bank BCA juga ada. Ada yang private ada yang publik, semua juga bisa dimuseumkan. Kalau menurut saya, fungsi museum itu tetap sama yaitu untuk memamerkan benda-benda langka atau ajaib, asli dan unik (no copies). Pergeseran yang terjadi di kehidupan manusia sejak datangnya tahap informasi belakangan ini adalah cara distribusi dan konsumsi ketimbang produksi benda-benda ajaib tersebut, berhubung koneksi internet kita semakin 4G/5G. Biaya logistik pun juga akan lebih murah dan terasa enteng. Benda-benda dari kebudayaan yang punah pun belakangan ini bisa di-revival dengan tampilan definisi tinggi di layar-layar smartphone kita. Kita tidak perlu kesana kemari untuk melihat bentuk fisik aslinya, yang penting mengerti secara visual, textual, atau linguistik. Analisa dan pemikiran seperti ini mengingatkan kita kembali kepada apa yang pernah di singkat oleh Marshall Mcluhan di tahun 1964 “the medium is the message.” Menurut saya, pernyataan yang padat singkat dan mempunyai seribu makna ini makin menggila relevansinya.
Museum juga dipandang sebagai tempat hiburan yang terjangkau. Menurut Anda mengapa popularitasnya masih lebih sedikit dibandingkan destinasi lainnya seperti mall/bioskop?
Menurut saya, itu karena mungkin museum dipandang orang sebagai place apart dari realita kebudayaan populer. Orang masih merasa terintimidasi dan menganggap ‘wah ini mah untuk orang-orang yang intelektual, tajir, atau cultured dan educated saja,’ yang bisa mengerti benda-benda seni bin ajaib/langka ini. Ditambah tanda don’t touch, kesannya memagarkan bentuk-bentuk partisipasi rakyat terhadap karya seni atau benda-benda langka yang dikoleksi museum.
Tapi menurut saya kalau di Jakarta, konsep seperti ini justru kebalikannya. Perbatasan antara art dan entertainment di tempat-tempat hyper-consumerism seperti di mall sudah menyatu dan menyaru. Contohnya Art Stage di Gandaria City Mall. Ada lagi, antrian yang panjang untuk menonton instalasi kacanya Yayoi Kusama di Museum Macan. Ingat, Museum Macan adalah salah satu proyek besarnya AKR Land Development – perusahaan properti swasta, yang juga aktif dalam mengembangkan pusat perbelanjaan atau mall dan bisnis rumah tinggal untuk kelas menengah atas di Jakarta, Bali, Gresik, dan sampai di Manado. Jadi museum sebagai tempat place apart tadi, di Jakarta sama sekali di-pop-culture-kan. Museum dan art spectacle seperti sudah jadi bagian penting dari realitas pop dan pembangunan.
Berbicara tentang museum tidak bisa dilepaskan dari pengunjung dan interaksinya lewat media sosial baik secara langsung atau tidak. Apakah ini menggeser persepsi kurator/seniman saat menyiapkan sebuah pameran di museum hari ini?
Menurut saya, interaksi pengunjung terhadap karya yang dipajang di museum dan yang dibagi di sosial media sudah jadi bentuk partisipasi baru. Dan ini liberasi pengunjung terhadap bentuk-bentuk benda bersejarah yang sifatnya permanen dan kekal. Going to a fancy museum, say, Louvre Museum, ini merupakan suatu kebanggaan kelas, dan why not share it in social media platform? Misalnya kelas menengahnya Jakarta, akhirnya bisa melihat The Monalisa Smile – kalau saya sih bangga sekali bisa akhirnya ada uang untuk pergi kesana dan melihat karya bersejarah tersebut, terus saya unggah itu dengan tujuan just to make you, you, and you envy or jealous (sarcastically). Apalagi kalau follower-ku (ngarep) mencapai 120K. Bagi seniman dan kurator, ya bisa, kedepannya menggeser cara mereka membuat/mengolah karyanya – bahkan saya pun sekarang terpengaruh karyanya oleh Instagram GIF feature. Kalau saya secara personal, why not use this time as an opportunity. Saya ingat dosenku sempat bilang bahwa dia depresi pas Andy Warhol taking over the avant-garde – karena si dosen ini kena efeknya. Trus dia bilang, “Saya tidak bisa melawan – mau tidak mau saya harus ikut market yang dibuat oleh pop artists.” Akhirnya dia bikin karya-karya yang pop-minimalist gitu, dan hasilnya menurut saya jadi aneh, kritis, jadul, digital, dan so fucking layered.
Kalau memakai logika ini di zaman ini, the kitsch viewer has re-emerged and they are the new artists/critics/curators. Jadi ke depannya, sudah tak terelakkan lagi bagi para seniman/kurator klasik untuk memikirkan sosial media sebagai platform baru untuk art criticism dan art-making. Kalau memang misalnya karya-karya yang cari “untung” dari “likes” economy-nya Instagram atau social media platform lainnya, kenapa tidak teruskan? Kan, tidak semua seniman/kurator bisa masuk museum, atau karyanya direview with words glossed over by fancy contextual intellectualism and densely deep philosophical debate-nya si, say, Boris Groys di publikasi-publikasi ternama seperti Artforum, October Journal, atau e-flux. Tinggal pilih mau yang mana, menunggu lama atau yang serba instan?
Jika dulu berkunjung ke museum adalah untuk menikmati karya, saat ini fokus kunjungan kerap kali berubah menjadi tentang eksistensi si pengunjung sendiri lewat datang ke karya/pameran yang viral. Apa tanggapan Anda akan hal ini?
Kalau memakai kerangka seperti pertanyaan diatas, berarti apakah karya seni completes the existential crisis of the viewer? Or does the viewer completes the lonesome existence of an artwork in a gallery? Kalau memang pamerannya sudah viral ya berarti siapapun di balik pembuat pameran itu sudah antisipasi pamerannya bakal terinfeksi. Apakah mereka berpikir tentang vaksinnya? Pertanyaannya kan, bisa tidak buat pamerannya viral? Siapa yang harus datang? Dan kalau memang pamerannya sudah viral dan makin banyak lagi yang datang yang untung pihak manakah? Dan kepada siapakah kita harus berterima kasih? Tuhan Yang Maha Ether.
Di samping media sosial, integrasi teknologi di dalam museum juga semakin menjamur (virtual reality tour/works, dll). Menurut Anda apakah ini mengubah cara pandang seseorang saat berkunjung ke museum/pameran dan menikmati sebuah karya?
Pertanyaannya mungkin bisa kita teruskan lagi; kenapa museum juga ikut-ikutan menggunakan cyberspace teknologi yang ajaib nan baru ini? Kenapa mereka mengadaptasi perangkat-perangkat yang digunakan di industri games atau animasi – and to an extent, porn untuk melihat benda-benda bersejarah, atau karya seni in general? Apakah artinya ini? Apakah museum paranoid? Museum kan fungsinya sebenarnya juga mempertahankan ‘keaslian’ suatu benda. Keaslian dan kualitas fisik suatu kebendaan ini selalu dipertahankan, sedangkan cybertech seperti VR dan sejenisnya lebih bermaksud untuk menggandakan keaslian tersebut agar bisa di-distribusi dan dikonsumsi secara global. Lalu kenapa museum membuka dirinya ke arah VR dan cyberspace yang bisa menggandakan the copy from the real? Apakah mereka merasa terancam relevansinya dengan film-film seperti Toy Story? Claire Bishop pernah bertanya, “in a hundred years’ time, will visual art have suffered the same fate as theater in the age of cinema?”
Saya bukan expert seperti Lev Manovich atau Bishop di sini, tapi menurut VR jelas akan memperluas nafsu kita dalam melihat. Penawarannya VR adalah kita bisa membuat dan melihat benda-benda bersejarah, misalnya, dari zaman batu, melalui kacamata spekulatif – dan yang paling parah yang asli itu belum tentu ada – tapi saking supremely fiktif tampilan visualnya kita bisa buat orang lain percaya. Di kasus lain kita bisa time travel to the deepest past, tapi tidak pernah bisa menghadirkan secara fisik the real cultural meaning from a specific time. Maksud saya, kita hanya bisa buat makna dari medium-medium buatan abad ke-21 saja. Tapi apakah baru konten artefaknya? Ya sepertinya tidak sih. My point is VR dan teknologi simulasi yang digunakan museum hanya tampilan luarnya saja yang diperbaharui supaya kelihatan perfect dari yang sekarang, dalam artian museum jadi tidak akan pernah mati. Dan apa yang kuno atau obsolete statusnya bisa dirasuki oleh forever zombie time – tidak mati-tidak hidup. Dengan VR kita memasuki museum melalui waktunya si pengidap insomnia (bisa juga drakula). Tidak pernah bisa tidur dan bangun pun bisa kapan aja. Inilah museum baru yang lagi ditunggu-tunggu semua orang.

Foto: Instagram/Mulyana
Mulyana
Seniman
Museum identik dengan peran edukatifnya untuk menyimpan/memamerkan benda berharga dari suatu masa kehidupan manusia. Adakah pergeseran fungsi museum saat ini?
Fungsi museum dari dulu sebenarnya sama. Cuma ada beberapa pihak yang mungkin menggunakan ‘museum’ untuk usahanya agar terkesan edukatif.
Museum juga dipandang sebagai tempat hiburan yang terjangkau. Menurut Anda mengapa popularitasnya masih lebih sedikit dibandingkan destinasi lainnya seperti mall/bioskop?
Untuk museum yang dibuat negara atau pemerintah daerah memang murah, cuma sayangnya dalam segi kegiatan atau penambahan koleksi mungkin sekarang masih jarang. Atau tidak selalu di-update, makanya popularitasnya kurang. Tapi ada beberapa ‘museum’ swasta yang mematok harga cukup mahal tapi bisa memenuhi keinginan konsumen atau membuat acara menarik banyak dikunjungi. Strategi promosi memang berperan penting disini.
Berbicara tentang museum tidak bisa dilepaskan dari pengunjung dan interaksinya lewat media sosial baik secara langsung atau tidak. Apakah ini menggeser persepsi kurator/seniman saat menyiapkan sebuah pameran di museum hari ini?
Nah, yang menarik di sini pada akhirnya kita tanya siapa sih pemilik museum dan orang yang kerja di dalamnya. Bisa ditebak sih. Pasti menyesuaikan dengan keinginan orang-orang dalam museum itu sendiri.
Jika dulu berkunjung ke museum adalah untuk menikmati karya, saat ini fokus kunjungan kerap kali berubah menjadi tentang eksistensi si pengunjung sendiri lewat datang ke karya/pameran yang viral. Apa tanggapan Anda akan hal ini?
Mungkin ini adalah masanya begitu. Kita tidak bisa menghakimi secara general. Dari dulu seni memang punya habitatnya sendiri. Kita lihat kedepannya. Semoga masyarakat bisa menghargai dan membaca seni dari berbagai lini, mendapat manfaat dan terus berkembang.
Di samping media sosial, integrasi teknologi di dalam museum juga semakin menjamur (virtual reality tour/works, dll). Menurut Anda apakah ini mengubah cara pandang seseorang saat berkunjung ke museum/pameran dan menikmati sebuah karya?
Saya yakin, sehebat-hebatnya teknologi, VR dan lain-lain, untuk melihat instalasi seni yang saya kerjakan harus datang langsung ke tempat pameran. Rasanya pasti berbeda. Begitupun kenikmatannya.

Foto: Style Decor Magazine
Agatha Carolina Dirdjohadi
Founder Bitte Design Studio
Museum identik dengan peran edukatifnya untuk menyimpan/memamerkan benda berharga dari suatu masa kehidupan manusia. Adakah pergeseran fungsi museum saat ini?
Menurut pendapat saya, secara fungsi museum masih mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan dan memamerkan suatu karya. Namun yang mengalami pergeseran mungkin adalah ‘behavior’ para pengunjungnya dalam menikmati ataupun mengapresiasi karya yang ada di museum.
Museum juga dipandang sebagai tempat hiburan yang terjangkau. Menurut Anda mengapa popularitasnya masih lebih sedikit dibandingkan destinasi lainnya seperti mall/bioskop?
Menurut pendapat saya, popularitas museum lebih sedikit dibandingkan dengan destinasi lain seperti mall dan bioskop karena satu dan banyak hal. Contohnya mungkin di ibukota Jakarta, jumlah ketersediaan museum yang ada di Jakarta berbanding jauh dengan ketersediaan mall ataupun bioskop. Dengan kata lain, semua orang dari berbagai area di Jakarta dapat dengan mudah mengakses mall dan bioskop karena hampir di setiap area di Jakarta terdapat banyak sekali mall dan bioskop. Sedangkan jumlah museum di Jakarta bisa dikatakan relatif sedikit. Melihat fakta lain misalnya di kota London, jumlah museum dan art gallery yang ada di kota London dapat dikatakan sangat banyak dan lebih banyak dibandingkan dengan shopping mall yang ada di kota London. Oleh karena itu apresiasi orang terhadap ‘art’ disana jauh melebihi apresiasi akan karya seni di Jakarta.
Alasan lain selain jumlah yang sedikit, mungkin museum juga dapat dikatakan lebih ‘segmented’, karena banyak orang yang masih beranggapan bahwa karya seni itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang, hanya untuk kalangan tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan apresiasi terhadap karya seni.
Berbicara tentang museum tidak bisa dilepaskan dari pengunjung dan interaksinya lewat media sosial baik secara langsung atau tidak. Apakah ini menggeser persepsi kurator/seniman saat menyiapkan sebuah pameran di museum hari ini?
Hal ini menurut saya sangat dipengaruhi dengan perkembangan zaman dan teknologi, dimana saat ini salah satu cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi diwadahi dengan platform media sosial. Hal ini menurut saya pasti menyebabkan suatu pergeseran akibat perubahan zaman itu sendiri. Dan pasti hal ini pun berpengaruh di bidang seni. Baik dalam bagaimana suatu karya dapat dinikmati maupun dalam pemikiran di balik karya dan cara menyajikannya, baik dari sisi kurator maupun seniman.
Jika dulu berkunjung ke museum adalah untuk menikmati karya, saat ini fokus kunjungan kerap kali berubah menjadi tentang eksistensi si pengunjung sendiri lewat datang ke karya/pameran yang viral. Apa tanggapan Anda akan hal ini?
Sebenarnya setiap orang pasti punya objektif masing-masing untuk datang ke suatu pameran seni. Dan cara mereka menikmati karya itu pun akan sangat bergantung pada objektif mereka itu sendiri. Menurut saya pribadi, tidak ada salahnya semua orang yang datang untuk mengeksistensikan dirinya lewat caranya masing-masing. Karena bagaimanapun manusia bebas berekspresi.
Yang mengganggu adalah jika cara berekspresi itu tidak sewajarnya dan mengganggu pengunjung lainnya yang memiliki objektif berbeda. Misalnya bila ada pengunjung yang datang hanya untuk berfoto tanpa mau peduli atau mengerti soal karya seni tersebut, itu hak mereka. Namun yang menjadi persoalan adalah jika cara mereka berekspresi itu mengganggu suasana dan pengunjung lainnya. Jadi intinya menurut saya, apapun itu objektif di balik datangnya seseorang ke suatu pameran seni, yang pasti harus tetap ‘thoughtful’ dan saling menghargai kepentingan orang yang datang ke sana.
Di samping media sosial, integrasi teknologi di dalam museum juga semakin menjamur (virtual reality tour/works, dll). Menurut Anda apakah ini mengubah cara pandang seseorang saat berkunjung ke museum/pameran dan menikmati sebuah karya?
Teknologi pasti membuat perubahan seiring perkembangan zaman, dan hal itu bisa memperkaya kita dalam menikmati karya seni. Tapi balik ke karya seni dan seniman itu sendiri, menurut saya seorang seniman harus mempunyai karakteristik yang kuat, sehingga dalam menyampaikan karyanya mereka dapat tetap mempertahankan karakter tersebut baik dengan mengintegrasikan teknologi ataupun tanpa mengintegrasikan teknologi.
Contohnya ada seniman yang karakternya ada di attention to detail dan delicate-nya karya tersebut, seperti Alexander Calder. Atau ada juga karya yang mungkin bisa dapat lebih dinikmati dengan teknologi, seperti TeamLab. Jadi cara menikmatinya itu sangat bergantung ke karya seni itu sendiri.

Foto: Instagram/Sally Texania
Sally Texania
Kurator
Museum identik dengan peran edukatifnya untuk menyimpan/memamerkan benda berharga dari suatu masa kehidupan manusia. Adakah pergeseran fungsi museum saat ini?
Ada, ketimbang pergeseran saya lebih suka menyebutnya sebagai perluasan.
Museum juga dipandang sebagai tempat hiburan yang terjangkau. Menurut Anda mengapa popularitasnya masih lebih sedikit dibandingkan destinasi lainnya seperti mall/bioskop?
Dalam konteks Indonesia, khususnya museum yang dikelola pemerintah, kelengkapan fasilitas dan kenyamanan ruang pamer belum menjadi prioritas sehingga masyarakat masih memilih mall dan bioskop.
Berbicara tentang museum tidak bisa dilepaskan dari pengunjung dan interaksinya lewat media sosial baik secara langsung atau tidak. Apakah ini menggeser persepsi kurator/seniman saat menyiapkan sebuah pameran di museum hari ini?
Karena fungsi pameran adalah menjembatani pengkaryaan seniman dengan publik, media sosial bisa kita lihat sebagai pendukung ‘misi’ ini dan menguntungkan seniman maupun kurator dalam membuka kesempatan dan menemukan publik yang baru. Tapi media sosial idealnya tidak menjadi orientasi utama karena persepsi seniman mengenai karyanya dapat menjadi kabur kalau hanya mencari legitimasi dari wilayah tersebut.
Jika dulu berkunjung ke museum adalah untuk menikmati karya, saat ini fokus kunjungan kerap kali berubah menjadi tentang eksistensi si pengunjung sendiri lewat datang ke karya/pameran yang viral. Apa tanggapan Anda akan hal ini?
Agak dilematis menjawab pertanyaan ini, karena bagi saya seni itu fungsi utamanya memang untuk ekspresi dan eksistensi baik dari pelaku ataupun apresiatornya. Selain itu, apresiasi pameran di museum Indonesia (bagi kalangan umum yang sehari-harinya bukan pecinta seni) usianya masih sangat muda. Mungkin apresiasi seni (di Indonesia) bermula dari selfie ketimbang penghayatan seni adiluhung. Kita tidak hanya perlu memberi waktu kepada ‘empu-empu’ seni rupa, tetapi juga apresiatornya.
Di samping media sosial, integrasi teknologi di dalam museum juga semakin menjamur (virtual reality tour/works, dll). Menurut Anda apakah ini mengubah cara pandang seseorang saat berkunjung ke museum/pameran dan menikmati sebuah karya?
Akhir-akhir ini seperti ada kepercayaan bahwa museum yang sesuai semangat zaman adalah museum yang punya virtual reality, dll. Tapi kita suka lupa juga bahwa integrasi teknologi itu adalah perangkat saja. Tanpa substansi yang menarik dan aktual pengadaan perangkat ini bisa menjadi useless juga. Menurut saya, idealnya integrasi media bisa membawa insight-insight baru atau membawa pesan dengan cara lebih menarik daripada catatan kuratorial yang kadang bisa sangat panjang, terlalu akademis atau membosankan.
Meski saat ini integrasi teknologi yang kita temukan lebih banyak bergerak di wilayah gimmick, ke depannya pengembangan integrasi ini perlu mempertemukan fungsi ‘hiburan’ dan ‘pendidikan’.

Foto: Instagram/Mira Asriningtyas
Mira Asriningtyas
Kurator Independen, Penulis Seni
Museum identik dengan peran edukatifnya untuk menyimpan/memamerkan benda berharga dari suatu masa kehidupan manusia. Adakah pergeseran fungsi museum saat ini?
Saat ini, institusi seni di dunia (termasuk museum) sudah mulai melihat ulang cara beroperasinya sesuai kebutuhan yang makin kompleks. Museum terus melakukan evolusi mulai dari karakteristik jenis koleksi yang disesuaikan dengan konteks zaman, sosial, politik, sejarah, dan agenda museum – serta jenis interaksi yang dibangun dengan publik maupun skena seni lokal dan internasional. Tidak berhenti pada peran tradisional untuk mengoleksi, menyimpan, melakukan riset, dan menyajikannya ke publik semata; saat ini museum juga mengambil peran sosial dan membangun dialog secara aktif serta mendukung ekosistem seni lokal. Ketika bentuk museum terus mengalami evolusi, tentu saja fungsinya juga berkembang sesuai konteksnya.
Museum juga dipandang sebagai tempat hiburan yang terjangkau. Menurut Anda mengapa popularitasnya masih lebih sedikit dibandingkan destinasi lainnya seperti mall/bioskop?
Mungkin perlu dipertegas bahwa konteks pertanyaan ini merujuk pada museum di Indonesia. Karena dalam konteks Belanda, misalnya, harga tiket masuk museum Van Gogh (EUR 21) yang antriannya mengular itu lebih mahal daripada harga tiket menonton di bioskop (EUR 9) sehingga konteks pertanyaan yang menganggap museum merupakan tempat hiburan terjangkau ataupun kurang populer dibandingkan mall dan bioskop saya rasa kurang tepat. Namun jika merujuk pada konteks museum di Indonesia, selain bahwa sejak awal museum merupakan tempat ‘hiburan’ yang cukup niche, budaya berkunjung ke museum bagaimanapun belum akrab tertanam di budaya masyarakat kita.
Kedua, membandingkan museum yang merupakan institusi budaya dengan mall atau bioskop yang merupakan industri kapitalistik, perbandingan yang diajukan tidak apple-to-apple. Mall dan bioskop bagaimanapun juga dibangun untuk menarik kunjungan banyak orang dengan strategi promosi yang gencar. Jika sebuah toko atau film kurang diminati, pasti akan langsung diganti. Logika ini tidak bisa diterapkan pada kasus museum. Lagipula, apa menariknya sebuah museum yang melakukan pemrograman hanya dengan tujuan banyak-banyakan pengunjung, bukan?
Berbicara tentang museum tidak bisa dilepaskan dari pengunjung dan interaksinya lewat media sosial baik secara langsung atau tidak. Apakah ini menggeser persepsi kurator/seniman saat menyiapkan sebuah pameran di museum hari ini?
Seharusnya tidak. Interaksi pengunjung museum melalui sosial media memang bisa dimanfaatkan untuk persebaran informasi, namun tidak seharusnya mempengaruhi persepsi seniman ataupun keputusan kuratorial. Pengunjung bukan merupakan satu-satunya pihak yang perlu diperhitungkan saat membuat sebuah pameran – ada faktor penentu dan stakeholder lain yang juga penting untuk diperhitungkan.
Jika dulu berkunjung ke museum adalah untuk menikmati karya, saat ini fokus kunjungan kerap kali berubah menjadi tentang eksistensi si pengunjung sendiri lewat datang ke karya/pameran yang viral. Apa tanggapan Anda akan hal ini?
Usaha meningkatkan eksistensi pengunjung ini tidak hanya terjadi dalam hal karya seni atau museum. Begitu juga alasan banyak orang mengunjungi tempat wisata, rumah makan baru, atau bahkan situs doa. Saya rasa ini adalah karakteristik dan dampak atas kebiasaan melakukan dokumentasi pribadi (foto maupun video) serta kemudahan akses untuk membagikannya melalui media sosial. Alasan apapun yang dapat membuat pengunjung berani mencoba datang ke museum saya rasa adalah awal mula yang baik untuk mulai mengakrabkan seni dalam budaya masyarakat kita. Dimulai dari alasan eksistensi, perlahan-lahan semoga saja pengunjung akan meningkatkan level keterlibatannya dan dari situ pendidikan atas seni bisa masuk.
Di samping media sosial, integrasi teknologi di dalam museum juga semakin menjamur (virtual reality tour/works, dll). Menurut Anda apakah ini mengubah cara pandang seseorang saat berkunjung ke museum/pameran dan menikmati sebuah karya?
Jika ditangani dengan cerdas, integrasi teknologi bisa meningkatkan pengalaman dan mempermudah transfer pengetahuan dengan efektif dan menarik. Namun jika tidak, bisa dengan mudah berubah menjadi gimmick yang justru mereduksi nilai, pengalaman, dan interaksi audiens dengan karya seninya itu sendiri.