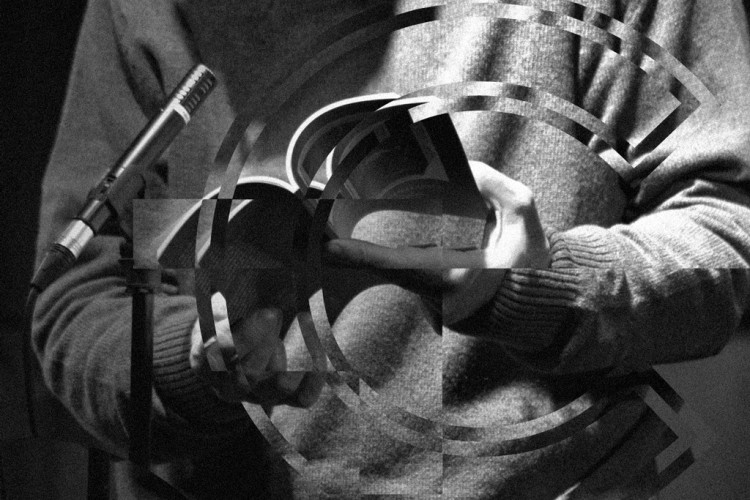Merayakan Perbedaan di Tengah Keseragaman
Anastasya Lavenia merenungkan esensi dari semangat persatuan yang justru membuat kita terjebak dalam batas-batas yang kita buat sendiri.
Words by Whiteboard Journal
Keragaman kelompok menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, termasuk pergesekan-pergesekan yang ditimbulkannya. Sejak masa kolonial, sejarah bangsa ini banyak diwarnai oleh konflik ras, suku, dan agama. Hari ini, multikulturalisme dan toleransi merupakan tajuk utama yang sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Internalisasi semangat persatuan yang sedang ditanamkan melalui kampanye-kampanye pemerintah sepertinya berhasil, melihat antusiasme masyarakat yang ternyata masih peduli dengan kesatuan negeri ini. Namun, saya sendiri belum merasakan implementasinya dalam pengalaman sehari-hari. Melalui interaksi dengan berbagai orang yang saya jumpai, saya mendapati masyarakat yang terus-menerus menekankan perbedaan ketimbang persamaan.
Sebagai anak yang dilahirkan dan dibesarkan di dalam keluarga ‘campuran’ (Ayah berketurunan Tionghoa-Indonesia dan Ibu berketurunan Jawa), saya merasakan bagaimana rumitnya hidup di dalam dua budaya yang berbeda. Perbedaan ini membuat saya terkadang merasa memiliki dua identitas, dan keduanya muncul bergantian tergantung situasi dan kondisi. Ketika menikah dengan Ayah, Ibu saya yang tumbuh dalam ajaran agama Islam memutuskan untuk pindah ke agama Katolik. Keluarga kami tinggal di pemukiman yang bisa dibilang cukup homogen, mayoritas warganya adalah keluarga keturunan Tionghoa-Indonesia beragama Kristen atau Katolik dari kelas menengah atas. Setiap Imlek tiba, segenap keluarga besar Ayah akan berkumpul untuk bersembahyang, menyantap hidangan khas seperti misua dan sayur telur, lalu tidak lupa saling berbagi angpao. Di tengah kentalnya budaya dari sisi Ayah, Ibu tetap menghormati warisan budaya yang dimilikinya. Setidaknya setahun sekali ketika Idul Fitri, saya menemani Ibu untuk mudik ke Tegal dan berkumpul bersama anggota keluarga besar yang lain. Walaupun pada akhirnya saya menikmati kedua sisi, budaya dari pihak keluarga Ayah cenderung lebih dominan dalam keluarga kecil kami.
Sejak kecil, saya didaftarkan ke sekolah swasta katolik yang populasinya didominasi oleh keturunan Tionghoa-Indonesia. Kesadaran bahwa saya ‘berbeda’ dari teman-teman saya yang lain baru benar-benar ada ketika memasuki SMA. Perbedaan etnis yang terlihat dari segi fisik pernah mendatangkan ejekan berbau SARA dari teman sekelas hingga tatapan aneh dari orangtua yang mendapati anaknya bermain dengan seorang anak perempuan berkulit cokelat dan bermata besar. Pengalaman tersebut tidak begitu menyenangkan, tapi saya tidak merasa harus marah karena toh bersekolah di situ memberikan banyak pengalaman berharga dan sahabat-sahabat yang luar biasa. Tapi tidak dapat dipungkiri pengalaman-pengalaman tersebut tetap ada, dan saya bukan satu-satunya yang merasa demikian. Hal yang serupa juga pasti terjadi apabila kondisinya dibalik. Apapun itu, perbedaan selalu mendatangkan respon tertentu, seringkali berupa ketidaknyamanan.
Ketika saya memutuskan untuk berkuliah di Yogyakarta, yang terjadi adalah sebaliknya. Teman-teman mahasiswa yang mayoritas datang dari etnis Jawa terkejut ketika mengetahui bahwa saya memiliki banyak teman berkulit putih dan bermata sipit. Mereka pun sama terkejutnya ketika mengetahui bahwa saya merupakan keturunan Tionghoa-Indonesia. Selebihnya, saya merasa lebih nyaman di lingkungan ini ketimbang di kampung halaman. Harus saya akui, kesamaan identitas merupakan salah satu faktor yang menciptakan kenyamanan tersebut. Tidak menjadi satu-satunya bunga matahari di antara kumpulan bunga mawar memberikan perasaan baru yang lebih nyaman, serta meningkatkan kepercayaan diri yang selama ini tersamarkan.
Setelah beberapa waktu, melalui proses perkuliahan, pengalaman ini justru memantik saya untuk berpikir lebih jauh. Berdasarkan apa yang saya alami, implementasi semangat persatuan justru patut dipertanyakan. Bukankah semangat persatuan yang selama ini terus-menerus dibicarakan bertujuan untuk membuat kita merasa satu, terlepas dari perbedaan yang ada? Lantas kalau begitu, mengapa ketika seseorang berwajah Indonesia memiliki banyak teman berwajah Tionghoa dipandang sebagai sebuah hal yang tidak biasa? Mengapa yang masih dipandang lazim adalah seseorang berteman dan berkelompok dengan orang-orang yang memiliki identitas yang sama dengan dirinya? Terakhir, mengapa saya justru merasa lebih nyaman ketika tidak menjadi berbeda?
Berbagai pertanyaan ini melahirkan sebuah dugaan sederhana, bahwa terlepas dari hidupnya semangat persatuan, kita masih memandang perbedaan sebagai sebuah hal yang tidak biasa, bahkan sebagai kelemahan. Mungkin visi bahwa semua inidvidu ataupun kelompok bisa melebur dan hidup berdampingan adalah cita-cita yang terlalu utopis. Sebab pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di zona nyaman kelompoknya masing-masing, sehingga identitas kelompok seringkali lebih ditonjolkan dibanding identitas individu. Pun pengertian mengenai identitas dalam bahasa sehari-hari masyarakat masih sangat kaku – seputar suku, ras, agama, dan golongan. Pada akhirnya ketika ada seorang individu yang memiliki identitas berlapis, ia seperti dihadapkan untuk memilih satu dan menanggalkan yang lain.
Dengan mempertimbangkan budaya komunal yang kental, memang wajar apabila setiap individu masih sangat melekat dan bergantung dengan kelompok masing-masing. Namun kemudian, persatuan seperti apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh negeri ini dan masyarakatnya? Sebab untuk bangsa yang merasa dirinya beragam, cara hidup masyarakatnya justru lebih banyak menggambarkan yang sebaliknya. Kalau sebatas mentoleransi kelompok lain tapi tidak menginginkan adanya pertukaran budaya, selamanya kita akan terjebak dalam batas-batas yang kita buat sendiri. Mengkotak-kotakkan manusia melalui identitas kelompoknya. Bagaimanapun juga kita tidak boleh melupakan sejarah dari mana kita berasal, toh identitas kelompok juga telah membentuk berbagai macam fase dalam penciptaan identitas seorang individu. Namun, bayangan atau impian untuk hidup di suatu masyarakat yang berhasil melampaui batas-batas tersebut dan identitas kelompok tidak lagi menjadi hal yang paling utama dalam memandang seseorang, adalah mimpi yang sangat menggiurkan. Saya ingin sekali tinggal di dalamnya.
Ketika timbul kesadaran bahwa identitas saya tidak bisa dikategorikan ke dalam satu kelompok saja, saya ingin merasa bahwa itu bukanlah sebuah kekurangan atau ketidakwajaran. Sebab sesungguhnya tumbuh besar di keluarga yang multikultur adalah pengalaman berharga yang telah berkontribusi terhadap perkembangan diri, pendewasaan, serta pembentukan pola pikir. Cukup lama dan tidak mudah bagi saya untuk bisa menyadari hal itu dan menerima diri ini seutuhnya, lagipula pengertian mengenai identitas yang cair memungkinkan saya untuk terus mengalami perubahan seiring waktu. Entahlah, saya hanya tidak ingin terbatasi oleh label “Cina” maupun “Jawa”. Saya ingin menjadi keduanya tanpa mengurangi kesempatan untuk menjadi yang lain.