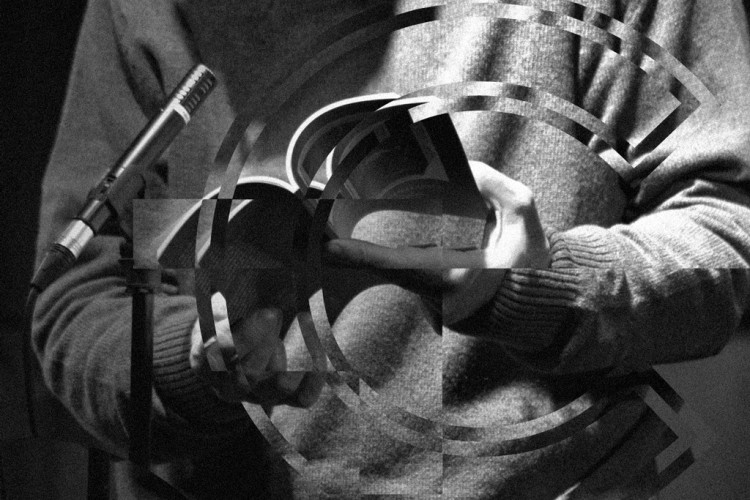Menyoal Puisi-Puisi di Media Sosial
Pada submisi Column kali ini, Arip Apandi berkomentar soal jenis-jenis puisi yang kini banyak bermunculan di media sosial serta pentingnya memiliki semangat membaca.
Words by Whiteboard Journal
Zaman dahulu, orang-orang menulis di dinding-dinding gua. Kemudian, orang-orang menulis di atas daun lontar. Selanjutnya, orang-orang menulis di atas kertas. Saya sangat tertarik untuk dapat membaca tulisan-tulisan, entah itu, yang terukir di dalam gua, yang tercatat di atas daun lontar, dan yang tercatat di atas kertas. Namun, saya sering bertanya-tanya pada diri saya sendiri, kenapa saya tidak pernah tertarik kepada tulisan-tulisan (baca: puisi) yang bertebaran di media sosial?
Saya akan menyebut suatu untaian kata-kata sebagai puisi jika ia dapat membuat saya mengernyitkan alis. Cara saya menilai apakah suatu deretan kata-kata itu puisi atau bukan yakni, pertama, melihat judulnya. Contohnya, Dingin Tak Tercatat — salah satu puisi bikinan Goenawan Mohamad — membuat saya tiada hentinya mengernyitkan alis. Dingin macam apa sebenarnya yang tidak tercatat pada alat pengukur suhu udara itu? Saya ragu apakah termometer di situ adalah termometer yang saya bayangkan. Dari judulnya saja sudah membuat saya menduga kemungkinan makna-makna dari apa maksudnya.
Pada akhirnya, saya tidak hanya mengernyitkan alis ketika membaca puisi penulis Catatan Pinggir yang terkenal itu, namun saya juga dibuat tercengang ketika sampai pada bait akhirnya: “Tuhan/Kenapa kita masih bisa bahagia?” Sampai di situ saya dapat mengecap kental akan makna filosofis namun disajikan dengan penuturan yang sederhana: kosakata, rangkaian kalimat, dan diksi yang sebenarnya sering kita ujarkan setiap hari. Namun, itulah menariknya puisi. Tuturan yang lumrah di telinga justru dapat membuat kita tersentak dalam puisi. Dengan begitu, puisi yang ideal adalah bacaan bersahaja yang tiada hentinya membuat kita berpikir atas maksud-maksudnya.
Sepertinya atas dasar itulah kenapa saya tidak pernah tertarik, apalagi asyik, membaca puisi-puisi yang berseliweran di media sosial. Akan tetapi, itu tidak berarti saya mengatakan puisi-puisi yang mejeng di timeline media sosial itu jelek dan tidak pula melarangnya. Saya setuju bahwa ini adalah persoalan selera masing-masing. Tak sampai hati saya menyuruh mereka, para penyair millenial di medsos, untuk dapat menulis puisi seperti Chairil, Sutardji, Rendra, Sapardi, dll. Toh, itu hak mereka dan saya tidak ingin juga mengusiknya.
Hanya saja, setelah saya perhatikan akun-akun yang khusus mengunggah kata-kata “indah” itu, saya menyimpulkan bahwa puisi, di mata mereka, adalah persoalan kenangan-kenangan kencan pemuda-pemudi yang baru kemarin lulus SMA. Dengan kata lain, puisi hanya dipahami sebagai pelepas dan peringan rindu yang, konon, katanya berat. Saya juga melihat kecenderungan bahwa puisi-puisi Instagram itu diperlakukan sebagai perwakilan suara “yang selama ini terpendam” terhadap gebetan. Kemudian, kecenderungan-kecenderungan itu dituliskan dalam, semacam, beberapa bait saja. Saya yakin, tulisan-tulisan yang dimodifikasi oleh font yang meliuk-liuk maupun latar belakang lanskap senja itu bukan haiku maupun aforisme.
Mungkin saya tidak akan mengomentari kata-kata yang didesain oleh gambar-gambar liris seandainya itu sekadar cuitan di Twitter ataupun keluh-kesah di Facebook. Akan tetapi, mereka secara terang-terangan menyebut itu sebagai “Puisi Senja”, “Sajak Kopi”, “Syair Sendu”, so on and so forth. Saya senang sekali membaca puisi dan saya merasa harus terlibat atas apa yang saya senangi itu. Atas dasar itulah kenapa tulisan atau gumam saya ini meluncur.
Menurut saya, media sosial akan menjadi wadah yang baik bagi penciptaan puisi-puisi seandainya para penulis sendu itu mempunyai semangat berkarya seperti para penyair besar. Memang, berita baiknya adalah bahwasannya para penyair millenial kita mengenal salah satu penyair besar kita, Sapardi. Bahkan, saya senang karena tahu bahwa banyak kawula muda zaman now yang mencintai Sapardi. Kita memang sudah seharusnya mencintai tokoh-tokoh hebat Indonesia, termasuk para penyair besar Indonesia. Akan tetapi, apakah mereka mengetahui apa sebenarnya yang membuat Sapardi menjadi Sapardi?
Jawaban saya adalah karena Sapardi merupakan seorang yang giat membaca. Ya, saya berani mengatakan bahwa semua penyair besar adalah mereka yang punya kebiasaan maniak membaca. Sapardi itu pembaca puisi-puisi Shakespeare. Hampir semua para penyair besar Indonesia merupakan pembaca karya-karya dunia, entah itu karya-karya dari Barat maupun Timur. Tentu, mereka para penyair besar itu tidak sekadar membaca, namun mereka juga mempelajari karya-karya yang mereka baca itu dalam rangka proses kreatif. Pembacaan para penyair besar Indonesia itu berangkat dengan etos memilih, mengupas, dan membuang. Etos di situ adalah pertemuan mereka dengan karya-karya para pendahulunya; membaca puisi-puisi kelas dunia; membuang remah-remahnya; lalu menerapkan sesuatu yang berguna pada konsep kepenulisan mereka sendiri. Dengan begitulah para penyair besar Indonesia menjadi besar.
Itulah yang tidak saya lihat dari para penulis kopi hitam yang sering nongol di media sosial. Saya melihat bahwa mereka mempunyai hasrat menulis yang besar, namun tidak diimbangi oleh semangat membaca. Padahal, menurut saya, a good writer is a good reader. That’s that.
Bagi saya, cukup mengherankan, di tengah pandemi sekarang ini, banyak dibuka kelas menulis, tapi kenapa tidak ada kelas membaca? Tentu, semua orang bebas meluapkan ekspresinya di media sosial. Akan tetapi, menumpahkan ekspresi ke dalam bentuk puisi itu ada syaratnya: membaca, membaca, dan membaca. Tentu, membaca puisi-puisi luar maupun dalam negeri sebanyak-banyaknya adalah salah satu syarat bagi para penyair muda.
Di zaman internet seperti sekarang, para pujangga di media sosial itu bisa mengakses puisi-puisi para penyair dunia dengan begitu mudah. Coba bandingkan dengan penyair Indonesia dulu, Chairil Anwar misalnya. Dia sampai harus mencuri buku dari perpustakaan H. B Jassin untuk bisa membaca karya-karya luar. Akan tetapi, para penulis di zaman sekarang bisa dengan mudah membaca karya-karya hebat dengan hanya bermodalkan kuota atau WiFi. Misal, dengan akses internet yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, para penggubah kata di zaman sekarang bisa dengan mudah membaca puisi-puisi Louise Glück, atau Pablo Neruda, dan penyair-penyair besar lainnya. Tentu, sekali lagi, tidak hanya sekadar membaca, namun juga mesti diiringi dengan semangat mengulik dan mempelajari bagaimana mereka para penyair besar menyampaikan rindu, cinta, dan kesepian dalam puisi-puisinya.
Oleh karena itu, kalau syarat itu sudah terpenuhi, maka jangan heran jika tulisan-tulisan para penyair di media sosial itu bisa nongkrong di akun-akun resmi Paris Review. Semoga.