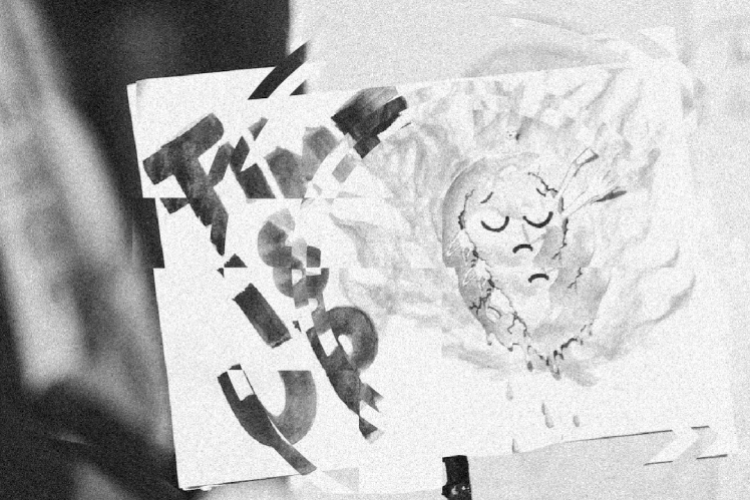Mencuri Raden Saleh: Kemunculan Wacana Seni dalam Perfilman Indonesia
[Tulisan ini mengandung spoiler] Pada submisi column kali ini, Sarah Monica mengutarakan argumen tentang betapa pentingnya film populer layar lebar bertema seni yang dieksekusi dengan baik sebagai pemantik sekaligus keberlangsungan diskursus seni rupa Indonesia.
Words by Whiteboard Journal
Sejak kapan pencurian karya seni di Indonesia menjadi sebuah isu negara?
Kegemparan kasus itu telah mencuri perhatian publik. Iya, publik film. Sebab, persoalan kriminalitas yang terjadi hanyalah konten dari gagasan cerita dalam film “Mencuri Raden Saleh”.Film ini sudah saya nantikan dengan debar penasaran sejak poster pertamanya muncul ke publik. Akhirnya, pada 25 Agustus 2022 lalu film yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko tersebut tayang di bioskop-bioskop Indonesia.
Mengapa film Mencuri Raden Saleh perlu dinantikan? Pertama, pemain utamanya Iqbaal Ramadhan–jelas patut ditonton. Kedua, sepengetahuan saya selama ini belum pernah ada film komersial layar lebar Indonesia yang khusus bertemakan karya seni ataupun membahas seniman nasional tertentu (koreksi saya jika keliru). Berangkat dari antusiasme tersebut, barangkali catatan kecil ini dapat turut menyemarakkan jagongan seni rupa yang wacananya telah muncul dalam perfilman tanah air.
Alkisah ‘Piko’ (Iqbaal Ramadhan), anak muda Ibukota yang terbebani biaya kuliah mahal dan ayah yang tengah dipenjara, mencari nafkah dengan merepro lukisan-lukisan seniman Indonesia ternama. Dia dibantu oleh sahabatnya ‘Ucup’ (Angga Yunanda), seorang hacker yang mencarikan klien bagi lukisan palsu hasil produksi Piko. Lukisan tersebut ternyata dikomodifikasi dalam Balai Lelang demi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari praktik pemalsuan karya.
Konspirasi kemudian terjadi antara Budiman, ayah Piko (Dwi Sasono) dengan mafia seni sekaligus mantan presiden RI, yaitu Permadi (Tyo Pakusadewo) untuk melibatkan Piko dalam proses forgery karya masterpiece Raden Saleh, “Penangkapan Pangeran Diponegoro”. Tanpa kecurigaan Budiman bahwa keterlibatan itu dimanipulasi lebih jauh oleh Permadi sampai pada tindakan penukaran dengan karya aslinya di Istana Negara.
Dengan iming-iming Rp2 miliar sebagai upah forgery yang diharapkan Piko dapat membayar pengacara bagi kasus ayahnya, Permadi menambahkan 15 miliar agar Piko bersama timnya mau dan mampu menukar lukisan tersebut dalam perjalanan ke Galeri Nasional untuk keperluan pameran. Dalam rangka menyanggupi misi, selain Ucup, empat orang tambahan berhasil direkrut. ‘Sarah’ (Aghniny Haque) pacar Piko yang jagoan taekwondo, ‘Tuktuk’ (Ari Irham) si pembalap jalanan, bersama saudaranya ‘Gofar’ (Umay Shahab), dan ‘Fella’ (Rachel Amanda) ahli strategi, bekerja sama melancarkan aksi itu. Namun, rencana itu gagal total.
Nyatanya, lukisan berhasil ditukar dan disimpan di rumah Permadi tanpa sepengetahuan tim. Merasa dikhianati, mereka berenam merancang rencana balas dendam untuk mencuri kembali lukisan asli Raden Saleh dari kediaman mantan presiden tersebut.
Sisi Gelap Bisnis Seni Rupa
“Mencuri Raden Saleh” merupakan film action-drama dengan penampilan laga memukau karakter Sarah di beberapa adegan. Sebagai satu tim yang awalnya dipersatukan oleh kebutuhan materi–ekspektasi duit 2,5 miliar akan diterima oleh masing-masing anggota–berujung pada kesadaran perkawanan dan ikatan solidaritas sebagai korban pengkhianatan.
Tema pengkhianatan menjadi benang merah dari fokus utama alur skenario yang coba dikaitkan dengan kisah historis di balik ide kelahiran lukisan “Penangkapan Pangeran Diponegoro”. Sejarah penangkapan tokoh Pahlawan Nasional tersebut terjadi disebabkan oleh pengkhianatan Belanda yang melanggar kesepakatan genjatan senjata selama bulan Ramadan. Pangeran Diponegoro berhasil dijebak dan ditangkap di hari kedua lebaran, 28 Maret 1830, sehingga mengakhiri perjuangan Perang Jawa (1825-1830). Perang itu merupakan perang paling mematikan, serta mengakibatkan kebangkrutan besar Belanda. Perang yang mustahil dapat mereka menangkan tanpa tipu muslihat terhadap pimpinan pasukan Jawa, yakni Pangeran Diponegoro.
Raden Saleh Sjarif Boestaman (wafat 23 April 1880) menciptakan karya “Penangkapan Pangeran Diponegoro” sebagai simbol perlawanan gigih rakyat Jawa sekaligus ejekan untuk pemerintahan Belanda. Sketsa awal lukisan itu dibuat pada 1856. Setahun kemudian, ia hadiahkan hasil akhirnya kepada Raja Belanda, Willem III. Berita tersebut dikabarkan melalui surat kepada rekannya di Jerman, Duke Ernst II dari Sachesen-Coburg dan Gotha pada 12 Maret 1857.
Lukisan berjudul “Ein historisches Tableau, die Gefangennahme des javanischen Häuptings Diepo Negoro” (Lukisan bersejarah tentang penangkapan seorang Pemimpin Jawa Diponegoro) merupakan tandingan atas lukisan “De onderwerping van Diepo Negoro aan luitenant-generaal Hendrik Merkus Baron de Kock” (Penyerahan Pengeran Diponegoro kepada Jenderal De Kock), karya Nicolaas Pieneman (1809-1860). Dalam lukisan Raden Saleh, sosok Pangeran Diponegoro digambarkan dengan penuh keagungan dan api perjuangan yang tak padam. Guratan ekspresi dan sikapnya tegar menghadapi pengkhianatan, takdir kekalahan, maupun menantang kematian.
Fondasi sejarah, warisan nilai, dan manifestasi semangat nasionalisme mencakup keseluruhan simbolisasi dalam karya “Penangkapan Pangeran Diponegoro” dari maestro pertama seni rupa modern Indonesia, Raden Saleh. Elemen-elemen inheren itulah yang di antaranya menjelma nilai tukar materiil dalam peta apresiasi karya seni, baik di lingkup nasional ataupun global. Lukisan-lukisan anak karya Raden Saleh dapat tembus seharga puluhan hingga ratusan juta dollar atau lebih di pasar lelang dunia, khususnya untuk lukisan “Penangkapan Pangeran Diponegoro”. Di akhir film juga diceritakan bahwa ada seorang kolektor asing yang bersedia membeli lukisan tersebut sejumlah miliaran rupiah.
Maka tidak heran, berangkat dari semua kekuatan internal karya, maupun faktor eksternal afirmasi publik global, lukisan tersebut yang dipilih sebagai tema film. Bukan karya dari seniman-seniman legenda Indonesia lainnya, sebagaimana ditampilkan dalam sebuah negosiasi bisnis antara Piko dengan Dini (kurator-broker), yaitu apakah lukisan Hendra Gunawan, “Three Prostitutes”, atau Sudjojono yang selanjutnya akan dibuat replika. Sebelum adegan itu, sempat tercetus juga oleh Piko nama-nama maestro lain seperti Lee Man Fong (1913-1988), Jeihan (1938-2019), Sunaryo (15 Mei 1943), Soenarto (PR?) (1931-2018). Akan tetapi, bahkan direspons oleh Ucup sebagai “pelukis-pelukis yang tidak dikenal”. Butuh satu nama pelukis Indonesia yang ketika disebut tak ada seorang pun yang takkan mengenalnya, ialah Raden Saleh. Selain semua nama itu dimunculkan pula lukisan Widayat dan Agus Suwage. Meskipun, agak bertanya-tanya juga mengapa tidak sekalian ditampilkan Affandi.
Di antara jenis seni lainnya, boleh jadi memang hanya seni rupa yang wujudnya dapat dikonversi secara nominal menjadi barang berharga. Produk seni rupa, terlepas dari kualitas estetis dan historisnya, sangat mungkin diolah dengan legitimasi wacana pengetahuan dari aktor-aktor otoritatif seperti kritikus seni, kurator, kolektor, akademisi, atau balai lelang sehingga ikut mengintervensi nilai jual karya di pasar seni rupa. Dengan demikian, fleksibilitas harga dan elektabilitas posisi seniman ditentukan oleh jejaring permainan pasar belaka.
Kajian ilmiah komprehensif apa yang kira-kira mampu memperlihatkan korelasi dari standar artistik sebuah karya berbanding lurus dengan pembentukan wacana harga terkait. Apakah korelasi tersebut ikut dipengaruhi oleh berapa usia karyanya, siapa senimannya, dari bangsa mana ia dilahirkan, dalam situasi sosial-kultural bagaimana karya tersebut dicipta, atau dengan model penjualan apa karya itu diperkenalkan dan ditawarkan ke publik? Kompleksitas dan ambiguitas dari itu semua membuat karya seni rupa, terkhusus lukisan, sangat mungkin ditransformasikan ke dalam bentuk medium kekayaan yang sulit diprediksi ekspansi harganya sekaligus ditetapkan harga pajaknya (atau mungkin memang tidak ada).
Gap antara lukisan sebagai komoditas barang mewah dengan basis legal formal yang mengaturnya mengakibatkan lukisan dapat digunakan menjadi produk investasi gelap, sebagai wahana pencucian uang (money laundering). Pada periode-periode krisis moneter seperti 1998, terjadi boom seni rupa di mana pembelian lukisan terjadi secara masif, baik pada karya seniman maestro maupun yang masih menjajaki karir. Fenomena ini terjadi karena para elit mafia ingin menyelamatkan uang mereka dari ancaman inflasi global. Lebih baik menyimpan uang dalam bentuk lukisan, daripada menderita pemotongan nilai tukar rupiah terhadap supremasi dollar.
Dalam film “Mencuri Raden Saleh”, kehidupan mafia di tengah ekosistem seni rupa ditunjukkan dengan menempatkan motif pencurian tidak hanya sebagai urusan materi, melainkan pembalasan dendam politik. Mengingat status hierarkisnya, dunia seni rupa memang merupakan konstelasi dari kekayaan dan kekuasaan yang melibatkan wacana pengetahuan, akses kapital, jabatan politik, serta jaringan elite. Akan tetapi, di level awam status seniman pelukis bukanlah sebuah prestise, karena bila dibandingkan pelukis yang sukses, masih jauh lebih banyak pelukis yang gagal. Sebagaimana Oma Sarah menasehati cucunya, “Kamu mau jadi apa kalau hidup sama pelukis (Piko)?”
Antusiasme Publik Seni di Indonesia
Menempatkan tema seni sebagai latar cerita merupakan angin segar bagi perfilman Indonesia, terutama bagi publik pecinta seni. Di perfilman internasional sendiri, film-film dengan tema seni baik sebagai latar, maupun berfokus pada kisah biografi seniman begitu berlimpah. Mungkin kita pernah menonton beberapa dari film berikut, antara lain “Basquiat” (1996), “Frida” (2002), “Pollock” (2000), “Girl with a Pearl Earring” (2003), “The Mill and The Cross” (2011), atau “Loving Vincent” (2017). Untuk film dokumenter ada “Ai Weiwei: Never Sorry” (2012), “Kusama – Infinity” (2018), “The Painter and The Thief” (2020), ataupun “The Lost Leonardo” (2021). Selain itu terdapat pula film genre drama romantis atau drama laga-kriminal tentang seni, seperti “Mickey the Blue Eyes” (1999), “Stealing Rembrandt” (2003), “Art Heist” (2004), “The Best Offer” (2013), “The Forger” (2014), “Red Notice” (2021), dan masih banyak lainnya bisa ditelusuri.
Film “Mencuri Raden Saleh” dapat menggugah semangat awal menggerakkan tema-tema seni rupa dalam layar lebar Indonesia. Meskipun kenyataannya selama ini produksi dokumenter tentang seniman Indonesia untuk target film festival pun sudah banyak dilakukan, namun bila mampu menjangkau penonton bioskop komersil tanah air akan lebih baik. Dengan masuk ke ranah populer, film bertema seni dapat menjadi sebuah medium edukasi bagi khalayak luas. Tentunya perlu eksplorasi lebih mendalam seputar sejarah seniman, termasuk proses kreatifnya. Sehingga, tak sekadar menyajikan nama-nama, tetapi cerita berharga di balik nama itu serta kontribusi bagi dunia kesenian di Indonesia.
Menarik mendengar dalam percakapan Piko-Ucup-Dini ketika menyerahkan hasil replika lukisan “Penangkapan Pangeran Diponegoro” bahwa detailnya dibuat sesuai dengan hasil restorasi pada 2012. Berdasarkan dari data internet, lebih banyak sumber menyebutkan bahwa restorasi lukisan tersebut dilakukan tahun 2013 oleh Susanne Erhards, seorang ahli restorasi dari Jerman, dengan dukungan Yayasan Arsari Djojohadikusumo dan Goethe Institute Indonesia.
Sebelum direstorasi, lukisan “Penangkapan Pangeran Diponegoro” pernah dipamerkan di Galeri Nasional pada 6-7 Juni 2012, bertajuk “Raden Saleh dan Awal Seni Lukis Modern Indonesia”. Kemudian pameran itu dilanjutkan dengan “Aku Diponegoro: Sang Pangeran dalam Ingatan Bangsa, dari Raden Saleh hingga Kini” di tanggal 6 Februari-8 Maret 2015 yang dikuratori oleh Dr. Werner Kraus, Dr. Peter Carey, dan Jim Supangkat. Sejak tahun 2014 hingga kini, karya tersebut menjadi salah satu koleksi Museum Istana Kepresidenan Yogyakarta.
Sungguh tantangan sendiri bagi kreator film dalam mengemas fakta-fakta sejarah ke substansi cerita. Namun, untuk menawarkan film sebagai ruang pembelajaran–bukan semata ajang hiburan–validitas dan realibilitas data perlu diperjuangkan.
Melalui film, gema apresiasi serta antusiasme seni rupa dapat semakin diamplifikasi. Kita melihat sendiri bagaimana momentum perhelatan seni di kota-kota tertentu seperti Biennale dan ARTJOG hingga Art Jakarta, serta aktivitas pameran seni di berbagai museum atau ruang publik kreatif senantiasa menarik keramaian. Platform visual digital, melalui media sosial, sangat berkontribusi menggaungkan gairah seni tersebut. Meski saat ini minat terhadap seni kebanyakan masih sebatas lomba publikasi foto menawan di depan karya-karya seniman, saya yakin, dengan sendirinya kegiatan-kegiatan tersebut akan mampu memantik diskursus seni dan membangun dialog pengetahuan yang dapat melahirkan tidak hanya para kurator, melainkan juga para kritikus di kancah seni rupa Indonesia.