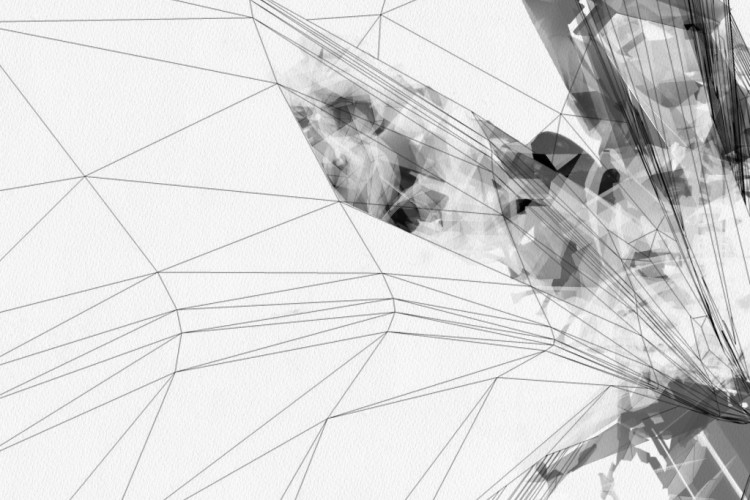Melawan Genosida dan Doktrin Media Barat tentang Palestina yang Queerfobik
Dalam submisi Open Column ini, Zar Mose berupaya melawan narasi media Barat yang kerap melabeli Palestina sebagai masyarakat fundamentalis yang menolak keberadaan individu atau komunitas queer melalui puisi-puisi dari penyair queer berdarah Palestina yang ia terjemahkan.
Words by Whiteboard Journal
Pada tahun 2020, seorang teman daring menghubungi saya untuk melakukan wawancara terkait dengan konflik Timur Tengah sebagai bagian dari tugas kuliahnya. Pertanyaannya sederhana, tetapi memicu refleksi mendalam,
“Dalam kapasitas kamu sebagai individu queer, apa yang mendorong kamu untuk mendukung kemerdekaan Palestina?”
Saya merenung sejenak, kemudian saya balik bertanya tentang latar belakang pertanyaannya.
“Kamu queer, negara seperti Palestina menolak komunitas queer.”
Melihat bagaimana logika serupa sering saya temukan belakangan ini di media sosial jelas membuat saya khawatir. Logika ini mengerdilkan kemanusiaan menjadi sebuah tindakan transaksional. Dalam masyarakat yang berorientasi pada mutual-symbiosis, terlebih lagi bagi mereka yang sudah dipengaruhi paham liberal, kebebasan individual menjadi prioritas yang paling utama. Individu queer dibuat membayangkan kengerian yang terjadi pada dirinya sendiri sebagai bayaran atas apa yang ia dukung. Bagi saya, kemanusiaan tidaklah sebuah upaya tukar-menukar nasib. Kemanusiaan seyogyanya bukan sebuah investasi—dan tidak boleh dilihat sebagai investasi.
Oktober 2023, menjadi catatan akbar gagalnya kemanusiaan di tanah suci Palestina. Dilansir dari Al-jazeera, sejak 7 Oktober hingga esai ini rampung ditulis, setidaknya tercatat 9.488 masyarakat Palestina wafat karena bombardir tanpa ampun Israel. Jutaan masyarakat dari penjuru dunia turun ke jalan menuntut gencatan senjata. Kampanye daring tidak henti-hentinya disiarkan untuk mengekspos genosida. Upaya-upaya diplomasi semakin sengit namun masih dibuntukan oleh hegemoni Amerika Serikat serta aliansi negara Barat lainnya. Bersamaan dengan itu para pendukung Israel masih berupaya mencuci otak komunitas queer dengan menggoyahkan keberpihakan kita: bahwa bila Palestina utuh sebagai sebuah negara, hukum-hukum yang queerfobik pasti akan disahkan.
Saya pribadi melihat upaya guilt-tripping yang dilakukan oleh masyarakat Barat, termasuk juga para liberalis, sebagai tindakan yang sia-sia. Dalam pepatah Minang dikatakan “bak basangai di abu dingin”, seperti berjemur di abu yang telah dingin. Mereka tidak bisa mencuci otak komunitas yang sudah fasih dengan bau anyir penjajah. Mengutip Alok Vaid-Menon dari bukunya yang berjudul Beyond the Gender Binary, “..we have been taught to fear the very things that have potential to set us free.”
Moral kompas individu queer tidak semestinya bengkok mengingat bagaimana masa depan generasi kita hanya akan ada bila kita berhasil mendeteksi hal-hal yang bisa memerdekakan kita secara kolektif. Ketakutan yang diciptakan oleh masyarakat Barat tidak lebih dari narasi usang penjajah untuk mengerangkeng kita kembali ke dalam belenggu mereka.
Esai ini saya tulis dengan dua tujuan: menentang logika yang hendak menggoyahkan kaki saya atau pun teman-teman queer Indonesia yang pro Palestina dan untuk menaikkan ke permukaan eksistensi penyair queer berdarah Palestina melalui puisi-puisi yang telah saya terjemahkan. Bersepakat dengan pendapat Antonio Gramsci, kelas penguasa memanfaatkan budaya dalam menyebarkan ideologi mereka. Saya yakin salah satu taktik penjajah dalam menghapus eksistensi suatu kelompok adalah dengan merenggut narasi yang dijajah. Dalam konteks ini, ideologi yang dimaksud merujuk pada zionisme yang mengakar di Israel. Tiga puisi ini hadir untuk merawat teks-teks penulis queer Palestina, sebagai bentuk bukti hidup sebuah budaya—sebuah negara—dan upaya memandulkan zionisme di Indonesia.
…
Untuk melacak sejarah perjuangan Palestina, kita perlu melakukan kilas balik pada tahun 1948. Tahun penuh darah di mana tentara Israel mengusir masyarakat Palestina dari tanahnya sendiri. Peristiwa ini lazim dikenal sebagai Nakba. George Abraham, seorang queer Palestina-Amerika, dan penulis buku puisi “Birthright”, mengeksplorasi Nakba pada puisinya yang berjudul “Searching for a Palestinian After”. Ia merekam efek Nakba baik secara psikologis, fisik, maupun sosial budaya. Sebagai pembuka, George menekankan gejolak rasa kehilangan dan pengusiran, sudah ada sebelum terjadinya Nakba. George meruntut rentetan peristiwa Naksa (Perang Enam Hari tahun 1967), Protective Edge (konflik 2014 di jalur Gaza), dan terus berlanjut di tempat-tempat seperti Nabi Saleh dan Sheikh Jarrah.
Mencari Masa Depan Palestina
“Masa lalu adalah masa depan tempat kita kembali”
— Fargo Tbakhi
Pernah ada Nakba sebelum adanya Nakba: Nakba di mana bumi tak terbelah, Nakba yang berongga tanpa akar, Nakba perebutan dan perebutan-kembali. Nakba di mana 1948 lebih singkat dari negara [ ]. Dan lalu, ada Nakba Naksa, Nakba Protective Edge dan dekade yang tidak terhindarkan, Nakba gas air mata, Nakba Nabi Saleh, Nakba Sheikh Jarrah. Dan setelah Nakba ledakan bintang, pecahan atom, fragmen DNA dari bioprotokol sebagai penjara terbuka, ada Nakba rekursi Gaza dari Nakba rekursi Gaza. Dan setelah dua lautan karsinogenik, ada Nakba di mana aku tak memiliki masa lalu. Aku yang terjerat. Di negara itu, Nakba satu-satunya ibu tempat kita berpulang.
Dan saat Nakba metafora. Saat Nakba nafas tak berbapak. Dan saat Nakba cadel, saat Nakba di mana dendrit telah rusak. Dan ketika Nakba jabat-khianat melahirkan Nakba huruf-huruf Amerika yang gagal melahirkan ع dan menghentikan glotal. Dan saat tubuh kita bagai Nakba taa marbuuTa. Lidah kelu karena diskursus Nakba dan nyanyian penjajah, aku muncul, sebagai sosok yang tersenyum, untuk menunduk melalui histeria kebahasaan yang telah dipangkas.
Dan saat Nakba pembuangan surga. Dan saat Nakba pembakaran Eden. Saat, ketidakbermakaman, Nakba Sebelum, dari Nakba Sebelum dan Sebelumnya terjadi di dalamku, aku tidak tahu tanah siapa yang dibakar, lereng siapa yang ditinggalkan, sayap siapa yang akan di-syntax ulang setelahnya-iya, kita terbang menuju setelah dan malah diberikan sebuah jarak yang mustahil: Nakba berkabung di Cakrawala. Nakba yang tak tercapai-Nakba tubuh النهر, tubuh البحر— tubuh dari cahaya tak utuh dari matahari yang sekarat.
…
Bila nuansa keputusasaan mewarnai puisi sebelumnya, Fargo Tbakhi, penulis queer Palestina-Amerika, merawat pengharapan akan kemerdekaan melalui puisinya “American-Palestine Incantation”. Puisi ini adalah rapalan mantra yang mengajak pembaca membayangkan semesta-semesta di mana merdeka adalah sebuah kenyataan. Di baris-baris awal puisi, aku-lirik menegaskan bahwa ketiadaan atau ketidakhadiranlah yang menumbuhkan keteguhan hati. Tragedi dan duka yang beruntun dituliskan dengan simbol-simbol seperti hantu, kista, hingga pemakaman Viking. Fargo turut mereferensi salah satu tragedi paling masyhur dalam narasi agama Ibrani di mana istri Luth berubah menjadi tiang garam karena melanggar perintah Tuhan agar tidak menoleh ke belakang selama proses evakuasi saat dihancurkannya kota Sodom. Sebuah upaya reklamasi narasi yang mengesankan mengetahui bagaimana: 1) Kisah Luth selama ini ditafsirkan oleh non-queer, 2) Israel mengklaim bahwa mereka bangsa yang diutus dengan misi unik sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Melalui pernyataan rasis dari Perdana Menterinya, Israel membenarkan penghancuran Palestina karena adanya anggapan bahwa Palestina adalah anak-anak kegelapan—sehingga mereka layak diratakan (sebagaimana Tuhan meratakan Sodom). Puisi ditutup dengan harap-gempita bahwa kemerdekaan Palestina ada jika “aku tidak berkedip dan terus membuka mata.”
Mantra Amerika-Palestina
Karya Fargo Tbakhi
ketiadaanlah yang membentuk hati
seperti air, aku belajar merupa bentuk
sesuai dengan ruang yang kupenuhi hari ini.
aku tak percaya pada bentuk yang permanen
aku tak percaya anjing adalah karibku.
tapi aku percaya pada hantu. hantu bisa membuatmu jatuh cinta.
hari di mana aku merasa terlalu padat,
kukalungkan pembatas di leherku: hitam-putih,
berumbai, berpolakan jaring ikan. dengan ini
kau tak perlu bertanya dalam bahasa apa darahku
mengerang. nadiku kista yang diisi hingga ke tulang.
seperti mesin capit, aku mudah
merelakan: kau tak menghubungiku seharian maka akan aku
makamkan kau selayaknya viking. aku belajar bahwa duka
lebih baik bila lekas dan ringkas:
terlalu banyak hingga terlalu sering
aku terlahir taurus, di tahun banteng:
keras kepala yang ganda, kakiku tumbuh tiga inci ke dalam tanah
di manapun kakiku berjalan. aku mengakar.
apa yang bisa kukatakan? dulu, kakekku menggali
tumitnya menantang penjajah. dan aku,
aku setengah serafim setengah queer.
aku bebas menjahit
setiap titik garis ke dalam kulitku. dengan ini
kau tak perlu bertanya negara mana
yang sedang kau cium. aku percaya kata-kata
muncul dari tembok, dan bukan sebaliknya.
aku percaya pada semesta paralel.
aku percaya bahwa aku berasal
dari suatu semesta. di suatu semesta,
kakekku dan aku, saat ini sedang
membandingkan ukuran sepatu. di suatu semesta,
aku mencium telapaknya hingga mengecap tanah yang bisa kunamai.
aku kalungkan foto album keluarga di leherku
wajah-wajah itu membaru setiap kali
kubuka. bila aku tak melihatnya
maka ia tidaklah nyata—inilah yang membuatku terlahir baru.
inilah yang membuatku seorang Palestina. inilah yang membuatku sulit dicintai.
apa yang bisa kukatakan? segala yang menciptakan kita
menciptakan kita lagi dan lagi. aku lelah maka aku ada.
aku percaya pada rudal. aku percaya pada terowongan
di bawah tembok. pun aku percaya, tuhan punya kaki yang bisa kucium.
apa yang bisa kukatakan? dulu kakekku berpaling
dan di saat ia menoleh, rumah kita telah hilang.
aku percaya andaikan aku tak berkedip,
andaikan aku terus membuka mata,
rumah kita akan kembali.
…
Duka masih akan menyelimuti puisi selanjutnya. Noor Hindi, queer Palestina-Amerika, mendedikasikan hidupnya menjadi reporter dan penyair. Ia telah merilis satu buku kumpulan puisi berjudul “Dear God. Dear Bones. Dear Yellow”. Dalam puisi I Once Looked at the Mirror but I Couldn’t See My Body, Noor mengeksplorasi pengalaman metafisika untuk menengok sejarah lampau Palestina. Puisi ini diilhami oleh lukisan Salvador Dali yang berjudul The Persistence of Memory. Puisi dimulai dengan penekanan bahwa pengalaman melihat diri sendiri di cermin tidak terasa jauh berbeda dari berjalan melalui negara ini, yang seolah-olah tanpa kewarganegaraan dan membawa beban sejarah. Penyair merasa terpisah dari tubuhnya, seakan-akan ada di suatu tempat, menyaksikan ayahnya pada malam hari menggambar peta Palestina berulang kali dengan tinta hijau. Rasa sakit yang mendalam berulang kali disampaikan. Puisi ditutup dengan simbol jam meleleh yang merupakan nafas lukisan Salvador Dali untuk mengisyaratkan kefanaan manusia dan keterbatasan manusia dalam menghadapi waktu.
Aku Pernah Berkaca, Tapi Tak Bisa Melihat Tubuhku
(Puisi Ekfaristik setelah ‘The Persistence of Memory’ oleh Salvador Dali)
Setelah Mahmoud Darwish
Rasanya tak begitu berbeda
Dengan berjalan melewati negara ini,
Tanpa kewarganegaraan, dan memikul
sejarah. Di suatu tempat tubuhku
sepi & menyaksikan ayahku
di tengah malam menggambar & menggambar ulang
Peta Palestina, tinta hijau —
& perih
& perih
& perih
& perih
Apalah Palestina bila bukan pohon zaitun yang tumbuh di lidah ayahku
Apalah Palestina jika bukan pohon zaitun yang tumbuh
Apalah Palestina jika bukan zaitun
Apalah Palestina
Apalah—
Di suatu tempat
Sebuah jam meleleh.
…
Terjemahan puisi-puisi tersebut tidak berupaya menjadi terjemahan yang sempurna apalagi pakem. Ada berbagai cara dalam mengalihbahasakan sebuah teks, dan saya menyadari kemampuan saya memiliki batasan. Terlepas dari terjemahannya, ketiga puisi itu memiliki satu motif yang sama: mendeklarasikan emosi yang terkerangkeng dalam penjajahan. Ketiga penyair itu, hanyalah sedikit dari banyaknya darah keturunan Palestina—dan queer Palestina—yang suaranya masih lantang terdengar menarasikan rekam hidup mereka. Interpretasi yang saya tulis pun hanyalah sedikit dari berbagai posibilitas interpretasi yang bisa muncul. Dengan semangat untuk merekam, hidup, dan merdeka, nilai-nilai estetika dalam puisi-puisi tersebut jelaslah di luar batas keindahan.
Dalam menjawab pertanyaan wawancara di awal tulisan ini, saya menambahkan bahwa pada dasarnya queer dan Palestina mengalami motif kejahatan yang sama. Maksud saya, selama ini agama dijadikan motif untuk menghancurkan kami. Kami dihapuskan karena kami terlahir sebagai queer. Palestina dihancurkan karena mereka berdarahkan Palestina. Kami dinarasikan dengan porak-poranda tangan-tangan penuh darah. Saya seorang penyair, dan sebagaimana semua penyair adalah tugas bagi saya untuk menarasikan hidup dari tangan pertama: tangan saya sendiri. Begitu pula penyair-penyair Palestina. Mereka enggan membiarkan kisah mereka dihapus dari kertas mereka sendiri. Saya percaya dekolonisasi bisa dimulai dari lidah: dari bahasa.