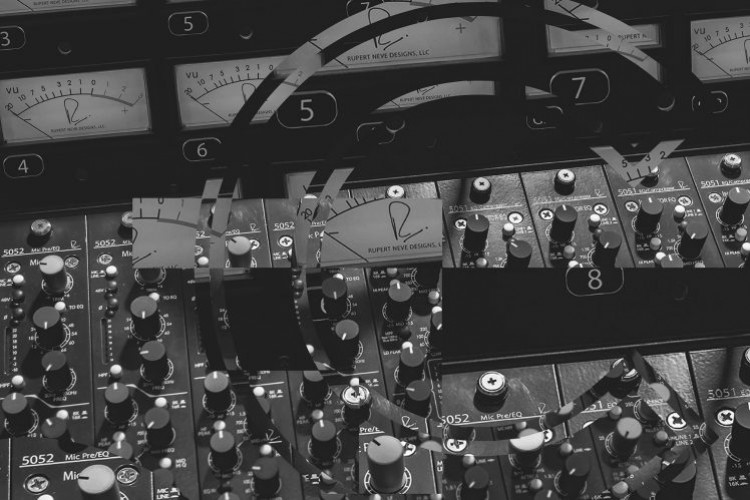Melampaui Goyangan Biduan: Dangdut dan Persoalan Kuasa Tubuh
Dalam submisi column ini, Iqa Kinanti Nandakasih mengurai kompleksitas dan stigma musik dangdut yang kerap dianggap norak, bobrok, dan hanya sekadar musik rakyat jelata. Lebih dari itu, ia menyoroti relasi kuasa yang bekerja melalui kesenangan dan tubuh para biduanita.
Words by Whiteboard Journal
Dangdut is the music of my country.
Dalam remang-remang panggung desa, dari kosan ke kosan sempit, di tiap sudut gang, di pasar baju bekas, angkutan kota, hingga tempat hiburan top satu di kota-kota besar tidak pernah lepas dengan alunan musik dangdut. Lagu-lagunya yang “merakyat” selalu berhasil merebut hati berbagai kalangan, terutama masyarakat menengah ke bawah. Bagi mereka, dangdut lebih dari sekadar musik dan hiburan–meskipun hingga kini masih banyak juga yang menganggap bahwa musik dangdut tidak prestise, marjinal, dan kampungan.
Akar-akar dangdut berasal dari etnis Melayu. Meskipun pengertian Melayu meluas, tetapi dalam konteks ini, “Melayu” dari segi geografi kultural (kawasan budaya Melayu), agama (Islam), bahasa (Melayu), serta adat dan upacara. Kemelayuan selalu diidentikkan dengan dangdut untuk mengaitkan silsilah historis kerajaan di Sumatera Utara. Lebih sederhana, dangdut adalah pengkristalan dari orkes Melayu dan Islam. Pada saat itu, dangdut menjadi tradisi Islam di kawasan Melayu dan pengiring musik di film India. Kemudian barulah pada tahun 1990 dangdut menjadi musik nasional Indonesia.
Rasanya tidak adil dan sudah tidak relevan lagi jika dangdut disebut hanya milik masyarakat kelas menengah ke bawah. Faktanya, dangdut bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya kalangan tertentu yang senang mendengarkan musik-musik dangdut, kini ia mendapat tempat dan menjadi teman bagi semua kalangan. Namun, dangdut yang menjadi salah satu budaya pop di Indonesia saat ini, masih jarang memperoleh perhatian serius yang layak.
Dalam sejarah dan perkembangannya, dangdut bukan sekadar musik dan identitas kultural seperti lirik Project Pop di atas. Dangdut sendiri telah menjadi wacana di berbagai aspek, seperti politik, agama, ekonomi, hingga wacana gender. Ruang dandgut selalu dikaitkan dengan tubuh perempuan sebagai objek seksual. Tidak berhenti sampai di situ saja, jika dilihat dari yang paling permukaan, lirik-lirik dangdut kerap menjadi kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak. Namun lagi-lagi, semuanya kemudian tetap menjadi nilai komersil.
Tubuh dan Goyangan
Sampai saat ini, dangdut menjadi hidangan yang menarik dan menggiurkan untuk diulik lebih dalam. Ada yang tidak dapat dipisahkan dari dangdut: perempuan dan goyangan. Dua hal ini menjadi titik sentral dalam dangdut yang menunjukkan adanya relasi kuasa atas tubuh hingga menimbulkan persoalan politik.
Ada ketidaksadaran masyarakat terhadap relasi kuasa yang bekerja melalui kesenangan dan tubuh biduanita.
Pedangdut perempuan atau disebut juga biduanita, sengaja menggunakan tubuhnya sebagai sarana ekspresi dan komunikasi terhadap penikmatnya. Selama ini dangdut hanya dilirik sebagai musik hiburan rakyat. Biduanita kerap menjadi objek seksual dalam ruang dangdut yang dapat dilihat dari bagaimana penonton yang memposisikan mereka sebagai objek seksual melalui saweran. Namun, lebih dari itu, ada ketidaksadaran masyarakat terhadap relasi kuasa yang bekerja melalui kesenangan dan tubuh biduanita.
Goyangan-goyangan yang diciptakan oleh para biduanita tidak semata-mata persolan seni atau sekadar memancing semangat penonton, tetapi juga bentuk kuasa biduanita yang sedang berlangsung. Jika selama ini mereka dianggap sebagai objek seksual, pada posisi ini, justru biduanita memiliki kekuasaan atas segalanya di atas panggung.
Di sinilah tubuh menjadi medan produksi kultural yang selalu dikonstrukikan dengan berbagai cara. Dalam konteks ini, tubuh merupakan atribut dan pusat kontrol pada setiap aksi panggung musik dangdut. Ada simbol privat atau ‘kenikmatan’, wujud ekspresi, hingga kuasa biduan untuk menghegemoni tubuh penikmat musik dangdutnya.
Inul Daratista dan Inul Lainnya
Generasi Inul Daratista yang disusul oleh Julia Perez, Dewi Persik, Trio Macan, dan masih banyak lagi, dianggap selalu seronok dalam membawakan musik dangdut baik dari lirik maupun aksi mereka di atas panggung. Hal ini kemudian meninggalkan kesan di sebagian masyarakat urban bahwa musik dangdut penuh dengan goyangan erotis dan kotor. Dengan kata lain, dangdut dianggap bobrok dan brutal.
Tubuh menari Inul merupakan simbol utama yang diperdebatkan baik dari agama, budaya, dan politik pada masa tumbangnya Soeharto (Andrew, 202). Sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya tentang dangdut dan penikmatnya, generasi Inul yang disusul oleh Jupe mayoritas dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah, seperti pembantu rumah tangga dan buruh perempuan. Di samping perdebatan populer atas tubuh biduan dalam wacana agama, politik, dan budaya, faktanya Inul berhasil mengobarkan api “Inulmania”. Lantas, mengapa kemunculan Inul di media begitu dikecam dan dipandang menyebarkan pornografi?
Pertama, agama. Tubuh Inul dan Jupe menjadi panggung bagi beragam budaya–dari yang paling liberal hingga yang paling konservatif. Sejak terbentuknya negara Indonesia dan kalangan Islam, tubuh penari perempuan telah menjadi objek pantauan pemerintah dan hujatan karena dianggap kental dengan bunyi seksualitas perempuan dan mengandung pornografi. Suara-suara keras kalangan Islam konservatif yang “anti Inul” pada masa itu memandang bahwa aksi-aksi Inul dan biduan lainnya berbahaya karena menunjukkan seksualitasnya terang-terangan yang membuat laki-laki tersesat dan menghancurkan rumah tangga.
Kedua, politik. Sebetulnya, ada banyak biduan yang goyangan panggungnya lebih provokatif secara seksual dibandingkan Inul. Hanya saja mereka ini tidak pernah direkam dan dimuat dalam VCD di sekitar tahun 1990-an. Inul mendapatkan akses tersebut yang menjadi mediumnya juga semakin meroket di TV nasional–membuatnya marak akan kontroversi atas aksi-aksi panggungnya, seperti “goyang ngebor”.
Ketiga, budaya. Citra Inul dan kemunculannya yang disusul oleh biduan lainnya dalam dangdut kontemporer hingga kini masih menjadi polemik di sebagian masyarakat Indonesia. Namun hal itu tentu tidak mengurangi penikmat dangdut. Dangdut yang setiap hari seliweran di berbagai tempat dan jalan adalah bukti eksistensi dangdut yang tidak pernah pudar. Dangdut dan aksi-aksi biduanita di panggung yang menjadi persoalan, nyatanya dangdut adalah identitas masyarakat Indonesia.
Berbagai macam tafsiran goyang ngebor Inul, tidak semuanya negatif. Justru “efek negatif” goyang ngebor dan aksi lainnya yang dilakukan Inul di panggung bukan tanggung jawab biduan itu sendiri. Sederhananya, “Kalau lu gak suka, jangan lihat.” Ketika tubuh menari seorang biduanita semakin dilarang, gerak mereka menjadi semakin erotis dan pakaiannya makin terbuka. Bahkan di era Inul hingga pasca-Inul, hampir setiap grup dangdut seksi siap tampil di pernikahan dan khitanan. Jadi, perang terhadap pornografi tampaknya merangsang, bukan mengekang.
Mari Berdangdut Ria!
Kenapa mesti dangdut? Musik-musik dangdut selalu dekat dengan penikmatnya. Diputar di mana-mana untuk menemani hati gundah dan lelah. Wajar jika dangdut mampu membawa penikmatnya ikut berdendang dan bergoyang. Iringan khas dan tidak lupa bagaimana biduanita memainkan perannya di panggung tidak dapat dipisahkan dari dangdut.
Pertarungan sebagian masyarakat terhadap tubuh perempuan dalam musik dangdut tentu bukan yang baru-baru ini terjadi. Dengan berbagai kontroversi dan kecaman dari berbagai kalangan, eksistensi dangdut tidak pernah pudar hingga hari ini. Dunia perdangdutan tidak akan bisa lepas dari tubuh perempuan dan goyangan. Boleh saja biduanita menjadi objek seksual bagi para penontonnya, terutama laki-laki, apalagi di era Inul. Namun menariknya, tanpa disadari, biduanitalah yang berhasil menghegemoni tubuh para penontonnya, tanpa peduli siapa mereka; rakyat, pejabat, tokoh masyarakat.
Dengan berbagai polemik dangdut, menjadikannya semakin liar dan gurih di telinga masyarakat. Tidak ada yang salah dengan wacana erotis dan kotor tentang dangdut, adalah hak masyarakat untuk menilai. Toh, yang penting saat dangdut menggema, semua boleh ikut bergoyang. Entah seluruh badan atau jari jempol saja.
Mari berdangdut, mari bergoyang!