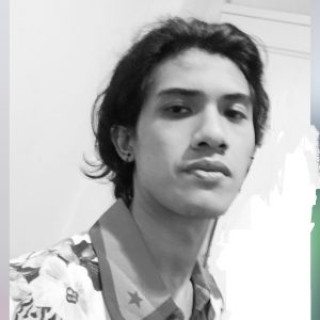Aku Bebas Maka Aku Tidak Bahagia: Sumber Kegelisahan Kehidupan Modern
Submisi Open Column dari H.S. Billy membedah arti kebebasan dan hubungannya dengan kebahagiaan di kehidupan modern.
Words by Whiteboard Journal
“Freedom is slavery”, begitulah ungkap George Orwell dalam novelnya berjudul 1984. Kebebasan malah membuat kita budak-budak kehidupan, seorang narapidana di dalam penjara yang lebih luas daripada institusi penjara itu sendiri. Bagi penulis, kebebasan adalah penjara paling mutakhir dan paling mengkekang. Ini yang menjadi fenomena menyedihkan ketika kita menonton film Shawshank Redemption (1994), dimana ada satu narapidana tua yang akhirnya bebas dari kekangan penjara. Namun saat berada di masyarakat dan mencoba mengalami kehidupan merdeka, ia malah gelisah dan tidak merasa nyaman. Suatu hari ia memutuskan untuk menghentikan hidupnya sendiri sambil menulis kalau ia pernah ada disini. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bukankah penjara mereduksi kebebasan individu, kenapa ia malah gelisah atas kemerdekaan yang ia terima? Kenapa pula ia menjadi tidak bahagia ketika mengalami hidup yang merdeka?.
Di dalam sebuah penjara, seorang narapidana akan mendapatkan ‘tuntunan’ hidup yang lebih terjaga. Ia diberi makan berpola setiap harinya, entah tiga kali atau dua kali sehari. Ia mempunyai jam tidur dan jam bermain, berinteraksi dengan sesama narapidana kemudian memutuskan untuk bermain bola. Ketika terjun balik kepada kehidupan luar penjara, semuanya berubah. Seorang narapidana tidak ‘dilayani’ sebagaimana mereka dilayani di dalam institusi penjara, semuanya serba individual, tidak ada bimbingan pasti, dia hidup bebas tanpa suruhan penjaga maupun aturan-aturan hukum direktur institusi. Tahanan kemudian melihat bagaimana kehidupan tersebut menjadi sebuah penjara, penjara yang lebih luas, layaknya lautan tanpa ujung, mereka lelah untuk menggapai destinasi pelabuhan. Mungkin akan lebih baik jika mereka masih berdekam dipenjara, semuanya serba dilayani dengan pasti.
Kehidupan nampaknya tidak memberikan kita kebebasan yang benar bebas ‘sebebas-bebasnya’, apalagi di dalam masyarakat modern. Pikiran mengenai free will sayangnya direduksi kepada determinisme juga, segala pilihan bebas hidup kita sudah ditentukan dan merupakan pengaruh dari lingkungan eksternal, tidak ada yang benar-benar merdeka. Ambil saja contoh ketika kita melihat sebuah iklan, kita melihat tampilan visual makanan yang baru saja dipanggang, atau minuman dengan embunnya yang membuat dahaga kita membuas. Saat itu, meskipun kita tidak ingin makan, kita ‘dipaksa’ mengamini dan membeli produk tersebut, dengan iming-iming kita mempunyai kebebasan untuk membelinya. Kehidupan modern ini membuat kita terpenjara, meskipun tak ada borgol maupun jeruji yang nampak disekitaran mata.
Mengenai modernitas, penulis mendefinisikan hal ini dengan kemandirian manusia dalam berpikir dan bereksistensi. Kehidupan seperti ini adalah produk akal dan pergerakan pencerahan dari dunia ketuhanan menjadi dunia manusia-sentris. Pengetahuan ilmiah, teknologi, sumber daya manusia, dan sebagainya merupakan hasil dari manusia yang memisahkan diri dari konsepsi akan adanya dunia ‘luar’. Lihatlah kehidupan kita, bagaimana dukun dicemooh dan dunia kedokteran menjadi peran utama dalam problema kesehatan. Bagaimana alam dituntun sebagai objek penelitian ilmiah bukannya dinamika penciptaan sang maha mengetahui. Bagaimana uang disaring menjadi alat pertukaran di dalam dunia perekonomian, padahal ada keinginan untuk saling berbagi. Tapi kompetisi membuat kita materialistik dan mengenyahkan kebebasan individu untuk mengejar mimpinya sebagai tujuan kehidupan. Tapi ketika kebebasan itu diraih, kenapa manusia malah cenderung tidak bahagia?
Jean-Paul Sartre melihat kebebasan manusia sebagai kemuakkan kehidupan di dalam modernitas. Ia beranggapan kalau kita dikutuk untuk bebas, ini diraih dari konsepsi bahwa tuhan itu sebenarnya tidak ada, setidaknya belum benar-benar ada secara nyata dan nampak di dalam ruang dan waktu. Akibat dari ketiadaan tuhan, manusia menjadi bebas ‘sebebas-bebasnya’ tanpa ada sesuatu yang memaknai hidupnya. Meskipun ini merupakan kabar baik bagi perkembangan manusia, kebebasan ini malah menuntut ketidakbahagiaan dan menghilangkan kebaikan. Ketika tuhan atau entitas tertinggi itu tidak ada, maka manusia mengalami kesulitan untuk menciptakan nilai-nilai bagi dirinya sendiri. Manusia menciptakan budaya, bahasa, hukum, norma moral, dan nilai-nilai lainnya sebagai pegangan di dalam hidupnya yang merdeka. Tapi karena tidak ada nilai utama atau tuntunan pasti, semua hal tersebut menjadi relatif, hukum bisa berubah setiap jaman, budaya bisa mencampur aduk seperti di Jakarta. Fenomena kontroversi RUU yang ramai di tolak masyarakat merupakan perwakilan nilai-nilai relatif manusia yang tidak mempunyai kungkungan pasti terhadap kehidupan. Inilah modernitas, dimana semuanya serba bebas tapi tidak menentukan mana yang pasti dan tepat untuk membuat kita bahagia.
Tapi kenapa bisa kebebasan itu sendiri menjadi sumber kegelisahan dan ketidakbahagiaan bagi seorang individu? Mengenai kutukan kebebasan manusia, Soren Kierkegaard menelanjangi ‘dosa asal’ nabi Adam sebagai fenomena pertama ketidakbahagiaan dalam sebuah kebebasan. Tuhan melarang nabi Adam untuk memakan apel surga, larangan ini bersifat perintah pasti dari sang maha kuasa tapi hal tersebut malah menawarkan sang nabi sebuah kebebasan untuk memilih, mengamini perintah atau melakukan larangan. Tindakan memilih ini merupakan elemen kebebasan seseorang individu untuk melaksanakan kebahagiaanya. Sang nabi dikutuk untuk memilih, dan ia menentukan pilihan yang membuatnya menderita. Ketidakbahagiaan itu bisa disematkan bukan pada konsekuensi pilihannya tapi ketidak-tahuan apa yang tepat baginya, apakah ia akan mendapatkan apa yang diinginkan dengan memilih taat? Ia tidak tahu, karena itu ia harus memilih untuk mencari keinginannya. Sama seperti di dalam kehidupan modern, kebebasan dalam memilih membuat kita gelisah, apakah dengan masuk Universitas Indonesia kita akan mendapatkan pengajaran sastra yang lebih baik dari universitas di luar negeri, atau kegelisahan dalam menentukan mana seorang wanita yang akan menghantarkan kebahagiaan padanya di hari esok. Karena kita bebas, kita tidak mempunyai suatu bimbingan pada pilihan yang tepat, kegelisahan datang menghampiri dan penderitaan menjadi hasil yang pasti.
“Anxiety is the dizziness of freedom”, ucap Kierkegaard dalam memakani sebab kegelisahan di dalam kebebasan individu. Pikiran berlebih, dan depresi akut menjadi akibat dari kebebasan yang memusingkan. Ketidakbahagiaan muncul dari sifat manusia itu sendiri yang bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada jeruji, tidak ada borgol di tangan kita, lalu kita sendirian untuk menentukan pilihan hidup yang tepat. Kita memasuki sekolah untuk mendapatkan nilai-nilai kehidupan dan bermimpi menjadi figur kebanggaan nasional, tapi karena kita mempunyai kebebasan untuk bermimpi, apakah kebahagiaan itu otomatis hadir ketika mimpi itu terwujud menjadi nyata?. Pertanyaan-pertanyaan “apa yang kau lakukan setelah kau lulus?” menjadi kegelisahan tersendiri diantara mahasiswa, ia terbebas dari penjara institusi universitas lalu hidup sebagai orang merdeka. Tapi kebebasan itu malah menghimpit kebahagiaan, karena ia tidak tahu harus kemana, apakah ijasahnya akan diterima cuma-cuma. Anxiety pun muncul kepermukaan, pikiran-pikiran genit nan mengerikan menghantui kehidupan seorang remaja. Sekali lagi karena ia terlalu bebas, ia tidak tahu destinasi mana yang pasti baginya. Ia akan menyesali tindakannya kemarin hari, atau mengharap esok akan lebih baik daripada hari ini, tapi toh kita tidak tahu besok akan seperti apa, kehidupan lebih bebas dari apa yang kita kira, lebih tidak terprediksi, maka dari itu kita akan gelisah.
Sartre dan Albert Camus merumuskan hasil dari ketiadaan tuhan dan kebebasan manusia ke dalam absurditas. Kita hidup di dalam dunia tanpa jawaban dan tuntutan pasti, tapi manusia dengan kebebasannya ingin mendapatkan hal tersebut. Pertempuran itu dianggap absurd karena seperti menabrak tembok. Pencarian jawaban di dunia tanpa jawaban membuat manusia menjadi makhluk paling absurd. Maka ketika manusia meyakini bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menyusun tujuan hidupnya, ia berpaling pada pilihan bebas lainnya yakni kematian (bunuh diri). Saking kita bebasnya, terkurung dalam penjara paling luas, terombang-ambing di samudra tanpa daratan, membuat individu lelah dan mencari jawaban di alam ‘lain’. Sebenarnya manusia tidak ingin bebas sebebas-bebasnya, ia ingin terikat pada kebenaran dan kepastian. Dunia ini tidak memberikan apapun mengenai keduanya, dan manusia dikutuk untuk bebas memilih kematian. Banyak artis-artis sukses di luar sana yang lebih memilih untuk berpulang dengan sengaja. Ini merupakan tanda bahwa sukses bukan berarti sebuah kebahagiaan, kita mencari kebahagiaan itu seolah-olah tujuan akhir dari segalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap kutukan kebebasan ini?
Menurut penulis, langkah awal yang cukup baik adalah penerimaan kalau kebebasan itu bukan fasilitas menuju kebahagiaan. Manusia yang bebas bisa disamakan dengan manusia yang merana, karena tidak ada bimbingan pada kebenaran, seperti bayi yang dilepas di gurun pasir, kita hanya bisa menangis. Nietzsche menyarankan agar kita tidak pasif dalam penerimaan bahwa semuanya merupakan hal yang sia-sia. Meskipun tidak ada jalan pasti dan nilai-nilai objektif di dalam kehidupan, kita harus aktif dalam menciptakan nilai-nilai relatif. Kita tidak perlu mencari apapun yang ‘benar-benar’ pasti, apapun yang cukup atau good enough dapat membuat kita ‘terkurung’ dengan nyaman. Budaya, hukum, moral dan nilai-nilai relatif lainnya diciptakan untuk membimbing kita dari dunia yang terlalu bebas. Meskipun ada kesalahan dan kecacatan dalam hukum, kita sebaiknya memperbaiki karena sifat relatif tersebut hadir untuk mencari kecukupan yang baik.
Mengenai kegelisahan dalam memilih, Sartre memberikan saran untuk tidak melihat pilihan-pilihan tersebut sebagai batasan. Ketika seseorang bebas memilih apa yang ada didepannya, dia harus menciptakan sesuatu dari pilihannya tersebut. Kebebasan tersebut bukan lagi sebuah tindakan memilih tapi menciptakan. Contohnya ketika seorang remaja harus memilih pasangan yang cocok baginya; wanita berparas cantik tapi materialistik, atau wanita berparas sederhana tapi baik hati. Remaja itu tidak boleh terpatok dengan batasan pilihan yang tersedia, ia harus menciptakan makna dan fungsi bagi dirinya sendiri. Jika ia bisa menciptakan kebahagiaan dari pilihan wanita cantik materialistik tersebut, maka ciptakanlah!. Meskipun ia akan menyadari bahwa ia akan menderita, tapi ketika ia mendapatkan kebahagiaan dari pilihan tersebut, maka tidak masalah. Toh, belum tentu juga ia mendapatkan kebahagiaan yang lebih berarti jika ia memilih wanita berparas sederhana, belum tentu kebaikan si wanita akan membuat si remaja lebih bahagia. Ciptakan lah nilai-nilai tersendiri dari setiap pilihan tersebut, jangan terbatasi oleh kriteria pilihan-pilihan yang tersedia.
Kierkegaard memiliki sarannya tersendiri atas kegelisahan manusia karena kebebasan tersebut. ia menyarankan individu untuk melakukan Leap of Faith. Manusia harus percaya pada imannya, bukan pada akal yang memikirkan kebebasannya. Meskipun ini bernada agamis tapi loncatan iman tersebut bisa menjadi senjata penumpas penderitaan. Gejala-gejala modernitas membuat kita bebas menentukan apa yang kita mau, tapi kita tidak tahu apakah pilihan kita menuntun pada kebahagiaan. Menurut Kierkegaard, jangan terlalu berpikir, loncatlah dan ambil keputusan yang berdasarkan dari iman. Ia menyarankan agar individu percaya bahwa tuhan memiliki esensi di dalam setiap individu, dengan mempercayakan pada imannya, dia telah menghilangkan keraguan atas kebebasan yang telah dikutuki.
Saran terakhir berasal dari pikiran Alber Camus. Ia menyuruh individu untuk merefleksikan diri di dalam mitos Sisifus. Dewa ini telah dikutuk untuk menggiring batu besar dari lembah ke atas puncuk gunung, hanya untuk mendapati bahwa batu tersebut turun lagi seketika. Sisifus terus mengulangi perjalanannya entah sampai kapan. Bagi Camus, kita adalah Sisifus, melakukan pengulangan setiap hari dan terjebak pada kebebasan dirinya sendiri. ia juga menyarankan kepada pembaca untuk membayangkan bahwa Sisifus bahagia menjalani kutukannya. Saran inilah yang sedang diproklamirkan kepada setiap individu. Kita harus menerima bahwa kebebasan ini merupakan sebuah kutukan dan dapat membuat kita menderita. Anggaplah penggiringan batu tersebut menjadi tuntunan hidup bagi kita semua dan merupakan tujuan hidup yang good enough. Hukum, norma, pekerjaan, pernikahan, moral, mimpi, hasrat adalah batu yang mesti kita giring untuk mencapai kebahagiaan. Terima lah semua itu sebagai nilai-nilai yang berguna di dalam kehidupan, meski semuanya relatif, belum tentu sifatnya palsu atau tidak membahagiakan. Barangkali kita butuh jeruji untuk menghindari kebebasan yang berlebih, dan hal-hal tersebut adalah jalan keluarnya.
Kita tidak akan bebas dari kebebasan itu sendiri, karena nampaknya kita butuh sebuah borgol untuk memantapkan diri bereksistensi di dunia. Kegelisahan dan pikiran yang terlalu menumpuk disebabkan karena kita tidak mampu menerima batasan kita sendiri untuk mencari jawaban pasti di dunia yang sama sekali tidak memberikan jawaban. Pilihan bebas di dalam dunia ini tidak ada yang menuntun kita pada kebahagiaan utama, tapi dengan kebebasan itu kita bisa menciptakan kebahagiaan kecil dan relatif demi bisa bertahan hidup dengan senyuman. Harapan-harapan akan hari esok merupakan hasil dari bebasnya manusia berpikir, dan menjauhkan dari aktualitas di sekitaran realitas. Kebebasan bukan satu-satunya sumber ketidakbahagiaan, ia merupakan sebagian dari itu, ada hal-hal lain yang mengutuk kita untuk menderita, yakni akal dan hasrat, mungkin di dalam tulisan lain, kita bisa membicarakan hal tersebut. Tapi setidaknya dengan tulisan ini, kita bisa sedikit mengurangi keinginan kita untuk bisa bebas ‘sebebas-bebasnya’ karena entah disadari atau tidak, kita membutuhkan penjara yang lebih kecil daripada kehidupan, kita butuh batasan, ujung perkara, dan kebenaran, meskipun semuanya merupakan hal yang relatif.