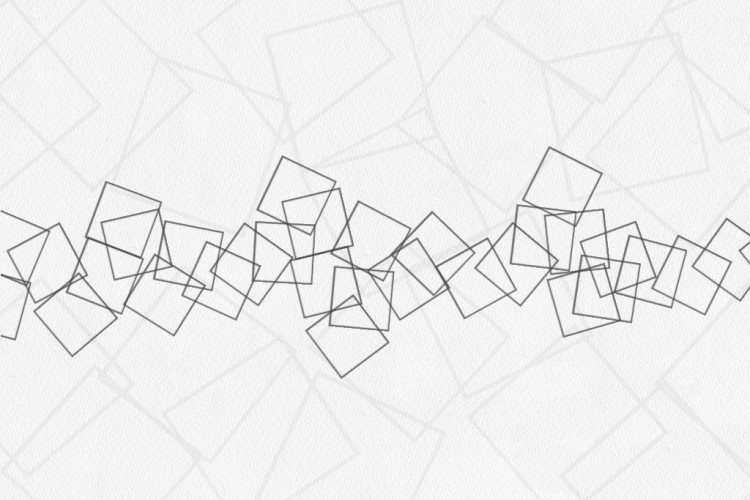“Belanja terus sampai mati” mungkin menjadi nosi yang tepat ketika melihat bagaimana warga kota menghabiskan uangnya saat ini. Saat lebaran, selain macet akibat buka bersama di rumah makan (hampir semua rumah makan ramai pengunjung saat magrib tiba), beberapa ruas jalan di Kota Bandung juga mengalami kemacetan akibat hadirnya pasar malam dadakan. Dadakan karena pasalnya, di waktu-waktu lain pasar ini sesungguhnya tidak ada. Sebutlah jalan Trunojoyo yang ramai oleh pemuda-pemudi, ataupun jalan Supratman (daerah dekat Pusdai) yang mulai gemerlap dan ramai oleh hiruk pikuk konsumerisme kelas menengah saat matahari tenggelam.
Kebanyakan dari pedagang menjual berbagai jenis pakaian yang sangat murah, mulai dari kaos polos seratus-ribu-tiga sampai sepatu KW lima-puluh-ribuan. Bagi sebagian dari kita yang biasa berbelanja di H&M ataupun Uniqlo, harga ini tentunya cukup mengherankan. Namun, sebagian dari kita itu juga akhirnya tetap memilih berbelanja di mall, kendati berbagai alternatif belanja yang muncul di kota ini.
Preferensi tersebut merupakan sebuah kewajaran. Daya beli dan selera membentuk pasarnya masing-masing. Kemudahan akses terhadap alat produksi dan barang jadi, juga memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memulai usahanya masing-masing. Implikasi dari kemudahan akses tersebut juga tercermin dalam akuisisi atas ruang, dimana kemampuan mengusahakan modal “sewa tempat” tidak merata di antara para pedagang ini. Munculnya pasar malam dadakan tersebut pada akhirnya merupakan realita dari konsep ekonomi sederhana: ada permintaan maka ada penawaran.
Urbanisasi dan Informalitas
Bandung saat ini begitu dikenal sebagai surga belanja berbagai jenis sandang, baik bagi warganya sendiri maupun pendatang dari luar kota. Kita bisa berbelanja murah meriah di Pasar Baru ataupun di Cihampelas. Jika mau yang lebih fancy kita bisa berbelanja di factory outlet yang tersebar di Jalan Riau. Daerah Sultan Agung dan sekitarnya kini terkenal sebagai kiblat belanja anak muda. Beberapa mall juga menawarkan alternatif belanja bagi kaum menengah ke atas, seperti department store semisal Matahari atau Sogo, serta retailer semisal H&M atau Uniqlo (yang baru muncul, akhirnya). Gabungkan daya tarik tersebut dengan berbagai kegiatan lainnya, seperti wisata kuliner, wisata leha-leha di taman kota, dan spot berfoto cantik, maka voila, jadilah Bandung sebagai magnet wisata yang begitu kuat.
Perdagangan dan jasa pada akhirnya menjadi tumpuan utama perekonomian Kota Bandung. Selayaknya kota yang bertumpu pada sektor non-agrikultur, penyerapan tenaga kerja menjadi semakin dibutuhkan dalam arus tersebut, di mana hal ini tentunya menjadi pulling factor tersendiri bagi para penduduk di daerah lainnya. Alhasil, tingkat urbanisasi di Bandung pun terus meningkat, dan menjadi tantangan baru bagi pemerintah kotanya. Ketidaksiapan dalam membendung fenomena tersebut menciptakan banyak masalah baru, seperti urban sprawl dan bentuk-bentuk ekonomi informal — seperti pertumbuhan jumlah PKL dan munculnya pasar malam yang menjadi bahasan di awal tadi. Fenomena “informalitas” dalam lingkup belanja sandang seringkali dipandang sebagai sebuah bentuk masalah yang harus diatasi. Namun, bagi beberapa khalayak, pada “informalitas” tersebut pula mereka menggantungkan hidup, plus harapan rezeki lebaran.
Dari Tren Kontemporer menuju Urbanisme Temporer
Keberadaan pusat perbelanjaan seperti mall, factory outlet, ataupun distro di Kota Bandung (idealnya) merupakan hasil dari pembangunan terencana. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ataupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kita dapat melihat bahwa secara struktur kota, terdapat daerah-daerah yang dikhususkan menjadi tempat berbelanja. Hal ini dimaksudkan agar satu kegiatan tidak mengganggu kegiatan lainnya, dan supaya fungsi kota secara keseluruhan dapat terintegrasi.
Munculnya pasar dadakan yang disinyalir bukan merupakan sesuatu yang direncanakan, dapat disimpulkan sebagai sebuah inisiatif kolektif dari para pelaku (pedagang) di dalamnya. Kesadaran akan perlunya belanja alternatif dengan harga murah dan pilihan yang banyak membuat para pedagang memanfaatkan berbagai kemungkinan sebaik mungkin, contohnya membuka lapak di trotoar ataupun membuka bagasi mobil lalu disulap menjadi etalase mini. Dimulai dari adanya inisiatif tersebut, secara keseluruhan, budaya berbelanja pun menjadi tidak biasa (tidak formal). Jika di mall, pilihan kita bisa saja terbatas pada harga yang sudah tertera pada tags, namun berbeda halnya dengan berbelanja di pasar dadakan tersebut, peluang tawar menawar harga masih memungkinkan (meski harganya sudah sangat jauh lebih murah dibandingkan di mall).
Konsep temporary urbanism yang sempat diurai oleh Megumi Koyama dalam “Can Temporary Urbanism be a Permanent Solution? Urban Spaces in Liquid Times,” menjadi sebuah konsep yang relevan dalam fenomena ini. Adanya aktor-aktor individu dan kolektif, pemanfaatan ruang sementara, serta dampak kultural yang dihasilkan, menandakan bahwa kita dihadapkan pada bentuk alternatif, baik dalam konteks pembangunan maupun bisnis. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks berkontribusi terhadap terciptanya hal ini, dengan wacana globalisasi dan urbanisasi yang menjadi katalisnya.
Masyarakat kontemporer yang terdiri dari berbagai strata sosial dan ekonomi, dengan berbagai selera dan daya beli terhadap barang dan jasa, membentuk sebuah atmosfer pasar yang tidak bisa terpaku oleh satu jenis produk, atau bahkan sebuah monopoli dari hal tersebut. Hal ini berdampak pada kuasa yang terbentuk secara organik, yang bergerak secara kecil, tersebar, dan terdesentralisasi. Resiko atau dampak lanjutan dari fenomena tersebut menjadi resiko bagi masing-masing individu yang beroperasi di dalamnya.
Terpecahnya bentuk kuasa yang formal, tersentralisasi dan lebih dominan secara hierarkis ini memberikan peluang terbentuknya bentuk alternatif ini. Alih-alih menunggu terciptanya ruang bagi mereka (oleh pihak yang bertanggung jawab, seperti perencana), mereka memodifikasi ruang yang telah ada, dan pada akhirnya menciptakan ruang mereka sendiri. Koyama mengutip Appadurai dalam tulisannya:
“…if we recognise that ordinary human beings have significant capacities to plan and design their own futures, we will find stronger connections between our ideas and the values and motives of those whom we actually claim to serve and to represent.”
Kreativitas yang muncul dalam proses ini juga menjadi elemen yang penting, terutama dalam proses city-making secara keseluruhan. Seperti yang dijelaskan Charles Landry, bahwa kreativitas diperlukan dalam menciptakan narasi dan membentuk identitas kultural dimana sekarang ini kota menjadi semakin homogen.
Tren sandang kontemporer, baik dari segi produk ataupun cara mendapatkan produk tersebut (baca: shopping), pada akhirnya tidak hanya terefleksikan dari majalah fashion, lookbook, ataupun etalase di mall saja, tapi juga dalam bentuk lapak terpal di trotoar, teriakan promosi dari pedagang, serta etalase kompartibel di mobil. Mengesampingkan privilege dan pride dengan memakai barang bermerek dengan harga yang menyesuaikan, tren selalu bisa direka-reka dengan kreativitas individu dan kolektif, dan dengan harga yang sangat menyesuaikan (baca: murah pisaaaan).
Bagi kita yang menilai bahwa pasar dadakan yang telah dibahas merupakan sebuah masalah, mengumpat karena menimbulkan kemacetan, mungkin kita harus melakukan refleksi kembali tentang bagaimana masyarakat kita sekarang terbentuk dan berevolusi. Bukan semata-mata menghilangkan apa yang telah ada, namun perlu adanya intervensi yang lebih strategis terhadap fenomena ini, agar semua pihak juga merasa nyaman dan adil. Hal ini terutama ditujukan bagi pemerintah yang nampaknya juga tidak mengambil tindakan apa-apa — atau mungkin sedang terlalu sibuk mengurusi pengamanan mudik lebaran. Karena seperti yang ditulis oleh Koyama:
“A successful urban planning will therefore incorporate elements of creativity, not only at the moment of implementation, but also thereafter, providing its citizens a capacity to self-organise and enhance its own local cultures.”
“Urbanisme Temporer” ditulis oleh:
Naufal Rofi Indriansyah
Mahasiswa S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung yang aktif menulis tentang permasalahan urban.