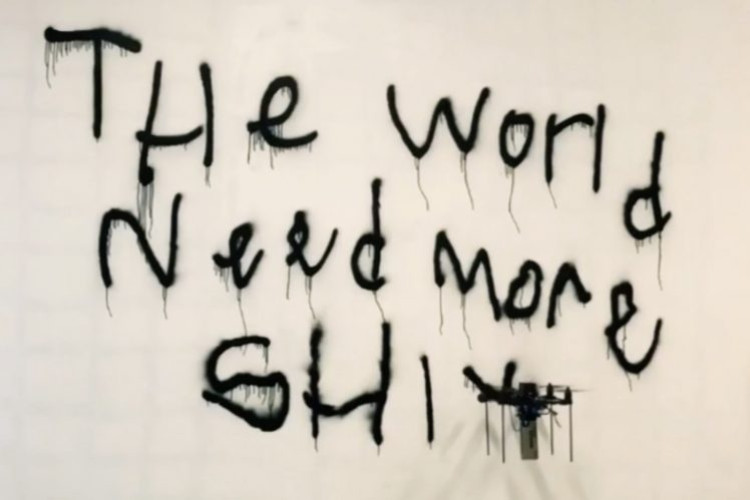Jakarta Biennale 2024: Pemaknaan Seni dan Kolektif yang Memancing Tanda Tanya
Jakarta Biennale kembali untuk iterasi terbarunya di 2024 dengan membawa tema “lumbung” dengan ketajaman kolektivitas komunitas. Meski begitu, terma “kolektif” di sini seperti terjebak dalam usahanya mendefinisikan kesatuan yang dimaksud.
Words by Whiteboard Journal
Teks: Ibrahim Soetomo
Foto: Jakarta Biennale
Desember 1974. Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyelenggarakan Pameran Besar Seni Lukis Indonesia. Delapan puluh tiga pelukis ikut serta, lima di antaranya meraih penghargaan lukisan terbaik. Tak hanya pameran besar, DKJ merintisnya menjadi peristiwa biennale, tiap dua tahun. Lima puluh tahun kemudian, kita memperingati peristiwa itu dengan Jakarta Biennale 2024. Lima puluh hari untuk lima puluh tahun.
Namun istilah “biennale” sendiri baru muncul di ajang yang kelima, Pameran Biennale V, 1982. Komite Seni Rupa DKJ tak lagi memilih lukisan terbaik melalui penjurian, melainkan mengundang pelukis berdasarkan timbangan umur, keberlanjutan dan inovasi berkarya. Setelahnya, biennale terus mencoba format berbeda. Skalanya menjadi internasional sejak 2009. Jakarta Biennale XIII: Arena tahun itu tak hanya menampilkan karya jadi di ruang pamer, tapi juga proyek-proyek seni dan intervensi artistik di ruang-ruang kota. Lalu, Yayasan Jakarta Biennale terbentuk pada 2014. DKJ yang tadinya penyelenggara menjadi konsultan, pembina dan pengawas. Ada sembilan belas biennale Jakarta sejak Pameran Besar Seni Lukis Indonesia 1974, meski pada akhirnya tak selalu dua tahun sekali.
Oktober 2024. Jakarta Biennale 2024 menghadirkan sosok baru: Majelis Jakarta. Dua puluh kolektif dan entitas seni di Jakarta tergabung di dalamnya. Dalam urutan alfabetis, mereka adalah Asosiasi Pematung Indonesia – Jakarta, Atelir Ceremai, Binatang Press!, Cut and Rescue, DKJ, Galeri Saku Kolektif, Girls Pay the Bills, Gudskul Ekosistem, Jakarta Wasted Artists, Kelas Pagi Indonesia, Komunitas Paseban, PannaFoto Institute, RajutKejut, Sanggar Anak Akar, Sanggar Seroja, Sekolah Sablon Indonesia, Serrum ArtHandling, Setali Indonesia, TrotoART dan Westwew. Sebelum pameran, Majelis Jakarta sudah mengadakan setidaknya dua kali pertemuan yang membahas imajinasi bersama tentang biennale mendatang, sembari memetakan sumber-sumber daya seni dan menggalang dana. Ada pula kolaborator, yaitu Topography of Mirror Cities, Baku Konek dan Majelis Palestina.
Jakarta Biennale 2024 mengusung konsep “lumbung.” Kita telah mendengar istilah ini secara lebih massal di ranah kesenian sejak Gudskul Ekosistem resmi dibentuk di Jakarta pada 2018, lalu ketika ruangrupa menjadi direktur artistik documenta fifteen, Kassel, pada 2022. Meminjam kosakata agraria, lumbung adalah wadah kolektif bagi segala sumber daya individu maupun kelompok untuk ditabung dan dikelola bersama. Ruang tafsirnya lebar dan likuid, karena lumbung juga “ruang tamu,” simpangan bagi tiap entitas dan identitas untuk berekspresi dan bereksplorasi. Dengan lumbung, Jakarta Biennale 2024 mengumpulkan lalu mendistribusikan sumber daya dan kerja pada kolektif, entitas, dan kelompok masyarakat di berbagai wilayah Jakarta yang menurutnya telah mempraktikkan kerja lumbung, disadari atau tidak. Kita sedang menyaksikan terbentuknya superkolektif, sebuah kolektif besar berisi kolektif-kolektif, yang di dalamnya juga ada kolektif berisi kolektif-kolektif, misalnya Gudskul Ekosistem. Kolektif, berisi kolektif, berisi kolektif.
View this post on Instagram
Tiap-tiap kolektif Majelis Jakarta diberi peran untuk mengelola pameran atau programnya di Jakarta Biennale 2024. Seandainya kita datang ke sana, kita akan lihat beberapa subpameran dari tiap kolektif dengan kuratorial dan pemilihan seniman tersendiri. Galeri Saku Kolektif dan Girls Pay the Bills adalah contohnya. Hanya saja, beberapa kolektif-pengelola tersebut adalah mereka juga yang memamerkan karyanya. Inilah kebingungan kita yang pertama. Siapa pengelola, dan siapa senimannya? Ya, tak ada aturan baku yang melarang barang siapa yang mengelola untuk turut menghadirkan karyanya di sebuah kegiatan yang ia kelola. Kerap kita jumpai karya tulis seorang penyunting di sebuah antologi yang ia sunting. Namun ini soal kredibilitas, etika barangkali, dalam sebuah kerja kuratorial. Pada Biennale sebelumnya, kita menjumpai sosok direktur artistik dan kurator. Direktur artistik adalah ia yang umumnya menentukan visi dan gagasan artistik besar biennale menjadi tema pameran, lalu kurator adalah ia atau mereka yang memilih karya dan seniman berdasarkan tema besar tersebut. Ketiga biennale itu memiliki visi artistik yang Jakarta Biennale 2024 tak miliki, atau nyatakan dengan terang, selain tawaran suatu metode dan struktur keorganisasian yang berbeda, jika bukan “baru.” Atau, metode itulah visi artistiknya, karena pengelolaan kegiatan seni adalah karya artistik khas kolektif seni yang berkembang sejak munculnya artist’s initiative setelah Reformasi. Jakarta Biennale 2024 tampak menghendaki yang rimpang, menghapus hierarki top-down di biennale-biennale sebelumnya dengan kolektivisme yang fungal dan horizontal. Relevan, dan aktual. Hanya saja, proses dan hasil musyawarah yang dicita-citakan dan dikesankan sebagai ruang terbuka dan raya justru terasa tertutup. Saya rasa penting bagi Jakarta Biennale 2024 untuk menampilkan seksi kuratorial khusus Majelis Jakarta, sebagai sebuah entitas baru, yang terpisah dari pameran-pameran tiap anggotanya; sebuah seksi yang memaparkan hasil panen majelis sejauh ini, cita-citanya, strateginya, serta hubungan kerja dengan ketiga kolaborator lainnya. Isi pameran yang ada kini lepas tak berpijak.
Terlepas dari situasi ini, majelis adalah upaya menyiasati tantangan keberlanjutan organisasional dan finansial. Biennale, sebuah ajang nonprofit, tak bisa terus menerus menjamin kepastian dana—dari pemerintah provinsi Jakarta, swasta, lembaga donor lain—untuk mengadakan pameran akbar tiap dua tahun sekali. DKJ sudah menyampaikan kendala anggaran ini sejak Pameran Besar Seni Lukis Indonesia 1974, sementara pelukis-pelukis di luar Jakarta kala itu terus bermunculan, tak terjangkau. Majelis Jakarta, dengan lumbung dan kurasi kolektif, mengajak kita mengimajinasikan biennale sebagai sebuah ajang evolutif di mana pertukaran yang berkelanjutan dapat terjadi atas peran para sumber daya seni yang ada, baik yang berwujud (tangible)—ruang, bahan, sarana—dan tak-berwujud (intangible)—bibit bakal, kepakaran, pengalaman; sebuah “nilai tukar” yang lain, meski sukar kita takar di lapangan, lantas harus terus diuji dan dievaluasi. Kita pun harus amat berhati-hati agar tidak bersikap eksploitatif dan ekstraktif terhadap kerja-kerja tersebut. Jalannya panjang, dan kita senantiasa mengibas kabut, karena Jakarta Biennale adalah lembaga, seberapapun ia selalu terbentuk dari inisiatif pelaku seni Jakarta, dan bukan pemerintah kota. Dengan demikian, Jakarta Biennale 2024 sedang menawarkan sesuatu yang ia sendiri belum tahu hasilnya. Salah satu upaya turunan Majelis Jakarta adalah menjadikan biennale sebagai ajang berkembang. Dalam durasi lima puluh hari, ada aktivasi ruang atau penempatan karya baru walau ia kerap muncul tetiba, nyaris tak berkabar. Majelis pun tak akan berakhir ketika pameran berakhir. Biennale tetap bisa jadi perayaan penting meski tak harus jadi blockbuster.

Credits: Jakarta Biennale.

Credits: Jakarta Biennale.

Credits: Jakarta Biennale.

Credits: Jakarta Biennale.

Credits: Jakarta Biennale.
Jakarta Biennale 2024 kembali ke Taman Ismail Marzuki (TIM), sebuah pusat seni yang didirikan pada 1968 dan direvitalisasi pada 2022. Yang perlu kita catat, ia kembali ke galeri seni sebagai ruang pameran konvensional dalam selingkung ekologi pusat seni, setelah empat biennale sebelumnya menjelajahi museum sejarah (Esok, 2021), bekas gudang (Maju Kena Mundur Kena, 2015 & Jiwa, 2017), dan ruang parkir bawah tanah TIM sebelum masa revitalisasi (Siasat, 2013). Biennale kali ini menggunakan tiga galeri TIM baru: Galeri Emiria Soenassa, Galeri S. Sudjojono, dan Galeri Oesman Effendi, untuk mempresentasikan karya-karya Majelis Jakarta, Topography of Mirror Cities dan Baku Konek, serta beberapa titik di luar galeri untuk karya-karya yarn bombing RajutKejut, sebuah komunitas yang membuat ragam karya dan kegiatan rajut dengan keanggotaan yang bersifat longgar.

Credits: Jakarta Biennale.
Memasuki Galeri Emiria Soenassa, kita menjumpai karya Puji Lestari (Gunung Kidul, Yogyakarta) dengan kolaborator Alyakha Art Center (Sentani, Papua) sebagai bagian dari program Baku Konek. Judulnya Tom dan Regi (2024). Pada selembar kulit kayu, dua sosok manusia tampak ingin memeluk satu sama lain. Di antara keduanya ada bentang hutan warna-warni, dua bangunan gereja, dan seekor kasuari raksasa. Puji Lestari, seorang penyandang disabilitas tuna daksa, belajar melukis secara otodidak. Kanvas-kanvasnya menceritakan pengalaman dan perjalanan hidupnya. Sedangkan Alyakha Art Center adalah sebuah wadah seni dan budaya yang ingin mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan kesenian lokal Papua, salah satunya dengan melibatkan generasi muda Papua untuk mempelajari kembali kesenian tradisi dan identitas budayanya. Alyakha Art Center mengadakan kegiatan belajar bersama budayawan lokal, pameran, dan pertunjukan, dengan sejumlah fokus isu seperti pembalakan liar, pencemaran air Danau Sentani, dan isu sosial setempat.
Selama bermukim, Puji Lestari mengamati budaya lokal Sentani yang luhur, berbeda dengan daerahnya di Gunung Kidul. Ia bertemu dengan pelaku-pelaku seni yang antusias di tengah kekayaan sumber alam yang mendukung, meski dukungan dan kepedulian pemerintah tentang ruang-ruang seni masih amat minim. Ide berkarya di atas kulit pohon kanvas muncul setelah setelah Puji Lestari bergiat bersama komunitas ini. Tiba waktunya Puji Lestari berpisah, dan ingin ia lukiskan jalinan kebersamaan selama masa bermukim. Ia menamai lukisannya “Tom dan Regi,” karena cerita tersebut sangat populer di kalangan masyarakat Papua. Tom dan Regi adalah oleh-oleh masa mukim yang sederhana, tulus, tanpa beban.
View this post on Instagram
Lalu ada Gandhi Eka. Ia menjalani masa residensinya di Riwanua, Makassar, sebagai bagian dari Baku Konek. Gandhi Eka memasuki dunia seni rupa melalui komik. Ia menginisiasi Supergunz, sebuah studio desain dan ilustrasi musik dan merch band. Ia juga membuat komik, zine, dan art book. Sedangkan Riwanua Karya Bersama, lengkapnya, adalah sebuah kolektif di Makassar yang menerapkan kerja bersama dan percakapan lintas disiplin melalui berbagai program: penayangan film, pameran, hingga residensi. Di Baku Konek, Riwanua banyak menghubungkan Gandhi Eka pada komunitas yang fokus pada karst dan gua-gua prasejarah. Ada lima gua prasejarah dengan peninggalan lukisan dinding yang ia kunjungi: Leang Tedongnge, Leang Karampuang, Leang Uhallie, Leang Bulu Sipong IV, dan Leang Sumpang Bita. Dari jelajah itu Gandhi Eka bereksperimen dengan mineral hematit, sejenis besi oksida kemerah-merahan, sebagai salah satu pigmen yang digunakan oleh mereka manusia purba. Dari bahan itu, Gandhi Eka membuat ilustrasi dengan berbagai cara, dari mencetak anggota tubuh dengan metode sembur dari mulut, memural di dinding-dinding gua, hingga membuat ilustrasi di atas kertas, termasuk poster gigs, sebagai sebuah bauran antara praktiknya sebagai perupa dengan temuan-temuan residensinya. Baik mural di dinding gua maupun ilustrasi poster gigs sama-sama mengangkat ide tentang catatan zaman.

Credits: Jakarta Biennale.

Credits: Jakarta Biennale.

Credits: Jakarta Biennale.
Baku Konek merupakan program ruangrupa bersama Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (PTLK) melalui program Manajemen Talenta Nasional (MTN) Bidang Seni Budaya yang ingin mendorong seniman untuk berkolaborasi dengan dengan lingkungan serta masyarakatnya. Baku Konek bekerja sama dengan sebelas ruang, kolektif dan komunitas di Indonesia dengan keragaman konteks sosial, budaya dan geografis, terutama sebagai mitra residensi. Ada dua puluh tiga perupa individu dan kolektif yang terpilih untuk menjalani residensi selama lima minggu, 16 Agustus–20 September 2024.
Menuju ke tengah-tengah Galeri Emiria Soenassa, kita melihat sepetak kolam dengan sepotong batang pohon di tengah-tengah dan empat gedung mungil di tiap sudutnya. Sambil Menyelam Minum Air, Eh Keselek (2024) adalah karya “kolaborasi” Atelir Ceremai, Sun Community dan Onesys Vincent. Idenya adalah merespons karya pentas Sun Community berjudul Jejak: Parasit (2024), yang tak kita ketahui bentuknya karena tak ada dokumentasi pentasnya di pameran, yang membicarakan Jakarta sebagai kota rawan banjir sejak dahulu kala. Lalu, Onesys Vincent bergabung dengan menaruh beberapa karya trimatra di atas empat gedung mungil itu. Sambil Menyelam Minum Air, Eh Keselek merupakan ilustrasi gamblang yang menolak kita pahami. Dan sejauh saya menunaikan kunjungan beberapa kali, kolam itu—bukan “banjir”—selalu saja lesu dan keruh, motionless. Kita tak melihat kolaborasi yang padu dan bertemu, melainkan hasil kegiatan menyusun beberapa karya dari entitas yang berbeda jadi satu; semacam “seni-untuk-seni” berjubah kolaborasi.
***
Gesyada Siregar, dalam esainya Bagai Melihat Jalinan Ampang: Mencari di (ke) Mana Seninya dalam Praktik Kolektif di Indonesia dalam Mengeja Fixer 2021 (Yayasan Gudskul Studi Kolektif, 2021), menjelaskan kalau pameran kolektif-kolektif seni, sehubung mengedepankan aspek keorganisasian atau edukasi, kerap berbentuk “simulasi ruang tamu atau kerja, pseudomuseum, lembar-lembar pemetaan, hasil lokakarya, arsip, artefak, publikasi, foto dan video dokumentasi aktivitas yang telah mereka lakukan sebelum pameran, serta mengedepankan interaktivitas dan kolaborasi dengan pengunjung.” Sementara kita melihat bentuk-bentuk itu di sini, banyak pilihan medium yang tak maksimal, serta presentasi yang tak tergarap baik. Presentasi pameran inilah yang amat kurang di Biennale kali ini. Sebagian besar karya seolah bingung pada dirinya sendiri, tak jarang berebut ruang, atau saling membuyar perhatian. Ada teks keterangan dengan deskripsi umum, namun ia tak menjelaskan kategori kuratorialnya—mana bagian Majelis Jakarta, Baku Konek, Topography of Mirror Cities. Barangkali memang sengaja supaya rimpangnya terasa, tapi kita harus memahami bahwa ketiga kuratorial ini punya laju tanam, tumbuh dan tuai yang berbeda, sedangkan pameran ini seolah monokultur jadinya. Rasanya, tak akan jadi masalah jika ada seorang atau seunit direktur artistik, kurator, atau perancang pameran yang terpisah dan tak berperan ganda dalam ekologi Majelis Jakarta, yang berfokus mengerjakan dan mengawasi rancang dan citra pameran, selama ia bisa memusyawarahkannya di tiap-tiap temu majelis. Para perancang pameran inilah yang bisa menerjemahkan kerja-kerja kolektif yang berbasis pengelolaan—lantas durasional, aktif, hidup—menjadi suatu presentasi artistik dalam pameran–yang kerap statis, lantas harus mandiri. Tak harus menjadi kolektif untuk berpikir kolektif, karena pameran ini memperlihatkan bahwa nyatanya kolektif juga berpeluang mengindividu dirinya. Hal ini sedikit banyak mengakibatkan ide dan kegiatan kolektif seni menjadi niche, terdisiplin, berjarak, seberapapun kita anggap bahwa bentuk-bentuk kerja bersama, layaknya gotong-royong, majelis, musyawarah, komunitas, silaturahmi, pesta rakyat dan lainnya, menubuh di keseharian masyarakat.

Credits: Jakarta Biennale.

Credits: Jakarta Biennale.

Credits: Jakarta Biennale.

Credits: Jakarta Biennale.
Seorang atau seunit direktur artistik, kurator, atau perancang pameran inilah yang akan menyiasati tantangan ruang. Gedung-gedung TIM baru adalah bangunan serba-guna (mixed-use). Perancangnya menyiapkan galeri tak hanya untuk pameran seni, tapi juga bentuk ekspo-ekspo lain. Dinding tepi kanan dari pintu masuk Galeri Emiria Soenassa berbilik-bilik, dan tiap-tiap seniman yang memajang karyanya di bilik-bilik itu seolah menjadi tenant yang mengisi booth-booth sebuah ekspo. Sedangkan Galeri Oesman Effendi adalah kubus putih beratap julang dengan lorong gelap yang mengitari bangunan ke lantai atas. Perancangnya mungkin membayangkan bahwa langit-langit ini bisa digunakan untuk memajang karya-karya seni instalasi gantung. Konsekuensinya, ia menyusutkan dan menenggelamkan karya-karya dinding yang dipajang di ketinggian mata, sebagaimana yang terjadi pada karya-karya kuratorial Topography of Mirror Cities.
Galeri Saku Kolektif (2020) dapat menyiasati lorong gelap di Galeri Oesman Effendi itu. Galeri Saku terdiri dari sejumlah mahasiswa/i dan lulusan Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta, yang kini bergiat sebagai seniman, kurator, pengelola program dan penangan karya seni—paket lengkap untuk mengadakan pameran dalam pameran di Jakarta Biennale 2024. Kini Galeri Saku punya dua fokus, yaitu berkolaborasi dengan seniman pendatang baru asal Jakarta, dan bergiat di ruang-ruang yang umumnya tak kita gunakan sebagai tempat berpameran. Setelah melihat lorong gelap bersiku itu, Galeri Saku menemukan jodohnya.
Galeri Saku terlebih dahulu menerima kenyataan bahwa lorong selebar 120 cm minim cahaya di galeri itu, yang mereka sebut “labirin,” tidak punya maksud jelas selain mengantar pengunjung naik ke sepetak balkon di atas untuk melihat pameran dari sana. Galeri Saku juga mengamalkan lumbung dengan cara yang tak kita duga, yaitu “lumbung portofolio” seniman-seniman muda di kitaran mereka. Dari lumbung itu, Galeri Saku memilih karya atau seniman muda yang punya tema tentang “ruang” sebagai kerangka kuratorial pamerannya, Labirin; 120 (2024). Salah satunya adalah karya sugar aquatint Valerie Averina Wijaya, Liminal Boundaries (2024) yang sengaja disenderkan di salah satu sudut liminal di lorong itu. Galeri Saku juga mengundang dua seniman komisi, yaitu Nico Trisnando, dengan karya-karya stensil alat-alat penanganan karya seni—meteran, bor, troli perkakas, dan lainnya—yang bermain-main di dinding dan sudut lorong, dan Narpati Kusumayudha, dengan performance Ruang Tumbuh (2024) yang cenderung teatrikal. Labirin; 120 membuat sudut dan siku di lorong Galeri Oesman Effendi lebih bermakna.
***
Di Jakarta Biennale 2021, kita membayangkan “Esok” sebagai “apa yang kelak datang.” Di tengah berbagai isu global, polaritas politik kiri-kanan, krisis iklim, lalu didorong oleh pandemi COVID-19, kita menyadari pentingnya kerja bersama, kebersamaan dan kemajemukan sebagai bentuk solidaritas dan resiliensi terhadap suatu krisis. Dan kerja bersama adalah daya yang terus menghidupi Jakarta Biennale, disertai dengan terus bermunculannya pelaku dan ekosistem seni baru, tahun demi tahun. Jakarta Biennale selalu diharapkan dapat menjadi ruang silaturahmi bagi seniman, aktivis, akademisi dan warga, dengan kota sebagai ruangnya. Rasanya ini yang belum tercapai pada gelombang pertama Jakarta Biennale 2024. Yang kita pelajari dari periode ini adalah formalisme kolektif: bentuk, metode, diagram, peta, pola, etalase, self-sustainability, seberapapun ia bertolak dari narasi-narasi di luar dirinya. Sukar mendeskripsikan Jakarta Biennale kali ini, karena ia sendiri sedang mencoba deskripsikan dirinya sendiri. Kita nantikan bagaimana ia berkembang dan menjadi.