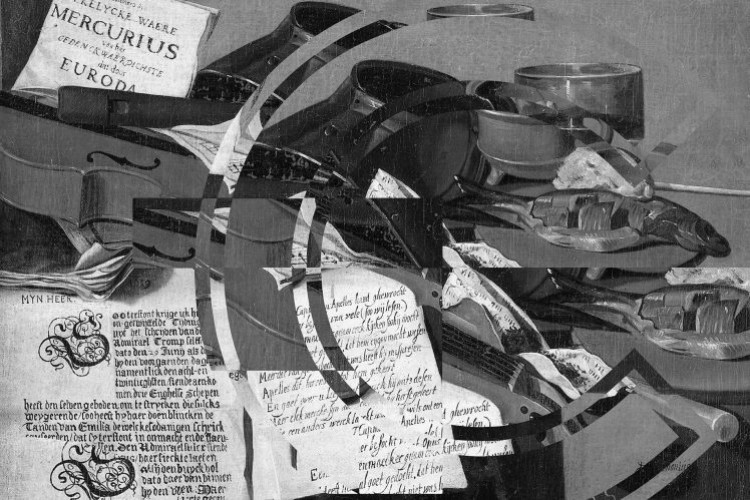Kenapa Semua Harus Serba Jakarta?
Pada submisi column kali ini, Iqbal AR merekam kota Jakarta dari jauh serta mempertanyakan kenapa semuanya harus serba Jakarta?
Words by Whiteboard Journal
Dari jauh sekali, Jakarta adalah kuasa. Segala wujud dominasi, injak-menginjak, serta kutuk sumpah serapah berserakan di sana. Jakarta adalah kemegahan, kompetisi meninggikan gedung dan ego. Jakarta adalah muara dari segala mimpi dan janji, sebuah pernyataan yang mungkin mulai tidak relevan lagi. Jakarta mungkin juga biasa saja, hanya sebatas identitas pusat. Tentu saja, Jakarta adalah kepongahan, arogansi sok kuat, namun rapuh di akarnya.
Bosan, adalah kata yang mungkin keluar ketika nama Jakarta muncul lagi ke permukaan. Semuanya Jakarta, apa-apa Jakarta. Telinga selalu penuh dengan Jakarta begini, Jakarta begitu, seakan Jakarta tidak pernah habis disantap. Semua kalimat “Jakarta adalah,” di atas sudah banyak menggambarkan apa itu Jakarta, tanpa bisa disanggah oleh siapapun, bahkan oleh Jakarta itu sendri.
Lalu, mengapa Jakarta? Mengapa selalu Jakarta, dan bukan kota-kota lain yang mungkin lebih manusiawi? Ya, Jakarta memang seperti bocah kelewat bandel yang tidak bisa ditegur hanya dengan mulut. Dipukul pun hanya akan meninggalkan bekas, dan akan tetap bandel. Namun, tidak ada pilihan selain dengan mencecarnya dengan ocehan apa saja, sembari sesekali pukul pantatnya dengan lidi.
Dari jauh sekali, Jakarta terbuat dari kapas-kapas impian yang indah namun rapuh, yang kadang hanya dengan sekali senggol pun sudah jatuh berguguran. Jakarta adalah tentang betapa megah dan kokohnya gedung pencakar langit dengan pemandangan kali kumuh di belakangnya, tentang gemerlapnya lampu disko yang kerap memusingkan kepala, serta tentang sempitnya ruang gerak untuk sedikit mengambil napas.
Jakarta adala gudang dari segala ketimpangan yang tersatukan. Obrolan orang-orang mengenai saham dan politik dunia di kedai kopi mahal yang ada di mall mewah, menjadi satu dengan teriakan bocah yang kegirangan karena melihat temannya berhasil melompat ke dalam kali yang tidak jauh dari mall itu. Semuanya menyatu dalam udara Jakarta, yang mana masing-masing mereka tidak saling mengerti satu sama lain.
Kehidupan bergelimang harta tergambar di sekitar Menteng dan Pondok Indah, yang tentu akan timpang dengan gang-gang kecil di belakangnya. Semua tersatukan oleh satu kata yang menjadi identitas hidup, Jakarta. Semuanya tersatukan dengan mesra, yang kadang kemesraannya tidak melulu sebatas peluk, cium, dan senggama. Ada juga caci maki, tamparan pipi kiri, hingga sayatan pisau yang melukai.
Apakah memang seperti itu Jakarta? Di balik segala kemegahan, akan selalu ada kegetiran yang mau tidak mau harus tersatukan. Di balik segala kemewahan, akan selalu ada kemelaratan yang terlampau kasihan. Atas nama apa? Kestabilan? Kenyamanan? Harmonisasi? Bukankan Jakarta sudah tidak pernah stabil semenjak negeri ini merdeka? Bukankan Jakarta sudah tidak pernah nyaman sejak pertama kali kota ini dijadikan pusat, entah oleh siapa. Bukannya harmoni itu nama jalan? Ah, sesekali bercanda dan sedikit sinis boleh, kan?
Dari jauh sekali, Jakarta adalah kota dengan masyarakatnya yang, entah istilah apa yang pantas untuk menggambarkannya. Masyarakat kelas atas yang seakan tidak pernah menunduk ke bawah. Masyarakat kelas bawah yang terlampau melarat, yang bahkan untuk mendongakkan kepala saja susah. Serta kelas menengah yang gaya hidup dan bicaranya berusaha seperti kelas atas, namun tidak kunjung sampai.
Kelas menengah Jakarta, apa kita menyebutnya, metropolitanis? Orang-orang dengan gaji nyaris dua digit, bahasa yang kelewat tinggi hingga kerap tersambar petir, serta gaya berpakaian yang kadang lebih mirip badut perempatan dibanding manusia. Semua itu atas nama internasionalisasi, tren, gaya hidup, atau apalah istilah tai kucing itu. Itulah cara untuk terlihat paling modern, paling barat, paling maju dari segala peradaban Jakarta.
Ketika dari jauh semua terpusat ke Jakarta, kelas menengah Jakarta justru melenggang dan memusatkan ke dunia barat. Apa ini yang dinamakan ketertinggalan? Disebut ketertinggalan mungkin terlalu berlebihan. Ini hanya sebatas lingkaran setan bias inferioritas masyarakat terjajah, yang memilih untuk menengok bangsa lain yang mereka anggap lebih maju, tanpa sekali pun menjadi seperti bangsa sendiri.
Jakarta dengan segudang masyarakat kelas menengah (tentunya politisi juga, secara tidak langsung dan meski tidak berkaitan), membentuk suatu narasi yang apa-apa harus Jakarta. Pembicaraan mengenai Jakarta itu sendiri, macetnya Kemang kalau akhir pekan, hingga tentang pengamen ondel-ondel meluber keluar dari Jakarta, menembus batas teritori kota. Dari jauh sekali, kita tidak perlu tahu semua hal itu, dan hanya perlu merekam apa yang terlihat saja, dari jauh sekali.
Begitu lah Jakarta dengan kelas menengahnya. Mereka bersekongkol, seolah apa yang menjadi pembicaraan di Jakarta, juga harus menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Di Magetan, di Kebumen, di Alor, bahkan di Biak sekalipun. Apa yang menjadi pembicaraan kelas menengah Jakarta, juga harus dibicarakan oleh orang di wilayah lain. Persetan relevansi, semuanya harus serba Jakarta, harus bersumber dari Jakarta, dengan bahasa yang serba Jakarta yang mulai kehilangan identitasnya dan mulai serba Inggris itu.
Apa saja yang muncul dari luar Jakarta, akan segera dianggap kampungan, tertinggal, dan pastinya akan diabaikan. Kalau pun mereka sedang baik hati, apa yang keluar dari luar Jakarta hanya akan dianggap sebagai eksotisme, heritage, hidden gems, atau istilah-istilah barat lainnya, yang hanya akan dianggap sebatas komoditi dan ditengok sesekali. Tentunya tidak akan pernah dianggap sebagai narasi utama. Karena semua harus dari Jakarta.
Dari jauh sekali, merekam Jakarta hanya butuh satu gulungan pita saja. Tidak perlu khawatir, karena satu pita cukup untuk merekam keseluruhan Jakarta yang serba paradoks yang kronis ini. Tidak perlu membangun kerangka cerita, karena sedari awal Jakarta memang tidak pernah berkerangka. Silakan mulai dari mana saja, karena Jakarta tidak ada pintu masuknya. Selesaikan secepatnya saja, karena semakin lama Jakarta semakin memuakkan.
Dari jauh sekal, inilah Jakarta. Sebuah narasi penuh kebosanan yang mulai kedaluawarsa. Esok, harusnya tidak ada lagi Jakarta. Biarkan tenggelam, atau babak belur dihantam. Dari jauh sekali, Jakarta hanya akan bersisa sepi. Semua kemewahan, kemelaratan, dan segala bualan kelas menengahnya menguap entah ke mana. Dari jauh sekali, apa itu Jakarta?