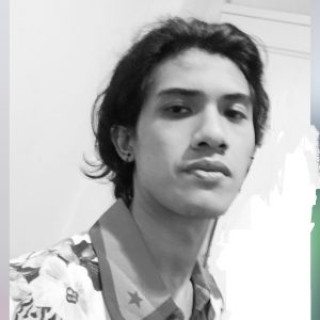Aku Berakal Maka Aku Tidak Bahagia
Submisi open column dari H.S. Billy, melihat bagaimana akal budi dapat menghambat jalan kita dalam mencari kebahagiaan
Words by Whiteboard Journal
“Semakin bodoh orangnya, semakin ia dekat dengan kenyataan. Semakin bodoh, semakin bersih. Kebodohan itu tak bertele-tele dan sedikit indah, sementara kepintaran menggeliat dan menyembunyikan kenyataan. Pintar itu tidak berprinsip, tapi kebodohan itu sama dengan kejujuran dan terus terang”, ucap Ivan Karamazov salah satu karakter utama dalam novel “The Brothers Karamazov” karangan Fyodor Dostoevsky. Ivan adalah seorang intelektual, memakai akalnya dalam memahami kenyataan dan keseharian, berbeda dengan saudaranya yakni Alyosha, seorang yang sensitif, spiritual, dan pencinta sesama. Ada suatu masa ketika keduanya bercakap mengenai kebaikan, Ivan mempreteli apa itu kebaikan dan abstraksi konsepnya dengan menggunakan akal. Alyosha tanpa pikir panjang malah bergerak dan langsung menolong sesama daripada merenung seperti kakaknya. Sepanjang perjalanan cerita, kita melihat bagaimana Alyosha mengalami hidup tanpa ketergantungan kepada akal, dia lebih memilih mencintai daripada memikirkan apa itu cinta, bisa dibilang tokoh ini adalah gambaran ideal Dostoevsky terhadap manusia; aktif, ke-nabi-an, positif, dan tidak terjerumus kepada kontemplasi pemikiran. Akal kadang kala menarik paksa kedamaian batin, dengan memikirkan kebahagiaan, kita malah tidak pernah ‘sedang’ bahagia, ‘memikirkan’ tidak selalu sama dengan ‘melakukan’.
Secara common sense, akal adalah privilese manusia di muka bumi ini. Dengan akal, kita mampu berpikir lebih tajam, kritis terhadap fenomena yang terjadi disekitaran realitas. Filsuf mencoba mencari kebenaran dengan akal, ilmuwan menjelaskan mekanisme alam dengan akal, wirausahawan meningkatkan kesuksesan dengan akal, seorang guru harus menggunakan akal agar anak didiknya bisa mengerti pelajaran, dan bahkan seorang remaja harus memiliki akal yang ter-asah agar tidak dicemooh kerabatnya atau orang yang lebih tua –yang menganggap remaja itu pencampuran dari kebodohan dan ke-nekat-an. Tidak ada yang bisa lepas dari kepemilikan akal, entah ia menguasai kita, atau kita yang mengontrol akal. “Gunakan akal sehatmu”, ucap seseorang kepada seseorang lainnya sehabis melakukan kesalahan. Tatapannya merekah, tenang selagi mengelus kucing, “tidak mau, aku lebih baik bodoh dan bahagia”. Apa jadinya ketika kebodohan malah menimbulkan kebahagiaan, apakah kepintaran selalu menyertai ketidakbahagiaan?, ada kalanya kita merenung dan bertanya dalam hati, “kenapa ya orang itu selalu bahagia setiap harinya, padahal ia tidak punya IQ tinggi, gagal dalam berdebat, tidak punya pangkat tinggi, dan tidak berpikir serius mengenai kehidupan?”, mungkin bisa jadi kepemilikian akal kawanku, bisa jadi privilese yang kita punyai adalah progresi menuju ketidakbahagiaan. Lalu apa yang menjadikan akal menjadi sumber ketidakbahagiaan?
Ada baiknya, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus merenungkan posisi akal secara historis. Pembicaraan mengenai kutukan akal, kita sematkan di dalam modernitas, kita hidup di dalamnya, kita anak-anak jaman tersebut. Apa yang disebut modernitas adalah kemandirian kita dalam berpikir mengenai realitas, tak ada gangguan dogmatis yang mengkekang pemikiran kita. Kejayaan sains meningkat, revolusi industri, keberadaan manusia ditingkat paling tinggi ada di dalam modernisasi itu sendiri, dan semuanya berkat akal. Tapi revolusi intelektual itu memberikan kepada kita semacam alegori kontrak iblis, dimana Mephistopheles (setan) memberikan perjanjian kepada Faust (manusia) mengenai pengetahuan yang berlimpah dan anti-menua. Tapi iblis menginginkan sesuatu timbal balik kepada manusia, Faust harus menyerahkan jiwanya demi segudang pengetahuan. Kita bisa memprediksi cerita selanjutnya yang tentu mengarah kepada penderitaan Faust di dunia. Kita adalah Faust, melakukan kontrak iblis demi akal yang lebih sehat daripada sebelumnya. Tapi ia tahu ia tidak akan bahagia karenanya, otomatis kita sadar bahwa pengetahuan dan akal tidak akan menggiring kita kepada kebahagiaan sepenuhnya.
Mari kita mengawali dengan Arthur Schopenhauer, filsuf pesimistik ini melihat perbedaan kebahagiaan di antara manusia dan binatang. Di dalam esainya berjudul (terj. bahasa) “Tentang Penderitaan di Dunia”, ia menjelaskan bagaimana manusia menderita karena akal, dan bagaimana binatang tenang-tenang saja tanpa akal. Kutipannya sebagai berikut:
“Melalui kemampuan untuk merenung, mengingat dan memprediksi, manusia seolah-olah memiliki semacam mesin untuk memadatkan dan menyimpan kesenangan dan kesedihan yang dialami. Sedangkan binatang tidaklah memiliki mesin semacam itu…”
“Binatang tidak memiliki kemampuan untuk memahami perasaannya sendiri. Itulah yang menjadikannya berwatak santai dan tenang.”
“Binatang tidaklah mengenal harapan.”
“Binatang yang memerlihatkan kebijaksanaan sesungguhnya, yakni kemampuan mereka dalam menikmati momen saat ini dengan penuh kesenyapan dan ketenangan.”
Apa yang bisa kita ambil dari cuplikan esai itu adalah: (1) Walaupun sama-sama sebagai organisme yang mekanistik, binatang tidak memiliki mekanisme berpikir dan memori. (2) Binatang tidak bisa merefleksikan dirinya sendiri. (3) Binatang tidak mengenal pemahaman waktu, dan manusia selalu mengharapkan masa depan dengan akalnya. (4) Binatang hidup di dalam kekinian, manusia tercakup pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena dengan akal, kita bisa terbang memikirkan waktu.
Lalu apa yang tidak membahagiakan dari keempat poin tersebut? mari kita ilustrasikan dalam cerita Schopenhauer mengenai dua sahabat lama yang bertemu kembali saat dewasa. Ketika keduanya bertemu –sambil menerima fakta bahwa mereka mengenal satu sama lain sedari kecil, keduanya mulai memikirkan masa lalu mereka, mengenang kejayaan fantastis masa kecil, sambil merefleksikan kekinian keduanya dan masa depan yang sedang ditempuh. Jika empat point tersebut diaplikasikan, maka kita akan mendapat gambaran seperti ini: Dengan berpikir mengenai masa lalunya, ia ber-nostalgia akan kebahagiaan masa kecil, lalu ketidakbahagiaan datang ketika membandingkan diri dengan masa kini. Pekerjaan yang serba melelahkan dibandingkan dengan tidur sepanjang hari. Kejar-kejaran wanita dibandingkan permainan kejar-kejaran. Menjadi dokter lebih menyusahkan daripada bermain dokter-dokteran. Bermain petak umpet lebih menyenangkan dibandingkan sembunyi-sembunyi dari peminta hutang. Apalagi ketidakbahagiaan ditambah ketika memikirkan masa depan sekaligus harapan-harapannya, “kapan aku menikmati seperti dulu lagi, apakah besok aku harus melewati penderitaan yang sama?”, semua hal tersebut datang ketika kita berpikir, merenung, membandingkan, dan mengharap. Kemampuan-kemampuan itu datang dari kepemilikan akal, lihatlah kucing menikmati momennya saat ini dan tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi padanya esok hari.
Schopenhauer juga memberikan persamaan antara kepintaran dan ketidakbahagiaan. Menurutnya bahagia datang dari hal-hal yang materialistik, ada hubungannya dengan tubuh kita. Bahagia ketika makanan enak, bahagia ketika nafsu terpuaskan, bahagia ketika tidur pulas. Memang ada kenikmatan dari akal, tapi tidak sedalam kenikmatan duniawi yang materialistik. Kepintaran merupakan abstraksi dari kehidupan, dengan menggunakan akal, kita selalu memikirkan sesuatu dalam bentuk ide. “kursi itu bentuknya seperti ini dan itu, gunanya untuk diduduki, dibuat dari kayu”, maka ia tidak mengacu kepada kenikmatan material, kita hanya mereduksi yang material menjadi abstraksi ide. Bahkan ketika kita ‘berpikir’ mengenai kebahagiaan, hal tersebut diabstraksikan, “bahagia itu menikah dengan lelaki yang banyak uang”, sebenarnya kita memikirkan kebahagiaan tapi tidak ‘sedang’ bahagia. Maka berpikir mengenai kebahagiaan tidak sama dengan berbahagia. Itulah mengapa banyak orang yang menyangka bahwa sebagian orang jenius di dalam sejarah jarang sekali menikmati kebahagiaan, mereka selalu menyendiri dalam dunia pikiran, memikirkan apa itu cinta daripada melakukan tindakan mencintai. Lihat saja betapa Schopenhauer merenung, dan dijuluki sebagai filsuf penyendiri nan pesimis.
Bahkan dengan akal kita bisa membuat orang lain tidak bahagia, sebaliknya pula dengan orang lain yang memiliki akal, mereka bisa membuat kita tidak bahagia. Modernitas memberi sumbangsih kepada pemikiran manusia dan posisinya di atas segala-galanya. Machiavelli dengan saran politiknya yang ‘mengerikan’, mengatakan bahwa dalam mengambil kekuasaan, kita bisa melakukan apapun demi efektifitas keteraturan negara. Ia menyarankan kepada kita untuk menggunakan akal dan melupakan kebahagiaan orang banyak. Thomas Hobbes mengatakan manusia adalah mesin anti-sosial, saling memerangi satu sama lain demi kebutuhan individualnya. Manusia dengan kemandirian berpikir, selalu mengenyahkan orang lain demi menghilangkan ketakutan akan kelemahannya di bumi. Francis Bacon mengatakan bahwa “knowledge is power” dalam artian bahwa dengan akal, kita bisa menguasai apapun, terutama alam, dan sains lah bukti nyata atas berpikir mengenai alam. Tapi apa daya karena alam dikuasai dan dikontrol, ada kasus kerusakan lingkungan akibat kemajuan sains dan industri, asap-asap mengepul dan menghilangkan udara segar. Makanya ada pergerakan pada saat itu yang dinamakan romantisme, salah satu penggeraknya ada Rousseau, ia memproklamirkan “kodrat asali manusia”, dia membayangkan manusia mengembara keluar masuk rimba, tanpa industri, tanpa bahasa, penuh perasaan. Sama seperti Schopenhauer dia membedakan manusia dan binatang. Apa mungkin ia menyuruh kita untuk menjadi seekor binatang?.
Lalu saran terbaik adalah benar-benar menjadi binatang? tidak juga. Di dalam setiap marabahaya pasti ada juru selamat. Semakin bahaya meningkat jumlahnya, meningkat pula raihan tangan untuk menolong kita. Soren Kierkegaard contohnya, ia selalu menyarankan kepada pembaca agar membedakan akal dan iman. Pencarian kebenaran kebahagiaan misalnya, tidak dapat diraih karena kita makhluk yang terbatas di hadapan Yang-Tak-Terbatas seperti Tuhan. Mengenai kebenaran kebahagiaan yang objektif, kita tidak dapat meraihnya dengan akal, karena akal kita memiliki batasan. Semua penderitaan terjadi karena akal selalu berusaha menghilangkan ketidakbahagiaan dan menemukan kebahagiaan. Apalagi dalam merasionalkan Tuhan, ia menyarankan agar kita memutuskan jembatan antara manusia dan Tuhan. Manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Karena itu ia menolak adanya pendeta yang seolah-olah bisa mewakili apa yang disampaikan Tuhan, padahal kebenaran objektif itu tidak bisa diraih oleh akal kita yang terbatas. Maka berimanlah, percaya pada kebahagiaan yang relatif, tirulah apa yang orang bodoh nikmati dari dunia ini, tirulah Alyosha. Lalu apakah kita harus menjadi bodoh supaya bahagia?
Martin Heidegger punya saran otentik terhadap bagaimana mengolah akal kita supaya dapat bahagia secara good enough. Menurutnya kodrati asal manusia adalah: (1) Makhluk yang dilempar ke dunia tanpa sebab dan tujuan.(2) Kematian adalah masa depannya.(3) Selalu larut dalam distraksi keseharian. Overthink, depression, dan anxiety malah bagus jika kita melirik apa yang disampaikan olehnya. Dengan berpikir kita bisa sadar akan kodrat asali kita, mengantisipasi kematian supaya tidak menyesal, dan melepaskan kebahagiaan yang semu karena distraksi-distraksi di keseharian. Baginya dengan mengetahui situasi hakiki sebenarnya, yakni dilempar ke dunia tanpa sebab dan tujuan, kita bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan dalam hidup. Ketika kita sedih karena cinta misalnya, kita pasti berpikir, “apakah aku layak dicintai? Kenapa hidupku seperti ini?”, pemikiran itu bagus menurut Heidegger karena dengan memikirkan kalau kita tidak memiliki sebab dan tujuan hidup, kita bisa memutuskan mau jadi apa kita di dunia ini, apalagi hidup itu tidak ada sekuel seperti film Marvel. Heidegger menyarankan kita agar menentukan visi hidup, jangan menunggu kematian datang, dan harus melepaskan diri dari distraksi keseharian karena distraksi tersebut membuat kita lupa akan keterlemparan kita di dunia. Kita ini makhluk berakal, bukan zuhandenes (alat-alat) yang di dalam kehidupan mempunyai fungsi, sebab dan tujuan. Maka dari itu, karena sesama manusia bukanlah alat-alat, mari tidak menggunakan akal untuk membuat orang lain menjadi alat, kebahagiaan datang bukan dari mengenyahkan kutukan akal, tapi bagaimana kita menggunakan akal tersebut.
Meskipun Schopenhauer pesimistik, dan melihat kebahagiaan dari sifat materialistiknya, ia pun tidak menolak adanya kenikmatan yang bersumber pada akal. Baginya kenikmatan ini tersusun bertingkat-tingkat, dari pandangan remeh dan naif, pembicaraan warkop maupun pembicaraan ‘tinggi’. Kenikmatan batin bisa diraih ketika kita membiasakan diri terhadap pandangan hidup seperti: “Mengatur harapan dengan tepat, berhenti memandang segala kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidup, baik besar maupun kecil, beserta penderitaan, kecemasan, dan kesengsaraan, sebagai sesuatu yang janggal atau di luar kebiasaan.” Begitulah ucap sang filsuf dalam esainya. Binatang juga memiliki penderitaannya sendiri, cemas dan takut menghadapi predator. Tapi karena tak ada refleksi, mereka bisa lupa dan terus menikmati momen hari ini. Maka dengan akal kita bisa mengontrol harapan, menguasai keinginan, tidak terobsesi akan kebahagiaan, menerima penderitaan, dan refleksi-meditatif terhadap kehidupan. Ya sejatinya hidup ini penuh dengan penderitaan, tapi dengan akal kita bisa meminimalisir kuota tersebut. Siapa tahu dengan berpikir “aku harus mengurangi penderitaan seminim mungkin, mustahil untuk menghilangkan penderitaan. Karena kebahagiaan hanya kelupaan atas penderitaan”, kita bisa mendapat ketenangan dari penerimaan bahwa kebahagiaan hanya rest area di jalan tol, bahagia dengan menerima bahwa penderitaan itu pasti selalu muncul.
Apa itu kebahagiaan? Apa itu cinta, apa itu Tuhan, apa pula manusia sebenarnya?. Dengan memikirkan hal tersebut, kita lupa bahwa kita bisa menggunakan akal agar menggerakan tubuh kita dalam mencari kebahagiaan, mencintai seseorang, melakukan kebaikan dari Tuhan, mengasihi sesama manusia. Kadang kala kita terpaku oleh abstraksi ide, tapi jarang sekali melakukan tindakan yang nyatanya dapat memberikan kebahagiaan. Daripada berpikir apa itu cinta, lebih baik melakukan kegiatan mencintai. Seperti Kierkegaard dan Alyosha, mari menggunakan akal kita agar bertindak seperti apa yang iman kita percayai terhadap kebahagiaan itu sendiri. Daripada berpikir terlalu dalam, lebih baik percaya, itulah mungkin rangkuman dari saran Kierkegaard. Daripada ‘berpikir’ lebih baik ‘bertindak’, itulah saran Alyosha, karena kebahagiaan bukanlah abstraksi ide tapi hasil dari tindakan. Setelah bebas kita dikutuk untuk memikirkan kebebasan kita, maka akal menjadi sumber kegelisahan selanjutnya. Jangan lupa pula, semua manusia punya akal, semua manusia berarti menderita karena akal. Melihat sesama jangan memanggil nama mereka, atau julukan jelek orang lain, mari menggunakan saran Schopenhauer, mari memanggil orang lain dengan “kawan sesama penderita”.