Kampung Jakarta bersama JJ Rizal
Muhammad Hilmi (H) berbincang dengan JJ Rizal (J), sejarahwan.
by Ken Jenie




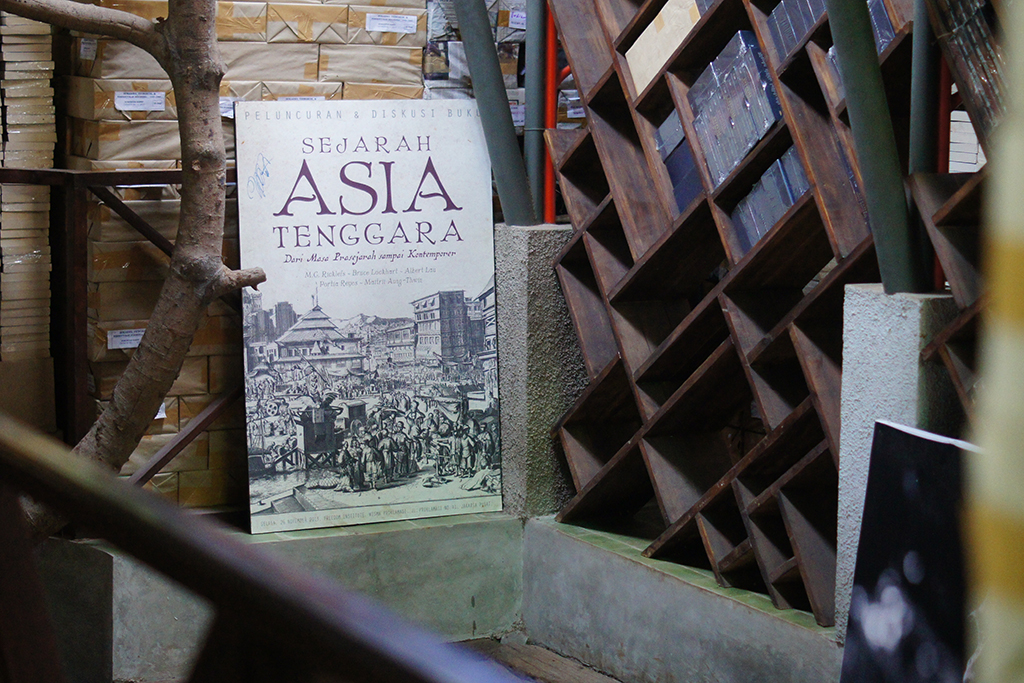

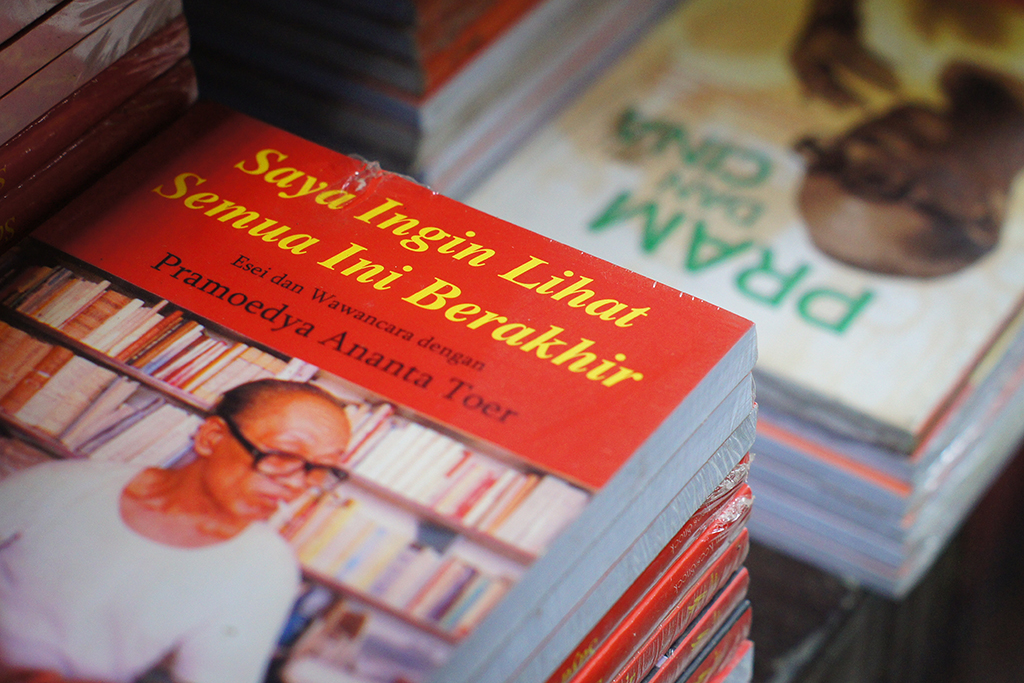












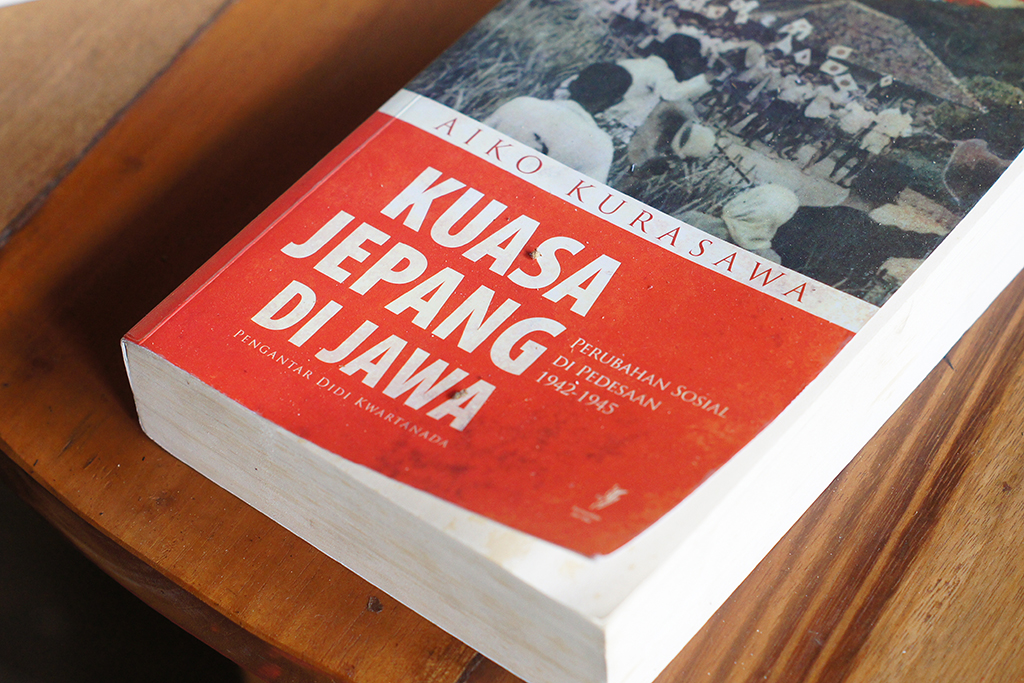







H
Bagaimana ketertarikan Anda terhadap sejarah dan dunia literatur muncul?
J
Ini agak lucu, saya baru bisa membaca kelas 3 SD (tertawa). Saya adalah anak pertama yang lahir dari pasangan yang menikah muda, dan jarak antara saya dan adik-adik saya selalu dekat, hampir setiap tahun. Jadi sesaat setelah saya lahir, tak lama kemudian ibu saya hamil lagi. Saya lantas dititipkan pada kakek saya, karena ayah saya saat itu masih kuliah. Di rumah kakek, saya diberi kebebasan untuk melakukan hal yang saya suka, saya banyak menghabiskan waktu dengan menggambar dan melukis, dan nyaris tak mempelajari hal lain.
Saat masuk kelas 3 SD, guru saya kaget, bagaimana ceritanya seorang anak bisa naik kelas terus tapi masih belum bisa membaca. Saat beliau bertanya kepada saya alasannya, saya menjawab bahwa ibu saya selalu memberi sogokan saat kenaikan kelas supaya saya lulus. Saya lalu disuruh turun kelas 1 karena memang belum bisa membaca, mendengar berita tersebut, ibu lantas menghampiri guru saya untuk melakukan hal yang biasa ia lakukan – menyogok guru saya supaya saya diloloskan tanpa harus mengulang. Tapi bedanya kali ini guru saya menolak uang sogokan tersebut. Setelah berdiskusi, akhirnya guru saya mau menerima uang, dengan catatan bahwa uang tersebut adalah biaya les. Semenjak itu, sepulang sekolah saya lanjut les di rumah guru saya untuk mengejar ketertinggalan saya, terutama dalam hal membaca.
Kebetulan, pas saya mulai bisa membaca, kakek saya yang berprofesi sebagai juragan ikan mengalami kesulitan, di tahun itu sekitar tahun 1981-1982, biasanya pembungkus ikan adalah daun teratai atau daun jati, penggusuran yang terjadi di Jakarta ketika itu membuat pohon jati dan teratai sulit ditemukan – padahal pohon jati terutama merupakan salah satu identitas daerah, bisa dilihat pada banyak nama area diawali dengan kata Jati, seperti Jati Padang, hingga Jati Petamburan. Kebingungan untuk mencari pengganti pembungkus, kakek saya lantas mengganti alat bungkus ikan tadi dari daun menjadi koran dan majalah bekas. Rumah kakek kemudian dipenuhi dengan koran dan majalah bekas, saya yang baru bisa membaca dan mulai bosan dengan bacaan dasar seperti “ini budi” dan semacamnya lalu menemukan dunia bacaan baru. Saya juga menemukan tipe bacaan kesukaan, biasanya seputar tulisan legenda, mite, pewayangan, superhero dan tulisan yang banyak bercerita tentang masa lalu.
Saat kuliah, saya kemudian menyadari bahwa sebenarnya saat baru belajar membaca tersebut saya belajar banyak hal, terutama mengenai sejarah dari majalah-majalah bekas yang dibuat jadi pembungkus bagi ikan dagangan kakek saya. Salah satunya yang saya ingat adalah mengenai Rampogan Macan yang ditulis oleh dosen saya Ong Hok Ham, telah saya baca saat saya baru bisa membaca. Sejak itu saya senang dengan sejarah, kebudayaan dan dunia literatur. Pemikiran ini terus terbawa hingga lulus SD, SMP dan SMA, fokus saya sudah terpatri pada keinginan untuk memahami masa lalu.
H
Ini yang membuat mas JJ Rizal kuliah di jurusan sejarah?
J
Iya. Sejak SMA saya sudah memantapkan diri untuk kuliah di jurusan sejarah. Tapi sempat ada debat dengan ayah saya mengenai pilihan ini. Beliau bertanya kepada saya mengenai pilihan yang saya ambil saat UMPTN (sekarang SBMPTN), saya menjawab bahwa pilihan pertama saya adalah Jurusan Sejarah di Universitas Indonesia dan Jurusan Ekonomi di universitas yang sama sebagai pilihan kedua. Pilihan tersebut ditertawakan oleh ayah saya dan beliau meminta pilihan tersebut dibalik urutannya, karena jurusan sejarah dianggap lebih bawah statusnya dibanding ekonomi, saya menurutinya. Saya sempat mengembalikan sejarah jadi pilihan pertama di malam hari, namun paginya ayah saya melihat form dan mengetahui bahwa pilihan saya ubah, saya dimarahi dan diminta mengembalikan jurusan ekonomi menjadi pilihan pertama. Karena sudah terlanjur mantap, saya kemudian kembali menukar pilihan tersebut sesaat sebelum mengumpulkan form UMPTN. Saya sempat disuruh mengambil kursus persiapan masuk universitas, karena tahu bahwa jurusan sejarah minim peminat, saya tak mengambilnya. Dan benar saja, saat pengumuman saya diterima.
Mendengar saya diterima di UI orang tua saya sangat bangga, bahkan kampung saya sempat geger, keluarga sampai syukuran besar-besaran. Meski sebenarnya mereka tidak tahu saya diterima di jurusan apa. Saat ayah saya tahu saya diterima di jurusan sejarah, beliau marah (tertawa).
H
Kecintaan terhadap sejarah ini pula yang membuat Mas Rizal membentuk Komunitas Bambu?
J
Awalnya itu tahun 1998, saat masa demo reformasi. Kampus saya, UI adalah salah satu kampus dimana banyak terjadi pergolakan yang mengawali jalannya reformasi. Saat krisis, saya sedang menjalani masa sebagai mahasiswa tingkat akhir, selain aksi demonstrasi, banyak pula diskusi di kampus. Pada diskusi-diskusi yang terjadi, kami mencari akar dari krisis yang kita alami saat itu. Banyak gagasan muncul, anak jurusan ekonomi berpendapat bahwa alasan terjadinya krisis adalah karena struktur ekonomi kita yang rapuh, anak politik berpendapat bahwa sebab kriris adalah sistem politik kita yang rusak.
Saya sendiri sebagai anak sejarah, melihat bahwa salah satu penyebab utamanya adalah karena kita sebagai bangsa tidak mengenali jati diri kita. Kita tidak tahu proses lahirnya Indonesia, kita tidak tahu asal-muasal bangsa ini, kita juga tak paham alasan berdirinya. Maka dari itu, dari perspektif ini saya melihat bahwa cara untuk menghindari krisis sebenarnya adalah dengan mengenali diri kita sendiri. Caranya adalah dengan masuk ke ruang sejarah, untuk mengetahui bagaimana Indonesia dibentuk, siapa pembentuknya, perspektif juga sikap mereka. Kita perlu mengenali isi kepala mereka supaya tahu landasan imajinasi besar yang lantas mereka namai Indonesia ini. Karena tanpa itu, kita akan jadi manusia tanpa imajinasi yang hanya bisa merusak Indonesia.
Komunitas Bambu lahir tanggal 20 Mei 1998, sehari sebelum Pak Harto lengser. Selain sebagai usaha mengenali diri sendiri, juga karena ketika itu kita bingung mengenai apa yang harus kita lakukan kemudian, Komunitas Bambu adalah cara bagi kami untuk mendedah hal tersebut. Dengan konsep komunitas, ada banyak orang yang terlibat di dalamnya, mereka yang di sana percaya bahwa jawaban atas kebutuhan negeri ini ada pada sejarah.
H
Dari pembacaan Mas Rizal terhadap sejarah selama ini, apakah sepakat dengan dampak kolonialisme dan neo-kolonialisme yang membentuk mental negatif bangsa Indonesia?
J
Selalu ada positif-negatif dari masa lalu. Kolonialisme memperkenalkan kita dengan nasionalisme, internasionalisme, modernitas hingga sepak bola. Nasionalisme sendiri merupakan antitesis dari kolonialisme, nasionalisme menguliti kolonialisme dengan berbagai ideologi di dalamnya, mulai dari komunis, sosialis, fasis juga islamis, tentang bagaimana cara mengalahkan kolonialisme yang dihadapi. Sikap nasionalis ini kemudian menjadi akar imajinasi tentang negara baru yang menolak praktek dan mental kolonial yang nantinya menjadi masalah besar negara ini, yakni: feodalisme, rasisme, etnisitas dan hipokrasi. Bapak-bapak pendiri bangsa kita lalu mendiskusikan mengenai masalah-masalah tersebut dan menemukan sikap baru, yakni sikap sebagai orang Indonesia.
Kalau hari ini kita justru hidup dalam mentalitas kolonial yang hipokrit, diskriminatif dan rasis, ini karena kita lupa dengan identitas yang diciptakan bapak pendiri bangsa yang kita tinggali ini. Nama-nama mereka ada di sekitar kita, beberapa diabadikan menjadi nama jalan, bahkan dikibarkan di bendera partai, tapi hanya sebagai slogan saja yang digunakan sebagai jalan mengambil profit oleh kalangan tertentu. Jadi ibaratnya hanya jasadnya yang diawetkan dan diberi pewangi, sedangkan pikiran, ideologi, gagasan, cita-cita mereka dilupakan. Ini masalah besar yang kita hadapi sekarang, karena sikap-sikap yang berlawanan dengan identitas bangsa kita justru hidup.
Sikap-sikap kolonial ini dengan mudah kita temukan sekarang, pertama adalah tentang penggusuran yang belakangan terjadi. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, dasar dari penggusuran itu mengacu pada pasal perundangan warisan kolonial yang diterbitkan tahun 20-30‘an. Perundangan tersebut dibuat dengan konteks negara dalam keadaan darurat perang, dengan kondisi darurat tersebut negara berhak mengambil alih harta atau apapun dari warga dengan cara apapun, termasuk dengan kekerasan.
Saya menemukan keganjilan ini saat teman-teman LBH (Lembaga Bantuan Hukum) mengurai dasar kebijakan dan menemukan undang-undang tersebut. Saya juga kaget saat melihat landasan perundangan ini dipakai hingga sekarang di era reformasi. Padahal salah satu poin reformasi adalah untuk menolak nilai kekerasan dan militeristik ala Soeharto.
Saat kemudian diajak menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, mereka pun bertanya kenapa undang-undang yang usang ini masih diterapkan. Karena bahkan jika dilihat lebih dalam, sebenarnya ini adalah produk tahun 1870-an di mana negara tak merasa cukup dengan berjalannya tanam paksa. Semua lantas dikuasai kerajaan dan negara. Dari sinilah muncul istilah tanah negara yang sering kita dengan sekarang. Soekarno sebenarnya pernah menolak konsep yang seperti ini, bahwa kebijakan yang seperti ini sangat mencerminkan kapitalisme purba yang jahat itu. Ini bukti bahwa sekian tahun setelah Soeharto, kita masih berpikir dalam pola pikir kolonial yang hipokrit. Bahwa kita masih menggusur rakyat dengan perundangan kuno, dan justru bangga dengan itu. Ini cuma salah satu contohnya, masih lebih banyak lagi yang ada di luar sana.
H
Sebagai sejarawan yang banyak berbicara tentang Jakarta, bagaimana melihat perjalanan perkembangan kota Jakarta dari masa-masa, dan apa yang Mas Rizal lihat semakin hilang dari kebudayaan Jakarta?
J
Jakarta sebenarnya tak pernah menjadi kota. Konsep kota salah satunya lahir dari Plato, dimana baginya kota adalah di mana terjadi keberagaman, kelayakan huni secara ekologis, dan imajinasi bersama penduduknya. Hal-hal tersebut tidak kita temukan di Jakarta. Secara sejarah, Jakarta lahir dari warisan kolonial, Batavia yang dibangun dengan oleh Belanda bukan sebagai kota, tapi sebagai markas dagang, tempat rendevous. Sebagai markas dagang, penduduknya selalu berkembang, mereka datang dan pergi, istilahnya adalah trekkers (kaum nomadik) bukan blijvers (kaum yang menetap). Trekkers yang banyak tinggal di Jakarta ini kemudian melihat bahwa Jakarta bukan sebagai tempat tinggal dan hidup yang mereka harus rawat dan pelihara, tapi semata sebagai ruang untuk mencari uang yang harus dieksploitasi.
Dan sebenarnya sejak awal Jakarta tidak pernah dibangun menjadi kota. Kalaupun ada yang melihat Jakarta sebagai kota, sembari mengangkat kehidupan warganya, mereka hanya muncul sesaat, dan tak pernah bertahan lama. Contohnya adalah Mohammad Husni Thamrin, tokoh pergerakan era Belanda, ia memperjuangkan hak hidup warga kota untuk hidup bersama – bukan milik segelintir orang saja, ia sempat melahirkan beberapa konsep revolusioner, tapi gagasannya tidak bertahan lama karena tak ada yang melanjutkan pemikirannya. Sekian puluh tahun kemudian baru muncul lagi dalam bentuk Bang Ali Sadikin. Pada jamannya Bang Ali mendapat kritik bahwa Jakarta hanya memperhatikan orang-orang yang menyumbang (tren minyak pada saat itu minyak sedang naik), ini sebuah hal yang ia tidak bisa pungkiri, karena ia memang memiliki kewajiban untuk membalas budi para penyumbang kota. Namun ia juga tak lantas mengabaikan warga kampung, tak mendapatkan uang dari pemerintah pusat, Bang Ali kemudian melegalkan judi dan lokalisasi untuk menarik pajak yang digunakan memeratakan pembangunan bagi semua. Memang ada orang-orang seperti Bang Ali dan Husni Thamrin, tapi keberadaan mereka tak kontinyu. Yang menang di sini adalah para trekkers, bukan blijvers yang melihat Jakarta sebagai kampung yang mereka harus rawat, karena di sanalah mereka akan beranak-pinak dan dikubur saat akhir hayat.
Pada tahun 1870 Jakarta dibilang sebagai kampung besar, memang begitu adanya. Dan sampai sekarang sebenarnya masih begitu. Yang ironis, sekarang Jakarta malu dengan predikat kampung ini. Dan sekarang kita berusaha menghapus predikat kampung ini, supaya Jakarta lebih kota yang seolah-olah dianggap lebih maju. Yang kita kejar juga kota dari perspektif trekkers yang berarti ruang uang, beton. Tanpa ada tempat untuk manusia. Ini problem besar yang kita hadapi sekarang.
H
Tapi idealnya bagaimana perkembangan Jakarta? Apakah kita harus kembali pada konsep kampung? Atau kita eksplor lagi konsep kota yang lebih ideal?
J
Sebenarnya kita salah kaprah dalam memahami konsep Duchaim yang merangkum Jakarta sebagai kampung besar. Kita melihat kampung sebagai bentuk usang yang harus ditinggalkan, padahal tidak demikian. Ini mungkin ada hubungannya dengan gap antara si miskin dan si kaya yang semakin jauh sejak kemerdekaan. Ini menjadi akar dari pemberontakan yang kerap terjadi di daerah, darisini lalu mobilisasi terjadi ke kota, terutama ke Jakarta.
Pola yang demikian ini melahirkan istilah baru, “orang kampung” dan “orang gedongan”. Orang kampung dikategorikan sebagai kalangan yang memalukan – sebuah hal yang telah ditanamkan sejak era kolonial – mereka busuk, sumber masalah, tempat hal-hal buruk terjadi. Konsep ini bisa kita temukan di kisah Nyai Dasima, dimana pada kisah tersebut tokoh-tokoh dari kampung dibuat sebagai orang yang jahat, yang baik adalah orang kulit putih. Konsep ini hidup terus hingga sekarang. Padahal faktanya tidak demikian, justru aspek-aspek hidup berkota seperti keberagaman, gotong-royong, komunialisme, ekologi ini tumbuh subur di kampung. Justru kampunglah identitas utama Jakarta.
Dengan konsep kampung ini akan lahir pribadi-pribadi yang egaliter, bukan dari konsep kota dari kulit putih, atau bila disesuaikan dengan konteks sekarang, kota versi kelas menengah ke atas. Kota versi demikian ini menghasilkan masyarakat yang tak bertetangga, yang lahir justru kawasan ghetto. Kampung akan menghasilkan kebudayaannya yang khas, pluralisme, bahkan interkulturalisme, tanpa diskriminasi dan rasisme. Secara ekologi juga lebih baik, di kampung lingkungan lebih sehat karena tak ada eksploitasi alam, air akan sehat dan terbagi rata karena tak ada yang membangun deep well, misalnya. Nilai-nilai seperti ini lahir di kampung.
Konsep kita dalam berkota ini keliru karena kita terkena sindrom kampung vs gedongan. Dulu Slank terkenal dengan album berjudul “Kampungan”, tapi kini mereka menyerukan “Jangan buang sampah sembarangan karena itu kampungan”, ini merupakan fakta yang menarik.
Di masa depan, jika kita ingin memulihkan Jakarta, kuncinya adalah kembali ke kampung. Pernah Pak Jokowi dan gubernur lain berbicara mengenai menghadirkan kembali arsitektur kampung Betawi, tapi sedikit yang paham bahwa menghadirkan kembali kampung tersebut bukan melalui ornamennya, tapi lebih ke konsep ruang di arsitektural Betawi yang memberi ruang lebih pada pohon, rumah hanya bagian kecil. Ini saya rasa konsep hidup yang baik, yang bisa diterapkan saat kita menghadapi krisis ruang resapan dan ruang hijau. Bukan dengan menghancurkan semua yang ada, tapi dengan audit mengenai bangunan dan aspek ekosistem yang ada di sekitarnya.
Karena mental block yang mengidentikkan kampung dengan ketertinggalan sejak masa kolonial, local wisdom tersebut terabaikan.
H
Bagaimana sebenarnya karakter dari kebudayaan Betawi?
J
Yang menarik dari Betawi adalah budaya ini lahir di pinggir sungai. Peradaban mereka tumbuh di pinggir sungai yang bermuara di laut, saat komunitasnya menjadi semakin besar, mereka kemudian membuat bandar di Sungai Ciliwung. Inilah yang kemudian di peta tertua, ada satu tempat yang bernama Kalapa. Saat kota bandar Kalapa diekspansi oleh Sunda, jadilah Sunda Kalapa, sebelum kemudian diekspansi oleh Islam Demak jadi Jayakarta. Kompeni datang dan mengubahnya menjadi Batavia.
Kota bandar ini karakternya cukup jelas, tempatnya terbuka, di mana terjadi persilangan dari berbagai suku bangsa. Masalahnya banyak di antaranya yang datang tanpa membawa istri. Akhirnya berkawin-mawinlah, dan ini membentuk suatu kebudayaan baru. Kebudayaan inilah yang tercermin dan mencerminkan komunitas yang tercipta.
Di Betawi ada rite of passage yang cukup unik yang dirangkum dalam tiga tahapan: nyunatin, ngawinin, kematian. Yang dianggap terpenting dari tiga itu adalah yang kedua, ngawinin. Kalau orang Betawi kawin, kita bisa lihat jati diri sekaligus asal-usul kebudayaan Betawi: mempelai perempuan dandan besar ala pengantin Cina, yang laki-laki, dandan besar ala pengantin Haji. Ini memperlihatkan unsur budaya yang membentuk Betawi. Sebelum prosesi pelamaran, dandanan calon pengantin pria juga menunjukkan banyak bendera yang melebur, tanpa harus saling claim, ada unsur Tionghoa, Belanda, Portugis, Arab yang menjadi satu di budaya Betawi. Betawi adalah semua yang menjunjung perbedaan itu dalam kesatuan.
Tumbuh di area sungai yang menjadi kota bandar membuat Betawi sebagai budaya yang sangat terbuka, dan inklusif. Hampir semua kebudayaan Betawi memperlihatkan inklusifitas ini. Bukan lagi pluralisme, tapi dalam bentuk interkulturalisme. Bukan cuma beragam, tapi beragam dalam saling berhubungan. Tak hanya orangnya yang berkawin-mawin, tapi kebudayaannya pun juga berkawin-mawin. Maka dari itu ada Kampung Melayu, Kampung Bandan, hingga Kampung Bugis. Sebenarnya ini adalah konsep yang dibuat oleh kompeni, untuk memecah-belah sebuah praktek politik segregasi. Tapi siapa yang bisa menolak cinta, anak Kampung Melayu bisa jatuh cinta pada pemudi Kampung Bugis, dan seterusnya. Ini banyak terjadi di abad 17. Pada sekitar tahun 1930, banyak sekali ditemukan orang dengan kesukuan yang tidak jelas dan sudah bercampur baur, ini adalah salah satu momen lahirnya generasi baru orang Betawi.
Percampuran yang seperti ini bisa kita lihat pada Tanjidor yang sebenarnya adalah brass band Eropa, namun membawakan lagu dengan cara mereka sendiri yang berbeda dengan cara Eropa. Hal yang sama juga terasa pada Gambang Kromong, apakah ini budaya Tionghoa? Bukan. Tapi masih ada sisa warna aslinya di sana, ini menunjukkan ada aspek kosmopolitan yang jelas di budaya Betawi. Ini yang membuat saya yakin bahwa akan susah untuk memindah ibukota dari Jakarta. Karena saya tidak melihat ada kota lain yang memiliki tradisi kosmopolitan yang lebih panjang dibanding Jakarta. Sayangnya sekarang nilai-nilai inklusifitas ini mulai hilang dengan konsep kampung yang semakin kita jauhi. Kalau ada yang bilang sekarang Betawi dipinggirkan itu karena kita memusuhi konsep kampung secara mental dan material. Karena kebudayaan tidak akan tumbuh saat ruangnya diambil alih oleh ruang kapital. Ruang kapital seperti ini tidak melihat esensi inklusifitas, pluralisme atau komunalisme, kalaupun ada yang melihatnya sebagai hal yang penting, biasanya cuma dijadikan semboyan kapital (tertawa).
H
Apakah ini berarti benar tentang isu mengenai mengembalikan Jakarta untuk orang-orang Betawi? Bagaimana juga melihat pendatang yang mewarnai dinamika kota Jakarta…
J
Yang banyak orang gagal mengerti adalah fakta bahwa arus orang ke Jakarta telah menyurut sejak tahun 90’an. Yang meningkat adalah angka kelahiran. Dengan taraf hidup yang lebih baik, banyak orang berkembang di Jakarta dan di sekitar Jakarta. Ini yang membuat seolah Jakarta mengalami ledakan penduduk.
Tentang arus pendatang, sebenarnya juga pernah ada percobaan untuk menghentikannya. Sebuah percobaan yang tidak berhasil, dan memang tidak mungkin berhasil dilakukan. Karena Jakarta adalah ibukota kita, ada kata “kita” di situ. Belum lagi mengenai konsep pembangunan kita yang sentralistik. Sifatnya mirip lampu petromaks, hanya yang ada di sekitar lampu yang terang, yang jauh akan tetap kegelapan.
Dalam konteks ini kemudian orang banyak berbicara mengenai pindah ibukota, karena Jakarta sudah tak lagi sanggup. Menurut saya, bukan pindah ibukota, tapi lebih ke mengurangi beban ibukota. Caranya mudah sebenarnya, yang sulit adalah menemukan political will dan kesadaran menuju kesana. Bung Karno pernah bilang bahwa ibukota tak mungkin pindah karena ada aspek historis yang tidak dimiliki kota lain. Aspek historis ini bisa dilihat pada bagaimana Jakarta berperan sebagai kota juang nasionalisme, di Jakarta lah Indonesia di proklamasikan, di Jakarta pula nasionalisme Indonesia dibentuk – ini tanpa menafikkan kota lain. Yang bisa dilakukan adalah dengan membagi beban, bukan memindahkan.
Kalau ada yang bilang stop memunggungi lautan, dan total melalui kementerian kelautan, untuk apa kementriannya berada di Jakarta? Kenapa bukan di jantung peradaban maritim, yang berada di timur Indonesia, bisa di Ambon, dan sekitarnya. Kalau kita mengaku sebagai negara agraris, kenapa kementeriannya ada di Jakarta, bukan di jantung peradaban agraris, bisa di Sumatra atau di Bali misalnya. Masih banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Karena kalau misalnya kita mulai membagi beban, kita akan memiliki banyak area yang bisa dipulihkan menjadi ruang resapan hijau. Pikiran-pikiran seperti ini bukan tidak ada, tapi elit kita sekarang berlaku seperti elit kolonial yang tidak sanggup hidup di luar kemewahan, di luar kemudahan. Bagi mereka hidup di luar Jakarta tak akan mengagungkan posisi mereka.
Problem utamanya mungkin mental, dan ini ditambah minimnya pengetahuan kita mengenai sejarah. Kita enggan melepas beban masa lalu yang ada di punggung, padahal sebenarnya kita bisa melepasnya jika paham esensinya.
H
Karena kalau kita berpikirnya menutup pintu kota, kita jatuhnya akan terperangkap pada rasisme ya?
J
Iya. Akan timbul rasisme kota. Sekarang sudah mulai terlihat kita kadang menerapkan rasisme pada kota di sekitar Jakarta. Yang paling terlihat adalah pada bagaimana pemerintah pusat yang menciptakan gap yang sangat besar dalam hal pembagian APBD terhadap kota sekitar Jakarta. Di Jakarta alokasi dananya sampai 76 trilyun, sedangkan Depok cuma 3 trilyun. Padahal apakah mungkin kita berbicara mengenai Jakarta tanpa melihat Depok, Bekasi atau Tangerang? Apalagi jika kita melihat bahwa masa depan ekologi Jakarta itu ada di kota-kota sekitarnya.
Contohnya ada pada masalah banjir yang akarnya pada masalah internal dan eksternal. Masalah eksternalnya adalah arus air dari selatan Jakarta, misalnya arus dari Puncak atau Bogor. Dengan fakta yang demikian artinya kita harus berbaik-baik pada wilayah sekitar. Solusinya adalah dengan membentuk megapolitan, bukan megapelitan. Jadi membagi uang Jakarta yang sedemikain besar ke kota yang ikut menahan bebannya. Juga supaya tak semua orang lari ke Jakarta, caranya adalah dengan mengembangkan kota sekitar dengan konsep megapolitan. Rancangannya pun sudah ada sejak 1965, dan telah ditandatangani oleh Soekarno. Saat itu beliau merencanakan konsep megapolitan yang wilayahnya sampai Purwakarta. Ide ini sempat dihidupkan oleh Bang Ali, tapi beliau tak mampu melawan hegemoni Soeharto. Beliau menurunkannya pada Sutiyoso, tapi Sutiyoso pun tak mampu meyakinkan SBY. Jadi masalahnya bukan Jakarta tak memiliki ruang, tapi lebih ke Jakarta yang tak mampu membagi ruang dan uang.
Depok misalnya, kota ini memiliki potensi menjadi penahan runoff air. Depok memiliki puluhan setu (danau), tapi beberapa di antaranya menyusut dan tercemar, Jokowi mengusulkan untuk membangun embung (cekungan penampung air) padahal bagi saya sebenarnya solusinya adalah revitalisasi setu, dan menjadikannya ruang publik baru, jadi arus orang pun bisa terbagi, tak semuanya ke Jakarta. Sekarang konsep megapolitan di lupakan dan orang berpaling pada reklamasi dengan alasan Jakarta kekurangan ruang. Padahal kasusnya adalah Jakarta rakus uang.
Selain itu juga ada mengenai keberanian kita untuk mengubah konsep tata ruang. Sekarang yang ada adalah rencana tata uang RT/RW, kita harus mengembalikan konsepnya menjadi konsep tata ruang. Akarnya sebenarnya kembali lagi tentang attitude trekkers yang tak melihat Jakarta sebagai tempat tinggal yang harus dirawat baik-baik. Masalah lainnya adalah ada beberapa orang yang baru dua-tiga bulan di Jakarta namun seolah-olah lebih tahu daripada orang yang sudah tahunan mempelajari kota ini (tertawa).
H
Jadi kalau ada jokes yang mengejek kota Bekasi yang sempat ramai beberapa waktu lalu itu sebenarnya bentuk rasisme?
J
Ya kalau kita menganalogikan Bekasi sebagai kota dari galaksi lain, lalu apa kabar Papua yang nan jauh di sana? Inilah kelakukan dan kesombongan warga Jakarta yang merasa agung dibanding daerah lainnya. Ini bentuk mental ala kolonial dan feodal. Orang yang melakukan bullying seperti ini mungkin tak tahu mengenai konsep kolonial dan feodal, tapi secara tak sadar mereka tengah mempraktekkannya. Ini sekali lagi karena kita tak paham dengan sejarah (tertawa). Cara untuk menghindarinya adalah dengan membaca buku. Komunitas Bambu menerbitkan buku karangan Susan Blackburn tentang sejarah Jakarta, kesimpulannya menarik, Jakarta dalam 400 tahun terus-menerus membangun, tapi yang ditinggalkan banyak negatifnya.
H
Tentang etnis, semakin hari semakin banyak sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa padahal ini adalah salah satu tulang punggung budaya Betawi. Dan ironisnya beberapa di antaranya yang rasis terhadap Tionghoa adalah komunitas budaya Betawi…
J
Sepertinya kita tidak bisa menggunakan Betawi pada konteks ini. Memang ada organisasi yang mencantumkan Betawi di nama mereka, padahal secara organisasi mereka terbuka, bahkan menurut penelitian Ian Wilson, keanggotaan orang Betawinya tak sampai 2%. Mereka menggunakan nama Betawi karena mereka merasa mendapatkan legitimasi dan bisa mendapatkan profit darisitu. Hal yang sama juga terjadi pada politisi yang mengatasnamakan dirinya sebagai Betawi, tapi aktivitasnya tak mencerminkan budaya Betawi.
Kalaupun memang benar mereka orang Betawi, mereka pasti orang Betawi dari planet lain, karena di bumi, bukan begitu perilaku orang Betawi. Kalau kita mempertanyakan posisi Tionghoa di budaya Betawi, itu berarti kita mempertanyakan asal-usul dan leluhur budaya kita. Contoh paling gampangnya adalah saat lebaran, mayoritas sajian yang disajikan di meja makan orang Betawi adalah sajian Kristen atau Konghucu. Antara makanan Cina atau makanan Belanda. Makanan Arab justru tidak ada di meja makan saat lebaran. Kurma baru dikenal saat Muhammadiyah masuk Jakarta di awal abad 20.
Mari kita cek, makanan utamanya adalah semur, yang datang dari menu Belanda, kecapnya datang dari budaya Tionghoa. Manisan yang banyak disajikan, itu juga tradisi Tionghoa. Jadi sebenarnya makanan lebaran orang Betawi itu sebenarnya makanan saat Natal dan Imlek. Lebaran yang katanya tradisi Islam, tapi sajian di mejanya menunjukkan interkulturalisme yang hidup di budaya Betawi. Begitu pula dengan saat Imlek, ada makanan Betawi yang jadi salah satu sajian utama, lontong cap go meh, itu kan budaya masyarakat agraris. Jadi sebenarnya Betawi tak pernah punya masalah dengan etnisitas, hal itu sudah mereka selesaikan ratusan tahun yang lalu. Mereka bahkan merayakannya dalam konsep unik yang berbentuk budaya Betawi. Yang merusak pluralisme ini sepanjang sejarah kita adalah politisi yang selalu menggunakan segregasi, dan diskriminasi sebagai manuver politik. Ini adalah warisan strategi politik kolonial yang diwariskan pada sistem politik orde baru.
Sayangnya rasisme seperti ini dipelihara oleh negara sekian puluh tahun, untuk mengontrol masa pada masa sulit seperti saat krisis dan pemilu. Di saat-saat seperti ini isu rasisme dimunculkan kembali karena bisa ada profit yang bisa diambil dari situ. Masyarakat dalam hal ini cuma jadi korban adu domba politik yang terus terjadi bahkan setelah reformasi. Padahal sebenarnya masyarakat sudah tak memiliki masalah mengenai rasisme, apalagi dalam hal ini konteksnya masyarakat Betawi yang sangat berwarna. Sayangnya para politisi kita masih melihat bahwa rasisme dan segregasi sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan.
H
Jadi satu-satunya cara untuk memutus sejarah panjang ini adalah dengan belajar sejarah?
J
Betul. Masalahnya dari 1000 orang, cuma satu yang membaca. Buktinya buku rilisan Komunitas Bambu hanya sekian persen yang laku. Politisi sekarang sebenarnya beli, tapi saya ragu mereka membacanya. Politisi kita dulu selalu punya sejarah dengan buku, sedangkan sekarang satu-satunya buku yang berhubungan dengan politisi adalah buku rekening. Mahkotanya bukan pengetahuan, tapi kekuasaan.
H
Apa proyek mendatang dari Mas Rizal?
J
Saya akan terus mengurusi produksi barang yang hanya dibaca orang hilang (tertawa).











